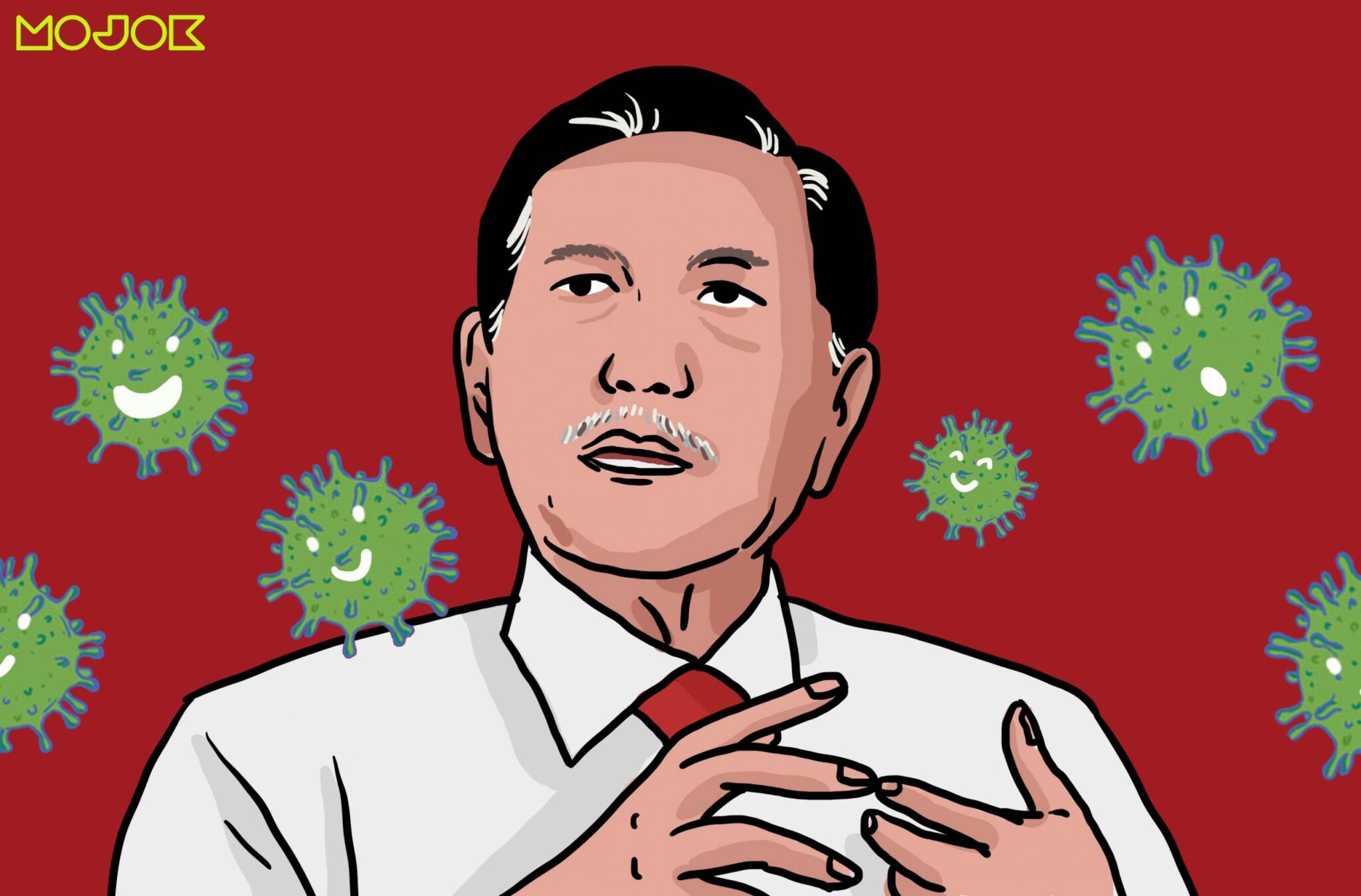MOJOK.CO – Menjadi warga biasa, tidak perlu di saat terjadi pandemi, adalah sebuah situasi yang tidak pernah jelas. Warga yang tidak punya keistimewaan apa-apa dalam kehidupan sosial.
Kalimat yang saya pakai judul tulisan ini berasal dari salah satu spanduk yang dibuat warga untuk menghadapi pandemi corona. Di antara sekian banyak spanduk tentang corona, spanduk ini paling menarik hati saya. Spanduk yang menyatakan perasaan paling gelap dari kenyataan paling terang tentang bagaimana menjadi warga biasa.
Di antara sekian banyak spanduk tentang corona, spanduk ini paling menarik hati saya. Spanduk yang menyatakan perasaan paling gelap dari kenyataan paling terang tentang bagaimana menjadi warga biasa. ? pic.twitter.com/xezF27aSnF
— Puthut EA (@Puthutea) April 12, 2020
Menjadi warga biasa, tidak perlu di saat terjadi pandemi, adalah sebuah situasi yang tidak pernah jelas. Warga yang tidak punya keistimewaan apa-apa dalam kehidupan sosial. Dalam semua syok dan krisis, mereka akan menjadi korban baris pertama. Mereka itu bisa siapa saja. Para buruh pabrik yang tetap harus masuk kerja karena jika tidak masuk maka pabriknya bisa tutup. Sementara kalau masuk kerja, potensi kena corona tentu lebih terbuka. Para pekerja di UMKM, yang dalam keadaan seperti ini, tempat kerja mereka lebih dulu kukut. Bahkan pebisnis UMKM itu sendiri. Termasuk tentu saja warga miskin di Indonesia, yang jumlahnya menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 24,79 juta orang.
Tetap bisa hidup adalah modus eksistensi mereka. Mereka tidak punya mimpi dan harapan karena mau bermimpi apa jika energi, tenaga, pikiran mereka terkuras untuk bertahan hidup. Harapan mereka pastilah sederhana saja, bisa tetap bertahan hidup dan siapa tahu hidup ke depan lebih baik. Tentu saja tanpa keterangan yang jelas tentang apa itu hidup yang lebih baik.
Tapi yang menarik adalah mencermati konsepsi “tidak berguna”. Pernyataan eksistensial ini, juga keberanian untuk mendefinisikan diri ini, sungguh menarik dicermati. Apakah “tidak berguna” itu sebagai batasan psikologis yang sengaja mereka buat, untuk membedakan diri dengan “orang-orang yang berguna”? Lalu siapakah orang yang berguna itu? Apakah mereka yang mapan secara ekonomi dan punya strata sosial tertentu?
Ataukah “tidak berguna” itu semacam pasemon yang dilontarkan untuk menyindir sebuah perilaku masyarakat lain yang merasa diri mereka berguna, jumawa, lalu merasa paling sahih kehadiran mereka di dunia? Orang yang berguna menjadi pusat perhatian, dan orang tidak berguna hanya menjadi penonton di daerah pinggiran? Sebuah strategi untuk menyatakan bahwa mereka telah mengalami keterdesakan dalam ruang sosial?
Apakah “tidak berguna” itu punya dimensi spiritual dalam konteks pandemi corona ini? Mengkritisi diri, bahwa manusia yang konon kuat, ternyata mesti siap lenyap dengan virus yang lembut tak kasat mata itu? Terlalu banyak hal yang bisa dikatakan dan ditafsirkan tentang rasa “tidak berguna” ini.
“Hindari corona” yang dipakai sebagai frasa pembuka, saya kira tidak terlalu punya makna kuat dalam konteks ini. Sebab yang menjadi kunci adalah “tetap hidup walau tidak berguna”. “Hindari corona” bisa diganti apa saja, seperti misal: “hindari narkoba”, “hindari patah hati”, “berhati-hatilah di jalanan licin”, “awas banyak kecelakaan”, “hati-hati di jalan”, dan sekian pesan lain.
Kalau Anda misal sering bersama orang-orang biasa, cobalah tanya apa mimpi dan cita-cita mereka, saya yakin mereka akan tertawa. Mimpi dan cita-cita adalah hal yang terlalu mewah, atau bahkan tidak kontekstual dengan kerasnya kehidupan yang mereka jalani. Itu hanya biasa mereka dengar ditanyakan oleh para guru kepada anak-anak mereka. Hidup itu ya lahir, besar, cari makan, bertahan hidup, dijalani.
Tapi justru dari situlah saya melihat letak kuatnya daya hidup mereka. Justru karena tak punya banyak keinginan, tidak ditimbuni oleh mimpi-mimpi, maka hidup itu ya dilakoni. Dihadapi. Dengan begitu mereka justru punya ketahanan prima dalam menghadapi penderitaan, sebab jangan-jangan konsep penderitaan pun tak mereka miliki. Ataupun kalau mereka miliki, tidak “semenakutkan” konsep penderitaan kita sebagai kelas menengah.
Sehingga tulisan di atas, yang terkesan sebagai sikap apatis, justru menunjukkan hal sebaliknya. Kekuatan daya hidup mereka. Dan itu adalah modal besar bagi setiap komunitas masyarakat. Mereka tak perlu mendengar pesan motivasi “Jatuh 16 kali, bangkit 17 kali”. Sebab yang manifes dalam diri mereka ya kalau jatuh memang harus bangkit. Supaya terus bisa berjalan. Menjalani hidup ini. Tidak perlu juga ditanya tujuannya ke mana, ya berjalan itu sendiri adalah sebuah tujuan.
BACA JUGA Pada Akhirnya Kita Harus Realistis dan esai Puthut EA lainnya di KEPALA SUKU.