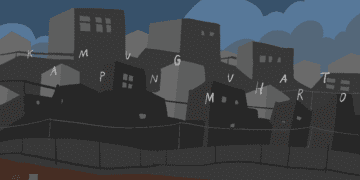MOJOK.CO – Jauh lebih penting memajukan patriotisme yang dikobarkan Kapitan Pattimura ke permukaan; alih-alih mengutak-atik akidah Sang Kapitan.
Nama Kapitan Pattimura van Maluku naik panggung lagi. Bukan hanya karena ucapan seorang ustaz yang mengungkit lagi soal “islamisasi” sang patriot, tetapi juga bersamaan dengan itu di Yogyakarta terjadi kerusuhan (lagi dan lagi) yang melibatkan para pemuda Maluku di Gotham Babarsari pada pekan pertama Juli ini.
Seperti tanah sengketa, Pattimura diperebutkan. Dia tanah yang bernilai sangat tinggi.
Bagi para dai ekspansif dan politis, Kapitan Pattimura dinisbahkan sebagai muslim. Dalih itu penting untuk memaklumkan betapa hebatnya parang-parang muslim dalam mengganyang serdadu-serdadu yang menempel di geladak kapal perusahaan multinasional bernama VOC itu.
Pattimura coba direbut dari “tangan nasrani” karena, sekali lagi, tokoh kita ini punya value yang tinggi sekali. Bahwa, tokoh muslim yang perwira itu melekat pada kampus (Universitas Pattimura), pada kesatuan militer (Kodam XVI/Pattimura), dan juga pada bandara di Ambon dengan status internasional.
Kapitan Pattimura ingin diambil dari “tangan nasrani” yang sebetulnya dalam posisi pasif lantaran versi sejarah negara (yang masuk dalam kurikulum pengajaran di sekolah), Kapitan Pattimura adalah Thomas Matulessy; keluarga Kristen.
Hanya sejarawan didikan akademis dengan disiplin verifikasi sumber yang ketat yang bisa menghentikan aksi klaim seperti ini. Dan, hal itu bukan perkara mudah. Apalagi, jika narasi-narasi itu sudah beredar di WhatsApp Group di lingkaran-lingkaran kecil dan eksklusif seperti WAG keluarga.
Bila itu terjadi, sekali lagi, wassalam saja. Tidak ada gunanya mengeremnya dan ujug-ujug kita mengatakan bahwa sumber kolonial jelas-jelas menuliskan namanya Thomas Matulessy dan bukan Pak Lussy. Belum lagi ditambah dengan hukum besi logaritma internet: “Hanya menyuguhkan berita yang diinginkan dan membuang otomatis yang tak diinginkan.”
Islamisasi Kapitan Pattimura
Apakah hanya kali ini saja kisah islamisasi Kapitan Pattimura? Apakah hanya berhenti di Pattimura dan tidak merembet kepada nona pemberani Martha Christina Tiahahu dari Nusalaut juga yang jika publik meleng dikit aja si nona sudah berubah penampakan outfit?
Oh, tidak.
Sejak saya masih berseragam putih abu-abu yang artinya berkegiatan di Pelajar Islam Indonesia (PII), kisah islamisasi sejarah kerap dilakukan.
Saya yang digembleng dalam sebuah pengaderan diperkenalkan kepada penulis sejarah bernama Ahmad Mansur Suryanegara. Nah, salah satu bukunya yang berjudul Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam Indonesia menjadi bacaan yang menarik karena narasinya yang dibuat memikat. Yang terpenting lagi, BEDA dengan arus utama dalam buku sejarah yang diperkenalkan sekolah.
BEDA, bagi anak muda seperti saya waktu itu, adalah keren. Kapitan Pattimura yang berakidah muslim lebih keren dari Pattimura yang nasrani karena BEDA dengan narasi arus utama.
Yang tak pernah saya ketahui saat itu, selain mengurusi keyakinan orang lain yang sangat privat, adalah bahwa imaji visual orang Indonesia dari dulu sampai sekarang tentang sosok Kapitan Pattimura adalah bikinan seniman Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). Lekra adalah organisasi kebudayaan yang satu arsiran ideologi dengan PKI.
Jadi, seniman Lekra-PKI-lah–begitu pengakuan Des Alwi dalam Sejarah Maluku, Banda Naira, Ternate, Tidore dan Ambon–yang mempopulerkan Kapitan Pattimura secara visual dan disebar secara masif semasif-masifnya oleh Bank Indonesia lewat uang kertas di bulan pahlawan di tahun pertama milenium ketiga. Secara kronik, usaha Bank Indonesia itu bisa dibaca sebagai bagian dari “resolusi konflik” di mana Maluku setahun sebelumnya terbakar oleh kerusuhan sosial yang memilukan.
Bank Indonesia menempatkan wajah Kapitan Pattimura yang diambil dari karya lukis seniman Lekra tersebut untuk mata uang kertas bernilai seribu rupiah. Ini adalah mata uang yang sangat penting artinya di Hari Raya Lebaran. Terutama, bagi adik-adik yang berpelesiran dari satu rumah ke rumah yang lain.
Bagi anak-anak gedongan di Menteng, Kapitan Pattimura barangkali asing. Namun, tidak bagi anak-anak yang tinggal di bantaran sungai Ciliwung yang busuk; Pattimura adalah sahabat akrab dan hangat untuk jajan murah.
Nama seniman Lekra yang melukis wajah Kapitan Pattimura itu adalah Chris Latuputty. Harian Rakjat tidak konsisten menuliskan namanya.
Pada Harian Rakjat edisi 31 Januari 1959, halaman VI, foto Chris ditampilkan sedang berpidato di atas podium Kongres Lekra I Solo. Keterangan di bawah foto itu tertulis: “Christ Latuputih, Lekra Maluku Irian Barat: Kami menerima sepenuhnya Laporan Umum Pusat.”
Pada esai 7 Februari 1959 berjudul “Pidato Joebaar Ajoeb (pada malam resepsi penutupan Kongres Nasional ke1 Lekra)” Harian Rakjat menulis: “Sebagai Pimpinan Pusat jang baru Kongres telah menjusun suatu komposisi jang terdiri dari wakil2 Lekra di-daerah2 seperti Chris Latuputty, Hr. Bandaharo, Sugiarti Siswadi; tokoh2 kesenian Rakjat seperti Tjak Bowo dari sandiwara ludruk “Marhaen” ….”
Nah, variasi penulisan yang lain lagi ditemukan pada artikel Harian Rakjat berjudul “Anggota Pimpinan Pusat Lekra”, 4 April 1959. Nama “Chrismanuputty” ditulis di nomor urut delapan sebelum seniman peran Dhalia dan setelah pelukis Affandi, penyair Agam Wispi, sutradara Bachtiar Siagian, peneliti sastra Bakri Siregar, pelukis Basuki Effendi, pelukis Basuki Resobowo, dan kritikus sastra Boejong Saleh.
“Chris Latuputty”, “Christian Latuputty”, “Christ Latuputih”, maupun “Chrismanuputty” tentu saja merujuk kepada satu sosok: pimpinan Lekra Maluku-Irian Barat. Dia adalah utusan dan simbol Lekra di kawasan yang penuh pergolakan, terutama Irian Barat. Saat itu, ibu kota Irian Barat ditempatkan di Maluku.
Selain dikenal sebagai pelukis, Chris Latuputty adalah sosok penting Lekra di Kepulauan Maluku dan Irian Barat yang menyumbang Tari Lenso menjadi tari pergaulan nasional. Di arena Kongres Lekra Solo pada 1959-lah, Bung Karno yang berpidato di penutupan kongres turun ke lantai menarikan Lenso asal Maluku yang dibawa utusan Lekra Maluku-Irian Barat yang dipimpin Chris.
Nyaris tak ada catatan atas kiprah berkesenian tokoh asal Maluku ini di kancah kebudayaan nasional. Padahal, dia adalah anggota Pimpinan Pusat Lekra yang namanya tersebut satu tarikan napas dengan Affandi, Agam Wispi, Bachtiar Siagian, hingga Pramoedya Ananta Toer.
Barangkali, satu-satunya warisan kebudayaannya yang diingat masyarakat seluruh Indonesia adalah lukisan wajah tokoh bernama Kapitan Pattimura.
Merevisi akidah itu tidak penting
Saya tidak membayangkan apa yang ada dalam benak Chris Latuputty ini saat menggambar sosok Kapitan Pattimura berselempang golok besar. Barangkali, dari semua lukisan wajah pahlawan nasional yang tergantung di dinding kelas dan tentu saja di lembar mata uang, hanya Kapitan Pattimura versi Chris Latuputty yang membawa sajam, senjata tajam. Besar pula ukurannya.
Namun, kita semua bisa memaklumi sajam Kapitan Pattimura bukanlah ancaman di mana polisi turun tangan meng-”aman”-kannya. Kita bisa menerimanya, menyimpannya di dompet dengan perasaan tawadu, ikhlas, dan haru-biru menjalani hidup kismin.
Jauh lebih penting dari itu, Kapitan Pattimura bagi Lekra dan bahkan bagi PKI, bukan soal apa agamanya, soal keyakinannya, tetapi apa yang diberikan tokoh ini dalam mata rantai pembebasan nasional.
Berkali-kali PKI menyebut diri mereka sebagai pewaris perjuangan heroik dan revolusioner dari tokoh-tokoh seperti Kapitan Pattimura ini.
Baca buklet “Bahan-Bahan Untuk Kongres Nasional Ke-VI Partai Komunis Indonesia” yang diterbitkan Depagitprop CC PKI tahun 1958. Di sana, PKI menempatkan diri dalam mata rantai revolusioner yang tak terpisahkan dari Kapitan Pattimura:
“PKI yang didirikan pada 23 Mei 1920 adalah pewaris dan penerus perjuangan yang heroik dan revolusioner dari Rakyat Indonesia. Perjuangan yang heroik dari Rakyat Indonesia dibuktikan oleh perlawanan-perlawanan Rakyat terhadap penjajahan Belanda dengan adanya Perang Banten Perang Timor, Perang Tondano, Perang Diponegoro, Perang Pattimura, Perang Hasanuddin, Perang Bonjol, Perang Palembang, Perang Banjar, Perang Aceh, Perang Jambi dan lain-lainnya, pemberontakan “Zeven Provincien”, perlawanan terhadap fasis Jepang, di antaranya di Blitar, Singaparna, Tanah Karo, Baju dan Pandrah (Aceh), perlawanan terhadap provokasi Madiun dan perlawanan terhadap pemberontakan-pemberontakan separatis dan kontra-revolusioner.”
Bahkan, jauh sebelum terbit buklet itu, D.N. Aidit dalam pidato memperingati ulang tahun ke-33 PKI di Gedung Kesenian, Jakarta, 22 Mei 1953, menekankan dalam satu garis kalimat utuh tiga perlawanan sengit yang diwarisi PKI apinya: Kapitan Pattimura di Maluku (1817), Pangeran Diponegoro di Jawa (1825-1830), Imam Bonjol di Minangkabau (1830-1839).
Bagi Aidit, perlawanan sengit itu lahir dari tindasan yang berat yang tidak kenal perikemanusiaan yang dilakukan oleh penjajah.
“Semuanya ini membuktikan betapa teguh dan militannya Rakyat Indonesia berjuang untuk kemerdekaannya dan betapa tingginya mutu patriotisme Rakyat Indonesia. Kekalahan-kekalahan yang diderita oleh Rakyat Indonesia dalam peperangan patriotik melawan Belanda bukanlah karena kurang sengitnya perlawanan, bukanlah karena kurang keberanian Rakyat atau kurang ketangkasan pemimpin-pemimpin dan panglima-panglima, tetapi adalah karena Rakyat Indonesia belum dipimpin oleh suatu kelas yang revolusioner dan persenjataan Belanda lebih banyak dan modern,” ujar Aidit.
Lihat, tak satu pun ada usaha dari PKI ini melakukan perevisian akidah “tokoh kita” ini. Mengapa? Karena sama sekali tidak produktif bagi penyelesaian proyek revolusi.
Ada hal yang lebih penting menaikkan Kapitan Pattimura sebagai patriot, sebagai kebanggaan bangsa, yakni memisahkan “citra negatif” frasa “Maluku” dalam semesta sejarah pergerakan nasional yang identik dengan loyalis KNIL, tentara boneka buatan Belanda.
Di masa kemerdekaan, loyalis-loyalis KNIL berasal dari Maluku inilah yang berhadap-hadapan dengan serdadu Republik di medan tempur revolusi. Nah, untuk mengikis sentimen buruk dari sebutan “Belanda Hitam” itu, penting memajukan patriotisme yang dikobarkan Kapitan Pattimura ke permukaan; alih-alih mengutak-atik akidah Sang Kapitan.
Mempertanyakan akidah dan usaha islamisasi Kapitan Pattimura seperti memutar kembali turbin kerusuhan sosial Ambon di mana saat itu juga muncul lagi narasi “Pattimura Muslim” dari lidah Ja’far Umar Thalib jelang tutup abad.
Dari Lekra, justru kita diingatkan untuk melihat Maluku dari patriotismenya. Juga, Maluku sebagai hulu dari mana pengetahuan botani kita bersumber.
Baca paragraf “Laporan Pimpinan Pusat Lekra tentang Ilmu” pada Harian Rakjat, 14 Februari 1959:
“Dalam pertengahan kedua abad ke-17 ilmu tentang tumbuh2an Indonesia dimulai dengan penjelidikan2 yang dilakukan oleh Rumphius di Maluku. Rumphius adalah seorang sardjana besar tetapi perhatiannja tidak dapat kita lihat lepas dari keadaan kolonialisme pada waktu itu … “
Bagaimana? Jangan bikin malu Kapitan Pattimura, ah, dengan ngacung-ngacungin sajam di jalanan Babarsari, Yogyakarta. Petantang-petenteng. Kalau mau main jago-jagoan, lawan tuh kekuatan-kekuatan yang bikin rakyat sengsara. Lho. Itu!
BACA JUGA Belanda di Maluku: Antara Cinta dan Benci dan analisis menarik lainnya di rubrik ESAI.
Penulis: Muhidin M. Dahlan
Editor: Yamadipati Seno