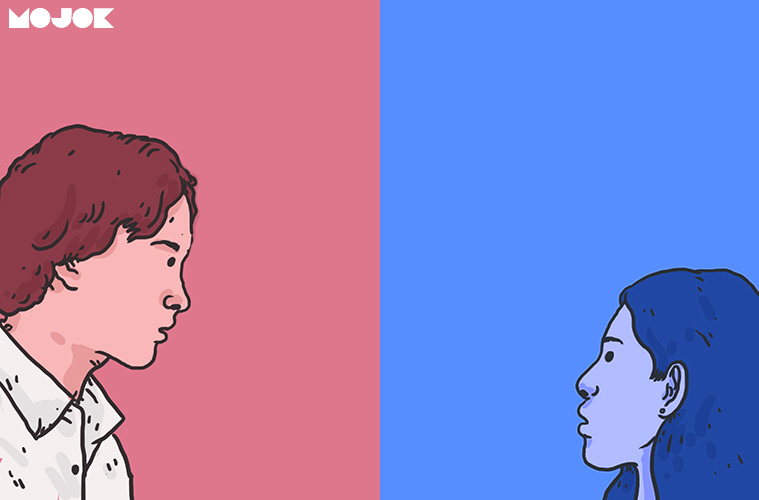Baca cerita sebelumnya di sini.
Seperti janjiku pada Rilla kemarin, aku datang menemui Aran. Aku sungguh malu kepada diriku sendiri, juga kepada Sonya. Aku yang selalu berkata padanya tentang filosofi gelas pecah: Jangan menjadi gelas pecah yang tidak dipersihkan pecahannya, yang pada akhirnya akan melukai orang lain. Namun ternyata, aku yang menjadi gelas pecah tersebut.
Ah, memang bicara itu lebih mudah daripada menjalani sendiri. Maafkan aku, Sonya. Aku janji, hari ini akan kubersihkan serpihan pecahan itu, serpihan luka itu.
Belum juga diriku sampai ke rumah tahanan tempat Aran akan menjalani masa hukumannya, handphone-ku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Tribhuana.
“Mas Dimas lagi di mana? Bisa ke RS Prabayekti sekarang? Mas Aran dirawat di sini.”
Aran di rumah sakit? Aku hanya mengetik “OK” dan mengirimkan balasan pesanku pada Bhuan. Aku memutar balik dari tujuanku semula ke rutan dan sekarang ke rumah sakit. Bhuan kembali mengirimiku pesan yang menginformasikan ruangan di mana Aran dirawat. Aku segera mempercepat laju kendaraanku ke sana.
Bhuan sudah menungguku di depan kamar rawat Aran. Ah, sungguh aku masih membenci aroma rumah sakit. Rasanya seperti banyak ada banyak dementor yang mengelilingimu. Mereka siap menghisap segala kebahagiaan yang ada di hatimu.
“Apa yang terjadi?” tanyaku setelah ia mempersilakanku duduk di sampingnya.
“Sipir menemukan Mas Aran pingsan di selnya. Paramedis rutan membawanya ke sini. Dokter sudah bicara padaku, katanya Mas Aran kena Hepatitis B. Sudah parah.”
“Hepatitis B? Aku tidak pernah mendengar Aran punya penyakit itu. Sonya tidak pernah bilang padaku.”
“Akhir-akhir ini memang Mas Aran mengeluh sering mual, muntah, dan kembung. Kata dokter, gejala ini mirip dengan asam lambung. Itulah yang membuat penyakitnya semakin parah karena orang menganggapnya hanya sakit maag biasa atau asam lambung. Stres yang tinggi bisa mengakibatkan narapidana menderita penyakit hepatitis B,” jelas Bhuan.
Aku terdiam. Aku bingung menjelaskan perasaanku. Bukankah kemarin aku senang jika Aran menderita dalam penjara? Tapi kenapa sekarang malah timbul rasa iba?
Aku dibimbing Bhuan masuk ke dalam kamar rawat Aran. Ia memberiku kesempatan bertemu empat mata dengan Aran.
Aku melihat Aran terlihat payah terbaring di ranjang. Infus yang menghiasi tangannya menambah kesan tidak berdaya. Oh, inikah laki-laki yang selalu terlihat sangar itu? Laki-laki yang dulu kubenci setengah mati dan sepertinya dia juga membenciku?
Perlahan ia membuka matanya, menyadari kedatanganku.
“Hai, budayawan muda,” sapanya padaku. Andai saja tidak dalam kondisi sakit, aku yakin dia akan menyalamiku dengan ramah walau akan canggung pada awalnya.
“Hai juga, komikus keren, walau agak temperamental. Haha,” aku berusaha membalas ejekannya.
“Sialan kau.” Walau dengan suara yang lemah, dia terlihat ingin mengakrabkan pertemuan ini.
Ada jeda sebentar di antara kami. Banyak hal yang terjadi dan sulit dikatakan. Aku membunuh hening itu dengan meminta maaf padanya. Aku bahkan mengaku pernah hendak membunuhnya dengan mengirim kue beracun yang kutitipkan pada Bhuan beberapa saat lalu. Ia menanggapinya dengan tertawa.
“Bodoh sekali kau, Dim. Harusnya kau riset dulu. Apa Sonya tak pernah berkata padamu kalau aku tidak suka kue-kue manis semacam itu? Kalau mau membunuhku, harusnya seperti Rilla kemarin, membawakan aku tempe kemul. Sudah pasti akan kumakan. Ah, kau ini memang seperti yang Sonya bilang, hatimu terlalu lembut, dengan kecoa saja kau tak berani membunuh.”
“Haha…. Entahlah, mungkin Sonya sudah pernah bilang, tapi aku malas mendengarkan kalau itu sesuatu tentangmu.”
“Sama. Aku pun malas kalau Sonya selalu membanggakanmu soal keahlianmu meracik teh. Huh, bukannya semua teh sama saja?”
“Wah, kalau itu sudah tak diragukan lagi. Ayolah sembuh. Setelah bebas, kuajari kau meracik teh. Aku biasanya tidak mau, loh, membagi resep rahasia itu.”
Tiba-tiba raut wajahnya berubah. Katanya, “Entahlah, Dim. Hidupku adalah Sonya. Aku tidak bisa hidup dengan separuh nyawa.”
Aku melihat raut keputusasaan di wajahnya. Aku sudah berkali-kali menyemangatinya, tapi usahaku sia-sia belaka. Wajahnya semakin pucat. Aku ingin memanggil dokter, tapi dia menahanku.
“Dim, kau masih ingat pohon mahoni di samping makam Sonya?”
Aku mengingat-ingat makam Sonya. Ia dimakamkan di samping makam bapaknya. Memang di sampingnya lagi masih ada tanah kosong, di bawah pohon mahoni.
“Iya, aku ingat. Aku ikut mengubur jenazah Sonya. Kenapa, Ran?”
“Tolong, makamkan aku di sana, di samping belahan jiwaku.”
Aku ingin memarahinya. Aku masih sama, selalu belum siap jika diajak berbicara tentang kematian. Dulu aku selalu memarahi Sonya kalau sudah menyinggung soal itu. Tapi melihat Aran berbicara dengan kepasrahan seperti itu, tidak ada yang bisa kulakukan selain mengiyakan permintaannya.
Aku merasa ruangan ini bertambah dingin. Sayup-sayup kudengar seseorang menyenandungkan sebuah puisi.
Pada suara hangat mesra
Aku rindu peluk aku
Senandungkan nada ungu
Kan kubuka dua pintu
Jangan takut lagi
Tali-tali terlucuti*
Perlahan Aran memejamkan matanya. Kedamaian menyertai kepergiannya. Aku menoleh. Sosok perempuan yang begitu kusayangi tersenyum padaku.
“Kekasihmu sudah kembali padamu, Son. Pergilah kalian berdua dengan tenang,” kataku padanya.
***
Tidak banyak orang yang mengantar kepergian Aran, berbeda dengan Sonya yang diantar banyak pelayat di hari pemakamannya. Wajar saja; dia meninggal sewaktu menjalani masa tahanan dengan kasus pembunuhan. Aku, Rilla, dan Bhuan termasuk dari sedikit orang yang mengantar kepergian Aran dalam suasana senyap.
Seperti wasiat Aran, ia dikuburkan di samping makam Sonya, di bawah pohon mahoni. Sonya pernah bercerita kalau dulu ia sering memainkan biji buah mahoni yang sudah kering. Dia suka menerbangkannya. Gerakan biji buah mahoni yang berputar-putar itu membuatnya senang. Sekarang mungkin ia mengajak Aran untuk memainkan hal yang sama.
Aku teringat ketika aku dan Sonya berziarah di makam raja-raja. Sonya memberitahuku bahwa ada pohon khusus dan langka di kompleks makam tersebut. Ia menyuruhku menebak apa nama pohon tersebut. Ia jengkel ketika aku selalu salah menebaknya.
“Dimas, itu bukan beringin, apalagi pohon salam. Jauh sekali. Ah, payah kau.”
“Aku bukan ahli botani, Son.”
“Dengar ya, ini namanya pohon nagasari. Bukan makanan, ya. Pohon ini usianya lebih tua dari makam di sini, mungkin sekitar 500 tahun. Pohon ini memang biasanya ditanam di area makam raja-raja. Tidak di kota ini saja. Kalau kau memperhatikan, di makam raja di provinsi tetangga sana juga ada pohon nagasari.
“Lihat pohon yang di pojokan itu. Salah satu cabang pohon itu patah dan tidak bisa bersemi lagi. Kata juru kunci sini, memang begitu sifat pohon itu,” jelas Sonya panjang lebar.
“Patah dan tidak bisa tumbuh lagi. Sounds familiar,” godaku. Waktu itu memang Sonya baru saja sembuh dari patah hati. Ia meninju pundakku.
“Ah, pait kau. Seperti biji mahoni saja,” kata Sonya. Itu pertama kalinya ia bercerita tentang pohon mahoni di makam kampungnya. Sejak kecil ia memang suka bermain di area pemakaman. Sampai aku mengenalnya, ia suka berbicara tentang kematian dengan begitu entengnya.
Aku memegang nisan Aran. Kupesankan nisan dengan ukiran yang sama seperti nisan Sonya. Rilla menabur bunga dan melangitkan doa-doa terbaik untuk Aran. Aku merasa kami ini kumpulan manusia aneh. Kenapa kami berada di sini? Kenapa kami peduli pada seseorang yang telah membunuh sahabat kami?
“Mas Aran memang membunuh Mbak Sonya, tapi dia tidak bisa membunuh rasa kemanusiaan dalam diri kita, Mas. Dendamlah yang akan membunuh kita,” ujar Rilla kepadaku. Ia seperti membaca pikiranku.
Aku memegang bahu Rilla. Memaafkan memang hal tersulit dalam hidup, namun jika bisa melakukannya sungguh itu sangat melegakan. Aku ingin mereka berdua pergi dengan tenang.
Mungkin benar kata Sonya, kematian hanyalah awal dari seseorang untuk menjalani kehidupan yang baru. Aku teringat pepatah lama Belanda yang kubaca dari sebuah novel: Alles heft een reden. Semua peristiwa pasti punya alasan untuk terjadi.
“Maafkan aku yang hanya bisa melobi keringanan masa tahanan. Aku tidak bisa melobi Tuhan untuk menunda kematian,” kata Bhuan di sampingku.
“Tidak ada manusia yang bisa melobi kematian, Bhuan. Namun kita bisa menghidupi kematian. Mari kita mengenang kepergian orang yang kita sayangi dengan bahagia,” kataku yang langsung disambut anggukan dua kawanku.
***
Aku dan Rilla sepakat untuk tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Kami ingat impian Sonya yang ingin menjadikan rumahnya sebagai ruang publik untuk berkesenian. Dengan dibantu Bhuan, kami merealisasikan impian Sonya tersebut.
Kami menamakan rumah tersebut dengan “Sendhang Indraswari”, gabungan nama Aran dan Sonya. Sendhang berarti telaga atau sumber mata air, sedang Indraswari artinya intinya kebaikan. Harapan kami, semoga rumah ini menjadi sumber inti kebaikan bagi banyak orang.
Dinding rumah ini kami hiasi dengan gambar-gambar Aran dan puisi-puisi Sonya. Rumah ini menjadi lebih hidup walau penghuninya sudah mati. Mereka mungkin mati secara raga, tapi jiwanya tetap hidup. Ini ikhtiarku untuk menghidupi kematian mereka.
Pelan saja ikhlas rela
Lepas semua duka lara
Telah kupilih baju baru
Wangi syukur senyum ranum
Antar aku ke rumah,
Nanti siramilah*
Aku sudah melepaskanmu, Son. Aku ikhlas seperti puisi yang pernah kau baca di depanku dulu. Aku sudah merumahkan puisimu di sini dan kusirami dengan cinta dan doa terbaik untukmu.
Berbahagialah bersama Aranmu, sendhang–mu, telagamu, sumber kehidupanmu.
***
*Puisi berjudul “Senandung Musim Gugur” karya Olen Saddha dalam buku “Memandikan Harapan” (Kekata Publisher, 2017)