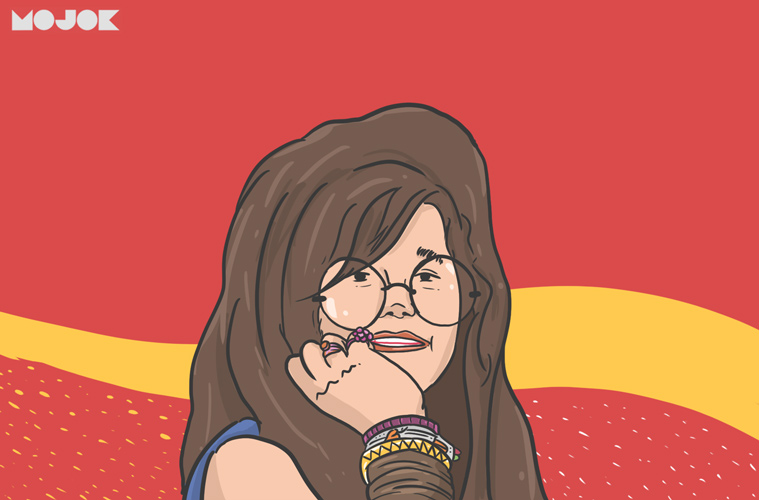Baca cerita sebelumnya di sini.
Hal-hal buruk terjadi setiap waktu, tetapi tidak akan berubah lebih buruk kalau manusia segera menyadari kenyataan itu. Sungguh aneh. Kurasa sekarang aku percaya apa kata Zulkarnaen—eh atau siapa itu, lah, namanya—bahwa untuk bisa bertahan hidup, spesies kami hanya perlu menguasai kemampuan beradaptasi.
Sekarang usiaku dua puluh delapan tahun. Aku pikir aku bakal mati tahun lalu, tetapi kenyataannya saat ini aku masih bisa mendengarkan seorang perempuan paruh baya dengan rambut keriting yang megar menyanyikan lagu Janis Joplin.
“O, Lord, would you buy me a Mercedes Benz?”
Tangannya memegang ponsel pintar dan ia menyanyikan bait selanjutnya tanpa melepaskan pandangannya dari benda tolol itu. Dia tak hafal lirik, tapi bolehlah kuakui, perempuan itu bernyanyi dengan sangat indah. Kurasa, kata bernyanyi bahkan kurang tepat: dia sedang mengatakan sesuatu.
“Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, O, Lord would you buy me a Mercedes Benz?”
Mungkin dia Janis Joplin yang berhasil lolos dari maut?
Apa pun itu, siapa pun dia, aku akan berdiri buat memberikan tepuk tangan yang paling meriah ketika lagu ini selesai, yang mana itu artinya hitung mundur: satu, dua, tiga … sekarang juga! Dia tertawa dan tersipu melihatku memberikan penghormatan. “Terima kasih,” katanya. Segerombolan pria bule yang duduk di depan lantas menoleh ke arahku.
Aku duduk lagi dan menyedot dalam satu kali tarikan pendek milkshake cokelat yang tinggal setengah gelas. Ada tiga kursi kosong yang melingkariku dan duduk dua meja dari sini ada sepasang kekasih yang nyaris bercumbu.
Kau tahu, ini hari yang aneh. Biasanya aku tidak peduli. Toh, tidak ada yang salah dari pasangan yang saling mencintai dan ingin segera menghabisi satu sama lain. Tetapi, hei, karena ini hari yang aneh, jadi sekali ini aku merasa muak dan aku ingin memperingatkan kelakuan norak mereka.
“Bisakah kau bilang pada dua orang yang duduk di sana untuk menahan hasrat mereka?” kataku saat seorang pelayan mendekat. Di tangannya ada sebuah nampan dengan seember bir dingin. Dia tampak bingung awalnya, tetapi kemudian tersenyum seperti seorang pendeta yang bijaksana.
“Mau kuambilkan bir dingin juga?” Aku menggeleng.
Alkohol tidak menyelesaikan masalah, kataku, setelah pelayan itu menjauh.
Bar ini cukup ramai pada hari Sabtu atau Minggu, tetapi tidak di hari-hari lain. Sekarang ini hari Selasa. Kau tahu, setiap pedagang bakal berusaha membuat barang jualannya laris manis tak peduli apa pun, kalau bisa setiap hari, tujuh hari dalam seminggu, empat minggu dalam sebulan. Di antara keinginan itu, orang-orang kecil lantas mencari celah mengais rejeki, misalnya penyanyi atau band baru atau band lawas yang berhasil bertahan tapi tak kunjung populer.
Jadilah, ada hari-hari di mana orang-orang itu didatangkan untuk bernyanyi, bermain alat musik, dan merapal mantra agar pengunjung datang sebanyak mungkin. Khusus tiap hari Selasa, pemilik bar membuat acara bernama Blues on Tuesday. Yah, lumayan. Setidaknya, aku jadi kelihatan tidak terlalu mencolok setiap kali datang sendirian dan bisa mendengar lagu-lagu The Doors dinyanyikan sampai kira-kira seratus kali.
Aku sedang menunggu seseorang. Kami punya janji bertemu pukul delapan malam, tetapi sekarang sudah hampir jam setengah sebelas dan ia belum juga tiba. Mungkin dia mati ditabrak bus pariwisata saat perjalanan ke sini? Atau dia tiba-tiba harus mendekam di kantor polisi karena ketahuan menghina seorang tentara? Atau karena dia seorang pengecut? Yang terakhir kurasa paling masuk akal.
Hal-hal buruk terjadi setiap waktu dan aku telah membayangkan yang terburuk dari semua ini jauh sebelum sekarang. Perasaanku selalu jadi lebih tenang kemudian. Bukankah itu aneh? Aku pikir aku akan mati pada umur dua puluh tujuh tahun, tapi ternyata tidak dan dengan begitu aku jadi lebih santai menghadapi kematian. Aku pikir aku akan ditinggalkan oleh setiap orang dan dengan begitu seharusnya aku tak perlu takut menghadapi penderitaan. Aku tahu pria yang aku tunggu-tunggu tak akan datang malam ini atau besok atau bahkan setahun kemudian. Aku hanya terlalu naif.
Lagu “People are Strange” dari The Doors mengalun dari pojok bar. Empat orang pemuda meng-cover lagu itu. Suara vokalisnya sumbang betul, bikin aku ingin melempar granat.
“Hei,” kataku, melambaikan tangan kepada pelayan.
“Ada yang bisa saya bantu?” katanya, sembari membawa menu, berdiri di sampingku.
“Aku mau pesan satu botol bir dingin.” Pria pelayan yang punya senyum seperti pendeta itu sepintas memandangku penuh rasa ingin tahu. Tapi tidak lama, mungkin cuma dua detik, ia kembali memancarkan aura keteduhan seorang pendeta. “Tunggu sebentar,” katanya.
“People are strange when you’re stranger. Faces look ugly when you’re alone. Woman seem wicked when you’re unwanted. Streets are uneven when you’re down.”
Ini bagian kesukaanku. Kau tahu, lagu bagus punya kemampuan merenggut jiwa seseorang. Membawanya berputar-putar di alam yang ganjil, yang hanya dia sendiri yang paham. Kurebahkan punggung ke sandaran kursi. Pria pelayan datang, kemudian membawa pesananku. “Terima kasih,” kataku.
Ia kembali tersenyum dan berlalu dan lagu “People are Strange” selesai dibawakan. Kutenggak bir dingin itu seperti seorang atlet lari yang kelelahan. Vokalis turun dari atas panggung dan seorang pria kurus naik menggantikannya. Perawakannya sudah tidak bisa dibilang muda, mungkin menjelang 40-an, memegangi mic dengan raut wajah melankolis. Intro terdengar, lantas pemuda yang lain memetik senar gitar: lagu “The End”.
“Tadi sore aku bertemu kawan lama. Kami dulu punya band dan suka meng-cover lagu-lagu Nirvana. Ya, mirip-mirip dengan kalian sekarang lah,” kata pria kurus. Ia mengenakan topi pet warna hitam, kaos lengan pendek, dan celana jins warna biru terang.
“Aku tidak bisa main alat musik, jadi tugasku seperti Jim Morisson, hanya bernyanyi. Dari dulu aku selalu ingin jadi Jim Morisson, bukan Kurt Cobain, ya tapi apa mau dikata? Perutku pernah dibogem waktu aku bilang Kurt Cobain nggak bisa bikin lagu.”
Pengunjung tertawa. Ia menguasai panggung dengan sangat baik. “Aku cuma mau bilang. Kalau nanti band kalian bubar, tetap jaga silaturahmi. Jangan bermusuhan,” katanya lagi. Kurasa pria itu sudah setengah mabuk.
“This is the end. Beautiful friend. This is the end. My only friend. The end.”
Pria itu mulai bernyanyi. Orang-orang bertepuk tangan. Sinar lampu yang kekuning-kuningan menyiram wajahnya, membuatnya terlihat seperti nabi. Kenapa ada banyak pemuka agama di dalam bar? Aneh. Kau menemukan orang-orang suci di tempat-tempat yang gelap. Eh, apa yang barusan kukatakan?
“Hei,” aku memanggil si pelayan lagi, “tambah bir.”
Aku mengangkat botol berwarna hijau itu setinggi mungkin. Seekor kecoak merayap di dekat kursi. Biasanya aku takut, tetapi karena ini hari yang aneh, aku bergeming.
Ah, ini bukan hari yang aneh; ini hari yang menyedihkan bagi seseorang yang baru saja ditinggalkan. Pukul sebelas malam lewat sepuluh menit. Ponselku berdering. Sebuah pesan singkat masuk.
Butuh dana cepat? Punya BPKB? Hubungi kami dan rasakan kemudahan mengajukan dana tanpa perlu ribet.
Seharusnya aku marah dan membanting ponsel, tapi ini hari yang aneh—eh, bukan, maksudku ini hari Selasa, Blues on Tuesday! Aku cuma mau mendengarkan lagu “The End” sampai selesai. Itu saja.
Baca cerita berikutnya di sini.