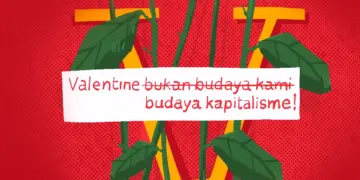MOJOK.CO – Bukan soal ena-enanya aja, mau kumpul kebo atau kohabitasi kek, mau menikah dulu kek. Keduanya sama-sama tak menghindarkan kita dari masalah.
Andai kumpul kebo tak punya stigma negatif di masyarakat, tak melanggar norma dan nilai agama, saya pikir, saya tetap memilih untuk nggak tinggal bersama pacar. Bukan, bukan karena saya punya argumen sok suci untuk nggak seks bebas dan ena-ena. Lho, tinggal bareng orang terkasih kan sebuah konsep yang menyenangkan. Lebih dari itu, keputusan untuk kohabitasi alias tinggal bersama sebelum menikah membutuhkan begitu banyak persiapan buat saling benci dan siap-siap saling cinta lagi meski tanpa ikatan. Hal tersulit untuk dilakukan di muka Bumi.
Mungkin argumen saya terasa kurang otoritatif karena saya belum menikah, saya juga nggak pernah kumpul kebo. Tapi, boleh kali saya urun pandangan. Lha wong pada akhirnya saya berada di titik ini juga hasil dari rangkaian keputusan-keputusan sebelumnya kok.
Jadi, mendadak pembahasan tinggal bersama sebelum menikah alias kumpul kebo ini ramai karena twit dari seorang netizen @bukanherbalife. Ndilalah, cuitan itu ramai dan banyak diamini abege Twitter progresif. Ya, monggo saja kalau merasa kohabitasi adalah sebuah “jembatan” menuju pernikahan damai langgeng sejahtera, tapi saya rasa definisi pernikahan tidak pernah sesederhana “tinggal satu atap”.
Living together before marriage is necessary. It’s not just about sex, but there are A LOT of things that could be uncovered only when u live together. https://t.co/XVKUcXRMVX
— boo boo the fool (@bukanherbalife) November 13, 2021
Beberapa orang yang saya kenal menerapkan hal ini. Mereka ngaku terang-terangan ingin tinggal bersama pacar atau kumpul kebo ya karena seks. Awalnya begitu. Mempermudah ena-ena biar nggak tekor karena harus nge-room terus-menerus. Tinggal berdua di kos bebas juga ternyata nggak enak. Masih ada tetangga kos yang julid. Saat melakukan seks mereka juga nggak bisa gedebag-gedebug karena jarak kamar ke kamar hanya terpisahkan tembok. Yah, maklum lah, Buos.
Akhirnya jadilah kawan-kawan saya ini sewa kontrakan berdua. Kumpul kebo. Kohabitasi.
Jujur aja, konsep macam itu memang terasa menyenangkan kalau dibayangkan. Nggak usah ribet-ribet ngurus pernikahan yang di Indonesia ina-inu dan ruwet minta ampun. Bisa langsung tancap gas yang-yangan tanpa ngerem. Pagi-pagi terbangun melihat si dia ngences aja lucu banget. Bikinin sarapan, makan bareng sebelum berangkat kerja, dan pulang kerja langsung disambut pelukan. Bisa Netflix and chill kapan pun. Beli perabotan bareng, grocery dating di Mirota Kampus, pulangnya kembali berpelukan. Udah kayak Teletubbies aja kelen.
Meski begitu, orang yang pro kohabitasi tentu menilai tindakan kumpul kebo itu sebuah upaya berkenalan lebih jauh dengan kekasih. Ada proses pertengkaran di dalamnya. Ada juga proses untuk meributkan anduk basah yang setiap hari ditaruh kasur lagi, kasur lagi. Sesekali berdebat kenapa pulsa listrik udah bunyi padahal baru ngisi seminggu yang lalu. Kita akan mengenal pasangan lebih jauh. Mengenali wajah aslinya dan tahu betul kebiasaan buruknya.
Konon, inilah yang dibutuhkan biar di kehidupan pernikahan nanti dua sejoli nggak akan kaget. Pikirnya, usai sah di mata agama dan negara, bisa langsung klop menjalani hidup bersama. Harapannya proses persiapan yang dilakukan dengan kumpul kebo bisa menuntaskan sekian perkara rumah tangga. Syukur-syukur mencegah dua sejoli mudah memutuskan bercerai.
Hash. Dengan segala hormat, saya agree to disagree.
Saya justru mikir sebaliknya. Kumpul kebo bisa menciptakan arena adu banteng baru, masalah baru, pertengkaran baru yang solusinya berpisah pula. Ada hal yang lebih “seru” dari seks, pelukan, dan ngeributin anduk basah dalam ranah kohabitasi, yaitu kita bisa berpisah dan tinggal bersama orang baru tanpa ribet ngurus perceraian. Lha dari awal kan memang hidup bersama tanpa adanya ikatan. Nggak perlu memutuskan ikatan kalau emang dari awal nggak ada ikatan.
“Keseruan” macam itulah yang bikin hubungan kumpul kebo paling rentan gagal. Sudah gagal, kenangan yang tersisa agak brengsek pula. Orang yang merasa “ditinggalkan” menganggap dirinya paling rugi karena sudah menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga demi kesia-siaan. Jadi, bikini sarapan dan kecup manja bangun tidur for nothing, berdebat pulsa listrik for nothing, pelukan sambil Netflix and chill juga for nothing.
Di dalam dan di luar pernikahan, saya yakin pertengkaran itu bakal selalu ada. Memutuskan tinggal bersama duluan atau belakangan, juga menempatkan kita pada titik saat kita benci setengah mati dengan orang yang kita cintai. Di saat yang bersamaan, ego harus diredam demi bisa jatuh cinta lagi dengan orang yang sama. Sayangnya, komitmen dan ikatan pernikahan-lah yang akan membantu kita melalui ini. Bukan pengalaman kohabitasi bertahun-tahun, bukan perasaan us against the world karena gunjingan tetangga.
Manusia itu makhluk yang setengah goblok dan setengah egois. Kita perlu disadarkan dengan komitmen dan ikatan yang akan memaksa kita jadi makhluk setengah cerdas, setengah penyayang. Perasaan manusia bisa berubah-ubah, tapi komitmen dan ikatan pernikahan perlu dipertahankan.
Kawan saya yang memutuskan tinggal bersama sebelum menikah, kini hubungannya sudah kandas. Tentu saja berakhirnya hubungan mereka juga penuh dengan drama. Kadang, menyisakan problem finansial pula. Ah, dulu mereka tampak sebagai pasangan paling bahagia, sayang sekali harus berakhir.
Namun, bukan berarti semua yang memutuskan kohabitasi itu nggak langgeng, ya ada juga yang berhasil. Kalau diurut kasusnya satu-satu, perdebatannya nggak mungkin selesai sih.
Intinya, saya pribadi sih nggak pengin tinggal bareng sebelum menikah karena beberapa alasan di atas. Kumpul kebo sepertinya lebih menguras tenaga dan menciptakan arena adu banteng baru. Kayak main rumah-rumahan, tapi lebih modal dan lebih banyak bertengkar aja. Harusnya kalau mau punya hubungan yang serius, ha mbok ayo berusaha bareng bikin komitmen. Kalau nggak serius ya sudah FWB-an aja.
BACA JUGA Menikah untuk Saling Melengkapi: Terdengar Indah dan Romantis Padahal Bullshit dan artikel lainnya di POJOKAN.