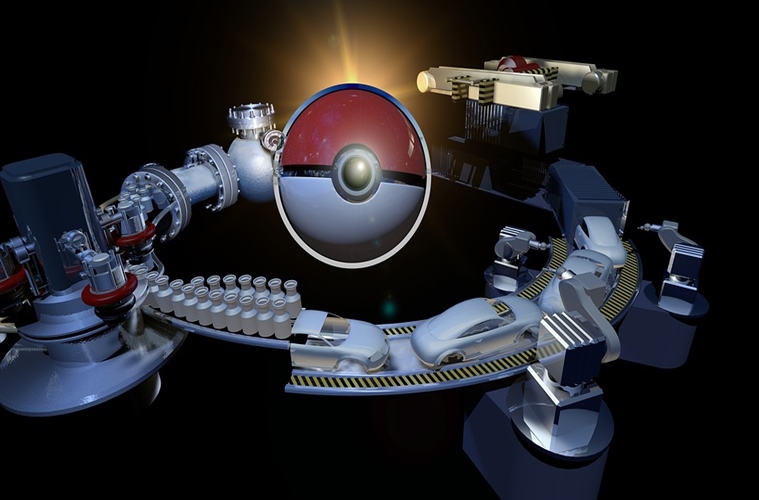Di Twitter, saya menemukan cuitan yang ditulis oleh seorang blogger, ia meresahkan kebiasaan para pelancong Indonesia yang ketika piknik ke sebuah tempat mereka hanya punya obsesi agar bisa berfoto di tempat-tempat terkenal.
Kegelisahan semacam itu tentu bukan sekali dua saya temukan. Sebelumnya, sudah ada banyak orang yang menuliskan kegelisahan serupa terhadap kebiasaan para pelancong Indonesia yang memang punya hobi berfoto di tempat-tempat terkenal di berbagai penjuru dunia.
Bagi banyak blogger, kebiasaan para pelancong Indonesia tersebut boleh jadi memang kebiasaan yang menyebalkan. Berlibur ke Singapura hanya agar bisa berfoto di area patung Merlion, atau jauh-jauh ke Paris, namun sampai di sana yang diincar hanya ingin berfoto dengan background Menara Eiffel, atau berlibur ke Inggris hanya demi bisa berfoto di depan stadion Old Trafford.
Menjadi menyebalkan, karena memang para travel blogger punya sudut pandang yang lain dalam menikmati penjelajahan. Mereka umumnya merasa rugi kalau sudah datang jauh-jauh ke satu tempat tapi tak bisa bisa menikmati banyak hal dari tempat baru yang mereka datangi. Mereka merasa rugi jika tidak berbaur dengan masyarakat dan merasakan kehidupan lokal, merasa rugi jika tidak menjelajahi kuliner khas yang ada di tempat tersebut, juga merasa rugi jika tidak bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru tentang tempat tersebut.
“Dan pertanyaan khas traveler Indo ialah ‘dapatnya banyak ga?’ karena ya emang demennya cuma sekedar sampai lokasi, foto2, udah selesai. Jalan-jalan koq kejar setoran. Padahal jalan-jalan itu kesempatan untuk belajar banyak hal-hal baru, bukan sekedar datang, foto, pulang.” begitu kata blogger yang saya sebut di awal.
Lantas, apakah yang dilakukan oleh orang-orang yang hanya mengejar foto di tempat-tempat terkenal saat piknik itu salah?
Menurut pendapat saya pribadi, jelas tidak salah. Sangat tidak salah.
Orang traveling, liburan, piknik, darmawisata, melancong, atau apa pun itu istilahnya, esensinya memang untuk mencari kesenangan. Dan kesenangan itu hal yang relatif sifatnya.
Kalau bagi banyak orang orang, kesenangan itu sudah bisa didapat cukup dengan berfoto di tempat-tempat terkenal untuk kemudian bisa diposting di sosial media, lha ngapain harus repot-repot melakukan hal yang lain?
Boleh jadi, para pelancong itu justru tidak akan bisa mendapatkan kesenangan bila mereka harus belajar tentang tempat yang mereka kunjungi, harus memaksakan diri menikmati kuliner daerah setempat yang belum tentu mereka sukai, atau menghabiskan waktu dengan menjalani kehidupan bersama warga lokal yang belum tentu cocok dengan kultur kehidupan mereka.
Semua orang saya kira punya kesenangannya masing-masing.
Travel blogger atau penulis catatan perjalanan boleh jadi baru merasa senang dan puas saat bisa menjelajah tempat baru secara total. Namun bagi orang awam, tentu tak bisa disamakan, sebab memang latar belakangnya beda. Ada yang uangnya terbatas sehingga tak mungkin bisa menjelajah dengan leluasa. Ada yang jatah liburannya hanya beberapa hari sehingga tak bisa berlama-lama di tempat wisata yang dikunjungi. Ada yang punya keterbatasan-keterbatasan lain yang tak memungkinkan dirinya untuk bisa menjelajah dengan total.
Traveling yang baik mungkin saja adalah traveling yang mampu membuat si traveler belajar akan hal-hal baru di tempat yang baru. Namun, terkadang kita lupa, bahwa banyak orang traveling justru karena sudah sumpek belajar dan bekerja dengan kesehariannya.
Traveling menjadi sarana eskapis bagi mereka untuk melarikan diri dari kesibukan-kesibukan yang selama ini terus menghantam kesibukan mereka.
Mosok sudah lama mikir kerjaan, ealah pas cuti buat liburan, masih disuruh belajar. Hidup kok ya kejam betul.
Kita mungkin punya perasaan semacam betapa menyenangkannya menjadi seorang Windy Ariestanty yang selalu bisa mendapatkan kisah-kisah dan pengalaman menarik di berbagai tempat yang ia kunjungi, juga menyenangkan sekali rasanya menjadi seorang Alm Pak Bondan Winarno, yang selalu punya ketertarikan khusus untuk mencoba sensasi kuliner di berbagai daerah yang ia datangi.
Tapi, ada satu hal yang seharusnya kita sadari betul: tidak semua orang harus jadi Pak Bondan atau Windy Ariestanty.