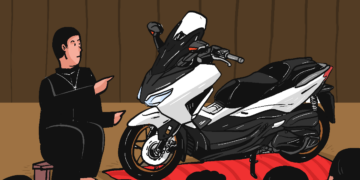MOJOK.CO – Selamat Natal untuk warga Katolik Dharmasraya dari saya umat Katolik Jogja yang masih sering datang terlambat misa pagi karena bangun kesiangan. Salam damai, berkah dalem.
Sudah menjadi “ketetapan” di mana saja kalau yang namanya minoritas akan terjepit. Agama apa saja, kalau jadi minoritas, harus punya kemampuan untuk merasa. Sedihnya, karena “merasa teraniaya”, mereka lalu berlindung di balik sebuah istilah bernama intoleransi. Agama tidak pernah jadi masalah, melainkan manusianya.
Kemampuan merasa bukan sebuah kemampuan yang bisa dikuasai dengan mudah. Dan sekali lagi, tolong jangan bawa-bawa agama dulu. Kemampuan merasa adalah proses mengasah diri sebagai makhluk sosial, tanpa memandang agama yang dipercaya.
Natal tidak boleh dirayakan di Darmasraya, Sumatera Barat. Kalimat itu yang banyak dipakai oleh media dan diamini oleh begitu banyak orang Indonesia. Keprihatinan menguar. Tangis kasihan membanjiri mata. Namun, pernahkah kita mencoba memahami kenapa Natal tidak boleh dirayakan di Dharmasraya?
Kampung Baru, Nagari Sikabau, Kabupaten Dharmasraya adalah kampung warga transmigrasi tahun 1965. Pemerintah dan tokoh adat membuat kesepakatan dalam program transmigrasi ini, yaitu peserta transmigrasi harus beragama Islam, kalau ingin menjual tanah harus ke warga setempat, harus mengaku induk (menjadi bagian salah satu suku di nagari itu) dan mengikuti aturan adat yang berlaku.
Kenapa peserta harus beragama Islam? Namanya saja aturan adat yang berlaku. Sebuah kenyataan sosial yang perlu dipahami sebelum kita berteriak soal intoleransi dan Natal yang tidak boleh dirayakan.
Pendatang, yang mana peserta transmigrasi, diberi lahan secara gratis, dibuatkan rumah oleh warga, dan disumbang bahan makanan sembari menunggu panen tiba. Pemerintah hanya mengantar warga transmigran ke sana. Terkesan diabaikan, warga asli mengulurkan tangan untuk membantu. Tidak saling mengenal, berbeda latar belakang, tapi mau membantu. Bukankah itu esensi hidup sosial?
Sekitar tahun 1980, beberapa warga transmigran pulang ke Pulau Jawa. Kacaunya, mereka menjual lahan ke warga non-muslim dari luar daerah. Perayaan agama lain mulai marak dan Natal salah satunya.
Padahal, di Dharmasraya sudah disepakati aturan kalau tanah hanya boleh dijual ke warga asli. Sejak saat itu, terjadi beberapa kali gesekan, yang awalnya dari pelanggaran adat yang dilakukan beberapa warga transmigran dan mereka yang merayakan hari besar keagamaan seperti Natal.
Setelah gesekan mereda, sebuah kesepakatan baru disusun. Warga non-muslim boleh beribadah, tetapi di rumah masing-masing. Sayangnya, pada tahun 2016 hingga 2017, warga non-muslim mengundang warga dari luar Dharmasraya untuk beribadah bersama, salah satunya Natal. Warga setempat tidak bisa menerima tindakan itu.
Haji Ahmad, warga setempat yang menuliskan sejarah Dharmasraya di Twitter juga menjelaskan kalau masalah ini sudah menjadi bola panas di media. Kalimat Natal dilarang di Dharmasraya menjadi narasi utama. Padahal tidak sepenuhnya begitu. Pemerintah setempat bersedia menyediakan kendaraan untuk umat Katolik yang mau merayakan Natal bersama.
LARANGAN NATAL DI DHARMASRAYA
Sebuah trhead dari sudut pandang Anak Dharmasraya.
Saya mau berbagi soal latar pelarangan perayaan natal oleh tokoh adat dan warga di satu desa di Dharmasraya. Ada persiteruan hukum adat dan hukum negara dalam kasus ini.— Haji Ahmad (@Arj_Nusantara) December 20, 2019
Sekitar 10 hingga 20 menit berkendara dari rumah mereka, ada titik-titik aman untuk merayakan Natal di Dharmasraya. Namun, umat Katolik yang berjumlah sembilan KK ini menolak. Mereka menolak dan ingin merayakan Natal di rumah masing-masing saja.
Hukum adat, biasanya lebih tua dibandingkan hukum yang berlaku di sebuah negara. Hukum adat ini juga biasanya saling melekat dengan ajaran agama. Misalnya di Bali, ketika Nyepi, umat Islam juga tidak keluar dari rumah sebagai bentuk penghormatan kepada perayaan agama Hindu. Dharmasraya dibangun dengan hukum adat (dan Islam) sebagai dasar. Sebuah aturan yang tidak bisa ditabrak oleh perkembangan zaman atau pemahaman akan toleransi.
Ketika umat Katolik tidak boleh menggelar perayaan Natal di daerahnya, pemerintah berusaha menyediakan kendaraan bagi mereka. Pemerintah mengusahakan Natal bisa dirayakan, tetapi di tempat yang sudah ditentukan. Saya tidak tahu istilah yang tepat untuk menggambarkan niat pemerintah setempat selain tenggang rasa.
Pemerintah setempat tentu tidak bisa menabrak aturan adat demi sembilan KK yang ingin merayakan Natal. Yang bisa mereka lakukan adalah menjaga perasaan umat Katolik yang ingin merayakan Natal dengan menyediakan kendaraan. Toh, apa salahnya merayakan Natal, misalnya, di gereja atau tempat lain bersama jemaat yang berbeda? Sama-sama mencintai Tuhan Yesus, kan? Sama-sama menjunjung hukum tertinggi bernama Hukum Cinta Kasih, kan?
Menjadi minoritas memang bukan status yang mudah untuk dikunyah. Yang bisa dan pertama dilakukan adalah menguasai ilmu merasa.
Terkadang, konflik terjadi bukan karena agama atau kepercayaannya. Konflik terjadi karena manusia yang melanggar kesepakatan bersama dan tidak mengindahkan aturan atas nama toleransi. Misalnya ingin merayakan Natal di lingkungan padahal adat sudah melarang.
Toleransi itu apa, sih? Toleransi itu mengizinkan jalan di depan rumah ditutup oleh tetangga untuk acara sembayangan, untuk ibadah mengundang banyak orang. Toleransi adalah menyediakan kendaraan bagi umat Katolik yang mau merayakan Natal. Toleransi bukan lantas menerobos adat yang sudah mengakar. Ini ilmu merasa.
Yang terjadi kemudian mayoritas terlihat selalu salah karena menang jumlah. Minoritas terlihat selalu menderita karena kalah jumlah. Padahal, hidup bertetangga bukan soal jumlah. Hidup bertetangga adalah usaha saling menghargai kesepakatan bersama. Kalau mau kuat-kuatan soal jumlah itu pemilu namanya.
Kamu bisa kok membalik-balik keadaan. Misalnya Dharmasraya adalah sebuah daerah dengan dasar adat dan agama Katolik atau Kristen atau agama apa saja. Umat Islam hanya boleh salat Ied di tempat yang disepakati. Disediakan kendaraan untuk menuju ke sana. Siapa yang menyediakan? Umat Katolik yang mayoritas. Umat Islam sedih, menolak, dan salat Ied di rumah masing-masing. Media mengabarkan: Umat Islam dilarang salat Ied di Dharmasraya.
Sama saja. Tidak ada ilmu merasa di sana. Agama, yang jika diperas akan keluar sari-sari positif, seperti menjadi sumbu konflik. Padahal, semuanya berasal dari manusia yang gagal merasa.
Sama kok seperti kehidupan di sebuah kampung. Ketika ada seorang bapak yang diizinkan tidak piket kerja bakti di Minggu pagi. Warga tahu kalau si bapak biasanya beribadah di misa Minggu pagi. Ini namanya ilmu merasa. Si bapak juga tahu kalau warga sudah pengertian. Dia membalasnya dengan cara berbeda. Misalnya dengan menyediakan gula dan teh sebagai konsumsi kerja bakti. Ini namanya ilmu merasa.
Menjadi merayakan Natal orang Katolik memang tidak mudah. Agama ini tidak pernah bosan untuk bertanya kepada umatnya: “Kamu kuat nggak memikul salib Kristus?”
Katolik adalah soal devosi, soal penyerahan diri kepada ajaran Tuhan. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk mendobrak adat. Tuhan mengajarkan kasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri.
Selamat Natal untuk warga Katolik Dharmasraya dari saya umat Katolik Jogja yang masih sering datang terlambat misa pagi karena bangun kesiangan. Salam damai, berkah dalem.
BACA JUGA Yesus Bungee Jumping: Penistaan Agama atau Cara Katolik Bercanda? atau tulisan Yamadipati Seno lainnya.