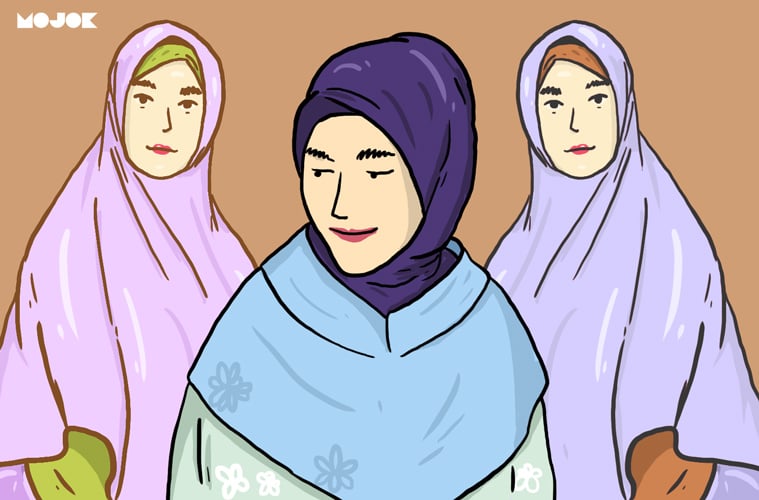Lebaran kemarin, di media sosial, banyak yang baper dengan aneka pertanyaan-pertanyaan menyebalkan dari sanak, saudara, dan kerabat. Pertanyaan yang, dianggap terlalu mencampuri urusan pribadi padahal sebenarnya biasa saja dan sama sekali tidak perlu dirisaukan.
Kapan nikah, kapan lulus, kok dari dulu nggak naik pangkat, sekarang kok tambah subur saja badannya, kok masih sendirian aja, dsb, dsb.
Keluarga, utamanya yang sudah lama tak berjumpa fisik, sering kali memang kehabisan bahan untuk berbasa-basi, sehingga pertanyaan-pertanyaan model begitu kerap menjadi ban serep yang paling ampuh.
Sayang, beberapa orang mungkin memang terlalu perasa atau memang tidak terlalu bisa menangkap hal tersebut.
Di facebook, tak sedikit yang menuliskan rasa sebalnya karena oleh tante-tantenya ditanya “Kapan nikah?”
Dengan kejam (untuk tidak menyebutnya bengis), mereka menganggap tante mereka tak punya etika, menyebalkan, dan aneka sematan buruk lainnya.
Padahal jika dilihat dari sudut yang berbeda, pertanyaan itu, di luar bahan basa-basi, bisa juga merupakan salah satu bentuk verbal kepedulian mereka pada keponakan-keponakannya.
Dengan bertanya kapan nikah, itu menjadi bukti bahwa mereka ikut bersuka-cita kalau kita menikah.
Tapi kan menikah itu urusan kita sendiri, bukan urusan mereka?
Urusan kita sendiri gundulmu. Tantemu, bulikmu, paklikmu, budemu, embahmu, kerabat dekatmu, semua berhak punya urusan pada pernikahanmu. Mereka orang pertama yang bakal sambatan, yang bakal cawe-cawe, yang bakal menyumbang tenaga dan (mungkin) harta paling besar demi lancarnya acara resepsimu.
Orang-orang terdekatmu, keluargamu, kerabatmu, selalu punya andil yang besar pada hidupmu.
Dulu saya punya bulik yang sering sekali bertanya soal sekolah saya. Nilai saya bagus apa tidak, di sekolah dapat ranking berapa? Dsb, dsb, dsb.
Pada titik tertentu, pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin terlihat sangat mengganggu, utamanya jika saya ternyata adalah murid yang goblok dengan lebih banyak nilai di raport yang berwarna merah ketimbang biru.
Namun belakangan baru saya ketahui, bulik saya itulah yang, dulu saat orangtua saya kesulitan membayar uang sekolah, ikut membantu membayarkan uang sekolah saya. Dia bahkan pernah menjual ali-ali emas miliknya demi meminjami orangtua saya uang untuk saya masuk ke SMA.
Dengan fakta tersebut, kalau kemudian saya menganggap pertanyaan-pertanyaan bulik saya adalah pertanyaan yang tidak sepantasnya, maka betapa kurangajarnya saya.
Keluarga adalah tembok terdekat dalam lingkaran kehidupan kita. Jangan pernah membangun jarak dan perasaan-perasaan yang tidak perlu.
Di hari lebaran, kebersamaan dengan keluarga jauh lebih mahal ketimbang sekadar rasa baper oleh pertanyaan-pertanyaan yang dianggap membosankan dan menyebalkan itu.
Percayalah, mereka bukan sekadar bertanya kapan nikah, lebih dari itu, mereka juga berharap dan bahkan ikut mendoakannya.
Pertanyaan seputar “kapan nikah” sejatinya juga tak melulu monopoli lingkungan keluarga.
Beberapa waktu yang lalu, saya disuruh mengisi kelas menulis di SMP saya dulu. Di sana, sambil mengisi kelas menulis, saya tentu saja klangenan sama sekolah dan guru-guru. Ada banyak guru di jaman saya yang belum pensiun dan masih tetap mengajar sampai sekarang. Dan ya, pertanyaan soal rabi sudah hampir pasti ditanyakan oleh para guru saya itu.
“Wah, Agus sekarang sudah sukses, sudah jadi penulis. Trus sudah nikah apa belum?” kata Bu Rochalimah, guru agama saya dulu. Tentu saja saya menjawab belum. Dan pertanyaan susulan pun langsung meluncur, “Lha trus kapan? sudah umur lho!”
Guru-guru yang lain tak jauh berbeda: menanyakan soal nikah.
Tak hanya guru, kalau sowan kiai pun biasanya begitu.
Di Magelang, kalau ndilalah saya datang di majlis ndengerin ceramahnya Gus Yusuf dan kemudian minta salim, belio pasti nggak pernah luput buat nanya, “Kowe kapan le meh rabi?”
Biasanya ya saya jawab, “Nyuwun dongane nggih, Gus.”
Dari situ, saya kemudian merenung sejenak. Betapa saya bakal begitu menderita kalau saya masuk dalam golongan yang anti pertanyaan kapan nikah. Sebab saya bakal takut datang ketemu sama guru sekolah. Takut salim sama kiai. Dan takut silaturahmi sama keluarga sendiri.
Saya tentu tak bisa bilang bahwa pertanyaan kapan rabi adalah pertanyaan yang tidak beretika. Sebab, bagaimana mungkin guru-guru saya, Pak kiai, atau mbah-mbah dan tante-tante saya tidak punya etika.
Jangan-jangan memang kita, generasi milenial, yang punya standar terlalu tinggi soal etika.
Ditanya sedikit soal “Kapan rabi” langsung teriak “Dasar nggak punya empati!”