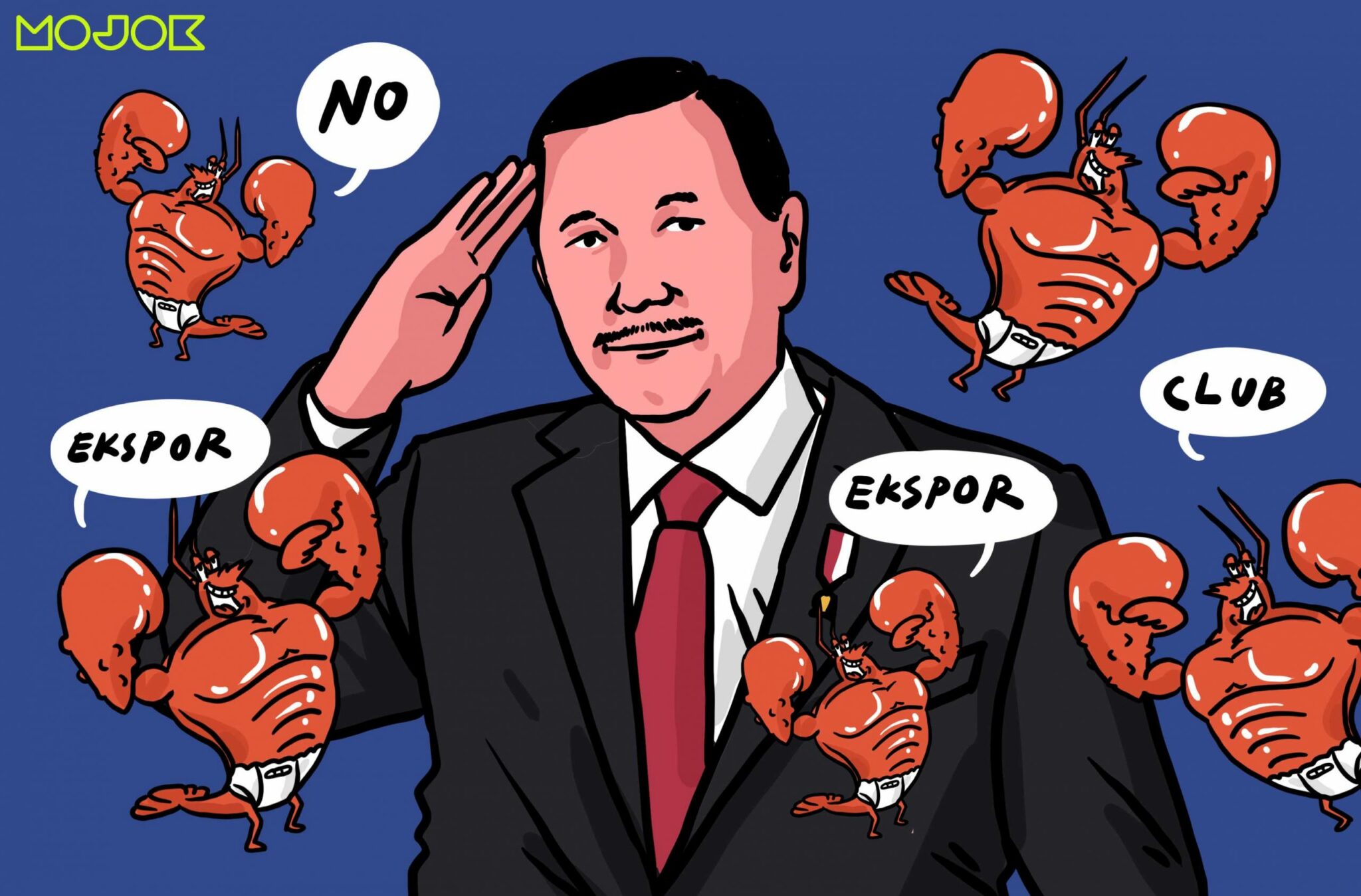MOJOK.CO – Makan lobster mungkin adalah aktivitas yang menyenangkan, namun tidak bagi orang yang belum pernah melakukannya.
Sebagai orang yang lahir dan besar di gunung, saya memang sangat jarang makan sea food alias makanan laut. Sedari kecil, saya terbiasa dengan makanan-makanan gunung, budaya tubuh saya adalah budaya gunung.
Satu-satunya makanan laut yang boleh dibilang sering saya santap adalah gereh pindang alias ikan asin. Itu pun rasanya agak aneh kalau disebut sebagai makanan laut, sebab walau ia memang berasal dari laut, namun saya tak pernah menemukannya di buku menu restoran makanan laut mana pun.
Ketidakbiasaan makan makanan laut itulah yang kemudian membuat saya jarang sekali mau kalau diajak makan ke restoran makanan laut. Bagi saya, pecel lele, yang tentu saja makanan darat itu, jauh lebih nikmat untuk disantap ketimbang ikan laut bakar yang, entah kenapa, di mulut saya rasanya ya begitu-begitu saja.
Kelak, akan ada banyak keadaan yang kemudian memaksa saya untuk terbiasa makan makanan laut. Pekerjaan seminggu penuh di Nusa Tenggara Barat beberapa waktu yang lalu adalah salah satunya.
Saya memang sedang mengerjakan sebuah proyek penulisan buku di Lombok dan Sumbawa bersama beberapa kawan. Dan di sana, kami banyak dijamu dengan aneka hidangan makanan laut oleh orang-orang yang menjadi objek penulisan buku yang sedang kami kerjakan.
Salah satu yang paling saya ingat adalah ketika kami satu rombongan dijamu oleh Sekda Lombok Timur untuk makan makanan laut di sebuah rumah makan apung tengah laut di wilayah Kecamatan Keruak, Lombok Timur.
Di rumah makan apung tersebut, kami dijamu dengan menu yang sungguh membikin kami satu rombongan, kecuali saya, terbelalak bahagia: olahan rajungan dan lobster yang disajikan dalam ukuran yang sangat besar dan cenderung tidak manusiawi.
Hanya butuh waktu sepersekian detik bagi kawan-kawan saya untuk mengagumi ukuran rajungan dan lobster yang disajikan sebelum akhirnya mereka menyantapnya secara bar-bar dengan selera yang paling paripurna.
Saya sendiri, adalah pihak yang paling bingung saat itu. Saya tak terbiasa (bahkan seingat saya tak pernah) makan lobster, apalagi rajungan. Tentu saja saya punya kecakapan untuk makan atau ngremus udang goreng, namun makan lobster adalah hal yang lain. Saya bahkan tak tahu, bagian tubuh lobster yang mana yang harus saya blejeti agar saya bisa mendapatkan sesuatu yang bisa saya makan. Sejak dulu, saya memang punya jarak dengan makhluk yang tubuhnya seperti hasil hubungan seksual threesome antara udang, kalajengking, dan ketonggeng itu.
Adalah tak mungkin bagi saya untuk tidak ikut menyantap lobster ini, saya bakal menyakiti perasaan tuan rumah. Maka, mau tak mau, saya pun harus mengadakan pengamatan kecil-kecilan sebelum saya bisa menyantap lobster yang sudah tersaji di depan saya. Saya amati dengan seksama bagaimana kawan di depan saya membabat “udang” raksasa ini.
“Oh, ternyata begitu,” batin saya.
Saya pun menyantap lobster berukuran besar di depan saya dengan cara persis seperti yang dilakukan oleh kawan saya.
Rasanya? ternyata enak. Yah, walau tentu saja masih kalah enak enak dengan sayur jengkol buatan emak saya di rumah.
Saya tak bisa menghabiskan banyak lobster. Saya hitung, saya hanya kuat menyantap satu setengah lobster. Itu pun sudah cukup membuat saya kenyang. Saya bahkan tak sempat mencoba rajungan. Selain karena saya merasa sudah cukup, saya juga sudah malas untuk melakukan pengamatan kecil-kecilan lagi.
Satu setengah lobster itu ternyata sudah cukup untuk memberikan efek yang besar pada tubuh saya.
Dalam perjalanan pulang menuju darat dari rumah makan apung tersebut, kepala saya terasa pusing. Nggliyeng.
Kata kawan saya, kemungkinan itu karena efek kolesterol sebab saya memang sebelumnya tak pernah makan lobster dalam porsi besar sebelumnya.
“Aku cuma makan satu setengah, lho. Kamu yang makan lebih banyak saja nggak papa, kok.”
“Iya, tapi sebelumnya kamu nggak pernah sebanyak itu, kan? Tubuhmu njeglek itu, nggak siap,” terang kawan saya.
“Ya, mungkin. Ini memang pertama kalinya aku makan lobster, apalagi sebesar itu.”
Dengan kepala yang nggliyeng itu, saya hanya bisa tiduran di perahu. Padahal sebelumnya, saya sudah berniat untuk saya berdiri di atas perahu lalu difoto dari belakang seperti poster film “Life of Pi” itu.
“Lobster-lobster gede yang tadi kita makan itu harganya berapaan, ya?” tanya saya iseng pada kawan saya yang tampaknya sudah terbiasa makan lobster.
“Wah, kalau yang tadi itu ya jelas mahal, itu tadi kualitasnya super.”
“Per porsi satu juta nyampai nggak, ya?”
“Yo jelas nyampai. Bahkan mungkin bisa dua juta.”
Demi mendengar jawaban tersebut, tentu saja saya terbelalak. Saya lemas seketika. Saya tak menyangka kalau lobster besar yang saya santap dan bikin kepala saya sampai nggliyeng itu harganya bisa semahal itu.
Diam-diam, saya meyakini, bahwa kepala saya yang nggliyeng itu bukan karena tubuh saya yang tidak siap dengan kandungan kolesterol yang tinggi pada lobster, namun itu semata karena mental saya yang belum siap dengan makanan berharga mahal.
Lamat-lamat, saya membayangkan betapa nikmatnya gereh pindang lengkap dengan sambal kosek buatan istri saya yang harganya tak lebih dari sepuluh ribu rupiah per keranjangnya itu.
BACA JUGA Begini Rasanya Menjadi Orang yang Tak Pernah Bosan Makan Makanan yang Sama Terus-Menerus dan tulisan Agus Mulyadi lainnya.