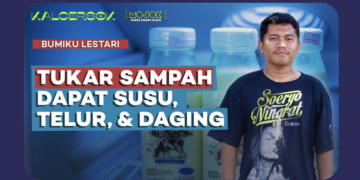MOJOK.CO – Tak adanya manusia dalam rantai makanan yang diajarkan di sekolah mengundang tanya. Padahal peranannya penting. Ia bisa jadi sosok penentu dalam rantai tersebut.
Sebagai manusia yang dibesarkan oleh sekolah selama bertahun-tahun, saya merasa ada yang janggal dengan aturan “Dilarang Membuang Sampah Sembarangan!”. Aturan itu mungkin banyak orang yang hafal, tapi jarang yang menerapkannya dengan sungguh-sungguh. Kalau dipikir-pikir lagi, larangan tersebut tidak ada bedanya dengan mitos rumah angker yang seringkali diabaikan terutama ketika suasana begitu meriah, seperti yang terjadi malam itu.
Pada suatu malam, lapangan dekat rumah saya yang terkenal gelap dan wingit menjadi meriah oleh pesta rakyat jathilan menyambut Ramadan. Biasanya, tempat itu selalu gelap, pun di siang hari. Rumpun bambu, pohon melinjo, pohon jati, dan semak belukar begitu lebat mengelilingi lapangan. Hanya ada satu rumah yang ada di dekat sana, selebihnya (mungkin) dihuni genderuwo dan kerabat-kerabatnya. Biasanya, kami, manusia, hanya berani beraktivitas di sekitar lapangan sebelum Maghrib tiba. Sesudahnya, boro-boro. Lewat di sampingnya saja, bulu kuduk sudah meremang.
Akan tetapi, pada malam itu banyak orang berdatangan melihat pertunjukan di lapangan. Hampir semua mengendarai sepeda motor, tapi ada pula yang berjalan kaki. Pedagang jajanan “masa kini” berjajar. Jangan harap ada kacang rebus atau jagung rebus, kuno sekali. Hampir semua pedagang menjual burger, sosis, tempura, cumi-cumi bakar, pizza, es teh dan segala macam minuman manis boba yang menjadi idola anak muda. Kehadiran beratus-ratus manusia di saat bersamaan seperti sedang menegaskan status quo terhadap lapangan dari para penghuni malam di sana. Begitulah manusia, berani kalau beramai-ramai.
Genderuwo yang akan menyapu sampah plastik kita?
Usai acara, seperti diduga sedari awal, sampah berserakan di mana-mana mulai di selokan, pinggir jalan, pojokan kebun, dan tengah lapangan. Tak terurus, diabaikan begitu saja. Seperti pepatah: gajah mati tinggalkan gading (karena dijual ke pasar gelap), harimau mati tinggalkan belang (jadi karpet lantai rumah para jutawan), manusia mati tinggalkan sampah plastik (tertimbun tak terurai ratusan tahun).
Semakin banyak orang berdatangan, semakin banyak pula yang lempar tanggungjawab untuk mengurus sampah-sampah itu. Sekalipun acara itu terselenggara di tempat seram, kediaman genderuwo dan kerabat-kerabatnya, sampah-sampah plastik itu tetap melimpah. Sedari kecil, kita diajari bahwa manusia adalah khalifah di bumi. Apapun di sekitar manusia, ada untuk melayani kebutuhan manusia. Termasuk di antaranya, para pengunjung keramaian itu yang mungkin mengira genderuwo akan bergotong royong menyapu sampah-sampah plastik mereka.
Apa yang tidak diajarkan di sekolah?
Apa yang sebenarnya tidak diajarkan kepada kita, manusia, sampai begitu entengnya membuang sampah di mana-mana? Saat merenungi pertanyaan ini, saya membuka-buka isi kepala, mengingat-ingat apa yang saya peroleh selama 18 tahun bersekolah (selain privilege karier sebagai pekerja kerah putih)?
Saya melongo seperti Patrick teman Spongebob dalam rumah batunya di Bikini Bottom. Kosong. Selayaknya itu lah sekolah. Jarak pendidikan formal pada kehidupan sehari-hari terasa jauh. Apa yang kita dapat sebagai generasi terpelajar ialah mewajarkan serangkaian perusakan berdalih pemanfaatan, dimulai dari pengabaian kecil seperti membuang sampah sembarangan. Klise, tetapi, kita tidak pernah benar-benar bertanya kenapa?
Pertama, mungkin kita bisa berjalan mundur ke-abad 15 saat revolusi ilmiah terjadi, ketika Rene Descartes mencetuskan “Cogito Ergo Sum” (Aku berpikir maka aku ada). Akal manusia berada di atas segalanya. Ia menandai perubahan cara pandang tentang manusia dan semesta alam, dari “alam sebagai kehidupan organis di mana manusia menjadi bagian di dalamnya” menjadi “alam sebagai sumber daya, alat produksi dan mesin akumulasi keuntungan yang direkayasa secara ilmiah.”
Tidak heran, cara pandang ini membuat kita kepalang berani membuang sampah ke tempat-tempat yang seharusnya dijaga. Mungkin, kita tidak tahu bahwa sampah plastik tidak bisa terurai oleh tumpukan daun bambu. Padahal kompos daun bambu mengandung banyak fosfor dan kalium, bisa menyuburkan daun dan mencegah penyakit busuk akar. Tetapi apa daya, kita tidak pernah diajarkan hal sesederhana itu dalam pendidikan dasar kita. Secara normatif, sekolah mengajak untuk tidak membuang sampah sembarangan. Namun, tidak pernah menjelaskan secara empiris, seberapa bahaya pengaruh mikroplastik pada daur kehidupan kita ini.
Kenapa tidak ada manusia di gambaran rantai makanan?
Kedua, pernahkah terpikir dalam benak kita? Saat guru IPA atau Biologi mengajarkan materi tentang rantai makanan, buku-buku diktat tidak memasukkan gambar “manusia” di dalamnya. Gambar-gambar yang tersedia selalu tentang hewan (invertebrata dan vertebrata) dan tanaman, tetapi tidak ada manusia sebagai bagian dari primata omnivora. Misalnya, rantai makanan di sawah terdiri dari padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang. Luput kehadiran manusia yang membuat ekologi sawah, memanen padi. Kita merasa lebih berderajat jika memasukkannya sebagai daur produksi sawah dan rantai komoditas padi. Semua itu seolah berada di luar rantai makanan.
Padahal manusia merupakan predator paling merusak dalam rantai makanan itu. Saat, manusia merasa terancam dengan ular, kita memburu dan membasminya. Kita lupa bahwa ular predator tikus. Lalu saat terancam oleh wabah tikus, kita memilih untuk menyemprot gas beracun ke lubang-lubang tanah tempat tikus hidup. Meski tanpa disadari, di saat bersamaan juga menghabisi mikroba yang berguna bagi proses penguraian.
Pandemi yang melanda berbagai penjuru dunia menjadi pengingat bahwa manusia merupakan bagian dari rantai makanan. Manusia sebagai predator besar bisa dipunahkan oleh virus yang tidak terlihat.
Ketiga, saat meniadakan manusia di dalam rantai makanan, saat itu pula manusia lupa untuk merawat basisnya melanjutkan kehidupan. Secara tidak sadar, pendidikan menjauhkan kita pada kerja “merawat kehidupan”, semacam tidak mengonsumsi plastik berlebihan agar tidak membuangnya secara sia-sia. Pendidikan hanya mengajarkan kita merekayasa teknologi yang mampu melipatgandakan produktivitas kerja memproduksi barang-barang. Pada akhirnya, barang-barang itu dikonsumsi massal dan sampahnya seolah menjadi hal alamiah yang harus bumi terima.
Penulis: Ciptaningrat Larastiti
Editor: Purnawan Setyo Adi