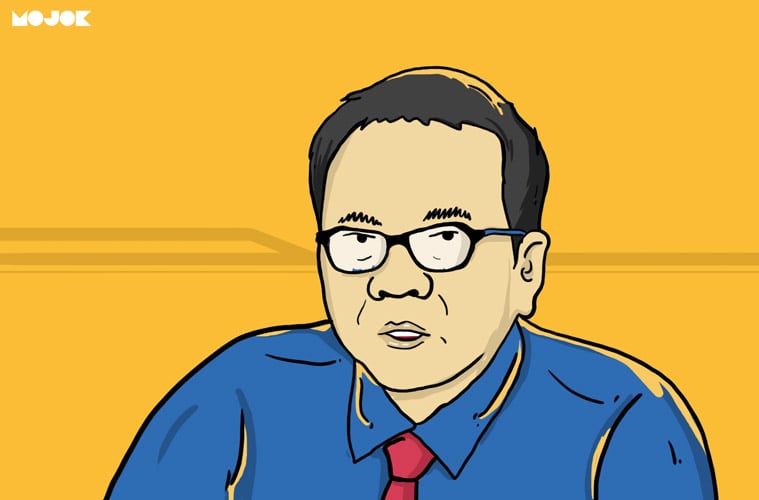Seluruh orang penikmat tengkleng menjadi sangat berduka. Pasalnya, Bu Edi meninggal dunia kemarin. Siapa beliau? Kalau pernah makan tengkleng Pasar Klewer, Solo, pasti tahu beliau. Dari tangannya, berbongkah-bongkah tulang kambing yang sepintas tak berharga, disulap menjadi makanan yang membuat orang lupa kolestrol.
Saya masih ingat sewaktu makan tengkleng Bu Edi pertama kali. Matahari seperti sejengkal di atas kepala. Para pelanggan antri. Pelayan membagi nasi dengan porsi yang sama persis. Bu Edi menyiramkan kuah tengkleng yang berwarna kuning keruh itu. Memberi beberapa potong tulang dengan sedikit daging yang menempel. Yang makan mulai usia muda, sampai mereka yang tak lama lagi dipanggil Izrail. Kolestrol sudah tak lagi dipikirkan. Kalau tak dapat tempat duduk, para pelanggan rela duduk ndeprok di manapun. Trotoar, bahu jalan, bahkan hingga ke pos polisi di sebelah warung Bu Edi. Makannya pun ora ngurus manner. Ngrakoti balung. Bunyi sluuurrrp terdengar kencang dan riang. Menyenangkan sekali.
Tengkleng itu selalu mengingatkan saya betapa cerdas dan inovatifnya masyarakat Indonesia perihal masakan. Sejarah kuliner Indonesia punya banyak cerita olah bahan yang apik. Dari yang awalnya tak berharga, menjadi makanan enak. Maklum, di posisi kejepit orang biasanya jadi kreatif.
Saat dijajah Belanda, semua kopi dari Indonesia diekspor ke Eropa. Para petani tak bisa minum kopi yang mereka tanam dan rawat. Karena penasaran ingin coba minum kopi, para petani kopi Minang memutar otak. Hasilnya adalah kopi kawa, minuman yang dibuat dari rebusan daun kopi.
Tengkleng juga demikian. Bahan baku tengkleng adalah tulang belulang kambing. Tentu karena dulu yang bisa menyantap daging kambing adalah para priyayi dan meneer. Maka diolahlah tulang belulang agar bisa disantap.
Begitu pula dengan kisah sate kere. Dari namanya saja, makanan itu adalah makanan orang kere. Mlarat. Karena tak bisa makan sate daging, maka lagi-lagi orang Solo mengolah tempe gembus untuk jadi sate.
Tapi ternyata tidak cuma orang Indonesia yang punya sejarah serupa. Di belahan dunia Barat, kisah paling masyhur adalah lobster. Udang karang yang kini berharga mahal itu dulu adalah makanan kaum papa, rakyat jelata, atau para narapidana. Bahkan dulu lobster sempat dianggap sampah. Tak ada yang mau makan. Penyebabnya karena bentuknya yang buruk rupa, sehingga dijuluki “kecoak laut”.
Pada tahun 1622, Gubernur Plymouth mendatangkan para pekerja kebun untuk menggarap tanah negara. Sebelum memulai kerja, sang Gubernur lebih dulu meminta maaf pada para pekerja. “Maaf karena kami cuma bisa menyediakan lobster, tanpa roti atau makanan lain.” Untung saja para pekerja kebun itu sabar.
Di Massachusetts, para pekerja kehilangan kesabaran, marah besar dan memberontak. Mereka demo. Tuntutannya adalah: kurangi jatah makan lobster, maksimal tiga kali seminggu. Rupanya mereka muak dengan lobster yang dihidangkan setiap hari.
Bahkan di Amerika Serikat titimangsa 1940-an, lobster masih dijual sangat murah. Banyak yang dalam bentuk kalengan. Dan, maaf maaf saja nih, yang biasa makan lobster adalah kucing.
Tapi sejarah tentu bisa berbalik. Tujuh dekade kemudian, kita bisa melihat seorang Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta merengek minta kenaikan uang perjalanan dinas. Menurut anggota DPRD DKI yang terhormat itu, jatah uang makan sekarang yang “hanya” Rp 470 ribu sangatlah kurang.
“Kalau uang makan masuk ke Rp 470 ribu itu, kami kalau mau makan lobster enggak bisa,” katanya.
Saya yakin bliyo tuna sejarah. Tak tahu kalau lobster dulu adalah makanan orang miskin. Bahkan dibuang-buang untuk makanan kucing. Tapi saya mafhum, anggota DPRD tentu lebih sibuk memikirkan daerahnya ketimbang ngurus hal sepele macam sejarah lobster. Kalau saya sih pembuang waktu bersertifikat yang tesisnya tak kelar-kelar, makanya sempat Googling hal-hal kurang berfaedah.
Selain tuna sejarah, saya kira anggota DPRD DKI itu juga belagu. Saya berani bertaruh kalau ia sebenarnya tak bisa menikmati lobster. Sebab lidahnya, sama seperti kita semua, terbiasa dengan cita rasa Indonesia yang kaya bumbu.
Jelek-jelek gini, saya pernah makan lobster. Pertama kali makan, rasa daging lobster teramat biasa. Kedua kalinya, rasa manis alami mulai muncul. Setelah beberapa kali makan, saya tidak terlalu terkesan. Karena sebetulnya, lobster mengandalkan rasa manis alamiahnya.
Di Barat, lobster dimasak dengan minimalis. Hanya direbus di air garam. Udah gitu doang. Tidak pakai bumbu macam-macam. Paling-paling ada saus pendamping. Yang paling umum mentega cair untuk cocolan. Karena mengandalkan rasa alaminya, daging lobster bisa kehilangan senjata andalan kalau tidak segera dimasak setelah ditangkap.
Lha kalau di Indonesia, mana enak makan hidangan laut dengan sedikit bumbu gitu? Ya kudu dengan lada hitam, saus asam manis, atau saus tiram. Lidah saya yang Nusantara ini sudah terlanjur terbiasa dibanjur masakan Indonesia yang kaya bumbu.
Karena tuna sejarah dan tuna rasa itu, sebaiknya Pak Anggota DPRD DKI yang terhormat itu gak usah belagu mau makan lobster. Malu-maluin. Bisa diketawain orang se-Indonesia. Padahal ada banyak makanan laut yang enak bukan buatan.
Kalau soal itu, nanti saya ajak ke Sea Food 45 Fatmawati langganan saya deh. Udangnya gede-gede walau bukan lobster. Dimasak bumbu aneka macam. Kalau uang dinas Bapak yang sekarang enggak cukup, biar saya yang traktir.