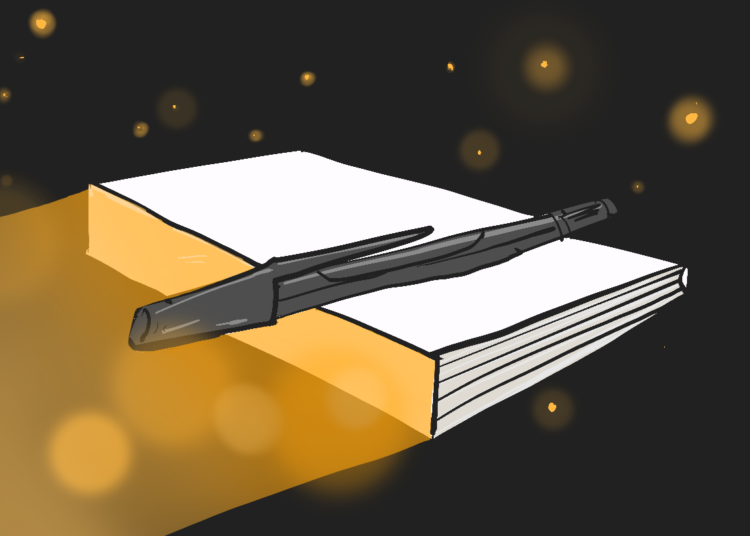Sebelum “menunjuk hidung” satu sama lain, soal siapa yang paling bertanggung jawab atas kematian YBS, siswa kelas 4 SD di NTT, agaknya kita perlu merenung bersama. Tak ada harga sepadan untuk mengembalikan nyawa seseorang. Pada akhirnya, pesan terakhir YBS menampar kita semua yang gagal melindungi hak-hak anak. Terutama mereka yang mengalami kekerasan.
Disclaimer: Tulisan ini tidak bermaksud menginspirasi siapapun untuk memiliki rencana mengakhiri hidup. Setiap masalah selalu ada jalan keluarnya, tapi bunuh diri bukan salah satunya. Selalu ada jalan lain untuk membuat hidup menjadi bermakna. Bagi pembaca yang merasakan gejala depresi dengan kecenderungan berupa pemikiran untuk bunuh diri, segera konsultasikan ke pihak-pihak yang dapat membantu seperti psikolog, psikiater, ataupun klinik kesehatan mental.
***
Apa yang kamu lakukan saat melihat anak-anak mengamen di lampu merah jalan? Apa tindakan kita saat mereka menengadahkan tangannya untuk meminta-minta? Atau, bagaimana reaksimu saat melihat anak kecil berjualan tisu?
Jujur saja, saya sering melengos dan hanya melihat dengan tatapan nanar. Tak banyak yang bisa saya perbuat. Beberapa kali saya sengaja membeli tisu dari penjual yang usianya masih anak-anak, walaupun harus membayar dengan harga yang mahal.
Di sisi lain, saya merasa buruk sebagai orang dewasa, karena melakukan kekerasan pada anak secara tidak langsung. Sebab pada akhirnya, yang saya ajarkan bukan nilai kerja keras melainkan membiarkan mereka kehilangan waktu bermain.
Kejadian itu pernah saya alami saat di Surabaya. Gambarannya seperti video di atas, di mana seorang anak laki-laki dengan nada memelas menawarkan tisu Paseo Travel Pack seharga Rp10 ribu kepada saya. Dia bilang, keuntungannya untuk beli sebotol air putih.
Lalu saya bilang, saya tidak bisa membeli tisu miliknya karena harganya terlalu mahal. Yang saya tahu, tisu dengan isi yang tak terlalu tebal tersebut biasa dijual dengan harga Rp6 ribu. Tapi, saya punya sebotol air putih untuk dirinya jika mau.
Mendengar jawaban saya, wajahnya tampak malu dan langsung pergi menjauh. Padahal, saya belum sempat memberikan air minum untuknya. Di sisi lain, jika saya iyakan tawarannya tadi, saya justru merasa bersalah. Karena saya tak ingin membeli “kesedihan” darinya.
Saya takut dia semakin puas, sebab dengan memelas saja, dia bisa mendapat sejumlah uang. Parahnya, kalau dia sudah berpikir bahwa sekolah bukan lagi aktivitas penting dan berguna untuk masa depan. Sementara, ada siswa di NTT yang mengakhiri hidup karena tak punya biaya untuk membeli buku dan pena.
Anak di bawah umur terpaksa bekerja
Saat mendengar kabar pilu dari siswa di NTT, entah kenapa saya jadi memikirkan anak penjual tisu tadi. Tiba-tiba saya merasa ada yang mirip walaupun kisahnya jelas berbeda. Saat memikirkan anak penjual tisu tadi, saya justru takut menormalisasi tindakan salah dari orang tua mereka, yang menjadikan anak-anaknya sebagai “alat” untuk menghasilkan uang lebih banyak.
Sebuah jurnal penelitian berjudul “Eksploitasi Anak yang Dijadikan Pengemis oleh Orangtuanya di Kota Surabaya” menegaskan, anak di bawah umur sejatinya tidak boleh dipekerjakan terutama yang memengaruhi pertumbuhan fisik, mental ataupun moral mereka.
Jika merujuk pada definisi World Health Organization (WHO), perilaku tersebut termasuk sebagai kekerasan terhadap anak. Padahal, anak-anak wajib dilindungi dari segala bentuk pelecehan, kekejaman, serta penindasan.
Namun sejatinya, persoalan mengeksploitasi anak hanyalah puncak dari gunung es. Masih dalam jurnal di atas, Rahmadany Septian, Mochamad Adam, dan Ferrario Mahatamtama menjelaskan eksploitasi anak bisa muncul karena banyak faktor. Salah satunya, faktor kemiskinan atau masalah ekonomi. Begitu pula yang terjadi pada YBS, siswa di NTT yang mengakhiri hidupnya.
“Saya mengajak anak untuk mengemis karena anak tidak ada yang jaga, apalagi kalo saya mengajak anak saya ngemis kan bikin orang lain kasihan dan iba biar mereka memberikan uangnya kepada saya,” ujar Yatmi dikutip dari Jurnal Penelitian Hukum tahun 2021 tersebut.
YBS, siswa di NTT itu telah pergi
Untungnya–walaupun kata ini kurang tepat dipakai, anak penjual tisu yang pernah saya temui di Surabaya tidak sampai mengakhiri hidupnya. Ketakutan saya ini wajar, sebab Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Andreas Budi Widyanta berujar anak-anak yang tidak mendapat ruang dialog aman dari keluarga, sekolah, dan masyarakat akhirnya bisa memilih jalan ekstrem.
“Di keluarga sering tidak ada afeksi, di masyarakat tidak ada pengakuan terhadap hak anak, dan di sekolah, guru masih diposisikan sebagai pusat kebenaran. Anak akhirnya tidak memiliki ruang untuk menyuarakan apa yang mereka rasakan secara jujur,” ungkapnya dikutip dari laman resmi UGM, Sabtu (7/2/2026).
Pada akhirnya, anak yang belum memiliki kemandirian penuh untuk mengambil keputusan eksistensial, bisa memilih mengakhiri hidup sebagai bentuk ekspresi kebutuhannya karena tekanan sosial yang berat.
“Pilihan bunuh diri menjadi bahasa kegelapan ketika anak tidak memiliki ruang untuk mengekspresikan perasaan, kecemasan, dan harapannya. Ini menunjukkan hilangnya ekspektasi terhadap masa depan,” jelas Ab, sapaan akrab Andreas Budi.
Begitulah yang terjadi pada YBS, siswa di NTT yang memilih bunuh diri karena orang tuanya tak sanggup membeli buku dan pena. Dan secara tidak langsung mengalami kekerasan.
Dari cerita YBS dan anak kecil penjual tisu tadi, kamu tentu bisa menarik sebuah benang merah bahwa keduanya memikul masalah serupa, yakni kemiskinan. Ironinya, yang satu dipekerjakan untuk menghasilkan uang, yang satu lagi memilih mengakhiri hidup.
“SURAT BUAT MAMA RETI
MAMA SAYA PERGI DULU
MAMA RELAKAN SAYA PERGI (MENINGGAL)
JANGAN MENANGIS YA MAMA
MAMA SAYA PERGI (MENINGGAL)
TIDAK PERLU MAMA MENANGIS DAN MENCARI ATAU MERINDUKAN SAYA
SELAMAT TINGGAL MAMA,” begitu pesan terakhir YBS dalam surat wasiatnya.
Di balik pesan terakhir YBS, siswa di NTT
Kita semua tentu sepakat, pesan YBS, siswa di NTT itu adalah tamparan keras bagi seluruh elemen masyarakat meski dia hanya menyebut spesifik nama ibunya. Anak usia 10 tahun itu bak aktivis yang rela mengorbankan nyawanya demi menuntut hak-hak anak di Indonesia, sekaligus membela korban kekerasan.
Ia mewakili anak-anak seperti penjual tisu yang saya pernah saya temui, Raya yang meninggal karena tak mendapat penanganan cepat dari rumah sakit, hingga 115 anak yang lebih dulu mengakhiri hidup sebelum dirinya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Namun tetap saja, keputusan YBS dan 115 anak ini tak bisa disebut tindakan heroik. Sosiolog UGM, Ab menegaskan kasus ini juga tidak bisa dilihat sebagai persoalan individu.
Lebih dari itu, kata dia, ada tanda kegagalan struktural negara dalam melindungi anak-anak. Terutama, saat negara menuntut kedisiplinan dan prestasi pendidikan, tapi di sisi lain gagal memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
“Negara terlalu banyak menuntut anak untuk menjadi generasi unggul, tetapi tidak mampu menyediakan fasilitas dasar untuk hidup layak. Ini merupakan ironi,” ujarnya.
Dia mengimbau perlu ada perubahan mendasar dalam tata kelola negara serta penguatan peran dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai upaya pencegahan.
Misalnya dengan menciptakan ruang afeksi di keluarga, menghapus stigma terhadap anak di masyarakat, serta menjadikan sekolah sebagai ruang dialog yang sehat dan inklusif. Dengan begitu, kekerasan pada anak bakal berkurang sedikit demi sedikit.
Ab juga menekankan pentingnya kebijakan penanggulangan kemiskinan yang akurat dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme agar layanan sosial dapat tepat sasaran.
“Kepiluan anak-anak adalah kepiluan bangsa. Fenomena bunuh diri anak menunjukkan retaknya wajah Indonesia dan menjadi peringatan bahwa negara harus segera berbenah dalam melindungi generasi mudanya.” Kata Sosiolog UGM tersebut.
Penulis: Aisyah Amira Wakang
Editor: Muchammad Aly Reza
BACA JUGA: Ironi Perayaan Hari Ibu di Tengah Bencana Aceh dan Sumatra, Perempuan Makin Terabaikan dan Tak Berdaya atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan