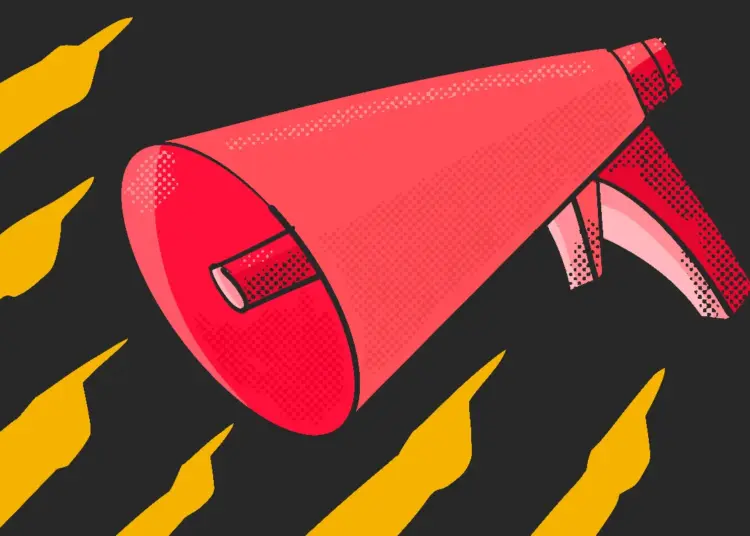Belakangan ini medsos sedang ramai. Ada korban kekerasan seksual yang mengungkap pengalaman traumatisnya. Namun, respons yang diperoleh bukan hanya dukungan. Ada memang dukungan, tetapi juga ada yang justru menghakimi.
Di saat seperti ini, orang-orang sebaiknya mengetahui kapan saatnya mereka boleh dan tidak boleh mempertanyakan, apalagi menghakimi. Sebab, saat ini adalah tidak.
***
Sebuah film berjudul Sorry, Baby (2025) yang disutradarai Eva Victor memotret pengalaman ini dengan cara paling realistis yang bisa, setidaknya saya, bayangkan. Bahwa adegan-adegan yang merupakan kepingan pengalaman korban terjadi secara mengalir sebagai bagian kehidupan, tetapi tidak terbantahkan membuat penonton merasa mual, marah, dan berbagai emosi lainnya.
Apabila kamu menonton filmnya, kamu bisa membayangkan. Namun apabila tidak, kamu masih bisa berusaha berempati kepada korban.
Peringatan: Konten ini mengandung unsur disturbing dan bisa memicu trauma atas tindakan pelecehan dan kekerasan seksual. Tidak disarankan untuk lanjut membaca jika dalam kondisi rentan.
Pengakuan korban kekerasan seksual kerap diganjar penghakiman
Dalam film yang sama, ketika Agnes yang menjadi korban melakukan pemeriksaan visum. Ada dialog yang paling mengusik di antara dirinya dan dokter forensik yang memeriksanya:
“Jadi, kapan ini terjadi?”
“Itu? Kemarin malam.”
“Dan kamu sudah mandi?”
“Ya,”
“Jadi, biasanya lebih baik untuk langsung melaporkan setelah kejadian seperti ini.”
Dialog ini tidak pernah dapat dibayangkan akan benar-benar terjadi dalam dunia nyata ataupun yang mewujud maya, sampai pengakuan korban di X mendapatkan balasan yang salah satunya seperti ini.
“Laporkan saat itu juga setelah masuk ke taksi online, putar ke arah kantor polisi terdekat. Bisa langsung divisum seperti salivanya yang dia cium kamu di telinga. Dia kan masturbasi tuh di celana/rok kamu pasti ada jejak sperma. Dia berhenti, lepasin kamu karena dia udah orgasm,” tulis akun pengguna bernama @kezia_stal, Minggu (8/2/2026).
Korban Saa dengan akun @aarummanis membalas komentar tersebut, menyatakan dirinya tidak dapat melakukan apa pun. Sebab, yang ingin dilakukannya sesegera mungkin hanyalah pulang dan membersihkan diri. Juga, kejadian yang diberi kiat-kiat “bagaimana” seharusnya korban melaluinya sudah terjadi hampir satu tahun yang lalu sampai korban berani mengatakannya melalui medsos.
“I can’t do anything at that time all I wanted was to go home and washed myself because I am so disgusted. And it happened almost a year ago [Aku nggak bisa melakukan apa pun saat itu yang aku inginkan hanya pulang dan membersihkan diri karena aku sangat jijik. Dan itu terjadi hampir satu tahun yang lalu],” tulis Saa.
Penghakiman seakan biasa, tapi tidak bisa dibenarkan
Situs penyedia bantuan untuk penyintas kekerasan dan pelecehan seksual di Inggris dan Wales, Rape Crisis, menyatakan, berusaha untuk hadir dan mendengarkan korban sudah merupakan bantuan.
Meski berat, melakukan tindakan-tindakan yang justru mendorong korban merasa tidak nyaman setelah memberanikan diri mengungkapkan pengalamannya bukanlah sesuatu yang dibenarkan.
Sama halnya Sexual Assault Centre of Edmonton, organisasi bantuan yang berbasis di Kanada, menyebut ada tiga hal pertama yang dapat dilakukan untuk merespons korban, yakni mendengarkan, mempercayai, dan mendukungnya.
“Kalau seseorang mengungkapkan mereka telah mengalami pelecehan atau kekerasan seksual, ketahui bahwa mereka telah mempercayai. Hal terpenting yang dapat dilakukan adalah mendengarkan, mempercayai, dan mendukung apa pun yang mereka pilih untuk lakukan,” tulis peringatan dalam laman tersebut.
Panduan-panduan ini tidak berbeda satu sama lain. Langkah yang harus dilakukan untuk merespons korban adalah mendengar, mempercayai, dan mendukung—dimuat di berbagai situs dukungan. Namun, bukan berarti orang-orang sudah memahami betul bahwa mereka seharusnya benar-benar menerapkannya. Bukan sebaliknya.
“Keputusan speak up atau reach out ke profesional atau curhat aja ke temen, itu udah keputusan yang nggak perlu dipertanyakan kapannya. Tapi, kenapa akhirnya dia berani speak up,” kata salah seorang penyintas berinisial NT kepada Mojok, Rabu (11/2/2026).
NT bermaksud menyoroti bagaimana orang-orang, khususnya warganet, justru mempertanyakan keputusan baru mengungkapkan kejadian setelah bertahun-tahun lamanya. Menurutnya, penghakiman berkedok penasaran ini bukan sesuatu yang sepatutnya dilakukan dalam merespons pengakuan korban.
Korban kekerasan seksual harus bertarung dengan pengalaman traumatis
NT pernah mengalami kejadian yang menjadi obrolan warganet akhir-akhir ini. Ia juga pernah melalui fase yang menempatkan dirinya dalam kondisi serbasalah. Lebih tepatnya, tidak tahu harus melakukan apa dalam situasi tersebut.
Menurutnya, perasaan itu adalah cara korban merespons secara psikologi, yang harus dipahami sebagai mekanisme pertahanan diri yang wajar terjadi. Setelah satu kejadian yang mengerikan, kebanyakan berusaha mati-matian untuk setidaknya bertahan.
“Di psikologi dalam konteks itu, ada defense mechanism yang beda-beda. Kamu flight atau fight. Apalagi korban, misalnya, perempuan, mereka nggak akan langsung berani nonjok dan motong titit, tapi kebanyakan pasti nge-freeze dan butuh banyak waktu untuk mencerna itu. Bahkan, banyak yang nggak langsung sadar itu KS, mungkin juga denial kalau ini nggak apa-apa,” katanya.
Sebagaimana yang disampaikan NT, masyarakat Indonesia belum sepenuhnya merdeka dari pelecehan dan kekerasan seksual. Data SIMFONI-PPA yang diprakarsai Kementerian PPPA mencatat 35.131 kasus, dengan 30.013 (85%) jumlah korban adalah perempuan pada tahun 2025.
Data yang menunjukkan besarnya angka korban ini tidak sejalan dengan pertarungan korban yang terus berlangsung, berlipat ganda, dalam berupaya menyuarakan pengalaman keji yang diterimanya.
Koordinator layanan psikologis di Yayasan Pulih, Danika Nurkalista, juga mengatakan, korban kekerasan seksual dapat enggan berbicara sebab hambatan yang datang dalam dirinya.
“Hambatan bisa datang dari diri sendiri, seperti trauma, posisi tawar yang tidak setara dengan pelaku, pengetahuan yang minim mengenai kekerasan seksual dan hukum, dan sebagainya,” katanya, dikutip dari ABC.
Faktor eksternal, yang salah satunya mewujud dalam penghakiman massa, juga dapat mendorong balik korban untuk dapat berbicara. Faktor ini hadir bersama kecenderungan lingkungan yang alih-alih berpihak kepada korban, justru berdiri bersama pelaku.
“Ada pula faktor keluarga, lingkungan, seperti reaksi victim blaming, persekusi, pemberitaan media yang mengeksploitasi informasi pribadi, kecenderungan lingkungan untuk membela pelaku,” tambahnya.
Sudah jatuh ketiban tangga, menjadi korban semakin sulit ketika tidak punya apa-apa
Itulah alasan NT mengatakan dengan gamblang, “Menurutku, orang tolol yang bilang kenapa nggak langsung lapor.”
Waktu yang diambil korban untuk berbicara dari waktu kejadian adalah otoritas korban sepenuhnya. NT mengatakan, tidak ada yang mengetahui pasti intensitas kejadian yang mencekam korban, kecuali korban itu sendiri. Ini membuat keberanian menampakkan diri sudah patut dihargai.
“Kasus seperti ini, menurutku, ngomong aja udah jadi bukti. Bisa speak up aja udah butuh keberanian dan waktu yang lama. Bahkan, kalau dia mau ngomong 20 tahun lagi juga nggak apa-apa, intensitasnya kan dia yang tahu,” kata dia.
Dalam hal ini, salah satu jeratan yang menghalangi tersebut disoroti sebagai relasi kuasa. Posisi korban yang sudah kerap disalahkan sejak awal, akan semakin dinistakan ketika ditempatkan dalam kekuasaan yang tidak sebanding dengan pelaku.
Layaknya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh owner M, merujuk pada Mohan Hazian, dalam sesi pemotretan talent sebuah merek pakaian miliknya, pola ini terlihat sama. Korban sudah berada di posisi rentan, lalu semakin dilemahkan hingga tidak berdaya dengan kuasa pelaku. Dijatuhkan pula apabila keberpihakan justru diposisikan sebaliknya.
Karena itu, berpihak bersama korban adalah setidak-tidaknya dukungan yang dapat dilakukan.
Penulis: Shofiatunnisa Azizah
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA Menyangkal Pemerkosaan Massal 1998 adalah Bentuk Pelecehan Dua Kali: Fadli Zon Seharusnya Minta Maaf, meskipun Maaf Saja Tak Cukup dan artikel liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan