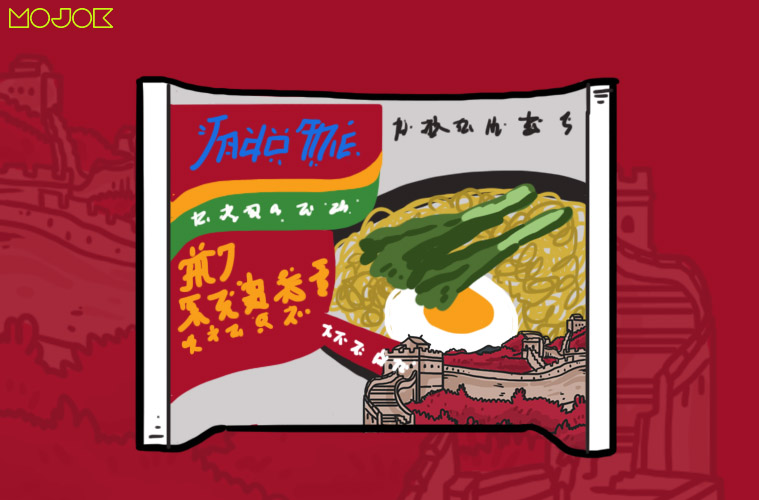MOJOK.CO – Pandemi corona memang mengubah ritme puasa Ramadan bagi mahasiswa-mahasiswa Indonesia di Cina. Hilang sudah perburuan takjil gratis.
Sepanjang 10 tahun terakhir, ini adalah kali pertama saya tidak mengawali puasa Ramadan di Cina. Saya biasanya berpuasa setengah bulan di Cina, lalu 15 hari sisanya di Indonesia.
Dulu bahkan saya pernah jadi seperti Bang Toyib yang selama tiga kali puasa tiga kali lebaran tak pulang-pulang dari Cina.
Saya senang sekali menjalankan ibadah puasa Ramadan di negeri komunis itu. Alasannya sederhana.
Pertama, saya bisa sebulan penuh berbuka puasa gratis di masjid-masjid Cina dengan makanan dan minuman enak nan berlimpah.
Tiap hari saya pasti ke masjid untuk itu. Saya dan teman-teman bahkan menamai diri kami yang demen ke masjid buat mencari penganan berbuka gratisan ini sebagai PPT: Para Pencari Takjil. Kami sebenarnya masih bisa membawa wadah untuk membungkusnya buat santap sahur—tapi itu kalau kami tamak dan tidak tahu malu.
Kedua, saya bisa menikmati pemandangan menawan sepanjang hari sehingga saya tidak begitu merasakan lapar dan dahaga kendati—karena musim panas—durasi waktu dari sahur hingga buka puasa di Cina lebih panjang ketimbang di Indonesia.
Ya maklum, musim panas yang kering membuat amoi-amoi Cina yang bening-bening itu senantiasa berpakaian terbuka untuk menghindari gerah. Kami jelas tertolong oleh mereka. Keterbukaan memang acap dapat menyelesaikan beragam bentuk masalah.
Namun pandemi corona keburu mengubah segalanya.
“Sekarang harus puasa lahir batin, Bung,” kata Alwi Arifin ketika saya hubungi lewat Wechat.
Alwi adalah adik kelas saya tatkala enam tahun silam saya masih kuliah di Xiamen, kota cantik di Cina bagian selatan di mana banyak leluhur orang Tionghoa Indonesia berasal.
Kini, setelah sebelumnya bekerja di Jakarta, dia melanjutkan pascasarjananya di kampus yang sama ketika dirinya menempuh pendidikan S-1, di Huaqiao University, dan masih jua setia pada kejombloannya.
“Cuma untungnya, kondisi seperti sekarang puasanya jadi lebih ringan. Cobaan tak sebanyak tahun-tahun sebelumnya,” tutur Alwi.
Saya tidak paham apa yang dimaksud Alwi.
Ada semacam apa yang disebut teori Marxis sebagai “kontradiksi” atau maodun kalau kata Mao Zedong, dalam ucapannya. Saya memintanya untuk lebih detail mengelaborasi.
“Puasa lahir batin karena tidak hanya menahan lapar dan haus ragawi, tapi juga menahan kerontangnya rohani karena tidak ada noni-noni yang wira-wiri. Tapi itu sekaligus menjadikan puasa jadi lebih ringan karena saya nggak disuguhi cuci mata penggoda iman pas ngabuburit di lapangan,” papar Alwi.
Saya terkekek.
“Bung kenapa nggak jalan-jalan ke luar atau ke masjid, kalau bosan?” tanya saya.
“Itu dia masalahnya! Saya nggak bisa ke masjid. Kampus mengarantina mahasiswa yang masih tinggal di asrama kampus. Tidak boleh keluaran. Hanya karyawan kampus yang bisa keluar-masuk,” keluh Alwi yang mengaku tak tahu kapan kebijakan yang mengekang ruang geraknya itu akan berakhir.
Saya kaget.
Awalnya saya mengira hanya kampus-kampus Kota Wuhan saja yang memberlakukan kebijakan melarang mahasiswa keluar area kampus seketat itu.
Sebelumnya saya mendapat kabar dari eks mahasiswa Wuhan yang turut dievakuasi ke Natuna bahwa salah seorang temannya yang kini masih tertahan di Wuhan dan tinggal di asrama kampus hanya boleh keluar asrama dan beraktivitas di dalam lingkungan kampusnya sekira 3 jam saja.
Kalau lebih, dia diperintahkan untuk balik lagi ke kamarnya dan dicek suhu tubuhnya.
“Di Ningxia juga gitu, Kak. Kami tetap harus stay di asrama. Tidak diperkenankan keluar gerbang sekolah. Boleh, sih, kalau izin. Tapi prosedurnya ribet banget. Sudah 3 bulanan saya mendekam di kampus mulu,” ujar Pramisti Andini Izatun Nabilah yang sekarang kuliah di Ningxia University.
Ningxia adalah daerah otonomi khusus suku Hui—suku yang, akhi dan ukhti fillah sekalian tahu, mayoritas orangnya memeluk Islam. Jaraknya dari Wuhan sekitar 1.500 km ke arah barat laut.
Sampai tulisan ini saya garap, penduduk Ningxia yang terkena corona cuma 75 orang dan dinyatakan sembuh semua.
“Alhamdulillah di Ningxia sudah 100% nggak ada corona. Tapi kata dosen-dosen saya di sini, ‘不要轻视这个病毒。这个病毒的伤害性是非常厉害的!!!’ [Jangan sepelekan virus ini. Virus ini jahat sekali!!!],” terang Andini.
“Makanya kalau dapat izin keluar kampus, kami dikasih waktu 1 jam doang. Tapi kadang kita lebih 1 jam sih,” lanjut Andini sambil ketawa, “soalnya pas keluar kami biasanya belanja banyak buat kebutuhan seminggu ke depan.”
“Itu untuk persiapan masak buat buka dan sahur Andini?”
“Iya. Tapi kalau malas masak saya delivery.”
Lain Alwi dan Andini, lain pula Wahdi al-Amiri. Wahdi adalah mahasiswa S-2 Tongji University, Shanghai.
“È Shanghai bèbas, Nom. Kèng ketat. Ngantri ngakan è kantin bhein jarak’en kodhuh 1,5 meter. Mèjanah èbherrik bhetes,” Wahdi menjawab pakai bahasa Madura untuk mengatakan,
“Di Shanghai bebas, Mas. Tapi ketat. Ngantri makan di kantin saja harus berjarak 1,5 meter. Mejanya diberi pembatas,” ketika saya tanyai apakah lelaki berdarah Madura itu bisa keluar kampus atau tidak.

“Brarti bhe’en bisa ka masjid?” Berarti kamu bisa ke masjid?
“Mon ghun ka masjid ye bisa, kèng masjidhâh ètotop!” Kalau cuma ke masjid ya bisa, tapi masjidnya ditutup.
Na‘am, sejak awal-awal corona, pemerintah Cina memang membatasi akses atau bahkan menutup tempat-tempat untuk kegiatan yang melibatkan orang banyak.
Rumah-rumah ibadah, misalnya, sampai sekarang masih belum boleh difungsikan laiknya sedia kala. Pemerintah Cina menyuruh rakyatnya beribadah di rumah masing-masing seperti yang belakangan juga dimakmumi pemerintah Indonesia dan Saudi Arabia.
“Tak a Trawi be’en, pas?” Kamu nggak Tarawih, dong?
“Ah, a Trawi, engkok, è kamar. Bik tang kancah. Rèng Messir.” Ah, tarawih, aku, di kamar. Bareng temanku. Orang Mesir.
Di Cina, Wahdi boleh lebih leluasa ketimbang Alwi dan Andini, tapi ketiganya bernasib sama: kesulitan buat pulang ke Indonesia. Per 5 Februari silam, pemerintah Indonesia resmi menutup penerbangan dari dan ke Cina.
Kalaupun pelarangan penerbangan ini dibuka kembali dalam waktu dekat, mereka tetap akan kesulitan pulang ke rumahnya sebab Jokowi melarang mudik. Entah kalau pulang kampung.
Makanya, untuk mengobati kerinduan akan Indonesia, Alwi hampir tiap hari masak masakan Indonesia. Wahdi demikian pula.
“Menu kampung halaman selalu terbaik dan tak tertandingi, Bung!” tegas Alwi, sambil mengirimi saya foto ketika dia berbuka dengan bakwan jagung dan sambal terasi yang sedang diuleknya.
Saya tahu cobek dan terasi yang dipakainya pasti dia bawa sendiri dari Indonesia—karena di Cina tidak ada barang begituan.

Andini pun girang bukan kepalang ketika bilang belum lama ini bertemu wanita Indonesia yang bersuamikan orang Ningxia dan membawakannya Indomie.
“Saya baru nyadar kalau saya ternyata satu-satunya mahasiswa Indonesia di sini, Kak. Nelangsa sekali hidup saya,” iba Andini.
Walaupun teman-temannya yang kebanyakan berasal dari negara-negara Asia Tengah berakhiran “-stan” sering memasakinya makanan khas negara mereka, tetapi bagi Andini itu tetap tidak bisa mengalahkan kenikmatan cita rasa Nusantara yang bersemayam dalam sebungkus Indomie. Tak disangka dalam masa pandemi ini, Indomie justru jadi pelipur laranya.

Kebalikannya, saya—yang belum bisa kembali ke Cina gegara pemerintah Cina sejak 28 Maret lalu menutup akses masuk warga negara asing—mulai merindukan masakan muslim Cina yang biasa saya santap saat berbuka puasa di sana.
Sedapnya Mi Lamian khas Lanzhou yang disajikan dengan kuah godokan daging sapi bertabur daun bawang dan seledri, serta renyahnya Melon Hami dan lezatnya sate kambing berlumur bulir jintan putih (ziran) khas Xinjiang, tak henti-hentinya menghantui saya beberapa hari ini.
Corona cepatlah berlalu, kami tak kuat kelamaan menahan rindu.
BACA JUGA Tradisi Begal di Sudan saat Buka Puasa dan Kecepatan Makan Orang Afrika atau tulisan Novi Basuki lainnya.