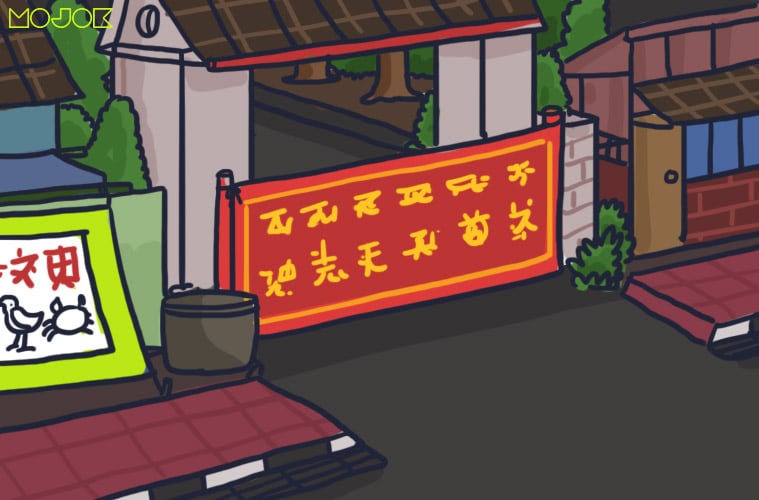MOJOK.CO – Sebagai separuh Batak dan Jawa. Penulis sering kena stereotipe etnis. Batak pasti begini, Jawa pasti begitu. Bhinneka kok Bhinneka streotipe.
Indonesia itu serba majemuk. Saking majemuknya, stereotipe etnis mahapekok pun ikut majemuk. Dan, kalau ada yang tanya, sebagai anak hasil kawin gado-gado, besar peluang saya menjadi sasaran empuk stereotipe-stereotipe mahapekok—yah, moga-moga cuman kegeeran saya doang sih.
Memang sulit ditampik bahwa penisbatan rupa-rupa cap, baik yang “positif” atau ugal-ugalan, ada di tengah masyarakat yang beragam identitasnya. Dan, sejujurnya, bahaya bukan main. Sudah seberbahaya cap PKI di masa Orde Baru.
Saya, sebagai (setengah) Batak Mandailing, kena juga stereotipe etnis sebagai orang yang kasar atau urakan atau kikir. Tiga sterotipe etnis yang kayak sudah bawaan lahir, sepasti key to happiness adalah kunci kebahagiaan.
Bahkan konon, kasar dan urakan dipercaya merupakan sifat alamiah orang Batak secara keseluruhan, dan kikir adalah mutlak-mutlakan sifat orang Mandailing—atau sifat uda-uda dan uni-uni.
Kepercayaan ini tak sedikit pengikutnya. Mau Batak totok, setengah atau seperempat, sama saja. Hal ini tentu menyebalkan, apalagi bagi orang-orang Batak yang berjiwa hello kitty, yang berkebalikan total dari penggambaran stereotipikal tersebut.
Lha memangnya nggak ada orang Batak yang kasar dan urakan?
Ya ada. Tapi kasarnya bagaimana dulu? Kalau doyan menganiaya bini seperti, berarti bisa dengan serampangan pukul rata semua orang Batak pelaku kekerasan—itu mah emang orangnya yang brengsek.
Kalau cuma nada bicaranya yang kasar dan urakan, nggak usah menjatuhkan vonis berat pada sekian juta orang Batak yang belum tentu Anda kenal benar.
Lalu soal cap positif tentang orang Batak. Orang Batak itu pekerja keras, makanya sakses di perantauan. Kalau tidak jadi pengacara, juragan metromini, ya pemilik perkebunan sawit sekian ribu hektar. Bahkan jadi mantu presiden—nah, yang ini semarga dengan saya, meski nggak ada hubungannya juga sih.
Dus, cap positif pun nggak kalah bermasalahnya dengan cap yang keblinger. Kerja keras itu keharusan bagi siapapun yang kepengin selamat di dunia yang mahakejam ini. Semua orang bekerja keras, bahkan jika harus 56 jam dalam sepekan, untuk memenuhi kebutuhan. Ya minimal cukup buat makan dan bayar sewa rumah tahunan yang biayanya bikin nangis darah.
Sementara sakses, yang entah kenapa patokannya selalu kebendaan, ditentukan you lahir dari keluarga mana dan punya atau tidak klik dengan penguasa. Anda kira tajirnya Hotman Paris semata-mata berkat kerja keras dari subuh ketemu subuh?
Maka saya, atau Batak-Batak lain, yang “nggak sakses”, nggak jadi pengacara atau menantu presiden (boro-boro punya mertua presiden, laku aja sulit), berarti “nggak normal” dan, ujung-ujungnya, jadi sasaran empuk buat di-bully.
Kayak gini: istri pasti pintar masak, dan bila ada yang masak air saja nggak becus, berarti bukan “istri yang baik”, ujung-ujungnya di-bully mertua. Percayalah, sinetron hidayah itu nggak absurd-absurd amat. Memangnya enak di-bully?
Dan, sebagai (setengah) Jawa, suatu kali saya ketiban apes. Lagi-lagi, semua gara-gara stereotipe etnis seenak jidat. Dan tentu saja sudah menjurus rasis.
Di Bali, lima tahun silam, kenalan bapak saya, sebut saja Budi, orang asli Bali—bahkan doi merupakan anggota Laskar Bali, Yakuza-nya Bali yang punya koneksi dengan penggede-penggede setempat—dengan wolesnya mengatakan semua pendatang asal Jawa adalah pemalas, akhirnya jadi copet dan maling dan selalu bikin perkara di tanah orang .
Dia katakan kalimat itu di depan saya punya muka. Apa pula maksudnya? Kejadian sepet pada 2014 itu sangat membekas dalam ingatan saya.
Jika niatnya sengaja bikin kesal, ya saya kesal. Bukan sebagai (setengah) Jawa, tapi memang omongannya sama sekali bermasalah dilihat dari sudut pandang manapun. Namun, saya berusaha memahami alur berpikir si Budi. Barangkali, dalam bayangannya, setiap perantau asal Jawa pastilah berotak kriminil, tangannya hobi ngutil—bahkan selalu layak dicurigai.
Barangkali pula, setiap orang Jawa adalah anak kandung daripada Pak Harto dan keluarga bencananya, yang dengan, meminjam kata-kata Pram, Fasisme Jawa-nya telah bikin blangsak mayoritas rakjat Indonesia. Menimbun kekayaan dan tidak bisa menghargai nyawa manusia—biarpun penanggung konsekuensi jangka panjangnya adalah seluruh rakjat Indonesia.
Jujur, saya gagal memahaminya.
Pencopet, maling atau pelaku terorisme relijius bisa siapa saja. Tidak peduli apa etnisnya atau apa keyakinannya. Bisa jadi maling kelas teri, bandit kelas coro yang kebetulan dari Jawa beroperasi mengincar bule-bule lengah di seputaran Legian adalah orang-orang yang “tersingkir”.
Sementara urusan perut tak bisa ditunda. Tentu sulit untuk dibenarkan, sesulit membenarkan stereotip etnis mahapekok yang mengendap dalam Budi punya pikir.
Orang cupet seperti ini tentu hanya kerikil kecil dari masyarakat Bali yang terkenal toleran. Para pecalang akan menjaga perayaan hari raya umat Islam dan Kristen.
Bahkan lazim belaka apabila penduduk Bali kangen sama pedagang sayuran, nasi bungkus, dan lain-lain yang kebanyakan berasal dari Jawa, di hari raya idul fitri, yang pada mudik ke kampung halaman.
Maka orang seperti Budi memang sepantasnya tidak usah terlalu dipedulikan—walau sesungguhnya kalau ditulis kayak begini bisa dapat honor yang menjanjikan.
Orang seperti Budi ada dan berlipat ganda, dan gampang saja budaya mereka memberi segala macam cap, yang melahirkan prasangka dungu terhadap yang lain.
Ada sekian ribu (atau malah lebih) Budi-Budi lain yang manasuka kasih stereotipe etnis ke perantau Papua sebagai biang keonaran dan pemabuk. Imbasnya, mau ngekos dipersulit dengan alasan yang tak masuk akal, mau kumpul-kumpul nobar film dokumenter digrebek dengan tuduhan “meresahkan masyarakat.”
Bahkan, jika Anda bertanya pada kompor-kompor NKRI Harga Mati, setiap orang-orang Papua yang berbicara tentang represi brutal aparat pastilah dicap sebagai simpatisan OPM.
Ada sekian ribu (atau, sekali lagi, lebih) Budi-Budi seantero Indonesia yang berkeyakinan bahwa etnis Tionghoa culas, rakus, dan segala sematan label yang buruk. Tiga tahun silam, kalau memori kita berumur rada panjang, seorang Tionghoa dipukuli dalam TransJakarta, setelah diteriaki “Ahok.”
Sementara yang beneran Ahok, terlepas dari kebijakan gusur sana-sini, keok dalam pilgub plus dibui atas kasus “penodaan agama” tidak bisa dipisahkan dari penisbahan stereotipe etnis atau etnis terhadap dirinya; sebagai Tionghoa dan sebagai penganut Kristen.
Merayakan kebhinnekaan saja tidak cukup untuk membendung penyakit laten ini. Alih-alih, menolak kebhinnekaan stereotipe dan syak wasangka yang makin hari kok makin merajarela.
Meski, tentu saja, jauh lebih mudah menulisnya ketimbang menghadapinya.