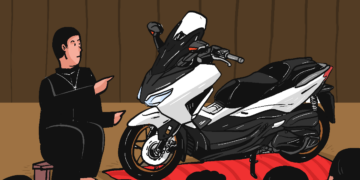Buddha.
Apa yang melintas di pikiran Anda ketika mendengar kata itu? Biksu? Ya. Vihara? Good. Borobudur? Sip. Waisak? Betul. Siddhartha Gautama? Pinter. Apa lagi, ya? Prambanan? TET TOT! Shaolin? Kera Sakti yang pergi ke Barat mencari kitab suci?? TET TOT TET TOOTTT!!
Saya sangat maklum kalau jawaban Anda makin melenceng ke mana-mana. Indonesia punya sejarah panjang kerajaan-kerajaan Buddha (Kalingga, Sriwijaya, dan Mataram Buddha), tapi, ironisnya, pemeluk agama Buddha kini hanya tersisa sedikit. Itupun sebagian besar keturunan Tionghoa, yang berarti bukan keturunan rakyat Sriwijaya.
Agama Buddha pun semakin jauh dari trending topic dan hanya menghiasi media sekali setahun ketika orang berduyun-duyun ke Candi Borobudur menghadiri perayaan Waisak untuk beribadah–atau untuk memotret yang beribadah.
Apa boleh buat, para guru sejarah di sekolah tidak banyak yang pintar bercerita dengan menarik. Kita (hanya diminta) menghafal nama kerajaan, raja dan prasasti di Indonesia, tanpa bisa menghubungkan dengan masa kini.
Tanpa disadari, kita menjadi bangsa yang tercerabut dari akarnya dan kehilangan identitas. Dan sebagai informasi sedikit, WNI Tionghoa, dengan aturan Orde Baru tahun 1967 yang melarang praktik budaya dan bahasa Tionghoa, adalah salah satu contoh jelas dari orang-orang yang tercerabut (dengan paksa) dari akarnya dan kehilangan identitas tersebut.
Apaahhh?? Lha itu, murid dicekoki linimasa dari Kutai, Sriwijaya, Mataram dan Majapahit, menghafal candi-candi dari Borobudur, Cangkuang, sampai Candi Sukuh yang paling seksi. Menghafal nama dari Balaputeradewa, Gajah Mada, Dyah Pitaloka, Brawijaya, sampai Airlangga dan Kebo Ijo. Bukan cuma dihafal malah, tapi dijadikan nama universitas, nama jalan, bahkan restoran.
Pergeseran menjadi negara mayoritas Islam dulu terjadi secara damai lewat hubungan ekonomi, politik dan kebudayaan dengan orang-orang Arab, Gujarat dan Persia. Sunan Kalijaga menggunakan wayang bertema Hindu untuk menyebarkan Islam, dan Sunan Muria menggunakan gamelan.
Eh, kok ya bisa-bisanya pemerintah tidak mengakui agama nusantara seperti Kejawen dan Sunda Wiwitan–yang menyisakan jejak akulturasi animisme, Hindu dan Buddha kuno–atau agama Islam Persia (baca: Syiah). Dan yang paling mengenaskan, banyak oknum yang mengaku mewakili kaum mayoritas jutsru ribut mengkafirkan sekaligus mengusir para pemeluk kepercayaan tersebut.
Syedih…
Oke, kembali ke Buddha.
Apa mau dikata, sekarang kita memang susah membedakan antara vihara dan kelenteng. Sebentar apa bedanya kedua bangunan tersebut? Tandanya adalah, kalau viharanya bercat putih dengan atap kuning berbentuk stupa, itu berarti vihara Buddha ala Thailand. Sedangkan jika viharanya berbentuk pagoda atau bangunan bercat merah dengan atap tumpuk berujung melengkung dan berhiaskan naga, itu merupakan vihara Buddha ala Tiongkok.
Bagaimana dengan isinya? Ya, sama-sama ambigu. Banyak vihara Buddha, baik yang bercat putih, merah, atau warna lain, sama-sama berisi patung Buddha Siddhartha Gautama (Shakyamuni Buddha), bersanding manis dengan patung Dewi Kwan Im, Dewa Kwan Kong (ejaan betulnya adalah Guang Gong, seorang panglima perang zaman Sam Kok yang didapuk menjadi dewa karena kejujuran dan kesetiaannya. Ciri khasnya badan tinggi besar, jenggot panjang dan wajah merah), juga patung Khong Hu Cu dan Lao Tze.
Favorit saya adalah patung Laughing Buddha, dengan ciri khas perut gemuk, telinga super panjang dan tebal, menggendong buntelan, selalu tertawa dan dikelilingi anak-anak, sambil duduk di atas teratai atau kepeng/uang emas Tiongkok kuno berbentuk perahu sekepalan tangan yang sering kita lihat di film-film. Sangat mirip dengan sosok Sinterklas. Sinterklas versi Tiongkok kuno. Ha!
Kenapa vihara dan kelenteng Khong Hu Cu menjadi ambigu? Saya kira, karena pada dasarnya keturunan Tionghoa di Indonesia masih memelihara tradisi menghormati dan berdoa pada para leluhur. Lalu ketika ada aturan Orde Baru yang mewajibkan memilih dari 5 agama, mereka merasa yang paling dekat dengan ritual Khong Hu Cu adalah Buddha, karena sama-sama:
- Dari sononya (Khong Hu Cu di Tiongkok & Buddha India) umum berdoa pakai lilin dan hio.
- Berkumpul untuk ibadah ketika bulan pernama.
- Suka lambang teratai.
- Masih memperbolehkan makan daging babi. (Salah satu menu sembahyang Sam Seng itu selain ayam dan ikan, juga ada kepala babi).
Jadilah kelenteng dan vihara berakulturasi. Umat Buddha Tionghoa setiap tahun merayakan Waisak di kelenteng. Sembahyangnya selain merayakan Trisuci Buddha Siddhartha Gautama, ya sekalian sembahyang juga ke Kwan Im, Kwan Kong, dll. – semua yang ada di kelenteng itu.
Sebagai keturunan Tionghoa yang dibaptis Katolik sejak bayi, saya menikmati akulturasi spiritual tersebut. Ke gereja tiap Minggu (dulu sih, waktu SD) dan ikut sembahyang ke kelenteng beberapa kali setahun.
Ketika ramai di media berita umat Muslim mempermasalahkan tradisi Tahlil dan Yassin sampai memecah belah keluarga–saya juga mendapati cerita ini dari Kepala Suku Mojok dalam buku Melawat ke Timur–saya teringat keluarga-keluarga Tionghoa yang ribut di rumah duka lantaran anggota keluarga yang sudah menjadi Kristen tidak mau memegang hio untuk mendoakan orangtuanya.
Harus diakui, ada beberapa aliran Kristen yang memang sangat ketat melarang mendoakan arwah walaupun orangtua sendiri, karena dianggap “kekejian bagi Tuhan” berdasarkan penafsiran beberapa ayat Alkitab.
Agama memang sulit dipisahkan dari ekonomi, politik, dan budaya. Nah, daripada kampanye negara khilafah, kenapa kita nggak kampanye ‘KEMBALIKAN KEJAYAAN SRIWIJAYA’ saja? Sudah jelas terbukti pernah berhasil, kan?
Simak bagaimana catatan masa kejayaan ratusan tahun Sriwijaya sebagai penguasa jalur perdagangan maritim se-Asia Tenggara. Wilayah kekuasaan Sriwijaya di Asia Tenggara kala itu meliputi Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Thailand, Kamboja, Vietnam, juga Filipina.
Pada masa tersebut pula, umat Buddha dan Hindu bisa hidup berdampingan dengan damai. Raja Buddha lazim mensponsori pembangunan candi Hindu, Raja Hindunya juga kerap mensponsori candi Buddha. Raja dan Permaisurinya pun seringkali berbeda agama. Bukankah itu sejenis toleransi yang kita kerap impikan selama ini?
Soal sistem pemerintahan, kita tinggal mengakulturasikan dengan zaman modern. Di era Transformer ini, bagusnya kita bikin: demokrasi monarki. Monarki parlementer kayak Inggris, noh. Negaranya sukses, tim sepakbolanya juga jaya. Joss banget. Hmm… Tapi kira-kira, siapa ya yang cocok jadi Raja/Ratunya?
Tahan dulu jawabannya. Ada baiknya mari kita ucapkan terlebih dahulu selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2560 BE untuk seluruh umat Buddha di manapun mereka berada.
Om mani padme hum…