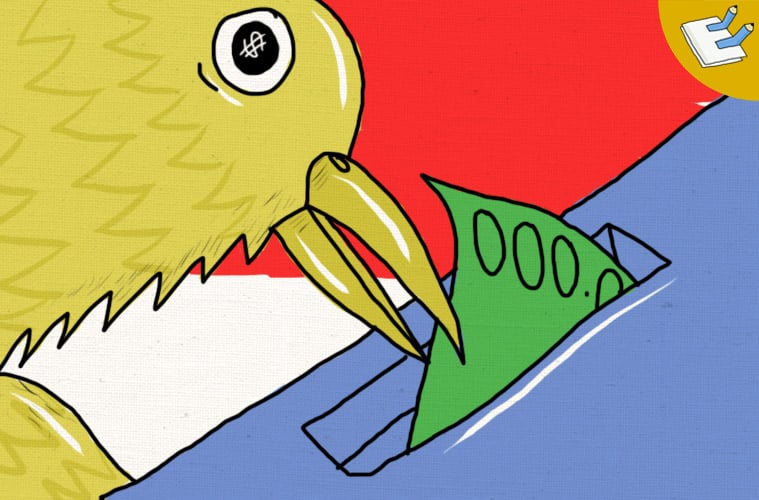Orang-orang yang gemar berbahasa dengan baik dan benar suatu saat nanti pasti akan sampai pada polemik perbedaan antara pinjam uang dan utang. Jika waktu tersebut tiba, tanpa ragu kita harus membangkitkan roh pahlawan bahasa Indonesia: Bapak Jusuf Sjarif Badudu.
“Pak Jus, mohon maaf sekali mengganggu istirahat Anda. Apa perbedaan pinjaman dan utang?”
“Beda tulisannya, Mas, tetapi maknanya sama, kewajiban yang harus dilunasi.”
Bandingkan kalau kita bertanya kepada seorang bankir atau ahli ekonomi, jawabannya hanya berbeda sedikit, tapi menimbulkan konsekuensi yang lain sama sekali.
“Pak Ekonom, apa perbedaan pinjaman dan utang?”
“Beda tulisannya, Mas, tetapi maknanya sama, bisa dicicil.”
Bayangkan saja kalau kita sedang berkecukupan harta dan tengah berniat melunasi utang, bertemu Pak Jus Badudu jelas membuat kita akan berteriak “Merdeka!” dengan los dan lantang. Sementara, kalau bertemu ekonom, kita akan senang karena bisa mencicil utang lainnya.
Itu salah satu paradoks hidup dalam sistem keuangan saat ini. Mau melunasi utang justru diimbau untuk mencicil saja.
“Sayang sekali, Pak, kalau dilunasi. Dana yang ada kan bisa diputar untuk usaha lainnya. Malah akan semakin menghasilkan, Pak,” begitu para kaki tangan kreditur lanyah berbicara.
Iya kalau punya usaha, kalau tidak? Banyak orang terprovokasi untuk menjadi pengusaha. Mencoba berubah dari karyawan menjadi pengusaha. Kalau usahanya jalan dan untung sih enak. Kalau rugi? Mau utang lagi? Tidak semua orang punya kemampuan menjadi pengusaha, tetapi hampir semua orang punya kemampuan menjadi pengutang
Itu utang di level individu. Bagaimana dengan negara?
Sampai hari ini, masalah utang negara yang semakin banyak terus menjadi polemik. Terakhir, berita tentang presiden terdahulu yang gencar menyoroti utang pemerintah. Beliau bilang, “Dua tahun ini pemerintah kita utang lagi untuk pembangunan infrastruktur.”
Kuda-kuda Pak Presiden Mantan itu kurang kokoh. Dalam beberapa saat saja pernyataan itu segera dibalas dengan trengginas oleh ekonom dari partai pendukung presiden sekarang.
“Loh, loh, loh … tak masalah utang negara digunakan untuk membangun infrastruktur. Sebab, penggunaan utang untuk infrastruktur merupakan kebijakan yang baik dan produktif.”
Maaf saja, Pak Jus Badudu sepertinya akan tersenyum simpul melihat dua pihak yang heboh dan cenderung saling serang tersebut.
Untuk menanggapi pernyataan SBY, Pak Jus tampaknya tidak akan berpanjang lebar: “Kalau utang sebelumnya sudah habis digunakan pemerintah terdahulu, tentu saja Jokowi berhak utang lagi.”
Kemudian, atas pernyataan politisi dari partai pendukung pemerintah terkait penggunaan utang untuk infrastruktur merupakan kebijakan yang “baik dan produktif”, Pak Jus akan mengernyitkan dahi dan bertanya, “Apa kalau utang digunakan untuk BLT (bantuan langsung tunai) bagi masyarakat miskin, juga untuk subsidi BBM, itu tidak bersifat produktif?”
Ada kecenderungan setiap pemerintah baru mengeluhkan betapa berat mewarisi salah urus pengelolaan negara dari pemerintah sebelumnya. Dulu, SBY terkenal dengan ucapannya, “Pesta telah selesai, saatnya bersih-bersih.” Sekarang, pemerintah menganggap bahwa pemerintah sebelumnya terlalu banyak membakar subsidi.
Kita harus melihatnya dari berbagai sudut pandang. Kalau Indonesia ibarat orang tua kita, kita harus menerima bahwa orang tua kita tidak mewariskan harta saja, tetapi juga kewajiban bernama utang. Ini harus disadari betul. Bahkan pendahulu Indonesia, Hindia Belanda, dengan akal-akalan sudah mewariskan utang ke negara kita. Indonesia menyanggupi poin tersebut agar Belanda mengakui kedaulatan. Fakta di balik perundingan KMB tersebut tidak banyak diajarkan di mata pelajaran sejarah kita.
Pengibaratan lainnya: Indonesia seperti gadis cantik. Orang luar tidak hanya menerima keindahan yang terpancar (dari hartanya), tetapi juga ingin si gadis cantik bergantung kepada mereka (lewat utang). Maka, dari dulu para kreditur itu sangat mencintai Indonesia. Kaya, tapi bisa dengan mudah diarahkan untuk terus berutang.
Bisakah kita tegak berdiri, tangan terkepal meninjau langit, dan meneriakkan “Merdeka!” sementara utang kita menumpuk dan tidak kunjung berkurang?
Bisa dong. Tidak ada susahnya memekikkan “Merdeka!”. Sayangnya, pengutang yang bermartabat adalah pengutang untuk melakukan hal-hal produktif agar tidak terlalu membebani anak cucunya.
Utang produktif itu bagaimana?
Utang yang dilakukan bukan demi kelas menengah ngehek. Kelas menengah ngehek itu kalau berutang biasanya untuk memenuhi hasrat konsumtif. Contohnya: beli hape pakai kartu kredit, makan hanya di resto yang menyediakan alat gesek, beli kendaraan mahal walau belum punya rumah, dan seterusnya. Pendeknya, mereka berutang bukan untuk menghasikan tambahan pendapatan yang lebih besar dari cicilannya.
Tentu saja contoh ketiga utang di atas dapat dikonversi menjadi utang produktif, tergantung niat dan amal perbuatan. Hape baru yang dibeli dapat dijadikan sarana untuk berniaga online. Makanan yang kita beli melalui utang dapat memberikan energi berlebih agar tidak pernah capek bekerja. Kendaraan yang kita beli bisa kita pergunakan untuk mencari penumpang setelah jam kantor.
Dalam pidato penyampaian nota keuangan dua hari lalu, Presiden Jokowi cukup hati-hati menyampaikan besaran utang, tambahan utang, dan macam penggunaannya. Menurut Presiden, utang dimaksudkan untuk menghasilkan dampak positif bagi pembangunan yang maksimal dan manfaatnya dapat dinikmati masyarakat luas.
Dari data yang ada, utang kita memang tidak hanya untuk infrastruktur, tetapi juga mendukung bidang pendidikan, belanja sosial, transfer daerah, kesehatan, dan dana desa.
Jadi, memang salah kalau ada mantan yang menuduh utang pemerintah untuk memenuhi ambisi pemerintah membangun infrastruktur. Utang yang ada ternyata memang sudah mendarah daging.
Untuk menguji apakah utang pemerintah tersebut merupakan utang produktif, tentu perlu data sangat banyak. Cara paling sederhana yakni dengan melihat angka pertumbuhan nasional. Pertumbuhan kita berada di angka 5,01%. Angka tersebut menunjukkan pertumbuhan kita stabil dibandingkan tahun sebelumnya.
Nah, seumpama ada klaim bahwa rapor kemiskinan turun, pengangguran berkurang, ketimpangan menurun; hal pertama yang harus kita lakukan adalah bahagia. Semoga itu semua benar adanya. Walau kita tetap harus mengkritiknya.
Benarkah pertumbuhan stabil dapat menurunkan jumlah kemiskinan dan pengangguran? Secara teori, pertumbuhan ekonomi lebih menyerupai kebijakan “sapu jagat”. Itu kelemahan paling mendasar. Semua permasalahan yang ada selesai hanya dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sementara dari data yang ada, kelompok bottom-40 (menengah bawah) terus menunjukkan kecenderungan penurunan konsumsi.
Kritik terhadap utang pemerintah tidak semata untuk menjegal atau menjatuhkan pemerintah. Utang punya dimensi lain soal kepedulian kita sebagai pihak yang “turut berutang”. Apakah kita akan melanggengkan pendapat “Sebelum lahir perjanjian utang dibuat orang tua, begitu lahir anak harus mulai mencicilnya”?
Pada akhirnya, merdeka bukan soal kita punya utang atau tidak, tetapi soal kita bisa melunasinya atau tidak.