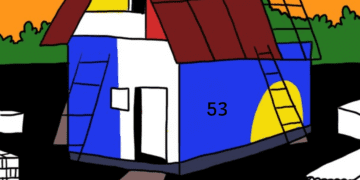MOJOK.CO – UMK Jogja sebesar 73 ribu sekian rupiah per hari, padahal kalau jadi buruh, kita cuma bisa kerja 21 hari dalam sebulan. Gimana rasanya? Sini, saya ceritain.
Kalau ingin merantau dan cari banyak uang, jangan jadi buruh, apalagi di Jogja. Mending kamu jadi pengusaha—usaha ekspor daun kelor atau apa kek gitu. Atau, ngimpor sepatu, lalu dijual di sini. Jual ikan cupang juga bole. Apa aja, lah~
Tapi kalau maksa, kamu harus mengingat ini, meski klise: Jogja memang istimewa. Jumlah kawasan industrinya sedikit, jika dibandingkan dengan Semarang, Surabaya, Jakarta, atau Medan. Tapi, perputaran uang di sini begitu besar dan cepat. Ribuan orang datang setiap hari dan bersikap nyah-nyoh di hadapan para pedagang, mulai dari yang hobi jajan emperan sampai di tempat yang lebih elite.
Pemodal dan investor yang datang dari berbagai penjuru amat cerdik membaca peluang. Sebab, pemandangan semacam ini begitu membangkitkan hasrat untuk menanam “masa depan”. Sementara itu, penghidupan orang Jogja sendiri…
…entahlah. Memang istimewa!
Sudah setahun saya tinggal di Jogja. Awalnya saya cuma berniat main. Berhubung main juga butuh makan, ya, saya sekalian jadi buruh di restoran pizza yang brand-nya terbesar se-antero negeri, tepatnya di salah satu mal besar di Jogja. HItung-hitung dapat makan satu kali sehari, gratis. Lumayan.
Tahun lalu, UMK Jogja sebesar 68 ribu sekian rupiah, sedangkan tahun ini naik menjadi 73 ribu sekian rupiah. Itu UMK per hari dengan durasi 8 jam kerja (1 jam istirahat). Sementara itu, hotel dan restoran kekeuh memberlakukan sistem kerja paruh waktu/part time, khusus bagi pekerja yang hanya bermodal ijazah SMA. Jatah kerja maksimal dalam sebulan dengan sistem ini hanya 21 hari. Itu pun tidak mesti, tergantung ramai sepinya penjualan.
Bahkan kadang, kami cuma dapat jatah kerja 12 hari. Maka, hitunglah berapa pundi uang yang bisa dikantongi orang-orang yang jadi buruh paruh waktu. Belum lagi nanti buat bayar indekos, makan, rokok, bensin, dan lain-lain. Duh syambaaatt, Pakde! Nggak sempat mikir yang-yangan!
Tentu, kesempatan jenjang karir tetap ada. Naik level pun bisa menjadikan kami sebagai karyawan kontrak, sebelum nantinya diangkat jadi karyawan tetap. Untuk naik level dari part time ke kontrak, waktunya tak bisa ditebak. Bisa cepat atau lambat. Tergantung usaha, doa, dan kenalan orang dalam, sih. Kancuuuut!
Hidup, dari dulu, memang keras. Kami tahu itu. Apalagi di rantauan, menjadi buruh, pula. Eh, paruh waktu, lagi. Dan, di Jogja! Mamam!
Tapi, kami mafhum. Dengan kenyataan sepahit itu, tak berlebihan jika kami bilang keadilan terasa nun jauh di seberang lautan sana.
Nah, berikut beberapa hal yang membuat buruh seperti kami bisa tetap bertahan hidup dan ayem-ayem saja dengan kegetiran UMK Jogja dan kegetiran lainnya. Mungkin, ini juga yang membuat kami tidak seperti buruh di kota-kota lainnya yang lebih progresif nan beringas, misalnya dalam hal menuntut kenaikan upah.
Pertama, iklan perusahaan kami tayang dengan manis di tivi. Kalau orang di rumah bertanya soal pekerjaan kami sekarang, inilah semangat kami untuk kemudian menjawab, “Sampeyan pernah nonton iklan pizza di tivi, Bu? Ya saya kerja di situ.” Pada momen inilah iklan tivi sangat berguna untuk membantu menyembunyikan kesedihan. Cukup ampuh menjadi penawar rasa pahit.
Saya tahu bayangan yang muncul di benak orang tua. Mereka akan membayangkan anaknya telah mendapat kerja yang iyup: ruang ber-AC dan tidak panas-panasan. Jika dibandingkan dengan anak tetangga di kampung yang menjadi kuli bangunan di rantauan, cukuplah itu melegakan hati orang tua. Sandiwara tapi nyata. Nyata tapi sandiwara. Yah, serupa kalau main bola di kampung dulu: kucing-kucingan. Permainan yang menggemaskan.
Pertanyaan selanjutnya soal besaran gaji pun bisa dijawab singkat dengan, “Alhamdulillah cukup buat sehari-hari.” Jawaban demikian akan menjadi sangat memuaskan, alih-alih harus sambat dulu soal UMK Jogja. Soalnya, prolog obrolan, kan, kami buka dengan iklan tivi tadi.
Tapi sebenarnya, kami-kami ini ingin menjawab lebih jujur:
“Ya, memang iyup sih, Bu. Tapi, ke-iyup-an sama sekali tak menjamin kaki seorang waitress tidak bengkak karena harus berjalan mondar-mandir selama 7 jam. Tidak ada kesempatan duduk. Belum lagi jika harus membersihkan muntahan para pelanggan—yang entah karena masuk angin atau kebanyakan makan itu. Oh, dan jangan lupakan perasaan kesal setengah mati saat menghadapi cangkeman para senior yang seenak silitnya sendiri itu!
Tapi, tenang saja, Bu. Anakmu tetap kuat dan insyaallah beriman, walau dengan sedikit sambatan. Kelegaan dan hati rida ibu telah menjadi segalanya bagi kami.”
Nah, yang terakhir ini alasan paling ampuh. Barangkali, di sinilah idiom Jawa “Mangan gak mangan asal kumpul” lebih terasa. Riil bukan fiksi, bukan pula kalimat fiktif belaka.
Dari kalimat tersebut, jelaslah bahwa tingkat kebahagiaan seseorang terbukti akan meningkat justru ketika sering berkumpul. Ini ilmiah, setidaknya berdasarkan teori filsuf Iran, Muh al- Sadr, tentang self-knowledge alias merujuk pada penelitian diri sendiri. Eh, alias menghibur diri sendiri ding. Wqwq.
Yah, intinya, sih, kalau kamu misqueen, pandai-pandailah menghibur diri, yha~
Nah, di Jogja, banyak sekali tempat yang bikin orang mudah berkerumun, mulai dari hiburan level pengamen Malioboro hingga seni pertunjukan, seperti teater atau pameran, maupun tingkat yang lebih serius yang sifatnya intelektuil dan spiritual di majelis dan ruang diskusi. Semuanya rata-rata gratis…
…kecuali yang berbayar. Haha.
Ruang-ruang komunal seperti itu bak oase. Tempat merehat diri sejenak. Mengisi ulang energi untuk kemudian besok bertempur lagi. Atau minimal, bisa bikin lupa kalau uang di kantongmu tinggal recehan koin saja. Tentu, ini bukan sikap eskapis.
Toh, kalau lelah berjalan, istirahatlah sebentar.
Mungkin, di luar sana ada banyak tempat merantau para buruh. Tapi, saya yakin, tak ada yang seintim seperti di Jogja. Dekat dan hangat.
Begitulah Jogja itu, Gaes: selalu menawarkan sesuatu yang lain. Ia tetap istimewa dengan menyisakan satu petak rumah untuk pulang, meski ada di tengah segala keasingan dan ingar-bingar. Di tengah arus yang begitu gegas dan lupa. Wataknya menampar jauh lebih keras dari hidup ini sendiri. Mengantarkan opsi bahwa: “Numpak Merci mbrebes mili, njunjung dhawet ura-ura.”
Artinya, lebih baik apa adanya tapi tenteram, daripada ngoyo tapi kacau.
Terakhir, ingat-ingatlah kata Ki Gede Mentaram (Putera ke-55 Sultan Hamengkubuwono VII): “Ketenteraman dicapai lewat hidup yang sak butuhe, sak penake, sak perlune, sak cukupe, sak mesthine, sak benere.”
Barangkali, kalau kita sudah lulus perihal ketenteraman, kelak kita bisa sampai pada titik “Numpak Merci sekaligus ura-ura.”
Tabique!