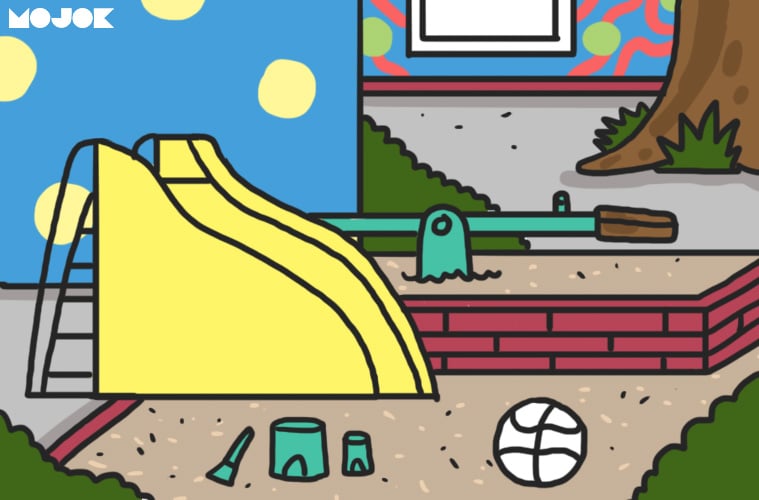MOJOK.CO – UNY membentuk saya menjadi mahasiswa yang bebas. Sementara itu, UAD menarik saya kembali ke jalan benar menuju kelulusan.
Saya adalah jenis mahasiswa yang jarang dirayakan di dunia akademik. Maklum, saya terlalu lama kuliah.
Terlalu lama sampai kata “proses” terdengar seperti dalih dan kata “nanti” berubah menjadi mekanisme bertahan hidup. Saya bukannya tidak pintar, cukup aktif, dan bukannya tidak peduli dengan kelulusan. Saya hanya terlalu lama diberi kebebasan, dan terlalu percaya diri bisa mengatur hidup sendiri.
Tujuh tahun lebih saya hidup sebagai mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Datang ke kampus, berpentas, berdiskusi, terlibat banyak kegiatan, tapi tidak selesai. Setiap ditanya, “Kapan lulus?”, saya punya seribu alasan yang terdengar masuk akal, tapi satu kesamaan bahwa semuanya menunda.
Rasa bersalah itu tidak datang seperti badai. Ia datang perlahan dan menetap. Sampai suatu hari kenyataan paling telanjang menghantam saya tanpa empati. Masa studi saya di UNY habis.
Ketika tidak ada lagi ruang untuk menunda
UNY tidak mengusir saya. Kampus itu hanya berhenti menunggu. Dan saya paham itu. Saya terlalu lama memanfaatkan kelonggaran yang diberikan. Kultur kebebasan yang saya cintai ternyata menuntut kedewasaan yang belum saya miliki.
Di titik itu, hidup akademik saya menyempit. Pilihannya tidak heroik sama sekali, yakni berhenti atau pindah kampus. Saya tidak pindah karena benci UNY. Saya pindah karena ingin satu hal sederhana, lulus.
Keputusan itu terasa seperti pengakuan kegagalan sebagai manusia dewasa. Tapi justru di sana saya mulai jujur pada diri sendiri. Saya butuh sistem yang lebih kuat dari niat baik saya.
Mencari kampus baru, UAD, dan prasangka yang jujur
Mencari kampus baru dengan riwayat studi panjang dan transkrip nilai yang biasa saja bukan pengalaman membanggakan. Saya bukan mahasiswa incaran. Saya mahasiswa yang berharap diterima.
Universitas Ahmad Dahlan (UAD) muncul sebagai opsi yang paling rasional. Tapi di kepala saya, UAD identik dengan hal-hal yang berkebalikan dari sifat saya yaitu tertib, islami, rapi. Terlalu rapi untuk manusia seperti saya yang tumbuh di ekosistem seni, diskusi liar, dan kebebasan nyaris tanpa pagar.
Saya takut tidak cocok. Anggapan tidak disiplin juga jadi hantu tersendiri. Tapi, saya tidak lagi punya kemewahan memilih berdasarkan ego. Saya butuh tempat yang membuat saya selesai, bukan sekadar merasa hidup.
Baca halaman selanjutnya: Menemukan kampus yang terbaik untuk “buangan”.