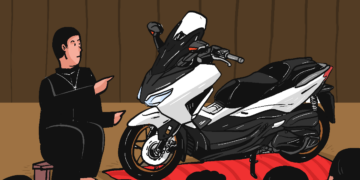Rupa-rupanya orang Jawa memiliki kebiasaan tertentu terkait bilangan 1.000. Kuartet angka yang disebut “sewu” ini memang sesuatu yang signifikan bagi orang Jawa. Dari skill bermatematika orang Jawa hingga elan mereka menggapai kemajuan dapat ditandai lagi ditakar dari bilangan ini. Hambok tenin.
Yang punya pengalaman buruk ngasih duit Rp1.000 ke tukang parkir, lantas dibalas wajah masam plus sebal, mungkin mencibir tak percaya pada omongan saya. Ya tak apa. Kan 1.000 sebenarnya tak cuma soal duit dan selalu dalam rupiah. Coba saja kali lain kasih duit pecahan 1.000 dalam mata uang mancanegara atau koin kripto sekalian. Ya, tukang parkirnya mungkin tetap cemberut. Terima bayaran parkir kok ribet banget harus bikin akun dulu.
Sebelum bergerak jauh, kita mesti juga ingat bahwa masyarakat Jawa hidup akrab bersama pemaknaan njelimet terhadap angka-angka. Deretan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10, masing-masing bisa memiliki makna terenkripsi. Itu dimanfaatkan sebagai sandi-sandi filosofis hingga dipakai sebagai numerologi. Angka-angka penuh sandi itu menyelinap pada setiap hari dan pekan dalam setahun, bahkan pada masing-masing jam.
Jika diuraikan, terlebih berkaitan dengan beberapa angka sekaligus, tak sedikit orang yang menyimaknya bakal terkesan. Meski saya yakin sih, tak sedikit pula yang justru jadi krik-krik-krik, merasa ini wasweswos apaan sih.
Aslinya ya, sistem pengetahuan penuh perlambang ala Jawa tadi sudah bukan sesuatu yang rahasia-rahasia amat. Untuk paham pun tidak wajib menjadi Robert Langdon atau Indiana Jones. Tidak juga memerlukan mesin sandi canggih semacam Enigma kepunyaan dinas intelijen serta militer Jerman semasa Perang Dunia II. Bisa dibilang semuanya tercantum dan bisa dibaca dalam Primbon, suatu kitab yang versi kiwarinya tidak seberapa tebal, pun mudah didapat tanpa perlu menempuh perjalanan jauh ke barat. Lha kan Primbon memang sejak lama dijual bebas di mana-mana. Yang menawarkan di aplikasi pasar daring warna oranye, hijau, biru, maupun merah nggak kurang-kurang juga.
Hanya saja, di sini soal bilangan 1.000 alias sewu, saya tak akan mengulasnya menurut Primbon. Saya akan mengajak mengamati kecenderungan pemakaiannya dalam praktik bermatematika dan berbahasa orang Jawa, baik yang digunakan secara kentara maupun yang menyelinap terkamuflase.
Menurut saya, istimewanya 1.000 alias sewu terletak pada telah dibawanya bilangan ini oleh orang Jawa ke tahap yang melampaui makna harfiah awal. Telah lama ia eksis dengan sekaligus mengusung makna turunannya, yakni menjadi sinonim bagi “banyak sekali”. Kecenderungan demikian ditengarai telah berumur hitungan abad. Tilasnya di antara orang Jawa dapat dirunut mundur setidaknya hingga ke awal abad XIX alias tahun 1800-an.
Dari Candi Sewu hingga Lawang Sewu
Kompleks percandian besar bercorak Buddha di utara kompleks percandian Prambanan mendapatkan penamaan ala penduduk setempat sebagai Candi Sewu. Toponim Candi Sewu bahkan telah dicantumkan Thomas Stamford Raffles dalam bukunya, The History of Java, yang terbit perdana pada 1817. Arti nama Candi Sewu sendiri jika dibahasa-Indonesiakan kurang lebih antara ‘percandian berisikan seribu candi’ atau ‘percandian berisikan banyak sekali candi besar-kecil’.
Di Magetan, Jawa Timur, ada kampung bernama Cemoro Sewu. Ia kondang di antara para pendaki gunung karena menjadi pintu masuk utama pendakian Gunung Lawu. Toponim Cemoro Sewu kurang lebih bermakna ‘daerah yang ditumbuhi seribu pohon cemara’ atau ‘daerah yang ditumbuhi banyak sekali pohon cemara’.
Lalu ada Gunung Sewu yang menjadi toponim untuk bentangan pegunungan kapur dan kawasan karst selebihnya di sisi selatan Pulau Jawa. Bertitik barat di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta; bertitik timur di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Di bagian tengah ia meliputi Kabupaten Wonogiri, Pacitan, dan Trenggalek. Gunung Sewu jika dibahasa-Indonesiakan kurang lebih berarti ‘pegunungan atau perbukitan yang jumlahnya seribu’ atau ‘pegunungan atau perbukitan yang puncaknya banyak sekali’.
Dikenal pula penamaan daerah Sonosewu yang kurang lebih mengandung makna ‘daerah yang ditumbuhi seribu pohon sono’ atau ‘daerah yang banyak sekali ditumbuhi pohon sono’. Sono yang dimaksud di sini adalah pohon yang menjadi salah satu penghasil kayu untuk pembuatan mebel. Toponim Sonosewu sendiri, sependek yang saya tahu, dikenal setidaknya ada dua. Sonosewu yang pertama yakni suatu daerah padukuhan di perbatasan antara Bantul dan Kota Jogja. Tepatnya termasuk Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul. Sonosewu yang kedua ialah suatu hutan di Kabupaten Tulungagung Jawa Timur.
Tak berhenti di sini. Sewu turut menyelinap dalam toponim yang lebih berbobot historis. Dalam hal ini saya akan mencontohkan dua di antaranya.
Sewugalur merupakan contoh pertama. Sewugalur sendiri secara relatif harafiah kurang lebih bermakna ‘seribu hal yang sangat panjang dan terasa tak berkesudahan’. Ini sekarang adalah nama salah satu dusun di dalam Kapanewon Galur, Kabupaten Kulonprogo. Oh ya, nama kalurahan yang memayungi Sewugalur juga mengandung kata sewu, yakni Karangsewu yang bermakna ‘lahan berjumlah seribu’ atau ‘lahan yang sangat luas’.
Semuanya tadi terasa cocok dengan catatan kesejarahan Sewugalur dan Karangsewu pada masa Kolonial Belanda. Tepatnya antara 1881 hingga sekitar pecahnya Perang Pasifik pada 1941, Sewugalur pernah disewakan Keraton Pakualaman kepada pihak investor dan pengusaha Belanda, yang menjadikannya lokasi suatu lahan perkebunan berikut pabrik pengolahannya. Awalnya untuk budi daya indigo bahan pewarna kain, paling lama dan berjaya ketika membudidayakan tebu serta memproduksi gula, tapi lalu berakhir sebagai pabrik penggilingan beras karena terhantam Malaise 1929-1939. Sejarah singkat ini merujuk kepada pemaparan dalam buku Suikerkultuur: Jogja yang Hilang (2019), hasil kerja sama Bentara Budaya Yogyakarta dan Komunitas Roemah Toea.
Contoh toponim historis kedua yang mengandung unsur sewu adalah suatu bangunan besar yang menjadi salah satu tetenger Kota Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Terkenal di antara penikmat wisata, mulai dari pencari foto maupun video berkesan oldies hingga creepy, sampai mereka yang terobsesi dengan kisah-kisah horor dan uji nyali supranatural. Apa lagi kalau bukan Lawang Sewu, eks kantor pusat NISM (Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij), salah satu sekaligus yang perdana dari maskapai pengelola sistem perkeretaapian di masa Hindia Belanda.
Lawang Sewu terbilang sebagai satu di antara bangunan adikarya arsitektur Indis, perpaduan seni arsitektur dan teknologi konstruksi ala Barat di satu sisi dengan seni arsitektur lokal Asia Tenggara serta iklim tropisnya pada sisi lainnya. Sebagaimana bisa ditebak dari makna nama yang disandangnya, ‘gedung berpintu seribu’ atau ‘gedung dengan jumlah pintu yang banyak sekali’, Lawang Sewu mendapatkan namanya dari banyaknya pintu—juga jendela—yang melengkapinya. Lawang Sewu tepatnya dibangun dalam dua tahap: diawali pada 1904-1907 dan lantas disambung perluasan pada 1916-1918. Demikian sedikit info yang dirujuk dari buku Kereta Malam (2015), hasil kerja sama Bentara Budaya Yogyakarta, Indonesia Trains Modelling Community, dan Komunitas Roemah Toea.
Semua yang diuraikan tadi menjadi bukti di lapangan betapa 1.000 alias sewu memang menjadi salah satu kata langganan orang Jawa ketika menamai suatu tempat. Dikit-dikit, ada aja tempat serta bangunan yang dikasih nama memakai sewu. Terlebih jika tempat atau bangunan tersebut memiliki unsur yang jumlahnya banyak banget.
Saya bahkan curiga bahwa kecenderungan itu ditularkan orang Jawa ke wilayah-wilayah lain. Soal ini, sebut saja toponim Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung, suatu penamaan yang memiliki kaitan dengan kolonisasi/transmigrasi penduduk asal Jawa ke Sumatera pada masa Kolonial Belanda. Saya juga curiga bahwa penamaan Kepulauan Seribu bagi gugusan pulau-pulau di sebelah utara Jakarta adalah contoh lain penularan pengaruh orang Jawa soal toponim. Cuma kali ini unsur angka 1.000 yang berkorelasi dengan makna ‘banyak’ dituliskan memakai bahasa Melayu/Indonesia. Namun, ada juga yang bilang toponim Kepulauan Seribu aslinya dikenal dari sebelum VOC merebut Jayakarta dan mengubahnya menjadi Batavia.
Dari Didi Kempot hingga Yogyakarta yang Istimewa
Kesukaan orang Jawa terhadap bilangan 1.000 alias sewu tak cuma terekam di perihal toponim alias penamaan tempat hingga bangunan. Hal demikian juga dapat ditemukan geliat kebudayaan maupun tata pemerintahan orang Jawa. Salah satunya di lagu ini.
Sewu kutho uwis tak liwati
Sewu ati tak takoni
Nanging kabeh
Podo rangerteni
Lungamu neng endi
Pirang tahun anggonku nggoleki
Seprene durung biso nemoni
…
Mendiang kecintaan dan panutan di genre campursari Jawa, the Godfather of Brokenheart alias Bapak Lara Ati Nasional, Lord Didi Kempot, punya “Sewu Kutho” sebagai salah satu di antara lagu-lagu hitsnya. Lihat bagaimana Lord Didi memanfaatkan frase bermakna “menggelandangi seribu kota” sebagai penegas pedihnya rasa rindu yang lama sekali tiada berbalas.
Judul dan lirik lagu milik Lord Didi mungkin dirasa sudah terlalu dekat kepada zaman kiwari. Musik campursari yang diusungnya pun mungkin lebih dipandang sebagai bagian dari budaya pop beberapa dekade terakhir. Jika yang dipinta untuk dihadirkan ialah contoh eksistensi 1.000 alias sewu dalam praktik kebudayaan yang lebih kental warna tradisionalnya, contoh untuk itu bukannya tak ada. Ingat, dalam masyarakat Jawa ada yang namanya Nyewu.
Ini merupakan peringatan 1.000 hari sejak meninggalnya seseorang. Ada selamatan besar yang dihelat sebagai penutup dari sekian selamatan sebelumnya: Geblag (setelah penguburan), Nelung Dina (3 hari setelah meninggal), Mitung Dina (7 hari setelah meninggal), Matangpuluh Dina (40 hari setelah meninggal), Nyatus Dina (100 hari setelah meninggal), Mendhak Sepisan (setahun setelah meninggal), dan Mendhak Pindho (dua tahun setelah meninggal). Dalam peringatan Nyewu, pihak keluarga akan memasang/membangun kijing, yakni batu penutup makam yang melengkapi batu nisannya. Sampai ada pula pembagian kenang-kenangan berupa piring sewon, yakni piring peringatan 1.000 hari meninggalnya seseorang. Piring hias tersebut bergambar potret diri mendiang yang meninggal, dilengkapi juga dengan tanggal-bulan-tahun kelahiran serta tanggal-bulan-tahun meninggal.
Kebetulan atau tidak, ketika berbicara tentang piring sewon, maka sewon selaku kata kedua sekaligus mengingatkan kepada nama daerah yang menjadi tapak kompleks kampus Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta, yakni Sewon di Bantul. Menurut penyebutan tingkatan daerah pemerintahan yang secara khas diberlakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sejak 2020, Sewon ialah daerah berstatus kapanewon, yang setara dengan kecamatan jika merujuk penyebutan generik nasional.
Kapanewon sendiri, istilah yang telah beberapa kali muncul sedari depan tadi, tepatnya adalah penyebutan khas ala DIY untuk kecamatan-kecamatan yang dibawahi kabupaten. Untuk kecamatan yang dibawahi oleh Kota Yogyakarta, penyebutan yang dipakai adalah kemantren. Sementara desa-desa kini disebut kalurahan. Kapanewon, kemantren, serta kalurahan adalah penyebutan tingkat pemerintahan menurut gaya sebelum Indonesia merdeka. Pemberlakukannya kembali konon bukan sekadar nostalgia, tapi sekaligus sebagai penegas kesekian kali dari keistimewaan Yogyakarta. Menurut Anda sendiri bagaimana?
Kapanewon sendiri dikepalai seorang panewu. Jika kini panewu cenderung dimaknai sebagai pejabat pemerintahan yang di provinsi-provinsi lain disebut camat, pada masa lalu istilah itu merujuk pada kepangkatan perwira prajurit maupun nayaka praja yang membawahi hingga sekitar seribu orang. Kini para panewu yang mengepalai kapanewon dalam lingkup DIY rasanya sudah tak lagi membawahi sekadar 1.000 orang, tapi sudah sampai sekian puluh ribu orang.
Sewu adalah candu
Di balik dipakainya 1.000 alias sewu oleh orang Jawa untuk penamaan ini-itu, sejatinya ada hal tak sepenuhnya baik yang mesti disadari. Ya, orang Jawa rupanya mengidap semacam kecanduan terhadap bilangan 1.000 alias sewu. Di dalamnya terkandung semacam viralitas lintas generasi untuk meremehkan dan mengabaikan kedisiplinan berhitung, terlebih jika berurusan dengan jumlah yang banyak. Ada sikap permisif yang disebarkan untuk enggan mengurus dan mencermati sekian jumlah dan angka di atas 1.000. Lembam pula untuk memastikan perihal akurasi jumlah pada tempat-tempat yang menyandang nama dengan unsur sewu. Mempertanyakan “benarkah mereka sungguh memiliki sesuatu dalam jumlah seribu?” cenderung dipandang sebagai sesuatu yang ribet. Disadari atau tidak, hal-hal begini telah menjadi kebiasaan kronis selama hitungan abad.
Lihat pula bagaimana satuan bilangan lain tak sampai sepopuler sewu dalam menyelinapi laku berbahasa orang Jawa, termasuk kurang sekali dimanfaatkan sebagai toponim. Satuan bilangan lain yang saya maksud ialah yuta/juta (1.000.000), laksa (10.000), maupun satus (100). Itu kembali menegaskan apa yang sudah saya bilang tentang kecanduan orang Jawa terhadap 1.000 alias sewu. Itu memang menciptakan kecenderungan kurang serius berhitung, baik terhadap satuan bilangan yang jauh di atas 1.000, maupun yang sebenarnya masih di kisaran ratusan, tapi tentu sudah jumlah yang agak sulit dikerjakan dengan mencongak, lebih lagi dengan sekadar mengandalkan bantuan jemari tangan.
Sebagai etnis terbesar di Indonesia, orang Jawa agaknya memang menularkan kecanduan terhadap 1.000 ke wilayah para etnis tetangga. Buktinya ya orang Indonesia terus mewajarkan penamaan Kepulauan Seribu sekalipun jumlah keseluruhan pulau dan gosong di sana sekitar 342 saja. Sependek saya tahu, tak ada pula yang mencoba merunut untuk memastikan mengapa orang-orang yang membuka lahan hutan bambu yang sekarang menjadi Kabupaten Pringsewu, Lampung, memilih toponim itu, bukan memilih toponim lain semisal Pringalas (Jawa: ‘hutan bambu’) atau Pringsalas (Jawa: ‘bambu sehutan penuh’).
Kekurangseriusan untuk sebisa mungkin mencapai akurasi hitungan angka juga terkandung dalam penamaan Lawang Sewu. Bangunan rancangan P. de Rieu dengan pekerjaan konstruksinya dilakukan oleh tim pimpinan J Klinkhamer ini nyatanya berpintu kurang dari jumlah 1.000. Menurut hasil perhitungan pada 2010, daun pintunya berjumlah 928. Jumlah tersebut bahkan berasal dari pintu-pintu yang jumlah lembar daunnya bisa mencapai 4-6.
Tentang inakurasi jumlah dalam nama yang dikandung, Lawang Sewu masih belum separah apa yang terjadi pada Percandian Sewu dan Prambanan. Pasalnya, dengan merujuk situs candi.perpusnas.go.id,akan ketahuan bahwa jumlah candi dalam Kompleks Percandian Sewu sejatinya jauh di bawah 1.000, tapi 249 saja. Demikian pula dengan Kompleks Percandian Prambanan, tetangga sebelah selatan Sewu. Percandian ini sangat lekat dengan cerita rakyat tentang Bandung Bondowoso yang gagal dalam upayanya memenuhi permintaan Lara Jonggrang, membangun 1.000 candi dalam semalam saja. Nyatanya jumlah candi di Percandian Prambanan tak pula mendekati angka 999 buah seperti yang digambarkan oleh legenda. Prambanan cuma terdiri dari 240 candi. Jadi, baik Sewu maupun Prambanan sama-sama berisi kumpulan candi yang jumlahnya jauh dari 1.000.
Di samping perihal inakurasi jumlah candi yang tidak sinkron dengan nama yang disandang serta legenda yang menyertai, masih ada hal lain yang sebenarnya disayangkan dari Candi Sewu dan Candi Prambanan. Tentang yang saya maksud ini, mari saya ajak sedikit menengok isi The History of Java-nya Raffles yang merekam keberadaan dua percandian tadi pada dekade kedua abad XIX.
Sungguh disayangkan bahwa Raffles mencatat kedua percandian tadi sebagai Sewu dan Lara Jonggrang, nama-nama yang sejatinya muncul belakangan dan jauh setelah masa pendirian mereka, bukan mencatat dua percandian tadi sebagai Manjusrigrha serta Siwagrha selaku nama asli mereka pada masa Kemaharajaan Medang Sailendra. Raffles mencatat demikian tentu karena demikianlah informasi yang didapatnya dari para penduduk sekitar dua percandian itu maupun dari para pejabat pribumi Jawa. Ini sejatinya mengindikasikan bahwa pada awal abad XIX, orang Jawa memang sungguh telah mengalami keterputusan ingatan tentang para leluhurnya dari sekitar masa 1.000 tahun sebelumnya. Untungnya, keterputusan memori itu pelan-pelan berhasil ditambal dan disambungkan berkat kerja keras para ahli sejarah dalam sekitar 200 tahun terakhir.
Semoga semua ini menjadi pelajaran kita ke depannya baik untuk menyeriusi laku hitung-menghitung angka, juga merawat memori sejarah bangsa.
BACA JUGA 6 Hal Ini Mestinya Sudah Dicapai Indonesia saat 76 Tahun Merdeka dan esai Yosef Kelik lainnya.