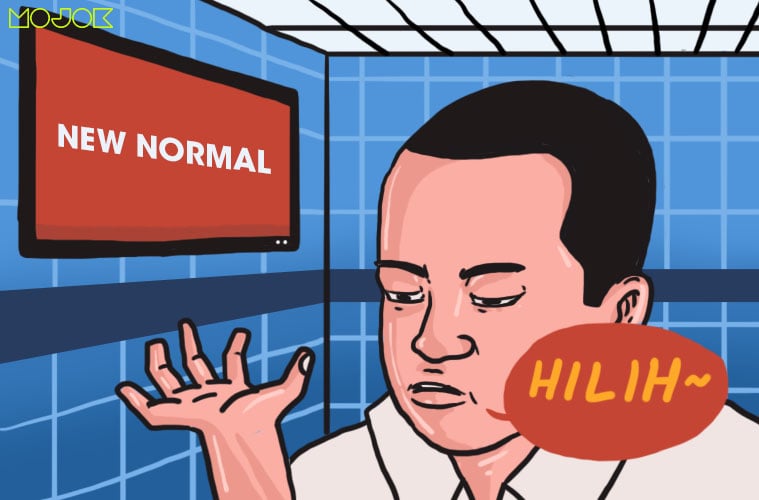MOJOK.CO – Seorang kawan pernah berseloroh, “new normal” itu diartikan sebagai “normalisation of the massive death”. Dipaksa, terpaksa, lantas jadi terbiasa.
Nggak ada negara mana pun di dunia ini yang bisa sesumbar bahwa mereka adalah pengecualian di hadapan pandemi COVID-19. Uniknya, cukup banyak petinggi negara kita memilih untuk percaya bahwa Indonesia adalah “negeri terpilih” yang bisa segera terbebas dari pandemi.
COVID-19 telah mengubah siklus hidup kita secara mendasar. Bukan hanya risiko kesehatan fisik yang mengancam, namun yang nggak kalah seriusnya adalah risiko kesehatan mental.
Tuntutan untuk membatasi pertemuan fisik berdampak pada hilangnya pekerjaan dan kerugian finansial yang dialami oleh banyak orang. Ditambah dengan rasa frustasi kapan pandemi ini akan berakhir. Kombinasi sempurna yang dapat menggerogoti daya tahan psikologis seseorang.
Saya tak asal bicara, pada kenyataannya, per 1 Mei 2020 Perhimpunan Dokter Kesehatan Jiwa melaporkan sudah ada 1.522 orang tercatat mengalami gangguan kesehatan mental atau depresi akibat pandemi COVID-19 di Indonesia.
Besar kemungkinan angkanya akan terus bertambah pada bulan-bulan berikutnya, mengingat semakin banyak orang yang makin frustasi karena nggak tahu kapan pandemi ini bakal berakhir. Ditambah kebijakan penanggulangan pandemi yang “kelewat fleksibel” dari pemerintah sehingga makin meningkatkan persepsi ketidakpastian ini.
Pada kondisi yang menekan ini, nggak sedikit praktisi kesehatan mental di Indonesia yang menganjurkan masyarakat untuk tetap menjaga optimisme supaya kesehatan mental dan fisik tetap terjaga.
Sekilas, anjuran ini adalah sesuatu yang baik, meski saya tak sepenuhnya sependapat. Saya akan jelaskan mengapa.
Begini. Dalam situasi normal, atau problem psikologis bersumber dari ranah personal, anjuran ini barangkali tepat dan bermanfaat. Namun dalam situasi pandemi persoalannya nggak sesederhana itu.
Pertama-tama kita perlu melihat kinerja pemerintah dalam mengatasi pandemi, sejak kasus pertama COVID-19 diumumkan pada awal Maret 2020 sampai sekarang. Dengan berat hati harus kita akui bahwa Pemerintah Indonesia masih belum bisa disebut berhasil, bahkan cenderung amburadul, ambyar, plus compang-camping.
Ironisnya, di tengah laju penularan yang belum menunjukkan grafik melandai (bahkan, mencapai puncak saja belum), pemerintah malah menunjukkan sikap nggak sabaran dengan kampanye pola hidup “new normal”, istilah yang masih sangat kabur bagi situasi di Indonesia.
Dengan getir seorang kawan pernah berseloroh, “new normal” itu sama artinya dengan normalisation of the massive death. Sebab, kebijakan sembrono “new normal” ini berpotensi memicu situasi yang dalam kosakata ilmu psikologi disebut sebagai “bias optimisme” di masyarakat.
Dalam situasi pandemi, ada tiga bentuk sikap yang menggambarkan bias ini: orang yakin bahwa ia dapat mengendalikan situasi eksternal (ilusi kontrol); orang yakin bahwa ia memiliki kekebalan yang lebih baik dibanding orang lain (ilusi superioritas); orang yakin bahwa ia adalah pengecualian atau kecil kemungkinan akan tertular atau menularkan penyakit (ilusi kemungkinan).
Apa yang akan terjadi ketika pemerintahan sebuah negara mengidap bias optimisme ketika pandemi melanda? Kekhawatiran kawan saya tadi nggak mustahil benar-benar bakal kejadian.
Jika mengacu pada kasus-kasus pandemi pada abad-abad sebelumnya, dalam situasi pandemi berpikir optimis berpotensi menimbulkan “rasa aman palsu”, sesuatu yang kontraproduktif bagi pengendalian pandemi. Mendongkrak kepercayaan diri secara nggak terbatas dalam kampanye “new normal” hanya akan mengantarkan kita pada bencana.
Ada kasus menarik di kampung saya. Orang-orang yang terjangkit bias optimisme di kampung saya percaya bahwa COVID-19 akan berakhir sebelum lebaran tiba, tanpa menyodorkan bukti apapun. Meski begitu, cukup banyak yang mengimaninya begitu saja. Sebagian hanya melanjutkan dari sikap serupa dari guru-guru agama mereka.
Entah kebetulan atau memang ada korelasinya, ada dari orang-orang ini yang—meski tergolong dari keluarga mampu—menuntut dimasukkan sebagai daftar penerima BLT Dana Desa untuk warga terdampak COVID-19.
Ketika saya jelaskan bahwa bantuan tersebut ditujukan kepada warga yang nggak mampu agar mereka tetap memiliki daya beli di tengah krisis, orang-orang ini menyergah, “Ini uang dari pemerintah, mestinya dibagi rata kepada semua warga.”
Dengan terpaksa saya menjatuhkan “vonis” buruk kepada tetangga saya ini: egois dan nggak bertanggung jawab! Bahkan saya berani bilang: orang-orang yang berimajinasi bahwa COVID-19 akan segera berakhir, bisa digolongkan sebagai orang egois.
Kok bisa? Sebab mereka menghendaki kondisi enak mereka sendiri dan menolak kemungkinan buruk yang sebenarnya sudah terjadi. Ini tipe orang yang ingin mengelak dari kesulitan, karena dalam kesulitan selalu menuntut tanggung jawab.
Kalau ia memiliki tanggung jawab, tentu ia tak akan menuntut bantuan. Padahal, jika ia memberi peluang kepada mereka yang berhak mendapat bantuan dengan jumlah yang lebih besar, secara sosial hal ini justru dapat menghapus kewajiban membantu sesama.
Saya sampaikan alasan ini, namun ia tak mempedulikannya. Akhirnya, dengan terpaksa, saya menjatuhkan “vonis” buruk kedua kepadanya: orang yang kelewat optimis berpeluang menjadi penjahat bagi orang lain!
Saya nggak menganjurkan Anda untuk percaya pada cara saya menilai tetangga saya di atas. Anda sebaiknya menunda untuk percaya sebelum Anda membuktikannya sendiri di lingkungan Anda.
Baru untuk hal yang satu ini, saya akan mengajak Anda untuk mengerti: Bila kita nggak tahu kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir, jangan terlalu sering mengajak orang lain untuk optimis. Beri kesempatan mereka untuk bersedih, kecewa, juga marah terhadap situasi. Semua respons ini alamiah. Evolusi kita yang menciptakannya.
Ya, secara evolusioner, risiko adalah medan penyempurnaan adaptasi manusia dalam rangka mempertahankan kelangsungan spesiesnya. Untuk itulah mengapa ada jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan justru untuk hal-hal yang nggak kita kehendaki untuk terjadi. Seperti asuransi, pemadam kebakaran, dan pekerjaan-pekerjaan antisipasi-risiko lainnya.
COVID-19 adalah risiko nyata kita hari ini, untuk itulah kita membutuhkan seorang epidemolog untuk memperkirakan hal-hal buruk pada masa mendatang supaya hari ini kita menyiapkan langkah-langkah antisipasinya.
Mengabaikan risiko, atau dalam situasi “New Normal” sekarang muncul dalam gejala bias optimisme bahwa “situasi ini akan segera berlalu” memang memberi sensasi melegakan, namun optimisme tanpa perhitungan hanya akan membuat spesies kita cepat punah.
Henry Dreher, dalam Mind-Body Unity (2003) melontarkan kritik keras terhadap nyaris semua riset yang melambungkan optimisme. Dia menunjukkan bahwa optimisme dapat menghasilkan perbedaan terhadap kesehatan tidaklah cukup.
Dreher melanjutkan, hampir semua riset telah mengabaikan faktor-faktor sosial yang menumbuhkan atau menyuburkan optimisme atau pesimisme. Akibatnya, optimisme dipandang sebagai problem psikologis belaka.
Dreher juga menyimpulkan:
“…Memang benar, orang bisa mengembangkan diri dengan berpikir, berperasaan, dan berperilaku lebih adaptif. Namun, jika masyarakat diminta lebih bertanggung jawab atas sikap dan kesehatan mereka, sosiolog, politisi, tokoh berpengaruh, dan penyedia layanan kesehatan pun harus diminta lebih bertanggung jawab atas kondisi yang kadang menghancurkan, bahkan terhadap pribadi yang paling tabah sekalipun” (hlm. 61).
Sampai di sini, saya berharap kita semua paham bahwa anjuran pemerintah agar masyarakat segera menyongsong pola hidup “new normal” tanpa mempertimbangkan dimensi struktural kebijakan (yang terukur dan terpadu), justru dapat menjadi pukulan balik yang jauh lebih telak.
Dan saya cuma berharap, seloroh seorang kawan soal “new normal” yang diartikannya sebagai normalisation of the massive death hanya jadi candaan dan tak bakal jadi kenyataan.
BACA JUGA Kemungkinan Hidup yang Berubah Setelah Pandemi atau tulisan soal Pandemi lainnya.