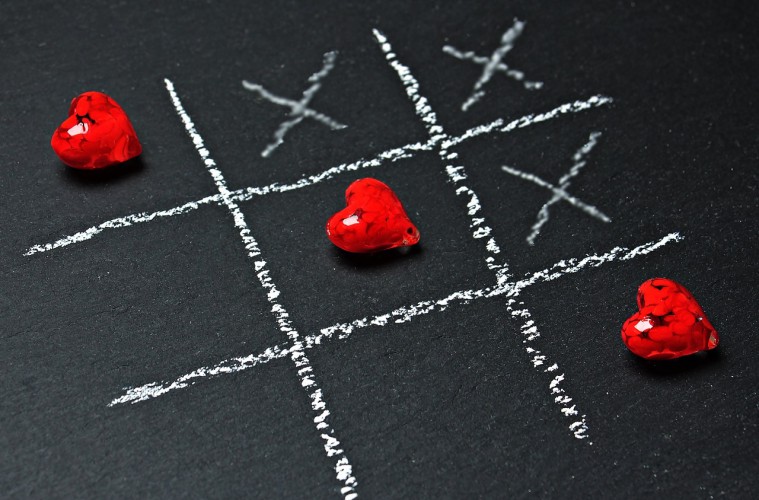Setelah sangat sibuk merantau, akhirnya saya pulang juga ke rumah. Dan rumah, sepeninggalan kakek, terasa agak sepi karena di siang hari hanya ibu yang mondar-mandir di rumah. Ayah muncul pada malam, begitu pula adikku yang sedang menikmati masa-masa sekolahnya. Sementara keadaan nenekku yang sakit-sakitan membuatnya cemas.
Oleh sebab itu, ibu berinisiatif untuk mengajakku mengobrol agar rumah tak menjadi sepi. Di meja makan itu, ia memulai bercerita tentang banyak hal yang menjadi serius. Sesuatu yang tak pernah kami lakukan sebelum meninggalnya kakek. Mungkin ibu mulai menua dan resah perihal nasib anak-anaknya sehingga percakapan ini ia perlukan.
Ibu bertanya kepadaku tentang banyak hal. Ia bertanya tentang kehidupan kuliah. Dan aku menjawab dengan jawaban normatif yang menyenangkan, tentu saja. Lalu ia bertanya perihal hidup dan apakah aku sudah tahu apa yang kuingini. Tentang kota mana yang akan menjadi tujuanku. Tentang mimpiku untuk S2 di Inggris. Tentang kerja apa yang hendak aku kehendaki nanti. Tentang pacarku, apakah aku akan menikahinya suatu saat nanti.
Kami terus bercerita, hingga tamu mengetuk pintu kami menjadi jeda dari obrolan kami.
Aku membuka pintu dan ia tersenyum. Ia adalah tetanggaku –ibu-ibu yang menjadi teman ibuku. Ia kemudian datang dan menyambutku selayaknya orang Melayu bertemu tamu jauh. Ia mengatakan beberapa kalimat-kalimat yang telah menjadi template di telingaku dan terus diulang saat aku pulang ke rumah. “Wah, sudah besar kau rupanya?”, “Gimana kuliah, enak ga?”, “kapan sampai? Kapan pergi lagi?”, dan sebagainya. Tanya-tanya itu aku jawab dengan penuh ketulusan. Hingga kemudian, meluncurlah sebuah tanya yang sebenarnya sangat tidak aku inginkan untuk ditanyakan.
“Kenapa kau tak datang ketika kakekmu meninggal?”
Aku berusaha menjelaskan bahwa adalah wasiat almarhum sendiri untuk segera diadakan pemakaman secepat mungkin setelah ia wafat. Ia tahu bahwa nenekku yang sudah terlalu tua itu akan menangis menjadi-jadi. Dan itu berarti membuat ibuku juga turut sedih. Kalau ibuku sedih, tentu adikku akan menangis terisak-isak. Hal itu akan membuat ayahku harus meluangkan waktu untuk menghibur seluruh anggota keluargaku. Ia bukan Tuhan, dan karena itu, pekerjaan itu akan menjadi mahadahsyat baginya. Ia tak ingin keluarganya berlarut-larut menatapi jenazahnya.
Setelah menjelaskan panjang lebar, aku mengatakan kepadanya, “Aku benar-benar ingin pulang waktu itu, Tante. Tapi ya bagaimana, itu keinginan kakek dan aku harus menghormatinya.”
Kemudian ia menjawab dengan perasaan iba. “Kau harusnya pulang, nak. Orang-orang banyak kok yang rela pulang demi memberikan penghormatan terakhir kepadanya. Apa kau tak ingin pulang?”
Ibu kemudian datang dan mengajak tamuku berbicara. Ia berbicara banyak hal. Tentang arisan dan janji jalan-jalan untuk sesama perempuan di kompleks kami.
Hingga sampai tamu ibu itu pulang, pertanyaanya tentang ketidakpulanganku di hari kematian kakek masih terus terpatri di kepalaku. Sangat membuatku cemas, sampai-sampai aku harus menanyakan perihal perasaanku itu kepada ibu.
“Bu, apakah pilihanku untuk tak pulang saat wafatnya kakek adalah pilihan yang salah?”
Ibu hanya tersenyum dan berkata, “tentu tidak, ibu justru berterima kasih kamu sudah menuruti inginnya kakekmu. Kau pulang atau kau tak pulang semua akan sama saja. Takkan mengubah takdir kakek yang telah meninggal. Malah, menunggumu pulang sebelum kakek dimakamkan akan membuat banyak kesedihan. Tetangga akan terus menanyai keluarga kita kakek meninggal kapan dan bagaimana secara berulang-ulang.”
“Kenapa kamu tanya itu? Pasti tetangga kita tadi menanyakan soal ketidakpulangamu, iya?”
Aku mengangguk. Ibu mengusap pundakku. Membuatku merasa lebih tenang.
“Ketahuilah, Nak! Tak hanya dirimu yang ditanyai orang dengan pertanyaan macam ini. Kau tahu keluarga kita awalnya tak berniat mengadakan tahlilan? Bukan, bukan karena keluarga ini tak sayang dengan kakekmu. Tapi itulah yang memang diingini oleh kakek. Ia berpegang teguh pada prinsipnya bahwa hanya ibu, anaknya, yang akan mampu menyelamatkannya di akhirat kelak selain amal jariyah dan ilmu yang bermanfaat. Mengadakan tahlilan, sama seperti menunggu kepulanganmu kala itu, akan membuat kita terus ditahan perasaan tidak ikhlas dan perandaian yang tak perlu.”
“Tapi pada akhirnya, ibu buat juga kan acara tahlilan?”
“Iya memang, namun itupun hanya tiga hari. Telinga ayah panas mendengar tetangga-tetangga bicara tentang apakah keluarga kita tak berduka setelah sepeninggalan kakek sehingga tak perlu mengadakan tahlilan. Tahlilan itupun kemudian digelar untuk mereka-mereka juga. Bahkan tiga hari itupun bagi mereka kurang. Mereka bertanya kenapa tak ada tahlilan tujuh harian. 40 hari. 100 hari. Satu tahunan. Dan sebagainya. Mereka malah mengatakan ayah pelit karena hanya tiga hari. Seolah tak puas mereka menyaksikan kita semua dipaksa harus terus berduka. Ibu katakan kepada ayah untuk jangan menuruti keinginan tetangga. Kita hormati saja keinginan almarhum.”
Sejenak, ibu menatap gelas yang terisi air. Seakan ia telah melihat dirinya di sana. Seakan ia sedang menemukan apa yang lama ia cari selama ini.
Ibu lanjut berbicara, “Ibu mengerti niat tetangga-tetangga itu baik. Tapi, selama ibu hidup, yang ibu tak mengerti mengapa seakan mereka selalu berkomentar di saat mereka tak betul-betul ingin menolong. Tak adakah empati sedikitpun untuk perasaan ibu, perasaan keluarga ini? Toh, tak sedikit juga tetangga-tetangga kita, teman-teman ibu, yang sampai rela hutang ke sana sini setelah kematian anggota keluarganya karena mereka diharuskan mengadakan tahlilan. Bikin ribet aja.”
Aku menatap kagum kepada wajah ibu. Tak lama, ibu meneguk air dalam gelas itu. Ia menjadi lebih tenang.
“Jadi, sudah ya, jangan sedih lagi?”
“Iya, Bu.”
“Nah, agar kamu tak sedih, ibu akan tanya ke kamu pertanyaan lain. Kapan jadi kamu lulus?”
“Insyaallah 2017.”
“Yakin kamu kalau 2017?”
“Yakin, Bu”
“Kalau tidak lulus 2017, ibu coret dari akte keluarga gimana?”
“Wah, Modar aku…”