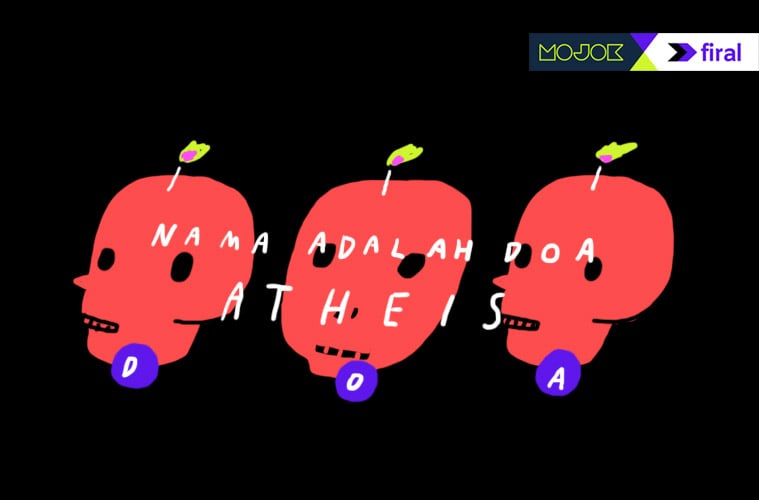MOJOK.CO – Memilih nama anak, mau perempuan atau nama anak laki-laki itu menyenangkan. Meski praktiknya, perlu banyak negosiasi. Terutama dari keluarga sendiri.
Dulu sebelum menikah sampai mempersiapkan diri menunggu kelahiran anak, saya pikir memberi nama anak tak mungkin jadi keputusan yang teramat sulit dalam garis hidup seorang calon ayah. Ya saya tahu memang nggak gampang, tapi kalau sampai bikin bingung kayaknya nggak mungkin banget. Paling sulit paling kayak lagi ngisi TTS doang.
Apalagi, sebelum menikah, beberapa teman lama sering tiba-tiba menelepon saya untuk meminta saran nama bayi mereka yang lahir. Saya juga tidak tahu apa motif dan alasan mereka. Dikira dukun bayi apa ya saya ini? Muka juga tua sana padahal. Mncrgkn skl.
Setidaknya sudah tiga kali saya memberi nama anak teman-teman saya. Jumlah yang tidak terlalu banyak, tapi juga tidak bisa dibilang sedikit. Paling tidak, dengan modal sudah pernah memberi nama anak orang lain, saya jadi cukup percaya diri ketika menanti kelahiran anak pertama.
Satu hal yang saya baru tahu saat menjadi calon orang tua, sejak trimester pertama kehamilan istri, bayangan nama anak sudah muncul di kepala. Jangankan sesudah menikah atau nunggu kelahiran, pengalaman ini saya pikir juga dialami oleh mereka yang belum menikah.
Semacam pikiran, “Wah, kalau saya nanti punya anak, saya mau kasih nama Bambang ah. Bagus kayaknya,” atau “Nama anak Susilo atau Yudho kayaknya keren,” dan sebagainya.
Maksud saya, cita-cita memberi nama anak sebenarnya sudah muncul jauh sebelum menikah. Lumrah saja. Bahkan ketika masih belum balig, saya sudah membayangkan asyiknya memberi nama ke manusia lain. Beserta deretan nama-nama alay lainnya.
Lalu tibalah di momen 9 bulan yang menyebalkan itu. Bukan, bukan proses kehamilannya yang menyebalkannya, tapi bagaimana sebagai calon orang tua amatiran kaya saya dan istri kelewat sering muncul ide nama anak laki-laki yang berbeda-beda.
Oh iya, untung ada USG untuk mengecek jenis kelamin anak, jadi saya sudah bisa mempersiapkan nama anak laki-laki jauh-jauh hari. Meski tetap saja, setiap pulang dari USG, setiap jalan-jalan, bahkan setiap makan Indomie ganti-ganti nama terooos kerjaannya.
Dari nama nabi, nama sahabat, nama malaikat, nama tumbuhan, nama gejala alam, bahkan sampai nama seleb Instagram.
Ketika akhirnya lahir, kegelisahan soal nama anak laki-laki benar-benar sempat terlupa. Sama sekali nggak kepikiran. Baru jarak dua hari setelah kelahiran, nama anak laki-laki apa yang cocok baru muncul. Dan di saat itulah saya tiba-tiba jadi nge-blank. Semua rencana nama anak selama berbulan-bulan hilang. Tak berbekas.
Benar-benar kayak pengalaman berangkat ke tempat karaoke. Udah punya bayangan lagu-lagu apa aja yang bakal dinyayiin. Eh, begitu sampai room karaoke, nge-blank. Utak-atik tangga lagu, bingung mau nyanyi apaan. Mirip kek gitu.
Kenapa tidak minta nama dari istri? FYI aja nih, saya baru tahu kalau seorang ibu yang habis melahirkan itu hampir cuek sama nama anaknya. Energi yang terkuras habis saat persalinan membuatnya nggak sempet lagi mikir soal nama anak.
Beberapa ibu mungkin ada yang request nama, tapi hal kayak gitu biasanya terjadi jauh sebelum kelahiran. Lebih banyak ibu yang pasrah dan menyerahkan tanggung jawab ini ke suaminya.
Ya saya bisa maklum juga sih, udah capek-capek ngelahirin kok masih diminta cari nama. Nggak bertanggung jawab sekali sih jadi suami? Kayak saya aja.
Setelah perjuangan cukup rumit, akhirnya saya mendapatkan rangkaian nama anak laki-laki dengan segenap kepercayaan diri yang harus saya paksakan.
Tapi masalah tidak berhenti di sana. Ketika kemudian nama anak laki-laki sudah didapat dan sudah cukup merasa percaya diri untuk mendaftarkan ke Kartu Keluarga dan bikin Akta Kelahiran, ribetnya memberi nama anak muncul dari keluarga sendiri. Terutama bapak saya.
Apalagi nama anak saya ada “Zlatan”-nya. Iya dari pemain bola Zlatan Ibrahimovich. Bukan nama umum seperti Muhammad atau Surgiyanto gitu. Jelas bakal butuh trik untuk membuat nama seperti ini bisa diterima keluarga besar.
Saya sebenarnya agak yakin, Bapak tak pernah masalah kalaupun misal anak saya mau saya kasih nama Filippo Inzaghi atau Franco Baresi—misalnya. Sebab saya tahu bahwa Bapak juga sempat punya masalah yang sama saat menjadi ayah amatiran kayak saya.
Bapak dulu, pernah ditentang ketika memberi nama kakak pertama saya yang rencananya mau dikasih nama “Kennedy”. Hanya karena kelahiran kakak saya terjadi ketika NASA berhasil mendaratkan manusia ke bulan.
Kata Bapak waktu itu, “Keren banget dulu itu, Presiden Kennedy bisa mendaratkan manusia sampai ke bulan. Cuma kakakmu itu harus ganti nama akhirnya karena nggak boleh sama simbahmu.” Nah lho.
Kebiasaan Bapak yang memberi nama anak-anak sebagai penanda era juga muncul ke kakak saya yang lain, dinamai pakai unsur nama Muhammad Ali. Ya karena saat kelahiran kakak saya ini bareng dengan masa petinju Amerika tersebut sedang berada di puncak kejayaannya.
Berlanjut terus sampai nama saya yang didapat karena nama “Kolonel” Libya Muammar Gaddafi sedang moncer-moncernya. Makanya sampai sekarang saya masih yakin, kalau saya punya adik laki-laki, pasti bakal dikasih nama Saddam Husein.
Kebiasaan memberi nama anak sebagai penanda era ternyata juga menular ke saya. Paling tidak, jika Bapak tak jauh-jauh beda sama urusan politik dan olahraga tinju, saya ingin jadi penanda era juga. Era pemain bola.
Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi jelas, tapi butuh penjelasan panjang kalau memilih dua nama itu—terutama untuk Bapak yang nggak ngerti-ngerti amat soal bola. Dan akhirnya terjadilah dialog itu. Soal nama anak laki-laki saya yang sempat diprotes Bapak.
“Siapa namanya tadi?”
“Zlatan, Pak,” kata saya.
“Slatan? Siapa tadi? Selatan?” tanya Bapak lagi.
“Zlatan, Paaaaak,” jawab saya.
“Selatan? Apaan itu selatan? Anakmu lair madep kidul po piye kok dijenengi selatan barang?” (Anakmu lahir hadap ke selatan atau gimana kok dinamai selatan segala?)
Hm, saya akhirnya mengerti kenapa Syahadatain bisa jadi Sekaten di tanah Jawa.
“ZLATAAAAN, Pak, pakai ‘Z’. Nggak pakai ‘S’.”
“Oh, Zlatan.”
“Nah.”
“Nama apa itu Zlatan? Mbok kamu itu kasih nama ada doa-doanya juga,” kata Bapak saya.
“Itu nama pemain bola, Pak, artinya ‘emas’ dari Bahasa Slavik Kuno orang-orang Balkan,” kata saya.
“Kasih nama anak kok pemain bola,” tanya Bapak.
“Sing penting kan Islam, Pak.”
“Oh, agamane Islam to.”
Oke. Dalam perdebatan kayak gini, cara-cara klasik memang penting sekali. Bapak saya jelas nggak tahu Zlatan Ibrahimovich kayak gimana. Kalau tahu foto-fotonya jelas bakal protes.
Badannya Ibrahimovich kan penuh tato dan Islamnya cuma KTP, komennya paling nggak bakal jauh-jauh dari ini: “Pemain kayak preman gini kok dijadiin nama anak laki-laki.” Untung aja sih Bapak nggak tahu, jadi semua beres sama kata “Islam” doang.
Bagi beberapa orang sepuh, hal kayak gini beneran ampuh. Apalagi untuk Pak Lik atau Pak De saya yang sama sepuh dan kolotnya. Maksud saya, ketimbang saya kasih nama Maradona—misalnya, butuh berapa busa kalimat coba untuk berargumentasi? Dan ya itu melelahkan saja. Apa susahnya sih nego-nego tipis?
Lagian, sebagai orang tua amatiran, kamu nggak bisa seenak udel akrobat memberi nama anak. Mau itu nama perempuan atau nama anak laki-laki. Benar-benar tak bisa semudah mengisi kolom TTS. Asal pas dan cocok gitu aja. Nggak bisa. Semua butuh penjelasan yang bisa diterima—paling tidak oleh keluarga.
Sebab, pada kenyataannya kita tetap harus mempertimbangkan latar belakang keluarga besar—kecuali kalau memang siap berdebat dan rela menjadi topik ghibah setiap lebaran. Kalau sudah siap seperti itu sih nggak masalah. Mau kamu kasih nama merek galon ya terserah aja. Ahmad Aquaria RO misalnya.