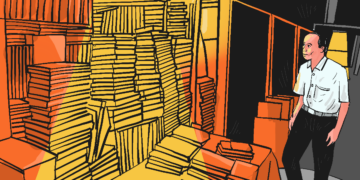Satu-satunya cara terbaik menjual buku—dalam pengertian buku itu jadi laris bak gorengan—adalah, berdoa pada Tuhan agar bukumu menjadi best seller. Sayangnya, yang berdoa pada Tuhan bukan cuma kamu saja, tapi juga ribuan penulis lainnya. Sukurin.
Lantaran semua penulis berdoa, maka tak mungkin Tuhan mengabulkan semuanya. Ya, sebetulnya mungkin saja sih, namanya juga Tuhan Sang Maha Segala. Tapi, ya coba logika saja, jika semua buku menjadi best seller, itu artinya tidak ada buku yang best seller. Bener, toh?
Sebuah buku menjadi best seller karena buku lain nggak laku. Simpel. Sederhana. Tapi justru di situlah letak keadilan Tuhan. Maka sampai ke langit ketujuh pun kamu menggugat Tuhan ya nggak bakalan menang. Nggak laku ya nggak laku. Titik.
Selama sekian tahun karier kepenulisan saya, setidaknya saya sudah mengalami lima cara menjual buku. Kelimanya sama-sama bikin hepi dan sama-sama bikin makan hati. Tolong jangan tanya bagian mananya yang bikin keki. Memori lama nggak perlu diungkit kembali. Ehem.
Cara Pertama adalah Menjual Melalui Penerbit
Ini cara yang dilakukan hampir semua penulis. Saya kirim naskah ke penerbit, disetujui untuk diterbitkan, dicetak, diserahkan ke distributor, lalu distributor mengedarkan ke toko buku. Rantai penjualannya cukup panjang. Penulis-penerbit-distributor-toko buku-pembaca.
Kelebihan menjual dengan cara ini adalah penulis cuma perlu mikirin naskah. Lain-lainnya diurus orang lain. Kekurangannya, bayarannya tidak terlalu banyak. Royaltinya di kisaran 6-10%. Dalam beberapa kasus bisa sampai 12%.
Mari hitung: Jika harga sebuah buku 30 ribu rupiah sementara royaltinya 10%, maka dari satu buku seorang penulis dapat tiga ribu. Kalau bukunya laku seribu, royaltinya tiga juta. Pembayarannya dua kali setahun. Artinya dalam enam bulan si penulis cuma mendapat 1,5 juta dari jerih payahnya. Mau makan apa tuh anak bininya? Syukur kalau royaltinya 10%, lah kalau cuma 6%?
Tolong jangan dihitung. Sedih dedek, Bang, kalau tahu hasilnya.
Makanya saya galau begitu denger kabar pajak penulis dinaikin pemerintah. Dikira pendapatan semua penulis Indonesia itu sama seperti Agus Mulyadi apa, atau kayak Andrea Hirata yang tembus di atas lima miliar lebih, atau kayak Kang Abik yang ‘Ayat-ayat Cinta’-nya tembus sampai angka 200 ribu kopi itu?
Mungkin memang ya dalam setahun ada seratus penulis yang bukunya best seller, tapi tolong diingat-ingat, di balik para penulis yang hepi itu ada seratus ribu penulis yang menangis karena royaltinya menyedihkan.
Hayati bukan lelah lagi, Bang. Tapi udah nyungsep.
Cara Kedua Menjual Buku adalah dengan Menjual Sendiri
Ini mulai dilakukan para penulis, baik yang udah beken di seantero jagat Indonesia, maupun yang bekennya masih di kalangan ibu bapaknya sendiri.
Mereka yang milih jualan sendiri akan mengambil alih tiga rantai penjualan, yakni, penerbit, distributor dan toko buku. Teknisnya begini, setelah naskah ditulis mereka mengeluarkan uang sendiri untuk mencetak bukunya, lalu setelah buku terbit mereka distribusikan sendiri ke berbagai toko buku, baik online maupun konvensional.
Tak cukup jadi distributor, mereka pun menjelma jadi toko buku. Para pembeli diundang untuk membeli buku di lapak media sosialnya. Kalau kita intip akunnya, isinya rata-rata promo buku baru serta link pujian untuk bukunya. Kelebihannya satu, seluruh laba penjualan masuk ke kantong sendiri.
Teman saya yang nyetak 300 buku, mengaku sudah balik modal setelah 100 buku terjual. Buku sisa menjadi laba. Jika satu buku berharga 30 ribu, berarti dia mendapat untung enam juta. Kekurangan menjual dengan cara ini adalah ribetnya itu lho, nggak tahan.
Ribet dengan Cara Kedua, Saya Mencoba Cara Ketiga: Menjual E-book
Mula-mula saya bekerjasama dengan sebuah lapak e-book ternama. Dua rantai penjualan saya gunting habis di sini: Distributor dan toko buku. Saya langsung berhubungan dengan penerbitnya. Royaltinya besar, di kisaran 40-50%. Tugas saya cuma dua, menulis dan mengunggah naskah. Situs itu yang mengurus penjualan dan pembayaran royalti.
Hasilnya? Alhamdulillah setelah setahun e-book itu belum terjual satu pun. Tiap dipantengin, jumlah peminatnya selalu memprihatinkan. Saya sampai nggak tega buka link-nya.
Akhirnya Saya Mencari Jalan Lain, Cara Keempat: Ikut Proyek
Cara keempat ini terhitung menguntungkan. Penulis memasukkan naskahnya ke daftar proyek pengadaan buku pemerintah. Nominalnya lumayan. Dibayar tunai tanpa perlu menunggu sekian bulan layaknya royalti. Penulis pun tidak perlu bersusah payah mempromosikan bukunya supaya laris. Lah, yang mendistribusikan pemerintah sendiri kok ke berbagai perpustakaan publik dan sekolah. Kekurangannya, penulis yang nggak punya jaringan belum tentu bisa dapat proyek ini.
Cara Kelima adalah Ikut Lomba
Ini termasuk yang cukup sering saya lakukan dengan catatan penyelenggaranya adalah penerbit yang punya kredibilitas tinggi. Cara ini mirip cara pertama dengan satu perbedaan, promosinya besar. Keuntungan lain, kalau menang saya dapat hadiah lumayan, naskah terbit, penjualannya bagus dan nama saya dikenal luas. Empat buku saya terbit dengan cara ini. Satu-satunya kekurangan adalah, kalau naskah nggak menang bakal nangis bombay sepanjang film India.
Beberapa Bulan Lalu Muncul Ide di Kepala Saya dan Ini Sepertinya Bisa menjadi Cara Keenam
Memasarkan buku melalui lapak e-book. Mirip dengan cara ketiga dengan satu perbedaan: Pembayarannya dengan pulsa telepon. Ide ini saya dapat ketika saya merasa rumit mentransfer uang ke seorang penjual buku yang banknya beda dengan bank saya. Apalagi saya nggak punya SMS banking.
Ada dua keuntungan menjual dengan cara ini. Pertama, biaya cetak nggak ada. Kedua, teknis pembayaran nggak ribet karena rata-rata orang punya ponsel. Aplikasi baca bisa diunduh dari Apple Store atau Playstore. Gampang. Akan lebih menyenangkan kalau penulis bisa menjual bukunya sendiri di situ.
Buku saya seharga 50 ribu bisa dijual separuh harga. Jika royaltinya 50%, saya akan mendapat 12.500 perbuku. Jika laku seribu saya berlaba 12 juta. Kalau laku 10 ribu? Wow banget kan ya.
Tapi, meski nanti terwujud cara keenam ini, tetap saja rumus menjual buku dengan baik dan benar itu tidak akan saya ketahui. Selera orang Indonesia itu persis seperti jodohnya jomblo, undpredictible.
Jadi, setiap kali saya melepas satu buku ke pasar, saya tetap akan kembali ke cara ‘primitif’: Berdoa. Dan gawatnya, karena yang berdoa bukan cuma saya, sepertinya saya masih harus bersabar. Entah saya ada di antrean ke berapa.