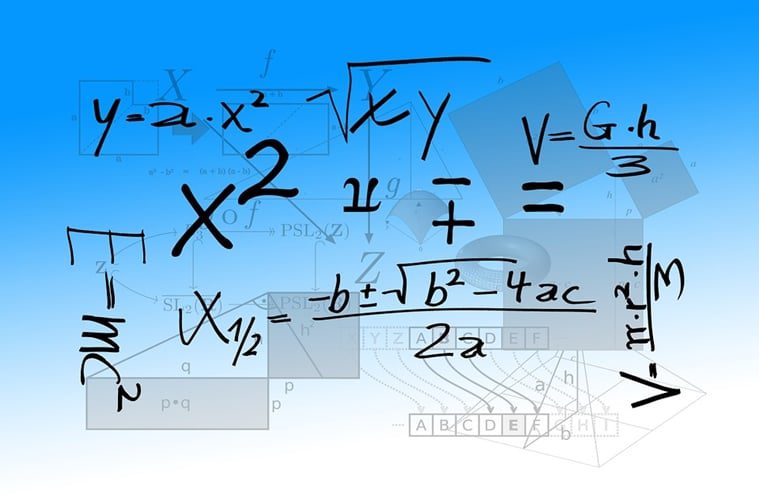Kami bertiga melangkah masuk ke pelataran. Segeralah tampak Syekh Abu Hayyun dalam pose standarnya: duduk di teras, menghadap secangkir kopi, dengan bibir umak-umik entah wiridan entah nembang campursari. Anehnya, tak ada kepulan asap rokok sebagaimana biasa. Apakah Syekh sedang kehabisan stok rokok, atau malah sudah ikut Aria Bima jadi jawara antirokok, wallahualam. Saya tidak merasa terganggu dengan itu.
Satu-satunya yang membuat saya terganggu hanyalah suasana padepokan ini. Ya, padepokan Syekh Abu Hayyun sekarang sepi. Sepi sekali. Persis sebagaimana yang dikabarkan orang-orang kepada kami.
Setelah kami beruluk salam dan dipersilakan duduk, saya pun mewakili teman-teman untuk menyampaikan maksud kedatangan.
“Syekh, begini, Syekh. Anu, kami tahu, padepokan sampeyan ini sekarang sudah hampir gulung tikar. Cantrik-cantrik pada bubar, karena semua lebih suka bergabung ke padepokan milik guru kami, Dimas Kanjeng Taat Pribadi.”
Syekh Abu Hayyun diam saja. Saya pun melanjutkan.
“Kami sudah mengkonfirmasi, para cantrik pada pergi karena sampeyan tidak pernah menunjukkan bukti karomah apa-apa. Ini beda banget dengan guru kami yang mampu melipatgandakan uang itu.”
Saya berhenti sekejap sambil memamerkan sedetik senyum bangga. Kemudian saya sodorkan poin kami, “Jadi kami berpikir, kenapa Syekh tidak ikut bergabung saja dengan Dimas Kanjeng? Saya yakin beliau akan memberikan posisi penting buat Syekh.”
Syekh tersenyum kecil. Lalu ia bicara pendek dan pelan. “Hehehe. Karomah ya masalahnya. Emang buat apa sih karomah macam gituan?”
“Astaghfirullah, kok gitu, Syekh? Apa sampeyan nggak percaya adanya karomah?” Saya kaget.
“Dalam Islam, diajarkan keimanan kepada hal-hal gaib. Allah memilih para waliyullah, dan mereka dikaruniai karomah, alias kelebihan-kelebihan yang bersifat irasional tapi nyata. Ini nyata, Syekh. Tanya saja ke Ibu Marwah Daud kalau nggak percaya. Beliau doktor lulusan Amerika, lho.”
Tangan Syekh Abu Hayyun diangkat sedikit, memberi kode agar saya tenang. Padahal sudah mau emosi saja saya ini, mendengar ada orang mencibir guru kami.
“Begini ya, Mas,” Syekh mulai pasang wajah serius. “Saya percaya adanya hal-hal gaib dan irasional. Agama kita memang mengajarkan itu, dan toh dunia ini memang tak semuanya berisi perkara logis, masuk akal, dan kasat mata. Tapi….”
“Tapi apa, Syekh?”
“Tapi begini. Saya meyakini, Gusti Allah tidak akan vulgar dalam melanggar hukum alam yang Dia tetapkan. Jadi hal-hal irasional semacam itu bisa saja muncul, tapi hanya akan berperan dalam lingkup-lingkup kecil. Tidak akan bisa dibawa menuju skala luas sampai ke ribuan orang, sebagaimana guru kalian itu. Apalagi dijadikan solusi persoalan-persolan umat di zaman sekarang.”
“Lho, apa maksudnya, Syekh? Bukannya mukjizat para nabi juga ditampilkan ke masyarakat luas? Ingat bagaimana Nabi Musa membelah Laut Merah untuk menyelamatkan Bani Israil. Ingat juga bagaimana Nabi Ibrahim menunjukkan diri tak mempan dibakar api di hadapan rakyat Raja Namrud!”
“Iya, iya. Saya pun percaya mukjizat para nabi. Tapi coba, kapan sih zaman mereka itu? Ibrahim diperkirakan hidup pada 4000 tahun lalu. Musa 3300 tahun lalu. Bagaimana sampeyan membayangkan kondisi masyarakat yang beliau-beliau dakwahi? Mereka masyarakat kuno, Mas. Masyarakat yang masih membutuhkan pertunjukan-pertunjukan keajaiban sebagai bukti adanya Tuhan. Sementara, para nabi datang dengan bahasa yang cocok dengan nalar umat yang mereka hadapi.”
Syekh ambil jeda sesaat untuk menyesap kopi dinginnya, lalu melanjutkan lagi.
“Bandingkan dengan umat Muhammad. Meski beberapa hal irasional juga diriwayatkan kejadiannya, namun apa sih yang selalu ditekankan sebagai mukjizat terbesar? Ya, mukjizat terbesar adalah Al-Quran. Kitab yang bukan cuma harus terus-menerus ditadarusi, melainkan juga ditadabburi, digali maknanya, ditafsir sebagai spirit membangun peradaban. Pada zamannya, umat Muhammad sudah bergerak lebih jauh, bukan lagi melulu berpijak pada nalar-nalar mitis, melainkan pada spirit kemajuan. Bahasa umat Muhammad dan bahasa umat Ibrahim sudah beda jauh, Mase.”
Saya mencoba mencerna.
“Makanya,” Syekh ternyata belum selesai.
“Andai memang benar guru kalian itu bisa melipatgandakan uang, dan itu sudah diverifikasi kebenarannya oleh doktor lulusan Ngamerika, lha trus habis itu mau dipakai buat apa? Kalau cuma sejuta-dua juta buat membantu sebuah keluarga korban penggusuran, monggo saja. Tapi kalau sudah ratusan miliar, emangnya apa yang terjadi? Ya inflasi to, Mas! Coba ada 10.000 orang ikut guru kalian, masing-masing menyetor 200 Miliar, lantas semua duit yang terkumpul dilipatgandakan 10 kali lipat sama guru kalian itu, trus disebar ke pasar. Ya bisa ambrol negara ini, hahaha! Mbok dipikir sedikit to….”
Mulut saya tiba-tiba terasa agak sepat-sepat gimanaaa, gitu. Buat obat sebel, saya tonjok lagi dia.
“Wah, sampeyan ini rasanya kebanyakan makan materialisme historis, Pak Syekh. Sama hal-hal gaib sinisnya minta ampun. Benar kata orang-orang kalau sampeyan dekat dengan kelompok kominis.”
“Lambemu. Ya bukan gitu, to ya.” Wajah Syekh agak kecut. Dalam hati, saya girang melihatnya.
“Bukan gitu gimana, Syekh?”
“Begini lho, Mas. Saya jelaskan ulang poin saya.”
Saya membetulkan letak duduk. Dua rekan saya ikut-ikutan.
“Prinsipnya,” Syekh mulai menjelaskan, “keajaiban yang terjadi di luar hukum ilmiah sebab-akibat hanya akan berperan dalam skala kecil. Ambil contoh yang paling populer. Anda perlu uang untuk kebutuhan yang amat sangat darurat. Tapi rekening Anda cuma berisi seperlima dari kebutuhan. Maka dengan bismillah, Anda sedekahkan semua isi rekening. Entah dengan cara bagaimana, tiba-tiba muncul orang baik yang menutupi semua kebutuhan darurat Anda. Nah, saya percaya kok mekanisme-mekanisme meta-rasional semacam itu kadangkala ada, dan bisa terjadi. Kadangkala, lho ya.”
“Lha itu nyatanya sampeyan percaya gitu?”
“Iya, tapi skalanya kecil, sebatas menjadi solusi-solusi yang bersifat personal. Sekarang bandingkan. Kalau sebuah negara kekurangan duit, dana APBN cuma seuprit, apa iya bisa diselesaikan dengan sedekah? Kalau memang begitu, bilang saja ke Bu Sri Mulyani. Itu tuh, biar segala program infrastruktur ambisinya Pak Jokowi cepat selesai, sedekahkan saja semua isi kas negara sampai sereceh-recehnya. Kasih semuanya ke Zimbabwe, gitu. Coba kita lihat apakah setelah itu mak bedunduk kas negara jadi luber-luber.”
“Wah sampeyan bercandanya keterlaluan, Syekh.”
“Lhooo ini bukan bercanda, Mase. Ini contoh. Kalau memang karomah dan keajaiban bisa dipakai sebagai jalan keluar dalam mengatasi persoalan besar, dalam skup yang luas, ya silakan dijajal saja. Tapi kalau menurut saya contohnya jelas. Kanjeng Nabi menyebarkan ajarannya juga pakai berjuang, Mas. Pakai metode komunikasi, pakai diplomasi, pakai militer, pakai strategi, taktik, dan kerja keras. Bukan cuma modal petir dan hujan batu!”
Sialan. Dari tadi orang di depan saya ini ngocehnya sok-sokan banget. Demi membela kehormatan guru saya, lebih baik kami pulang saja. Saya pun berdiri.
“Ya sudah, Syekh. Sepertinya kita memang susah nyambung. Saya tahu kok sampeyan ini cuma pura-pura percaya ini-itu, padahal sebenarnya ya memuja akal banget. Liberal. Pantesan saja nggak punya karomah.”
Syekh Abu Hayyun diam mendengar kalimat mutung dari saya. Dia, lagi-lagi, cuma tersenyum kecil.
Sambil tampak abai pada kami bertiga, Syekh mengulurkan tangannya meraih cangkir kopi. Persis sebelum kopi dingin itu ia seruput, dada saya berdesir. Ada segaris uap tipis muncul dari cangkir. Air hitam pekat di dalamnya mendidih.