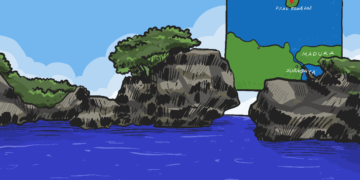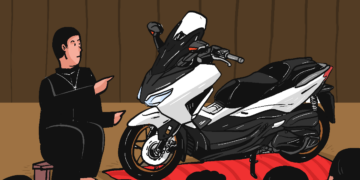MOJOK.CO – Jawacana berusaha memanfaatkan asumsi kelangkaan, keeksotisan, dan keantikan untuk menghadirkan aksara Jawa. Ingat, barang yang antik dan langka itu tinggi nilianya.
Saya akan memulai tulisan ini dengan menceritakan kegiatan kami di circle aksara Jawa. Kurang lebih empat tahun belakangan, saya mendirikan Jawacana, organisasi independen sastra dan budaya Jawa yang salah satu kegiatannya menggelar kelas baca dan tulis aksara Jawa.
Sebelum pandemi, kami rutin menggelar kelas mingguan, berkolaborasi dengan Sanggar Seni Kinanti Sekar sebagai tempat belajarnya. Ketika tren sekolah online, Jawacana juga berkolaborasi dengan kelaspedia.id untuk menggelar kelas daring. Selain itu, kami juga menerbitkan cergam anak-anak beraksara Jawa, merilis tabloid bahasa Jawa, merilis lagu-lagu dengan subtitle aksara Jawa di YouTube. Kami pun juga bergandengan dengan gerakan dan komunitas independen serupa yang tersebar di Bantul, Sleman, Kulonprogo, dan Gunungkidul.
Komunitas-komunitas swadaya dan swadana di DIY ini kadang me-nyambat-kan hal yang sama. Yaitu “susah jualan” karena kursus aksara lokal susah dijadikan komoditas menjanjikan. Memang benar, kami juga sepenenuhnya sadar, gerakan seperti ini tidak mendatangkan keuntungan secara ekonomi. Sampai saat ini, Jawacana juga masih gagah untuk tombok menghonori para mentor dan menyediakan fasilitas pengajaran. Namun, spirit dan visi kami memang melakukan semua ini demi kerja budaya. Kerja budaya itu tidak boleh melihat untung dan rugi. Kalau mau untung, namanya bisnis budaya.
Lalu ketika ada pertanyaan “Ngapain ngurusin aksara Jawa? Ngapain mau repot-repot ngurusin barang yang nggak laku?”
Jawaban saya hanya satu: CINTA!
Mungkin dianggap berlebihan, tapi ini jujur. Bahkan sebelum menikah, saya pernah mendeklarasikan ke calon istri bahwa cintaku terbagi tiga: “Kamu, sastra Jawa, dan Manchester United.” Itu harus dibagi adil, tidak bisa diganggu gugat.
Berjibaku secara independen untuk hidup dan menghidupi aksara Jawa adalah wujud kecintaan itu. Untuk senantiasa repot menghadirkan aksara Jawa di ranah publik juga merupakan inisiatif agar eksistensinya tetap terjaga. Agar tetap “ada”. Jadi, jika muncul pertanyaan, apakah aksara Jawa masih ada di Jogja? Kami bersama-sama komunitas dan para pegiat akan serentak menjawab: MASIH ADA!
Meski harus diakui dengan kebesaran hati bahwa untuk menjadikannya tetap ada di tengah modernitas dan globalisasi ini dibutuhkan energi yang luar biasa. Supaya tidak kehilangan ruangnya untuk tetap hidup, walaupun ruang itu gelap dan senyap, namun api harus tetap dinyalakan, bukan?
Saya pribadi juga sadar penuh bahwa posisi aksara Jawa sebagai medium tulis tersisihkan dari aksara dan huruf lain. Kita jelas harus mengakui supremasi alfabet (huruf latin) dengan segala dayanya mampu menjadi media tulis bahasa primer di seluruh dunia.
Bahkan harus diakui pula kehadiran aksara-aksara asing justru lebih populer dan mampu meraih fungsi lebih strategis. Seperti aksara Arab dan Korea, misalnya. Aksara yang pertama berhasil menempatkan makna dan fungsinya di Jawa melalui pendekatan agama. Aksara yang kedua, popularitasnya meroket berbarengan dengan booming budaya Korea. Lantas bagaimana dengan aksara Jawa?
Sebagai aksara lokal, idealnya, aksara ini jadi tuan rumah, misalnya sebagai medium tulis bahasa di Jawa. Tapi, kami di Jawacana sepenuhnya sadar. Untuk mewujudkan hal tersebut membutuhkan perubahan sangat besar.
Kami menganggapnya sebagai rencana jangka panjang, alih-alih menyikapinya sebagai impian utopis. Menjadikan aksara lokal berposisi seperti aksara Arab di Timur tengah, atau seperti Kanji dan Hangeul di Asia Timur butuh kerja keras.
Berhadapan dengan wawasan kesatuan bahasa Indonesia pun aksara Jawa akan menemui gesekan. Negara juga akan kerepotan ketika secara sosial dan hukum harus mengubah posisinya sebagai aksara utama.
Bagaimana jika aksara Jawa harus bergesekan dengan aksara Arab dalam hal keagamaan di Jawa? Atau berhadapan dengan aksara latin dalam bahasa sehari-hari? Apakah kita semua siap menghadapi friksi yang mungkin terjadi jika hal itu dipaksakan?
Gerakan revolusioner mengutamakan aksara lokal di Jogja saja pasti akan memercikkan bara konflik. Kita mesti belajar bahwa setiap revolusi membuahkan korban. Bisa saja korban tenaga, waktu, biaya, dan korban sosial.
Kalau dibandingkan dengan aksara Arab, Jepang, Cina, Korea, atau Thailand, aksara lokal di Jawa memiliki kasus berbeda. Kondisi penjajahan dari bangsa asing dan konsep multikultur dan multietnis yang disepakati sejak Indonesia merdeka menjadikan aksara Jawa juga harus memosisikan dirinya seperti ini.
Orang Jawa sebagai bangsa mayoritas di Indonesia harus hati-hati akan hal ini. Jangan terjebak chauvinisme. Memang benar, aksara dan budaya Jawa pernah berada di puncak kejayaan dan posisi unggul di Nusantara. Namun, jika keadaan tersebut mau dipaksakan untuk dikembalikan lagi tentu akan berseberangan dengan konsep keberagaman NKRI.
Saya pribadi sebagai pegiat kebudayan Jawa tidak termasuk golongan yang berambisi dengan semangat renaissance Jawa. Pikiran untuk mengembalikan kejayaan Majapahit dan Singosari itu delusional jika diterapkan untuk kondisi sosial masyarakat hari ini.
Kita telah sepakat untuk menjadi kosmopolit, beragam, toleran. Begitu juga dengan penempatan aksara Jawa di Jawa. Alih-alih sibuk dengan cita-cita jangka panjang penuh fantasi, namun berpotensi konflik dan membutuhkan “revolusi budaya”, Jawacana mengambil langkah-langkah strategis pendek dalam menghidupi aksara lokal. Kami menawarkan strategi budaya.
Hegemoni kolonialisme (dalam hal ini bukan saja penjajahan fisik seperti perang, namun apa yang sering disebut neokolonialisme, yaitu penjajahan budaya) terhadap budaya Jawa memang memunculkan stereotipe bahwa segala hal yang berbau Jawa adalah kuna, irasional, tidak beradab, tidak modern.
Namun, segala hal yang negatif tersebut juga memunculkan asumsi bahwa budaya tradisi lokal itu langka, eksotis, antik. Dalam strategi kami, stereotipe tersebut bukan hal yang harus secara frontal dilawan. Kami memilih untuk “menungganginya”. Ride the wave.
Jawacana berusaha memanfaatkan asumsi kelangkaan, keeksotisan, dan keantikan untuk menghadirkan aksara Jawa. Ingat, barang yang antik dan langka itu tinggi nilianya.
Kenyataan hari ini di Jogja, masyarakat masih memandang aksara Jawa sebagai sesuatu yang sensual dan fenomenal secara bentuk dan fungsinya. Kondisi tersebut justru harus dimanfaatkan. Menjadikan fenomena aksara Jawa sebagai aset untuk mempopulerkannya, sekaligus menjadikan keunikan dan keantikannya sebagai senjata untuk mempromosikan budaya dan pariwisata Jawa.
Sederhananya, kami merelakan jika aksara lokal masih menjadi sebatas fenomena visual pada slebor becak, papan nama jalan, ornamen pariwisata, atau pada tato di kulit. (Banyak yang konsultasi tato aksara Jawa ke saya).
Masyarakat masih dalam fase “menyukai dan mengagumi”. Kenapa tidak kita tambah saja porsinya? Tentunya tidak asal banyak secara kuantitas. Secara kualitas juga harus dipikirkan.
Jika dianggap sebagai “simbol grafis”, kualitas desain aksara lokal juga harus bagus. Jogja itu kota seniman, pasti banyak yang bisa desain dengan bagus. Selaras dengan tren posting foto medsos, kita hadirkan visual aksara lokal ini sebagai aset budaya yang Instagramable.
Inilah misi Jawacana sebagai strategi budaya jitu jangka pendek dalam memasarkan aksara Jawa. Memperbanyak hadirnya fenomena visual, baik di medsos, YouTube, di jalan-jalan, di mall-mall, di desain visual. Bahkan mungkin bisa jadi solusi pada mural, jadi hiasan kota, sekaligus kritik terselubung tapi tidak dihapus, karena yang disindir mungkin tidak bisa baca aksara Jawa.
BACA JUGA 3 Versi Asal Muasal Aksara Jawa dan tulisan menarik lainnya di rubrik ESAI.