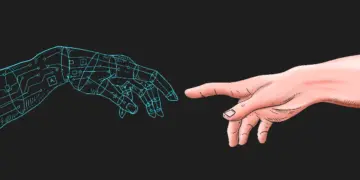MOJOK.CO – Bos perusahaan teman saya bilang, “Lulusan filsafat itu kan bisanya cuma mikir, dan yang agak lumayan, bisa nulis. Selain itu mereka bisa apa?”
Kesuraman lulusan filsafat di Indonesia ternyata tidak hanya dirasakan oleh mereka yang bergelar sarjana. Memegang ijazah M. Phil (master filsafat) sekalipun—sungguh, gelar ini terkadang bikin orang bergidik—dari kampus sekaliber Universitas Gadjah Mada (UGM) ternyata sampai saat ini juga masih sama masalahnya.
Pada wisuda periode Juli lalu, Program Studi Magister Ilmu Filsafat UGM meluluskan dua mahasiswa. Dan sial, saya salah satunya.
Sampai saat ini, saya dan teman saya yang satunya itu, masih luntang-lantung menanti perusahaan yang mau menerima kami. Saya sendiri sudah mengajukan lamaran ke puluhan perusahaan di beberapa kota, tapi tak satu pun ada yang sekadar memanggil untuk wawancara.
Di samping itu, peluang untuk menjadi dosen pun tak serta-merta tersedia. Belum lagi, untuk sekadar menjadi tenaga pengajar ban serep di UGM pun tak gampang. Butuh relasi yang benar-benar kuat untuk mencapai itu.
Maka, tiap hari pun saya lewati hanya dengan makan, tidur, buka laptop mencari lowongan, makan lagi, berak, makan lagi, buka laptop lagi, tidur lagi, makan, berak, dan begitu seterusnya. Ya, sesekali cebok tentu saja—eh, dua kali ding.
Semua itu bukannya tidak enak. Enak sekali, malah. Cuma masalahnya, dari mana uang buat makan dan membayar kos, kalau bukan hanya modal dengkul, lalu telepon ortu buat ngirim uang?
Sungguh, hidup seperti ini terasa sangat menyedihkan. Meski uang ada, tapi sulit rasanya menelan nasi hasil minta dari ortu. Kalau boleh saya akui, menjadi pengangguran berijazah S2 seperti ini jauh lebih sampah daripada pengemis sekalipun. Kadang-kadang saya berpikir, betapa menyesal saya melanjutkan kuliah kalau ujung-ujungnya seperti ini.
Ya, sebelum saya berkubang di lumpur pengangguran seperti ini, dulu saya sempat sudah mapan bekerja sebagai wartawan di sebuah surat kabar ternama di Kota Medan. Bermodal gelar sarjana Ilmu Komunikasi yang saya peroleh dari Universitas Sumatera Utara (USU), tak butuh waktu lama bagi saya untuk dipanggil.
Tahun demi tahun berlalu dan saya pun jadi wartawan paling produktif di kantor. Lalu, karena beberapa faktor, Pemimpin Redaksi mendapuk saya sebagai wartawan liputan khusus yang dapat bagian halaman depan.
Jika boleh berandai-andai dan berhitung, saya tinggal sedikit lagi diangkat jadi redaktur—posisi yang cukup mentereng untuk saya waktu itu. Apalagi soal besaran gaji, sudah lebih dari cukup untuk sekadar bayar kos dan kebutuhan bulanan.
Lebih dari itu saya juga bisa menyisihkan sebagian untuk kencan, menabung, dan belanja di mal. Sumpah, saya ingin membuktikan wartawan juga bisa ke mal tanpa harus pakai alibi liputan saat itu.
Masalahnya karena ada sedikit konflik di kantor, dan kebetulan saya yang waktu itu sedang idealis-idealisnya, saya jadi kepikiran ingin mundur. Pada saat yang sama, muncul keinginan saya untuk kuliah lagi.
Kejemuan itu mencapai puncaknya tepat berbarengan dengan keinginan saya untuk kuliah yang makin menggebu-gebu. Maka, dengan tekad yang sudah dibulatkan, saya pun mendatangi pemred saya untuk berpamitan. Pemred saya waktu itu tak bisa bilang apa-apa, kecuali merestui kepergian saya.
Sampai di sini, segalanya tak ada masalah sama sekali. Bukankah sekolah, menuntut ilmu, itu baik?
Ya, benar, memang baik. Tak tanggung-tanggung, ilmu yang saya tuntut adalah jurusan filsafat.
“Kok ambil filsafat? Nanti susah lho. Kan kamu S1-nya Komunikasi. Sudahlah, ambil komunikasi saja. Nanti kalau kamu mau mengajar, lebih gampang. Apalagi profesi kamu jurnalis, lebih cocok,” ujar salah seorang teman.
Dengan idealisme menggebu-gebu, saya menampik mentah-mentah saran itu dan bersikukuh bahwa menuntut ilmu bukanlah untuk kegunaan praktis, melainkan semata karena kecintaan terhadap ilmu.
“Ya, kalau begitu, ya sudahlah,” katanya.
Lalu, berangkatlah saya ke Yogyakarta. Dengan modal tabungan selama beberapa tahun, saya bisa menyanggupi biaya kuliah semester pertama. Namun selebihnya, dengan muka tebal saya terpaksa meminta kepada ortu untuk biaya semester 2, 3, dan 4, karena gaji saya sebagai kontributor sepakbola di sebuah media online, tidak dapat menutupi besaran biaya semester.
Untungnya, beban ortu tidak saya tambahi dengan kuliah yang molor. Saya tamat tepat waktu, bahkan paling cepat dibanding 10 teman lainnya di kelas. Saya tak harus membayar biaya kuliah semester 5 seperti mereka yang sampai saat ini belum juga tamat. Semua itu berkat motivasi saya ingin segera bekerja untuk membebaskan beban ortu.
Tetapi ternyata, dan di sinilah kenelangsaan saya bermula. Menjadi seorang master filsafat tak lantas membuat saya dilirik oleh perusahaan. Dalam benak saya, barangkali para petinggi perusahaan yang saya lamar itu bergidik bila harus menerima saya sebagai karyawan mereka.
Bisa jadi mereka cemas; ini anak kalau diterima nanti bukannya malah kerja, dia malah mempertanyakan kenapa pekerjaan ini harus dikerjakan.
Pikiran negatif seperti itu baru satu. Akibat tak dipanggil-panggil, berbagai pikiran negatif lain pun terus menghantui saya. Tapi yang paling bikin saya penasaran adalah, sebenarnya seperti apa perusahaan-perusahaan memandang mahasiswa lulusan jurusan filsafat? Apalagi yang sampai kecemplung di sekolah masternya seperti saya?
Saya mendapatkan titik terang atas pertanyaan itu minggu lalu, ketika seorang teman—yang saya tanyai apakah perusahaan tempatnya bekerja mau menerima saya atau tidak—menyampaikan kepada saya bahwa atasannya bilang, “Lulusan filsafat itu kan bisanya cuma mikir, dan yang agak lumayan, bisa nulis. Selain itu mereka bisa apa?”
Begitu kata-kata atasan dari teman saya itu yang dia screen-shot dan kirimkan ke saya. Sekadar untuk diketahui, teman saya itu bekerja di perusahaan industri makanan yang berbasis di Jepang. Sebagaimana industri pada umumnya, pastilah ada berbagai posisi di dalamnya.
“Tapi, kata Bos, nggak ada satu pun posisi yang butuh lulusan filsafat,” imbuh teman saya itu.
Sebegitu sepelekah orang-orang memandang lulusan filsafat? Mungkin tidak semua. Tapi yang jelas, fakta bahwa lulusan filsafat kurang diminati dibanding lulusan jurusan lain, bahkan dibanding sastra atau tata boga misalnya, adalah suatu hal yang agaknya sulit untuk dibantah lagi.
So, sampai kapan keadaannya seperti ini? Apakah jurusan filsafat memang bukan untuk mencari pekerjaan? Ya memang bukan ternyata—apalagi sampai S2 seperti saya. Kalau mau kuliah langsung kerja, ya lebih baik di BSI saja sana.
Oleh karena itu, saya pikir perlu dibuat keterangan ketika penerimaan mahasiswa baru atau ketika seleksi masuk PTN dibuka untuk jurusan ini.
Keterangannya kurang lebih seperti ini: “Kisanak, coba pikirkan ulang untuk memilih jurusan ini karena jurusan ini bukan pilihan untuk memudahkan cari pekerjaan, tapi kalau kamu ingin dianggap bisa mikir saja, ya sudah lanjut saja.”
Atau, biar lebih gamblang: “Mau jadi pengangguran bijaksana dan berbudi luhur? Masuk yuk jurusan filsafat? Sekarang ada ekstraknya lho, bisa bikin betah sampai S2 lagi.”
Lantas, bagaimana pula nasib lulusan filsafat di masa depan?
Membayangkan itu membuat saya ngeri jika berkaca pada bagaimana Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan telah menggantikan banyak peran manusia, mulai dari penjaga loket hingga dokter.
Tetapi tunggu dulu, justru di situlah angin segar asa itu muncul. Deccan Chronicle melansir kabar bahwa pada tahun 2030, sesuai perkiraan para ahli, lulusan filsafat akan laris manis di pasar kerja.
Lah kok bisa?
“Seiring dengan merebaknya pemanfaatan AI, perusahaan-perusahaan akan membutuhkan lebih banyak lulusan filsafat untuk mengisi posisi ‘Chief Ethics Officer’ (pegawai yang mengurusi masalah etika), untuk melihat output yang terkait dengan AI melalui lensa manusia,” demikian prediksi Pratik Dattani, Managing Director Economic Policy Group, sebuah perusahaan konsultasi ekonomi dan strategi. Prediksinya memang terdengar sangat bombastis—saya nggak mau nyebut utopis ah.
Lalu bagaimana dengan di Indonesia? Mungkinkah ini alasan kenapa sampai sekarang jurusan filsafat masih tetap dibuka? Padahal keluhan seperti saya ini rupanya bukan kali ini saja pernah berkumandang.
Atau jangan-jangan jurusan ini memang sedang menyambut potensi pasar untuk 2030 itu?
Jadi, sembari menunggu tahun 2030, untuk saat ini kabar itu cukup lumayan buat menenangkan pikiran saya. Setidaknya memberi saya napas untuk terus hidup sampai 12 tahun lagi.