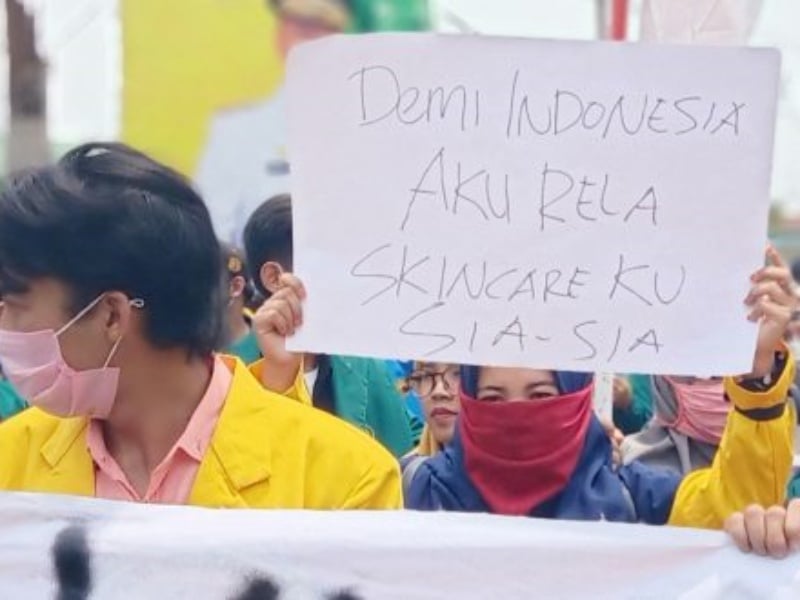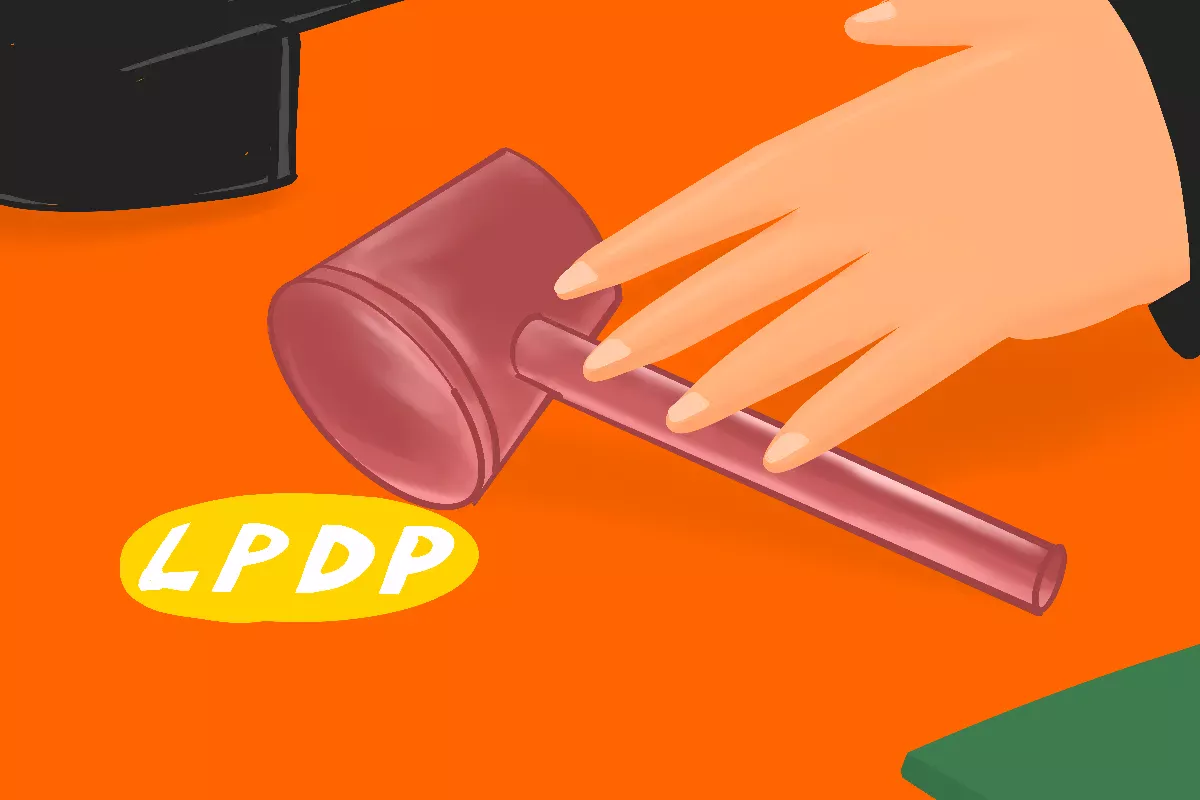Bagaimana sih sebetulnya manusia, kita ini, harus menjalani hidup? Awalnya ini bagaimana. Kok tiba-tiba saat dewasa kita mengisinya dengan sambatan-sambatan setiap saat.
Imajinasi saya lalu melesat jauh ke masa silam. Saya menemui diri saya hidup pada zaman purba. Katakanlah, saya lahir dari batu kali seperti Sun Gokong. Anggap saja saya tak punya ibu-bapak. Sehingga kelahiran saya tak perlu dimulai dari tahap bayi yang menangis. Saya langsung gede begitu aja deh. Hehehe. Tentu dalam keadaan telanjang di belantara hutan.
Tiba-tiba, kemungkinan pertama yang terjadi sesaat setelah kelahiran dari batu itu adalah saya merasa lapar. Maka, ada naluri untuk meniru hewan-hewan dalam melakukan perburuan mencari makan. Kemudian mungkin tubuh saya yang purba ini kedinginan, dan saya mencari dedaunan atau bahkan kulit macan untuk menghangatkan badan saya. Saya butuh berlindung dari hujan atau terik matahari, maka saya bikin gubuk.
Sudah, cukup sesimpel itu. Sandang, pangan, dan papan. Apa lagi hidup ini?
Oh, mungkin nanti saya ketemu manusia purba dalam bentuk lainnya. Kita kawin. Dia hamil dan melahirkan manusia purba lagi. Dan kita hidup bersama. Saling menjaga. Bahagiakah? Mungkin biasa saja. Atau minimal kita hidup tak kenal sakit hati dan baper. Ngoahaha.
Nah, kita hidup, tiba-tiba bermasalah (lapar, kedinginan, dan merasa terancam), lalu dibantu oleh akal untuk menemukan solusinya. Hidup masih pada tataran hewaniyah. Sebatas memenuhi kebutuhan, memburu makanan, bertahan hidup, dan berkembang biak. Sampai pada akhirnya manusia sadar bahwa ia berbeda dengan hewan. Apa yang membedakannya?
Manusia punya akal dan hati— yang membuat ia bisa bertanya. Menciptakan pertanyaan. Sementara tak mungkin hewan bisa bertanya. Dengan pertanyaan-pertanyaan itu kita bisa membangun teknologi dan bahkan peradaban.
“Bagaimana ya cara biar bisa mendapat ikan di kali?” Lalu kita bikin teknologi tombak.
Pertanyaan berkembang lagi; “Bagaimana ya mendapat ikan banyak dalam waktu yang cepat?” Kita jawab dengan teknologi jala. Begitu seterusnya.
Pertanyaan-pertanyaan itu menggiring manusia untuk mencipta teknologi yang pesat dan canggih seperti yang bersama kita nikmati sekarang ini. Lampu, motor, mobil, pesawat, dan internet.
Daya cipta manusia memang luar biasa. Ironisnya, justru teknologi juga memperumit hidup kita sendiri. Tepatnya, ketergantungan kita terhadapnya. Dimanjakan. Pertanyaan-pertanyaan semakin terjawab oleh teknologi. Tapi, manusia semakin asing untuk mempertanyakan keberadaannya sendiri.
“Manusia semakin suka mempersulit hidupnya sendiri,” seru Diogenes, seorang filsuf (abad ke-6 SM) yang mendapat julukan ‘Si Anjing’ dari Athena.
Karena terlanjur dianugerahi akal, saya juga ingin belajar seperti kalian. Saya ingin memulainya dengan mengisahkan ulang sedikit cuplikan kehidupan Diogenes. Tentu dengan harapan bisa mengingatkan kembali kepada saya pribadi. Sebagai bekal untuk menjalani hidup sehari-hari. Terutama di tengah perasaan-perasaan yang selalu sambat terhadap apapun yang tengah kita lakukan.
Kenapa memilih Diogenes? Bagi saya, ia amat kuat bertahan hidup dengan cara ‘purba’ dan memaksimalkan akal di tengah masyarakat yang begitu gegas.
Berikut saya tulis cuplikan riwayat hidup Diogenes.
Ia lahir di Sinope, salah satu kota pelabuhan di Turki bagian selatan. Menginjak usia remaja, ia bersama keluarganya diusir dari Turki. Sebab, ayah Diogenes terjerat kasus pemalsuan uang saat itu. Mereka sekeluarga pindah ke Athena, ibukota Yunani. Nah, disinilah ‘kegilaan’ hidup Si Anjing ini dimulai.
Saat itu adalah zaman Yunani Kuno era Kekaisaran Alexander The Great. Atau orang kini lebih mengenalnya Alexander Agung. Yaitu seorang Raja Kekaisaran Makedonia, salah satu negara di Yunani bagian laut timur. Alexander Agung adalah orang besar yang pada zaman keemasannya menguasai lebih dari sepertiga dunia.
Stop disini dulu. Saya tidak akan bercerita panjang lebar soal Alexander. Tapi, mungkin nanti akan sedikit saya singgung beberapa anekdot interaksi antara Diogenes dan Alexander Agung.
Selama hidupnya di Athena, Diogenes menggelandang di tengah kota. Kalau tak mau disebut rumah –ia bertempat tinggal di gentong bekas yang hanya cukup untuk satu tubuhnya saja. Ia hidup bersama anjing-anjing liar perkotaan.
Diogenes sengaja memilih jalan hidupnya sendiri. Meski menggelandang, ia tetap dihormati oleh orang-orang kota. Karena kecerdasannya. Omongannya lugas dan ceplas-ceplos. Kepada siapa saja ia tak takut untuk mengungkap kebajikan.
Sebab, di mulut para filsuf seperti Diogenes lah, pertanyaan-pertanyaan akan kembali kepada diri manusia sendiri. Tanda tanya akan membantu mengembalikan manusia pada fitrahnya.
Diogenes tak bekerja seperti orang pada umumnya. Ia benar-benar hidup menggelandang. Bahkan untuk makan sehari-hari, Diogenes meminta-minta kepada orang-orang. Kepada yang memberinya makan, ia selalu bertanya terlebih dulu,”Apa aku saja yang hari ini kau kasih makan?”
Ia juga berkata,”Aku sengaja meminta makan. Agar orang-orang bisa melatih dirinya untuk rendah hati.”
Sebagaimana filsuf, ia mencintai kebijaksanaan. Adalah manusia bebas. Merdeka. Diogenes terkenal dengan gaya sinismenya (bukan dalam pengertian yang selama ini kita maksud; nyinyir. Tapi, sinisme yang kritis, masuk akal, dan punya gagasan besar)
Baginya, orang hidup harus merasa cukup dengan dirinya sendiri (bukan dalam artian mengabaikan yang lain. Melainkan, tak bergantung kepada di luar dirinya sendiri). Hanya bergantung kepada Tuhan.
Selama hidup di gentong besar itu, ia hanya memiliki satu barang. Yakni cangkir kecil untuk tempat minum. Diogenes berpikir, bahwa orang-orang hidup terlalu memperumit diri mereka sendiri dengan barang-barang yang sebetulnya tidak terlalu penting. Bahkan ketika Diogenes melihat gelandangan lain bisa minum dengan tangan, ia lalu membuang cangkir yang dimilikinya.
“Orang kaya adalah orang yang rasa memilikinya paling sedikit. Semakin banyak barang dalam rumahmu, semakin kau miskin, karena semakin banyak yang kau urusi,” katanya.
Orang suka memperumit segala sesuatu pemberian Tuhan yang sebetulnya amat sederhana ini. Rasanya seperti tak bisa hidup tanpa benda-benda. Ketergantungan kita terhadap gadget dan internet, misal. Bagaimana rasanya jika kuota internet habis? Kita merasa butuh baju satu almari, padahal lima saja cukup. Belum lagi kita merasa tidak PD kalau tak memakai pakaian yang brandnya tak terkenal. Selera kita justru memperumit hidup.
Maka saat kita sudah dibelenggu oleh obsesi tentang banyak hal yang diluar diri itulah kita kehilangan kemampuan alamiah sebagai manusia. Semakin asing dengan rasa manusia sendiri. Bahkan kita rela menggadai apapun untuk mendapatkan semua ambisi itu.
Pernah saat Diogenes memakan ubi dari sampah, ia dipergoki oleh seorang pelayan kerajaan. Lalu pelayan itu mengatakan,”Kalau kau mau jadi hamba raja, pastilah makananmu terjamin dan tak perlu kau makan ubi sampah itu,”
Diogenes lugas menjawab,”Mestinya kau yang perlu belajar makan ubi sampah ini. Supaya kau tak menjilat-jilat raja,”
Dan di suatu siang yang bolong, Diogenes mengelilingi pusat kota dan pasar. Sambil menenteng lampu di tangan kanannya dan berteriak-teriak kepada orang-orang,”Dimana ada manusia? Aku ingin bertemu manusia.”
Lalu, apakah harus ‘gila’ seperti Diogenes untuk menjadi manusia?
Ya, nggak. Mana mungkin kita mau jomblo seumur hidup. Hanya saja, Diogenes punya metode agar manusia hidup dengan cara hidup yang baik:
- Menjadi manusia alamiah. Diogenes menyarankan untuk selalu memakai standar minimal dalam hidup. Sederhana. Jangan mau terikat pada aturan yang ribet. Berambisi memiliki apapun. Sebab ambisi lah yang membuat manusia menjadi bukan manusia lagi. Karena ini hidup Diogenes dikenal dengan hidup yang berambisi untuk tidak punya ambisi.
- Pengendalian diri. Atau dalam Islam kita mengenalnya puasa/tirakat. Melatih untuk tidak melakukan apa yang kita senangi. Menahan diri terhadap kesenangan-kesenangan yang tidak penting. Yang sebetulnya semua kesenangan itu adalah ornamen-ornamen kejahatan. Maka rasa sakit dan lapar amat diperlukan untuk melatih moral manusia.
Diogenes hidup dalam keheningan yang luar biasa. Tindakan-tindakannya tak terpengaruh oleh rasa suka atau tak suka. Ia sama sekali tak gentar, tak malu, untuk berlaku yang tidak sesuai dengan orang kebanyakan.
Oleh karena itu, Si Anjing ini dihormati. Bahkan oleh Alexander Agung ia kerap dihampiri di gentong besarnya itu. Banyak anekdot yang lucu dan penuh hikmah dari interaksi antara Diogenes dan Alexander Agung.
Di suatu pagi, Diogenes sedang leyeh-leyeh di gentong besarnya itu. Lalu, Alexander Agung datang menghampirinya. Sang Kaisar menawarkan kepada Diogenes.
“Hei Diogenes, aku mau menawarkan kepadamu apa saja yang kau inginkan. Sebutkanlah, aku pasti memenuhinya.” kata Alexander Agung yang berdiri persis di depan mulut gentong tempat tinggal Diogenes.
Lalu, kau tahu apa jawaban Si Anjing ini? Dia lugas meminta kepada Sang Kaisar,”Hei kaisar. Aku minta padamu bergeserlah dari hadapanku. Aku sedang butuh cahaya mentari pagi,”
Hubungan keduanya memang begitu dekat. Alexander Agung ini amat senang dan terkesan dengan sosok Diogenes. Hingga ia pernah berkata,”Andai aku bukan Alexander Agung, maka aku berharap aku adalah Diogenes.”
Mendengar itu, Diogenes menjawab,”Andai aku bukan Diogenes maka aku berharap aku tetap Diogenes.”
Saking terkesannya, Alexander Agung pun terindikasi dipengaruhi oleh pikiran Diogenes. Bahkan, ia pernah berpesan kepada orang terdekatnya di kerajaan. Alexander Agung berkata,”Nanti jika aku mati dan dimasukkan dalam peti, tolong keluarkanlah satu tanganku. Biar semua orang tahu. Bahwa aku yang menguasai sepertiga dunia ini tak membawa apa-apa juga saat mati.”
Biasanya kita dibikin sambat oleh kesukaran-kesukaran yang kita hadapi. Juga oleh banyak keinginan dan ambisi yang belum selesai. Saat itu kita lupa bersyukur. Nah, kita juga amat mudah bersyukur jika melihat orang-orang yang nasibnya tidak seberuntung kita. Kita lebih mudah bersyukur saat melihat orang-orang yang hidupnya susah.
Kalau kita sambat dengan pekerjaan, biasanya kita lebih mudah bersyukur saat melihat orang-orang yang masih pengangguran dan belum dapat pekerjaan. Untuk bersyukur saja saat ini kita merasa perlu untuk menginjak yang lain. Jadi, mari teman-teman, dengan segala kesambatan-kesambatan ini mari bersama kita injak hidup gelandangan Si Anjing Diogenes. (*)
BACA JUGA Memotret Buku lalu Menguploadnya di Media Sosial itu Sebenarnya Buat Apa, Sih? atau tulisan Khotib Nur Mohamad lainnya.
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.