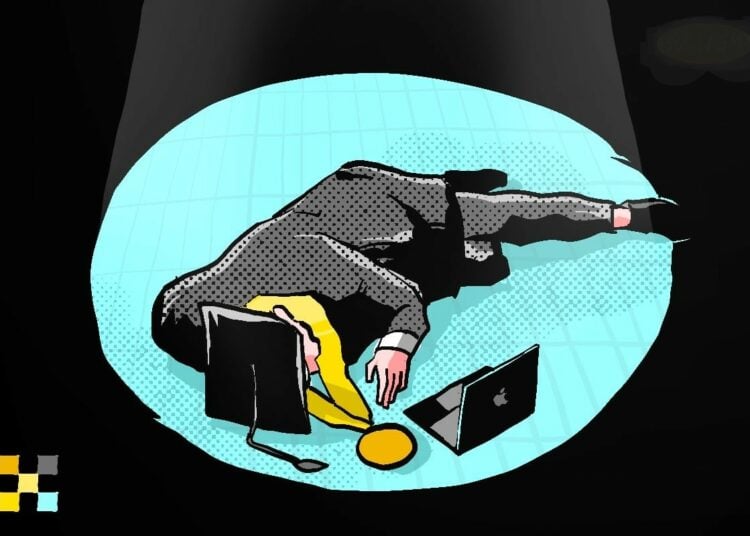Kuliah mahal-mahal, ujung-ujungnya jadi sarjana nganggur
Sialnya, setelah melewati momen bangga dan haru wisuda pada 2023, Dita tahu betul bahwa hidup yang sebenarnya baru dimulai. Ya, dunia kerja.
Apalagi ia juga mulai menyadari bahwa “wangsit” guru BK empat tahun sebelumnya seperti omong kosong. Atau, kalau mau memilih kata yang lebih sopan, kurang relevan di zaman dia sekarang.
“Ya, gimana ya. Lulusan keguruan biarpun lulus cepet dan nilai bagus, mentok jadi honorer. Kalaupun mau cari kerjaan lain, susah. Kami kepentok ijazah S.Pd,” ungkanya.
Sepanjang 2023 saja, misalnya, Dita mengaku sudah kirim lamaran ke puluhan bimbel bahkan perusahaan. Sebab, ia tahu kalau kerja di sekolah sebagai guru honorer, gajinya tak seberapa.
Namun, tak ada satupun email lamaran pekerjaannya yang berbalas. Cari alternatif di Linkedin atau Glints pun juga sama aja.
“Apalah daya. Kami yang ijazah keguruan ini kudu bersaing dengan lulusan lainnya yang gelar sarjananya lebih mentereng,” kata lulusan PTN ini.
Mirisnya, Dita hanyalah satu dari sekitar 1 juta sarjana di seluruh penjuru Indonesia yang menyandang gelar “sarjana nganggur”. Pengalaman Dita, seolah juga mengamini data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2024 yang menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan universitas masih berada di angka 5,32%.
“Coba ditotal aja, aku 7 semester kuliah rata-rata bayar 5 juta per semester. Ini sih hampir setara 15 kali UMR Jogja. Tapi sia-sia, karena sampai hari ini aku masih nganggur. Nggak jelas.”
Sarjana nganggur korban inflasi IPK?
Kisah Dita adalah cerminan gamblang dari fenomena “inflasi IPK” yang belakangan banyak disorot. Guru Besar Sosiologi Pendidikan Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya, Tuti Budirahayu, menganalisis bahwa IPK tinggi kini tak lagi jadi jaminan mutlak untuk mendapatkan pekerjaan.
“Menurut saya, kenapa IPK tinggi kok tidak berbanding lurus dengan mendapatkan pekerjaan, karena memang ada kapitalisme pendidikan tinggi,” ujar Tuti, dikutip dari Detik.com.
Ia menjelaskan, PTN dituntut untuk menerima dan meluluskan mahasiswa sebanyak mungkin, yang membuat institusi lebih fokus pada kuantitas daripada kualitas. Selain itu, sistem akreditasi juga berperan, karena kampus cenderung memberikan nilai tinggi demi menjaga status akreditasi.
Pun, Tuti tak memungkiri kalau IPK memang sering menjadi “saringan pertama” bagi perusahaan dalam menerima pekerja. Namun, kisah Dita membuktikan, saringan itu tak selalu efektif.
Tuti menekankan bahwa kualitas mahasiswa seharusnya tidak hanya diukur dari IPK semata. Tapi juga dari bagaimana aktivitas dia dalam kegiatan kemahasiswaan, organisasi, atau Sistem Kredit Prestasi (SKP).
Sementara bagi Dita, seperti yang ia katakan di awal, IPK besar cuma menjadi kutukan alih-alih prestasi. Sebab apa gunanya IPK tinggi, tapi buat dapat kerja saja susahnya setengah mati.
“Apakah aku menyesal? Ya, jelas, jawabannya sangat menyesal. Karena jika dulu aku nekat memilih jurusan seni, kalaupun nganggur aku pernah kuliah sesuai passion,” pungkasnya.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA: Lulusan S2 UGM dengan IPK Tinggi Jualan Bakso di Jogja Kala Mimpi Jadi Dosen Tertunda atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan.