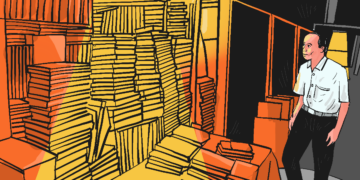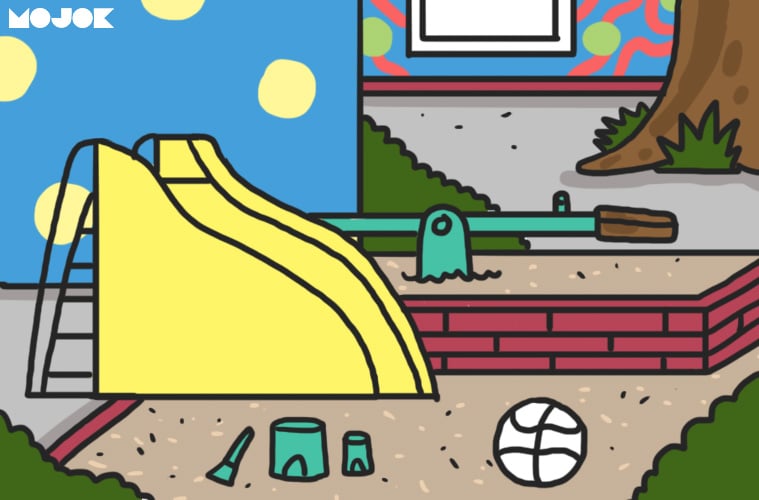Saya yakin, kalian pernah sebel banget ketika baca jenis “komentar bego banget” dari seseorang di media sosial. Jenis komentar yang bikin kalian mikir, “Ini orang nggak pernah baca buku X kali ya,” atau “Duh, ini orang masa hal simpel begini aja nggak bisa narik kesimpulan dengan logis sih.”
Ini fenomena yang kian hari kian banyak saja. Bisa jadi, dan memang sangat mungkin terjadi, penyebab kelemahan logic berpikir ini karena kurangnya membaca.
Ketika Najwa Shihab mengisi sebuah sesi di panggung Festival MocoSik, ia menyampaikan kalimat-kalimat yang lumayan menggelitik buat saya. Najwa sebagai Duta Baca Perpustakaan Nasional RI kala itu mendapat pertanyaan dari Tompi, “Selama ini membaca katanya bikin bla-bla-bla, tapi sebetulnya, mengapa sih kita harus membaca?”
“Membaca itu bikin kita bahagia,” jawab Najwa.
Ada banyak alasan yang bisa diteruskan dari jawaban itu. Alasan ilmiahnya, karena ketika membaca, sel-sel syaraf di otak kita jadi aktif. Saya jadi teringat pelatihan jurnalistik yang pernah saya ikuti, salah satu pesertanya adalah kakek tua berusia 85 tahun. Hingga usia itu, si kakek masih tetap aktif membaca koran tiap hari, bahkan di sesi diskusi, ia sempat-sempatnya mengingatkan peserta lain perihal beberapa tanggal momentum penting dalam sejarah perpolitikan Indonesia. Ketika ditanya apa alasan ia ikut pelatihan, ia menjawab tegas, “Untuk mencegah pikun!”
Selain yang ilmiah, Najwa menambahkan bahwa kegiatan membaca bukanlah sekadar mengeja kalimat-kalimat dalam buku. Lebih dari itu, membaca adalah memahami makna literal maupun kontekstual dari kalimat-kalimat yang dibaca. Membaca adalah menghubungkan satu paragraf ke paragraf lain (atau dalam level yang lebih tinggi: satu buku ke buku lain), untuk kemudian bisa ditarik kesimpulan dari apa yang sudah dibaca, sembari membandingkannya.
Bacaan makin banyak, minat membaca semakin sedikit, maka jangan heran jika membaca menjadi makin tidak sederhana. Terlebih di zaman keberlimpahan informasi seperti sekarang ini, yang kecepatan perputaran arus informasinya tidak diimbangi dengan minat membaca yang serius. Orang-orang jadi tampak “banyak yang bego”. Sebabnya, membaca juga merupakan keterampilan yang, seperti keterampilan sederhana lain seperti mengayuh sepeda misalnya, mesti dilatih terus-menerus agar semakin cakap.
Saya lalu teringat pada Gus Dur. Gusti, rasanya kata kagum saja tidak cukup buat memandang seorang Gus Dur. Esai-esai Gus Dur sudah banyak dibukukan. Satu judul, Melawan Melalui Lelucon yang diterbitkan TEMPO, memuat ratusan esai Gus Dur yang terbit di majalah mingguan tersebut sepanjang 1970-an hingga 1990-an. Dibanding nama lain seperti Kuntowijoyo atau Mahbub Djunaidi, esai Gus Dur lebih gila dalam hal isi. Gus Dur bisa bicara apa saja, mulai dari politik, ekonomi, sosial budaya, arsitektur, kebijakan publik, sains, hingga sepak bola. Dalam semua topik itu, karakter esai Gus Dur adalah karakter yang tidak nggedabhus; tidak sekadar berindah-indah dalam kalimat, tapi sangat kaya akan pengetahuan dan manifestasi pengalaman perjalanan.
Dari sebuah sumber, seorang teman karib Gus Dur (sayang banget saya lupa namanya karena kurang cakap membaca) bercerita, kala Gus Dur kuliah di Kairo, hampir atau bahkan ia berani bilang, semua buku di perpustakaan universitasnya sudah dibaca Gus Dur. Buktinya, tanda tangan Gus Dur ada di halaman paling belakang semua buku-buku itu. Fakta itu adalah jawaban hidup Gus Dur sebagai seorang kolumnis, seniman, dan penerjemah buku babon Syed Hossein Nasr. Juga seorang pemimpin dan guru bangsa yang saking kontroversial kebijakannya hingga tidak dipahami banyak orang. Ya gimana mau paham, Ketika buku paling lawas yang pernah kita baca mentok di karangan Kahlil Gibran (itu pun bangganya sudah setengah modiar), Gus Dur bahkan sudah melahap babon-babon sastra Yahudi dan puisi penyair Arab yang hidupnya 500 tahun sebelum Rasulullah Saw.
Minat baca yang besar dan jumlah bacaan yang memuaskan lambat laun akan mendorong seseorang untuk terbiasa berdiskusi. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk mencari pemahaman-pemahaman baru yang tak hanya bersumber dari satu pintu. Sebab, bagaimanapun, pemikir yang hebat selalu berawal dari pembaca yang lahap.
K.H. Yahya Cholil Staquf, mantan juru bicara Presiden Gus Dur sekaligus pengarang buku Terong Gosong pada suatu ketika pernah mengatakan, cara beragama yang baik bukanlah sekadar membaca teks dari kitab; lebih dari itu, harus disertai pula dengan punya guru. Apa bedanya? Beragama dari kitab akan membawa kita pada kebingungan pada sebuah persoalan karena kita ini nggak pinter-pinter banget. Tetapi, jika kita punya guru, kita nggak perlu bingung dan cukup bilang, “Oh, Kiai As’ad Syamsul Arifin dulu mengambil sikap begini ….Oh, dalam peristiwa ini, Kiai Bisri Syansuri dulu mengambil sikap begini ….Oh, Kiai Maimoen Zoebair pernah memberi nasihat seperti ini.” Sesederhana itu, dan kita cukup nurut saja. Tahu diri, tidak ngeyelan, sambil terus membaca dan belajar.
Dalam kehidupan non-pesantren, gambaran itu terwujud dalam forum-forum diskusi sehingga interpretasi terhadap sebuah bacaan bertemu dengan interpretasi orang lain, hingga akhirnya muncullah kesimpulan-kesimpulan pemahaman baru yang lebih segar.
Cerita dari K.H. Yahya Cholil Staquf itu saya pikir ingin menunjukkan bahwa ragam bacaan mestilah diperkaya, ragam orang yang kita temui mesti kita perbanyak, dan berguru juga tidak dari seorang saja. Insya Allah kita akan bahagia dan nggak edan di era Internet.
Dan yang paling penting, tidak ada lagi alasan bahwa sumber bacaan kita terbatas. Wong di luar Jawa saja susah banyak program, mulai dari perahu pustaka dan duta-duta literasi lain. Utamanya, buat pembaca Mojok yang akses internetnya saja lancar begini, mbok sana pesen buku di Mojok Store. Banyak diskon, adminnya ganteng, mbribikan pula.