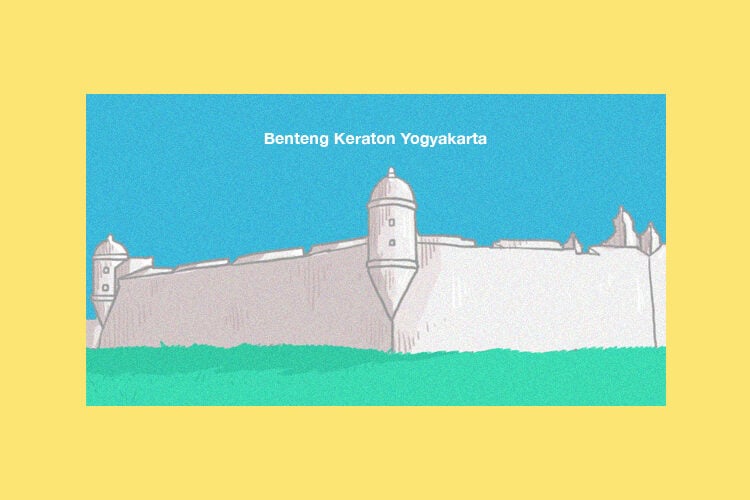Sebagai warga kelas teri di sebuah monarki, kami bisa apa?
Sekilas, tinggal berhadapan dengan tembok tinggi kokoh putih sepanjang jalan rasanya kok sesak. Tetap bisa pergi kemana-mana, tapi rasanya seperti dikurung oleh tembok Keraton Yogyakarta.
Akan ada yang berpendapat bahwa yang saya tulis ini berlebihan. Ya silakan. Mungkin sebagian orang bisa tenang-tenang saja. Yang penting bisa hidup, berkeluarga, dan bekerja di situ. Gitu saja, kok, repot.
Saya kesulitan untuk beroperasi seperti itu. Sebisa mungkin, perlu ada ikatan emosional dan kesenangan tersendiri di kota yang saya tinggali, supaya betah dan punya rasa bangga akan kota itu, apalagi di Jogja. Ya namanya juga rumah. Masak, sih, nggak ada ikatan emosional?
Saya pun paham yang terjadi pada saya (dan kami) ini bukan apa-apa dibandingkan mereka yang saat ini mengalami peristiwa atau bencana yang jauh lebih berat. Meskipun demikian, ketika satu peristiwa buruk itu terjadi, saya berharap akan selalu ada “penjelasan” yang menjadi versi saya sendiri, yang masuk akal baik di pikiran maupun batin. Intinya, how do I make sense of this tragedy? Apa hikmah yang bisa saya ambil?
Dengan adanya penjelasan itu, mudah-mudahan, saya akan bisa move on lebih cepat, bisa merespons dengan lebih tepat, semua demi kebaikan saya sendiri. Itu adalah satu life skill yang saya mulai peroleh sejak usia 25 dulu. Sayangnya, hingga saat ini, saya masih bergelut dengan sekian kemungkinan penjelasan dari peristiwa penggusuran di balik tembok Keraton Yogyakarta.
Nasib angkringan korban penggusuran tembok Keraton Yogyakarta
Karena juga tergusur oleh tembok tembok Keraton Yogyakarta, Angkringan Sartini sudah sejak September lalu berjualan di halaman rumah saya. Awalnya, Mbak Sar dan Mas Jum berniat sementara saja berjualan di sini.
Mereka ingin menambah pelanggan baru, yakni para pekerja proyek tembok Keraton Yogyakarta. Di sisi saya (dan ibu), kami berharap dengan mereka berjualan di sini, suasana sepanjang jalan bisa menjadi sedikit lebih hidup, khususnya di malam hari.
Setelah membicarakannya secara intens, akhirnya angkringan Sartini akan terus berjualan di halaman saya. Mereka akan geser sedikit ke tengah setelah Lebaran. Saya juga berusaha mendirikan tempat jualan yang lebih bagus untuk mereka.
Ini agak-agak taruhan, sebenarnya. Dengan pindahnya sekian warga, apalagi banyak yang meninggalkan Jogja, mereka sebenarnya sudah kehilangan banyak pelanggan. Ditutupnya gang sempit jalan tembus ke Jalan Brigjen Katamso pun mengakibatkan pelanggan yang kalau dulu mau ngangkring tinggal berjalan kaki, kini harus rela naik motor dan memutar lebih jauh. Harapannya, mereka bisa merasa lebih worth it untuk tetap ngangkring di sini karena tempatnya kini lebih bagus.
Kita juga sedang memikirkan gimana caranya ada aktivitas yang bisa mengundang atau melibatkan banyak orang. Yang saya amati belakangan, mulai banyak orang bersepeda atau jogging menyusuri tembok-tembok Keraton Yogyakarta. Apa bisa ya angkringan ini disertakan dalam rute mereka untuk mampir istirahat?
Ini bukan semata-mata agar dagangan mereka tetap laku. Tapi juga, kita (saya) juga butuh kok melihat ada interaksi dan tanda-tanda kehidupan di sepanjang jalan ini. Supaya nggak terbunuh sepi kalau kata Slank zaman dulu. Supaya tetap merasa aman dan tenteram di Jogja, yang sementara ini masih kami anggap sebagai rumah.
Ikatan emosional yang tidak lagi terasa
Dulu saya pernah tinggal dan bekerja di Jakarta Selatan selama 6 tahun. Alhamdulillah, saya betah sekali tinggal di sana. Saya bahkan jarang pulang ke Jogja. Seperti impian anak rantau untuk “menaklukan” ibu kota, saya menikmati sekali menjalani mimpi itu. Ini terlepas dari beban pekerjaan yang suka nggak rasional khususnya di 3 tahun pertama, dan sempat sakit lama.
Meskipun ada masa-masanya saya pulang kerja naik motor kena macet parah, merasakan antrean penumpang di halte Transjakarta yang panjang dan gerah luar biasa, menjalani ritme hidup cepat dan berinteraksi dengan orang-orang yang gaya komunikasinya tidak sehalus orang Jogja, lagi-lagi saya tekankan, saya menikmatinya. Saya bersyukur sekali dengan pengalaman-pengalaman hidup selama di Jakarta.
Walaupun begitu, entah kenapa ya, saya tidak pernah merasa Jakarta adalah “rumah”. Ia lebih mirip sebuah fase yang harus dilalui dan suatu saat harus berhenti. Berbeda dengan mayoritas teman-teman saya, nggak pernah terlintas di benak saya untuk mencari dan mencicil rumah di sana. Bahkan untuk tujuan investasi sekalipun.
Mungkin ada ya, sekian alasan praktikal. Misalnya, belum tentu besok-besok betah dengan macetnya, kemana-mana jauh, banyak kejahatan, dan lain-lainnya. Namun demikian, kalau orang sudah cinta, pasti ia akan rela melalui semua halangan untuk meraihnya. Dari sini, saya bisa menyimpulkan bahwa ikatan emosional saya dan Jakarta saat itu tidak cukup kuat untuk merasakan “rumah” di sini.
Dengan nalar serupa, makin kesini saya semakin berpikir kalau ikatan emosional saya dengan Jogja mungkin sebenarnya juga hanyalah sebuah fase yang suatu saat harus berhenti. Artinya, saya perlu mulai mencari tempat atau bahkan kota lain untuk saya tinggali berikutnya. Karena di balik tembok Keraton Yogyakarta, semua tak lagi sama.
Entahlah.
Penulis: Suryagama Harinthabima
Editor: Yamadipati Seno
BACA JUGA Konflik Batin yang Saya Rasakan Saat Tinggal di Dalam Benteng Keraton Yogyakarta dan pengalaman menarik lainnya di rubrik ESAI.