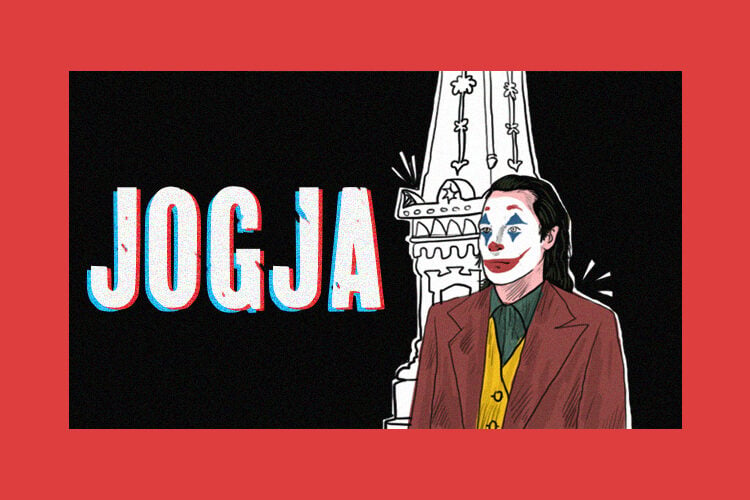MOJOK.CO – Dulu, saya menganggap bahwa Jogja itu kota ali sakit. Setelah berpetualang, ternyata semua kota sama-sama sakit.
Saya lahir, hidup, dan tumbuh di Jogja. Setelah dewasa, saya sempat menganggap bahwa kota kelahiran saya ini adalah kota paling sakit di muka bumi. Masalahnya banyak banget dan seperti dicegah untuk selesai. Mulai dari masalah empati sampai mencengnya nalar para penguasa.
Oleh sebab itu, saya memandang Jogja adalah satu-satunya kota paling sakit di muka bumi. Sementara itu, saya adalah manusia paling menderita. Sampai pada akhirnya pandangan itu agak meluas. Ingat, meluas, ya, bukan berubah. Semuanya terjadi setelah saya memutuskan untuk berani melihat dunia.
Ternyata, saya memang bukan pusat dari sebuah galaksi yang bernama penderitaan. Saya mendapatkan kesempatan mencicipi Jakarta, jalan ke kota-kota di Sumatra, sampai ke Bali, lalu mampir ke Lombok. Selain itu, saya juga sempat mengunjungi negara-negara di Asia Tenggara. Setelah perjalanan panjang itu, saya mendapati kenyataan yang bajingan betul.
Nggak cuma Jogja yang sakit
Ternyata, nggak cuma Jogja, karena dalam artian tertentu, warga urban di daerah-daerah tersebut juga mengalami penderitaan. Bandung, misalnya.
Saya baru tahu bahwa Bandung mengalami masalah pelik dalam sektor infrastruktur. Saya kira, setelah membangun tempat ibadah mewah dan instagramable, mereka sudah senang. Nyatanya enggak. Jalan berlubang, penerangan jalan, kendala transportasi, dan kejahatan jalanan yang di Jogja disebut klitih, ada semua.
Situasi “sakit” saya temukan juga di Lombok, di mana masalah pernikahan dini jadi keprihatinan. Bahkan, dengan telinga sendiri, saya mendengar seorang bocah bercerita. Dirinya ingin terus sekolah supaya nggak dikawinkan oleh keluarganya. Pengakuan itu saya dengan di Lombok Utara. Namun, setelah berselancar di mesin pencari, masalah ini nggak hanya terjadi di Lombok Utara.
Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Lombok Barat, pada tahun 2022, 80 persen pernikahan anak terjadi atas dasar masalah ekonomi. Sebagai negara yang baru saja jadi tuan rumah KTT G20, di sebelah pulau yang jadi tempat perhelatan, masih ada kasus “hilangnya masa depan” anak-anak karena kemiskinan.
Hanoi yang super bising
Masalah juga saya temukan di Hanoi, Vietnam. Iya, jauh sekali dari Jogja yang kini menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa.
Suatu kali, saya dibuat stres berat ketika hendak menyeberang jalan di salah satu perempatan di Old Quarter Center, Hanoi. Semua pengendara memencet klakson, lampu lalu lintas banyak diterobos, dan kecepatan memacu motor bukan main-main.
Saat saya ke sana, kurang lebih 2019, Hanoi memang sedang bergelut dengan meledaknya jumlah kendaraan bermotor dan kebisingan yang ngaudzubillah bikin ngelus dada. Dilansir VNExpress, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Institute of Occupational Health and the Environment menemukan data menarik. Setelah melakukan survei di 12 titik teramai di Kota Hanoi, kebisingan rata-rata pada siang hari adalah 77,8 sampai 78,1 dBA, lebih tinggi dari standar normal pada 65, sampai -75,7 dBA.
Dari Jogja, Jakarta, Bandung, Lombok, bahkan sampai Hanoi, kota-kota yang pernah saya kunjungi, selain sama-sama menyimpan borok, kesamaan lainnya adalah penanganan dari pemerintah setempat yang belum tepat guna. Saya sering heran karena saya yakin mereka tahu sumber masalah. Namun, seakan-akan, seperti sengaja untuk mencari solusi yang salah.
Bandung mirip Jogja, sama-sama sakit
Misalnya penanganan masalah di Bandung yang begitu mirip dengan jogja. Kita tengok kasus minim PJU di Jalan Sudirman pada 2022. Salah satu respons Wali Kota Bandung adalah mengurangi aktivitas yang nggak diperlukan pada malam hari.
Sama seperti respons Raja Jogja ketika menangani masalah klitih. Salah satu poinnya adalah memberikan jam malam bagi anak-anak di bawah usia 18 tahun. Distopia sebuah kota terjadi ketika nggak ada lagi langkah taktis yang dilakukan oleh pemangku jabatan. Pada akhirnya, mereka memilih tindakan yang hanya teoritis belaka.
Padahal, dalam kasus di Bandung saat itu, dua pemuda asal Cimahi tewas akibat dibegal di Jalan Sudirman. Sedangkan klitih di Jogja seperti sebuah tradisi tahunan yang selalu muncul. Darah dan nyawa berceceran di Jogja kala malam, namun kasusnya hilang karena digempur oleh narasi pemerintah daerah yang melulu menggembar-gemborkan pariwisata alih-alih memberi pemahaman kepada wisatawan bahwa Jogja sedang gawat.
Pernikahan dini dan sebuah parodi
Ketika membahas pernikahan dini di Lombok, saya juga menemukan celah. Dilansir dari Inside Lombok, Perda NTB Nomor 5 tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak belum berjalan maksimal di lapangan. Harus dibuat semacam perdes agar daya jangkau lebih mendalam. Sedangkan jika membahas desa, di salah satu desa yang saya sambangi di Lombok Utara, menerapkan aturan pernikahan usia dini itu nggak mudah.
Yah, “Satrio Piningit” memang sebuah ramalan yang terasa menyejukkan. Katanya akan ada sosok pemimpin yang baik. Entah dalam artian eksplisit atau implisit, tetap saja di sebuah masa serba lobi-melobi bak lingkaran setan, ramalan itu menyejukan.
Namun, jika kita melihat kondisi para sosok “pahlawan” yang dipilih secara demokratis (kecuali Gubernur Jogja), mungkinkah utopia pemimpin baik akan muncul?
Komik The Boys garapan Garth Ennis dan Darick Robertson menyajikan parodi yang cukup apik. Ketika para pahlawan super itu korup, jahat, terlibat skandal, dan mementingkan citra munafik di hadapan kamera, adakah sosok superhero yang luhur, berbudi pekerti dan siap mati untuk masyarakat seperti yang ditampilkan komik pahlawan super garapan Marvel dan DC?
Para pemimpin yang sakit
Sama saja seperti para pemangku kuasa di Jogja, Jakarta, Bandung, dan kota lainnya. Ketika kekuasaan seperti tumpeng yang akan dibagi dan menjadi rayahan, adakah pemimpin yang mendahului kepentingan rakyat ketimbang kendaraan politik seperti partai, ormas, perusahaan, dan trembelan lainnya?
Adakah yang rela mati untuk melindungi warganya ketimbang mendengarkan pidato nir-makna yang dilakukan ketua umum partainya? Adakah pemimpin yang menyingkirkan kekayaan bisnis pribadi dan keluarga dan memasang punggung untuk rakyatnya? Apakah kebaikan hanya ada di baliho pinggir jalan selama masa pencalonan, yang justru terlihat bak pelacur yang tengah menjajakan jasanya?
Pemangku kuasa yang baik, selalu melakukan tindakan sebelum adanya korban jiwa atau hilangnya mimpi-mimpi masyarakat. Namun, yang ada sekarang, masyarakat harus kehilangan nyawa dan mimpi-mimpinya terlebih dahulu, itu saja belum pasti pengorbananmu akan diusut dan diurus.
Ternyata, nggak cuma Jogja, semua kota itu sakit. Kita semua cuma bisa terdiam dan tidak mampu bergerak.
BACA JUGA Jogja Provinsi Termiskin: Matur Nuwun Raja dan Gubernur Jogja dan analisis menarik lainnya di rubrik ESAI.
Penulis: Gusti Aditya
Editor: Yamadipati Seno