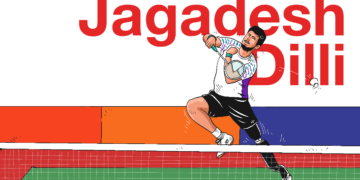Kurdi itu bangsa besar. Punya rakyat, punya akar sosial-budaya-sejarah, punya bahasa persatuan, tapi sayang tidak punya tanah air. Mereka terpencar di Irak, Iran, Suriah, sebagian juga tercecer di negara lain di jazirah Arab, sebagian kecil berdiaspora di Eropa. Bangsa ini melahirkan raksasa-raksasa yang dikenang sejarah: Salahuddin al-Ayyubi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khallikan, hingga Ibnu al-Atsir dan Ibnu Shalah as-Syahrazuri, tapi hingga kini kedaulatan mereka sebagai sebuah bangsa yang merdeka 100% belum terealisasi.
Di India, sebaliknya. Mereka punya akar kesejarahan yang gemilang, geografi yang luas, jumlah penduduk jumbo, tapi belum memiliki bahasa persatuan. Hindi memang menjadi bahasa paling populer, tapi belum menjadi bahasa pemersatu. Adapun bahasa Inggris hanya mentok menjadi bahasa administrasi dan penghias dialog film Bollywood yang aktor-aktrisnya sangat fasih melafalkan “Owh, shit!” itu.
Sebagai sebuah negara berpenduduk lebih dari 1 miliar, India punya bahasa populer yang dituturkan secara dominan, Hindi, dengan banyak menyerap istilah Arab dan Persia, meski ditulis menggunakan aksara Dewanagari. Hal ini berkebalikan dengan bahasa lainnya, Tamil Nadu, Kannada, Malayalam, Maithili, Kashmir, Sanskerta, Punjabi, dan bahasa lokal lainnya yang dituturkan oleh etnis yang tinggal di masing-masing negara bagian.
Kalau belum percaya India belum punya bahasa pemersatu, Anda bisa nonton Chennai Express yang dibintangi sepupu jauh saya—jauh sekali—Tuan Shah Rukh Khan dan Deepika Padukone. Shah Rukh Khan hanya bisa berbahasa Hindi-Urdu, sedangkan keluarga besar Deepika—dan sukunya—hanya bisa bahasa Tamil. Ruwet dah!
Kalau diandaikan di Indonesia, itu kayak Joko jatuh cintrong sama Annabelle, putri Batak. Sayangnya, keluarga si cewek tidak bisa berbahasa Jawa, sebaliknya Joko tak bisa berkomunasi dengan bahasa Batak. Macet. Komunikasi dan interaksi manusiawi hanya menggunakan bahasa isyarat, paling mentok pakai penghubung juru terjemah. Untunglah 89 silam para pemuda lintas suku memproklamirkan kedaulatan berbahasa dengan memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa Persatuan.
Sebuah bahasa pemersatu suku-suku bangsa yang variatif bukan hanya meminimalisir ikatan primordial, melainkan juga menjadi sarana pengikat kemajemukan. Sehingga Wan Amat, keturunan Arab yang tinggal di Jalan Sasak, kawasan Kampung Ampel, Surabaya, bisa nyaman guyonan sambil pisuh-pisuhan dengan Ahong, keturunan Tionghoa yang tinggal di Kampung Melayu, Makassar. Komunikasi tanpa sekat bisa dijalankan dengan mulus antara lain karena bahasa Indonesia.
Bahasa nasional sekaligus bahasa persatuan ini efektif menjembatani perbedaan bahasa dan istilah lokal yang sering menimbulkan salah tafsir. Amis dalam bahasa Sunda punya arti ‘manis’, tapi dalam bahasa Jawa kata tersebut berarti ‘bau anyir’. Bujur dalam bahasa Batak Karo berarti ‘terima kasih’, namun orang Sunda memaknainya sebagai ‘pantat’. Lawang adalah sebutan pintu bagi orang Jawa, tapi kata ini berarti gila bagi masyarakat Palembang. Nah. Sekali lagi bersyukurlah negara maritim yang dipersatukan oleh laut ini dijembatani oleh sebuah bahasa persatuan.
Namun, sebagai orang Jawa, saya tetap mendahulukan pengajaran bahasa ini di dalam keluarga. Mengajari anak berbahasa daerah bukan lambang primordialisme, melainkan bagian dari pengokohan identitas personal, sebagaimana kata Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Bahwa, dengan mengajari anak berbahasa daerah, saya sebagai orang Jawa adalah bagian dari “kita Indonesia”. Sebagaimana Sunda, Batak, Dayak, Bali, Papua, Bugis, Madura dan berbagai suku bangsa lainnya yang telah menjadi mozaik pembentuk Indonesia.
Bangsa Kurdi memang punya identitas sebagai sebuah bangsa yang punya bahasa persatuan, tapi mereka tidak punya tanah air. Sebaliknya, India memang punya bahasa nasional, Hindu-Urdu, namun mereka tidak punya bahasa persatuan.
Dan, kita, kurang apa lagi? Sumpah Pemuda 89 silam yang kita peringati kemarin telah berwujud lengkap: “tanah air Indonesia”, “bangsa Indonesia”, dan “bahasa Indonesia”. Fabiayyi ala-i rabbikuma tukadzdziban?
Sebagai bangsa Indonesia yang bertanah air Indonesia dan berbahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, setiap suku tetap bangga dengan identitas primordialnya tanpa harus berpura-pura menjadi suku lain, sebagaimana anekdot orang Madura yang jatuh cinta dengan budaya Jawa tapi tidak mampu menutupi logatnya meski sudah berbahasa Indonesia.
“Bapak aslinya mana?”
“Oh, kalok sayya aselli Sollo, Dik ….”
Wallahu a’lam bisshawab.