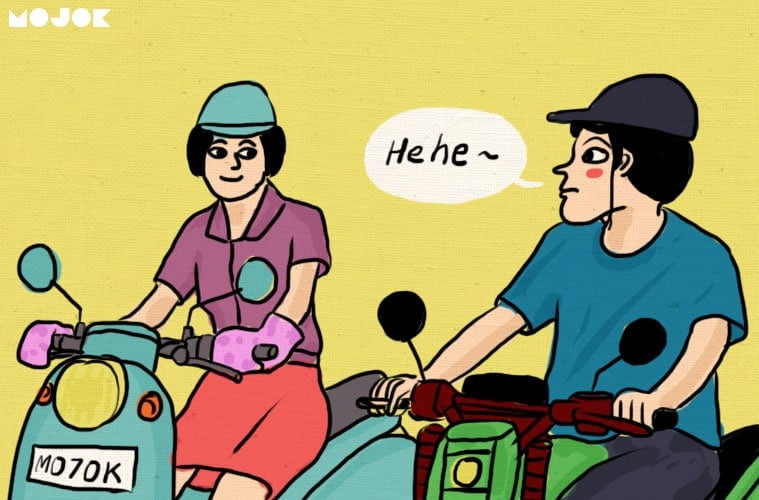[MOJOK.CO] “Nabi Muhammad sendiri terekam sebagai pribadi yang enggan melakukan hukuman atas zina.”
Sebelum menjawab pertanyaan itu, perlu ditegaskan bahwa keputusan MK belum lama ini yang menolak permohonan uji materi terkait “pasal zina” di KUHP tidaklah berarti, seperti disebut sebagian orang Islam, MK membolehkan atau melegalisasi zina. (Apa betul istilah “zina” dipakai di KUHP?)
Mengikuti Putusan MK, yang benar adalah MK tidak ingin dan, secara aturan perundang-undangan, tidak bisa mempeluas cakupan pidana “zina”, dari yang hanya berlaku untuk yang sudah menikah (adultery; istilah Islam: zina al-muhshan) menjadi juga berlaku untuk yang belum menikah (fornication; istilah Islam: zina ghayr al-muhshan), plus mengubah deliknya dari delik aduan menjadi delik biasa.
Bila MK melakukan hal ini, berarti MK telah membuat norma hukum baru, yang juga berarti MK memasuki ranah kewenangan yang hanya dimiliki pembuat undang-undang, dalam hal ini DPR dan presiden. Dengan kata lain, bila ingin memidanakan zina (persisnya zina sebagaimana dipahami dalam Islam), usulan seharusnya disampaikan ke lembaga legislatif.
Jadi, dengan bahasa yang sedikit kasar, memohonkannya ke MK adalah salah tempat mengadu. Sesederhana itu.
Di luar soal keputusan MK itu, sekali lagi sebelum menjawab pertanyaan di atas, ada satu paradigma yang mendasari upaya pemidanaan zina dan mengubah deliknya menjadi delik biasa. Yaitu bahwa zina dipahami sebagai sebab rusaknya moral dan hancurnya ketahanan keluarga, dan cara untuk mengatasinya tidak lain ialah dengan hukum pidana. Cara berpikir ini, khususnya dalam wacana populer, laik untuk diproblematisasi dengan paling tidak dua cara: dengan khazanah yurisprudensi (fikih) Islam sendiri dan dengan anugerah Tuhan yang bernama akal.
***
Banyak orang Islam sering menyatakan bahwa zina masuk kategori dosa besar, dibuktikan dengan kutipan ayat atau hadis yang menunjukkan betapa kerasnya hukuman zina, yakni cambuk 100 kali untuk yang belum menikah dan hukuman mati dengan dirajam untuk yang sudah menikah.
(Bayangkan hukuman rajam: ditanam setengah badan hidup-hidup lalu dilempari batu oleh orang ramai hingga mati.)
Namun, yang jauh kurang disorot ialah dengan kerasnya hukuman itu, proses pemidanaan zina sangat sulit. Sebegitu sulitnya sehingga hampir mustahil bisa terpenuhi.
Dengan kata lain, yang banyak diketengahkan dalam wacana populer tentang zina ialah KUHP-nya Islam tentang zina, sementara KUHAP-nya jarang. Padahal keduanya berkaitan secara integral. Spirit hukum pidana (jinayah) Islam tak bisa dipahami tanpa keduanya.
Sekadar mengambil pandangan fikih konvensional tentang hukum acara pidana zina sebagaimana yang dianut mayoritas: pembuktian zina harus melalui empat orang saksi (sementara dalam kasus pembunuhan dan pencurian cukup dua orang). Empat orang saksi itu harus memenuhi syarat laki-laki muslim, merdeka, dan adil. Pengertian adil di sini adalah jarang melakukan dosa kecil dan tidak pernah melakukan dosa besar, tentu saja termasuk zina.
Keempat orang saksi itu harus melihat langsung dan aktual penetrasi penis ke dalam vagina. Dalam melihat itu penetrasi itu, keempat saksi harus yakin betul telah menyaksikan bahwa kulup penis (hasyafah) benar-benar tenggelam sempurna dalam farji. (Dalam Hasyiyah I’anatut-Thalibin, salah satu kitab fikih mazhab Syafii, di bab tentang hudud [hukuman badaniah] ada pengandaian hipotetis yang menarik: kalau seseorang membengkokkan zakar penisnya dan yang masuk hanya batangnya dan bukan kulupnya, ia tidak kena hadd zina.)
Dengan mekanisme pembuktian yang sesulit itu, apakah pemidanaan zina bisa terjadi?
Bisa, yakni jika orang melakukan zina di tengah jalan yang padat oleh orang-orang yang saleh nan jarang berdosa di siang hari di bawah terik matahari.
Tak kalah penting, dalam fikih klasik juga diatur, jika seseorang menuduh orang lain melakukan zina, namun ia tak berhasil memenuhi syarat-syarat pembuktian itu, si penuduhlah yang justru kena dakwaan qadzaf (tuduhan zina) dengan hukuman 80 kali cambukan.
Jadi, tuduhan zina bukan hal yang main-main. Banyak orang biasanya menyebut ada lima poin “tujuan-tujuan syariat” (maqashid as-syari’ah), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Sebenarnya ada tambahan satu lagi, yaitu menjaga kehormatan (hifzh al-‘irdh), dan hukuman qadzaf termasuk dalam yang terakhir ini.
Dengan ayat/hadis yang amat keras mengatur hukuman zina, apakah Kanjeng Nabi Muhammad ‘alayhisshalatu wassalam sendiri pernah melakukan rajam?
Pernah, sebanyak tiga atau dua kali (karena sebagian pendapat menyatakan bahwa ada dua narasi yang berbeda, namun sebenarnya merujuk pada kasus dan orang sama.) Tetapi, dalam hadis-hadis itu, kisahnya mirip: si pelaku zinalah yang mengaku sendiri kepada Nabi dan minta untuk dihukum. Jadi, kalau ada istilah delik biasa dan delik aduan, mungkin ini bisa diistilahkan “delik akuan”.
Apakah ketika si pelaku zina itu datang kepada Nabi (sekali lagi, merekalah yang datang mengaku seraya minta dihukum) maka Nabi segera memutuskan hukuman rajam?
Tidak.
Dalam satu kasus, Nabi terus memalingkan muka, namun orang itu terus mengejar Nabi, sampai dia mengatakannya sebanyak empat kali bahwa dia telah berzina dan minta dihukum, baru kemudian dihukum Nabi.
Dalam kasus lain, si pelaku zina mengaku dan Nabi merespons dengan berkata, “Mungkin kamu cuma meraba saja.” Si pelaku tak puas, mengaku lagi, dan Nabi meresponsnya, “Mungkin kamu cuma mencium saja.” Hingga setelah pengakuan keempat, Nabi bertanya, “Apakah kamu waras?” Setelah si pelaku menyatakan ia sadar penuh mengatakan hal itu, barulah dihukum.
Kasus lain lagi melibatkan seorang perempuan yang hamil karena zina. Ketika perempuan itu mengaku zina dan minta dihukum Nabi, pertama kali Nabi menyuruhnya untuk pulang, menunggu si anak lahir. Setelah anak lahir, perempuan itu datang lagi dan minta dihukum. Nabi menyuruhnya pulang lagi, menyuruhnya untuk menyelesaikan masa persusuan si bayi. Setelah usai penyusuan si bayi, perempuan itu datang lagi dan minta dihukum, barulah Nabi melaksanakan hukuman.
(Dalam kisah-kisah hadis itu, Nabi baru menghukum setelah terjadi pengakuan empat kali. Ini kemudian menjadi dalil fikih, khususnya mazhab Hanafi dan Hambali, bahwa pengakuan dilakukan empat kali. Jika tiga kali mengaku melakukan, namun di kali keempat jadi ragu dan kemudian berkata tidak, hadd zina tak jadi dilaksanakan.)
Tampak dari hadis-hadis itu bahwa Nabi sesungguhnya cenderung enggan melakukan hukuman. Menangkap spirit di baliknya, diktum kaidah fikih menyebutkan bahwa sebaiknya hukuman hudud urung dilaksanakan selama ada celah untuk tak melakukannya (idfa’ al-hudud ma wajadtum madfa’an) dan bahwa “salah dalam memaafkan adalah lebih baik daripada salah dalam menghukum.”
Teladan dari Nabi ini berkebalikan dengan perilaku sebagian orang yang, setelah menangkap adanya pasangan yang melakukan perbuatan mesum, cenderung mempermalukan pasangan itu di depan umum.
Dengan terang pemahaman mengenai Nabi yang cenderung enggan menghukum ini, pandangan MK sebagaimana tertuang dalam putusannya itu (bahwa hukum pidana semestinya dirumuskan dengan hati-hati, superketat, dan menjadi alternatif paling akhir [ultimum remedium] setelah pilihan lain benar-benar tak berhasil, dalam pandangan hamba yang daif nan fana ini, sebenarnya sudah Islami meski tak mengatasnamakan Islam.
***
Hal lainnya yang laik mendapat problematisasi, sebagaimana disebut di muka, ialah kecenderungan umum untuk memandang zina sebagai sebab, bukan sebagai akibat, seolah-olah suatu tindakan dengan risiko yang tinggi muncul dari ruang vakum.
Kita ambil contoh yang paling kentara: prostitusi. Soal: mengapa orang mau jadi pelacur atau pekerja seks komersial (PSK)? Mengapa, dengan adanya stigma negatif dari masyarakat dan sadar bahwa tiada penghasilan yang meningkat seiring naiknya jenjang karier, seseorang mau jadi PSK?
Akal akan segera mengasumsikan: kemiskinanlah penyebabnya.
Dengan asumsi itu, maka pemidanaan zina, apalagi dengan mengubahnya menjadi delik biasa, akan membuat para PSK mengalami tumpukan penderitaan (mendapat stigma, miskin, penghasilan minim, sebagian darinya merupakan korban trafficking, kadang mendapat perlakuan jahat dari pelanggan, lalu dipenjara), sementara si lelaki yang menggunakannya jasanya cenderung mudah lepas dari jerat hukum.
(Ada satu kebijakan untuk meminimalisasi prostitusi di Swedia [yang kadang disebut sebagai the Swedish approach], yang diilhami oleh ide feminis mengenai prostitusi sebagai manifestasi eksploitasi tubuh perempuan, yaitu dengan mendekriminalisasi PSK dan mengkriminalisasi orang yang membeli jasa PSK sehingga, dengan turunnya sisi demand, turun pula sisi supply-nya. Terlepas dari debat mengenai sukses/tidaknya kebijakan Swedia itu, poin minimalnya adalah bahwa negaranya Zlatan Ibrahimovic yang sekuler itu ternyata peduli pada persoalan prostitusi.)
Dalam kondisi yang seperti itu, menerapkan hukuman menjadi berat sebelah dan karena itu tak adil: kaum rentan, yakni perempuan, juga anak-anak (karena pemidanaan zina yang dimohonkan ke MK itu ingin memperluas subjek pidananya turut mencakup yang belum menikah) adalah kaum yang paling rawan kena hukuman.
Memahami zina sebagai akibat juga membantu untuk memikirkan jalan lain untuk meminimalisasinya sebelum merumuskan regulasi yang rawan menyasar kelompok rentan. Di sinilah perlunya riset dan mengamalkan ayat iqra’ bagi umat Islam sebelum marah-marah.
Di antara caranya ialah dengan mendirikan, misalnya, The Mojok Institute for the Elimination of Poverty and Prostitution, atau kalau ingin memakai bahasa Arab, Harakatu Mojok Dhidd al-Ittijar bil-Basyar wa Bigha’ al-Athfal (Gerakan Mojok Melawan Perdagangan Manusia dan Pelacuran Anak). Jadi, diawali dengan menyisir dari pinggir, dengan menyelamatkan orang-orang yang rentan jadi korban, sebelum memaksakan hukuman dari atas dengan tangan negara.
Paradigma punitif (maksudnya, yang cenderung menyelesaikan persoalan dengan hukuman) ini seyogianya diubah. Dalam pandangan hamba yang daif nan fana ini, dan semoga para alim nan bening hatinya mau bersepakat: keislamian suatu masyarakat tidaklah diukur dengan seberapa banyak masyarakat itu menghukum, tetapi dari seberapa perlu/tidaknya suatu hukuman diadakan untuk menertibkan masyarakat itu. Masyarakat yang Islami ialah yang mampu menjauhi dosa dengan sepenuh kesadaran hati tanpa memerlukan paksaan dari negara.
Terkait hal yang terakhir ini, MK dalam putusannya di halaman 446 menyatakan,
“Membangun argumentasi bahwa menata tertib sosial harus dilakukan dengan cara memaksa anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang itu dengan ancaman hukuman, lebih-lebih hukum pidana, sama artinya dengan menyatakan bahwa tertib sosial hanya mungkin tercipta di bawah ancaman.”
Demikian, sampai di sini saja. Kalau kepanjangan, capek bacanya.