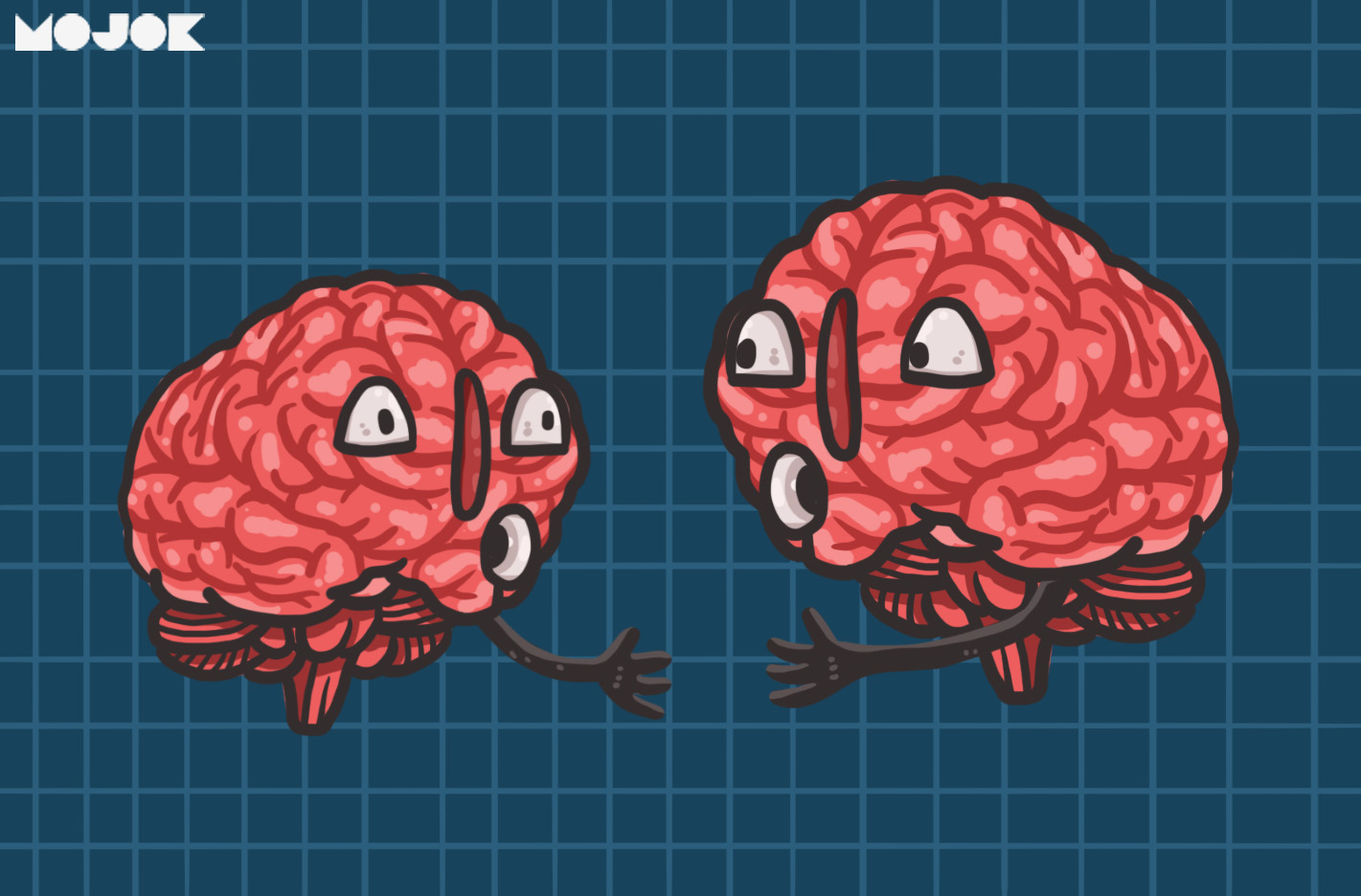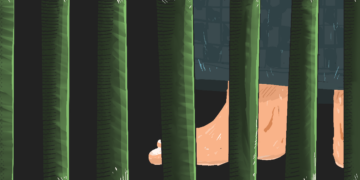Negeri ini tidaklah kekurangan orang pintar, yang kurang dari negeri kita ini adalah orang baik. Untungnya, dalam momen yang berdekatan dengan hari guru nasional kemarin, orang-orang baik (dan pintar tentu saja) yang mulai langka ini menunjukkan contohnya.
Catat dua nama ini: Gus Mustofa Bisri (Gus Mus) dan Mbah Kiai Maimun Zubair.
Dihina dan dihujat di media sosial hanya karena hal yang bersifat khilafiyah, dua sesepuh umat Islam ini menunjukkan respons yang luar biasa. Mereka menunjukkan bagaimana menjadi menjadi sosok yang bisa digugu dan ditiru.
Uniknya, tidak hanya memaafkan, keduanya malah sukarela “disowani” oleh orang-orang yang secara terbuka menghinanya.
Lebih ajaib lagi Gus Mus. Bukan hanya menerima dan menyambut hangat, beliau malah memberikan nomor whatsapp-nya. Alasannya pun lucu: supaya si penghujat, kalau mau uring-uringan dengan pendapat Gus Mus tidak perlu ada orang lain yang tahu.
Ini kan bikin iri betul! Saya malah curiga, jangan-jangan orang ini sengaja menghina biar dekat sama Gus Mus. Sayang sekali, kok ya saya ini tidak rela dan tidak berani jika harus menggunakan cara yang sama biar bisa dekat dengan idola saya ini.
Apa yang ditunjukkan Gus Mus dan Mbah Kiai Maimun mengingatkan saya akan hal yang juga pernah dilakukan Zakia Belkhiri beberapa bulan silam (pertengahan Mei) di Belgia. Diawali dari terpilihnya seorang Muslim bernama Sadiq Khan sebagai walikota London, gerakan anti-Islam kembali mengemuka di beberapa negara Eropa. Salah satunya Belgia.
Aksi Belkhiri ini sempat jadi buah bibir di media sosial kalau Anda ingat. Waktu itu, dengan enteng Belkhiri yang kebetulan lewat di Antwerpen, melihat gerombolan massa gerakan anti-Islam ini. Bukannya ciut nyali karena dirinya adalah bagian dari “objek” yang sedang “dilawan”, Belkhiri malah mengambil hapenya, lalu melakukan hal yang tidak akan dilakukan oleh Ahok di hadapan Habib Rizieq sekalipun, yakni: selfie!
Yak. Selfie di depan tulisan-tulisan “no headscarves” atau “stop Islam”. Yakin deh, ini keren betul. Bukannya terbakar amarah karena merasa didiskriminasi, Bakhiri malah menunjukkan karamahtamahan yang sejatinya bikin malu peserta demonstran. Dia menyerang balik dengan cara tak terduka. Serangan yang dengan sangat telak memukul balik para demonstran.
Hal yang dengan jelas menunjukkan, siapa sebenarnya “pemenang” dari kejadian tersebut. Yang demo ya terpaksa ikut senyum-senyum waktu diajak selfie Belkhiri. Yah, meski senyumnya sedikit kecut sih.
Reaksi-reaksi semacam inilah yang belakang mulai jadi barang langka di negeri ini. Apa yang ditunjukkan Gus Mus, Mbah Kiai Maimun, sampai Belkhiri adalah bukti bahwa ada “cara terbaik” untuk menunjukkan bahwa wajah Islam adalah wajah adab maupun peradaban.
Nah, sebelum jauh membahas soal Islam dan peradaban ini, perlu saya ceritakan bagaimana santri belajar ngaji di pesantren untuk memberi sedikit “asbabul nuzul”-nya. Yah, istilahnya sebab kenapa kita harus mengutamakan adab yang baik dulu sebelum menginjak ke hal-hal yang lebih rumit—utamanya dalam persoalan syariat. Dan tidak perlu jauh-jauh, saya akan ambil contoh dari pesantren saya saja.
Begini. Jauh sebelum mempelajari ilmu fiqih, nahwu, sorof, sampai balaghoh, atau ilmu-ilmu rumit lainnya. Seorang santri angkatan pertama akan disodori dua kitab yang mesti dikhatamkan terlebih dahulu. Yakni Akhlaqul lilbanin dan Ta’lim muta’alim.
Bagi yang pernah mondok, atau punya saudara yang pernah mondok, mungkin familiar dengan dua kitab ini. Kitab-kitab ini secara garis besar berisi mengenai bagaimana berperilaku, adab, dan akhlak kepada orang lebih tua, lebih muda, atau orang-orang yang dianggap sebagai “guru”.
Saya tidak akan menceritakan isi dua kitab tersebut secara detil di sini, karena memang saya tidak punya kredibilitas yang cukup untuk memberitahu situ apa saja pelajaran di dalamnya. Kalau situ penasaran ya saran saya; silakan mondok atau masukkan anak situ ke pondok.
Yang lebih ingin saya tekankan di sini adalah—yah, menurut kesimpulan saya bertahun-tahun kemudian—ada alasan khusus kenapa dua kitab ini jadi “wajib” dipelajari di awal. Begini. Seorang santri lebih diutamakan jadi orang baik lebih dahulu, bukan jadi orang pintar dulu. Poinnya tentu saja bukan kemudian menjadi santri itu tidak boleh pintar. Tidak, bukan itu. Titik tujuan praktik ini sebenarnya adalah mengajarkan seseorang yang belajar agama diutamakan agar dirinya membiasakan berperilaku baik pada mulanya. Menolong orang lain, bersabar ketika dihina, membantu nenek-nenek yang mau menyeberang jalan, yah, pokoknya mirip-miriplah dengan apa yang ada di buku pelajaran PMP zaman orde baru.
Harapannya, saat kemudian si santri kemudian diisi dengan pelajaran-pelajaran agama yang lebih rumit. Penerapan ilmu di masyarakat nantinya tidak hanya soal konsep benar atau salah saja, namun juga soal cara penanganan yang baik atau buruk juga.
Sebabnya tentu saja didasari karena agama berisi mengenai ajaran kebaikan. Kan jadi percuma situ mengajarkan kebaikan tapi menyampaikannya tidak dengan cara baik-baik. Membentak-bentak, mata merah menyala, otot leher keluar semua kemana-mana sampai tidak pulang-pulang, misalnya.
Toh, sekalipun yang situ ucapkan adalah kebenaran dan ada dalilnya—soheh lagi, kebenaran yang situ sampaikan akan terasa kasar dan bakal terlihat mengerikan. Tuhan tidak semenakutkan itu kok, jadi tidak usahlah diseram-seramkan begitu. Daripada menunjukkan kebenaran lewat cara-cara panasnya api neraka, mengapa sih tidak menyampaikan kebenaran dari perspektif betapa teduh Tuhan pemilik semesta?
Ini penting, karena menjadi pintar itu bisa diupayakan semua orang, dan semua orang mau melakukannya. Namun menjadi orang baik, itu perkara yang berbeda. Alasannya tentu saja karena kebaikan tidaklah semewah kebenaran. Menjadi orang baik tidak sekeren jadi orang pintar.
Orang pintar mah enak, cari duit gampang, mobilnya keren-keren, kalau bicara didengarkan banyak orang, sekali mengatakan “salah” pada orang lain, semua orang akan mengamini. Banyak yang mendukung, tidak hanya santri-santrinya saja, namun kadang pejabat-pejabat pula.
Coba bandingkan dengan orang baik—terutama golongan orang baik yang tidak merasa dirinya pintar, baru ngomong perkara bid’ah saja, sudah dicacimaki habis-habisan. Baru menghimbau untuk mudah memaafkan orang lain saja sudah disesat-sesatkan.
Namun apakah dengan begitu orang baik akan marah?
Oh, jelas tidak. Orang baik memiliki pondasi adab yang lebih baik. Golongan ini punya pondasi akhlak yang luar biasa. Ya, karena pendidikan golongan orang-orang ini didasari dari bagaimana membangun peradaban lebih dahulu, bukan bagaimana mencetak dan membesarkan orang-orang pintar lebih dahulu.
Ingat, keilmuan lebih erat kaitannya dengan peradaban daripada orang-orang pintar dadakan.
Jadi, situ mau beradab atau cuma mau jadi pintar?