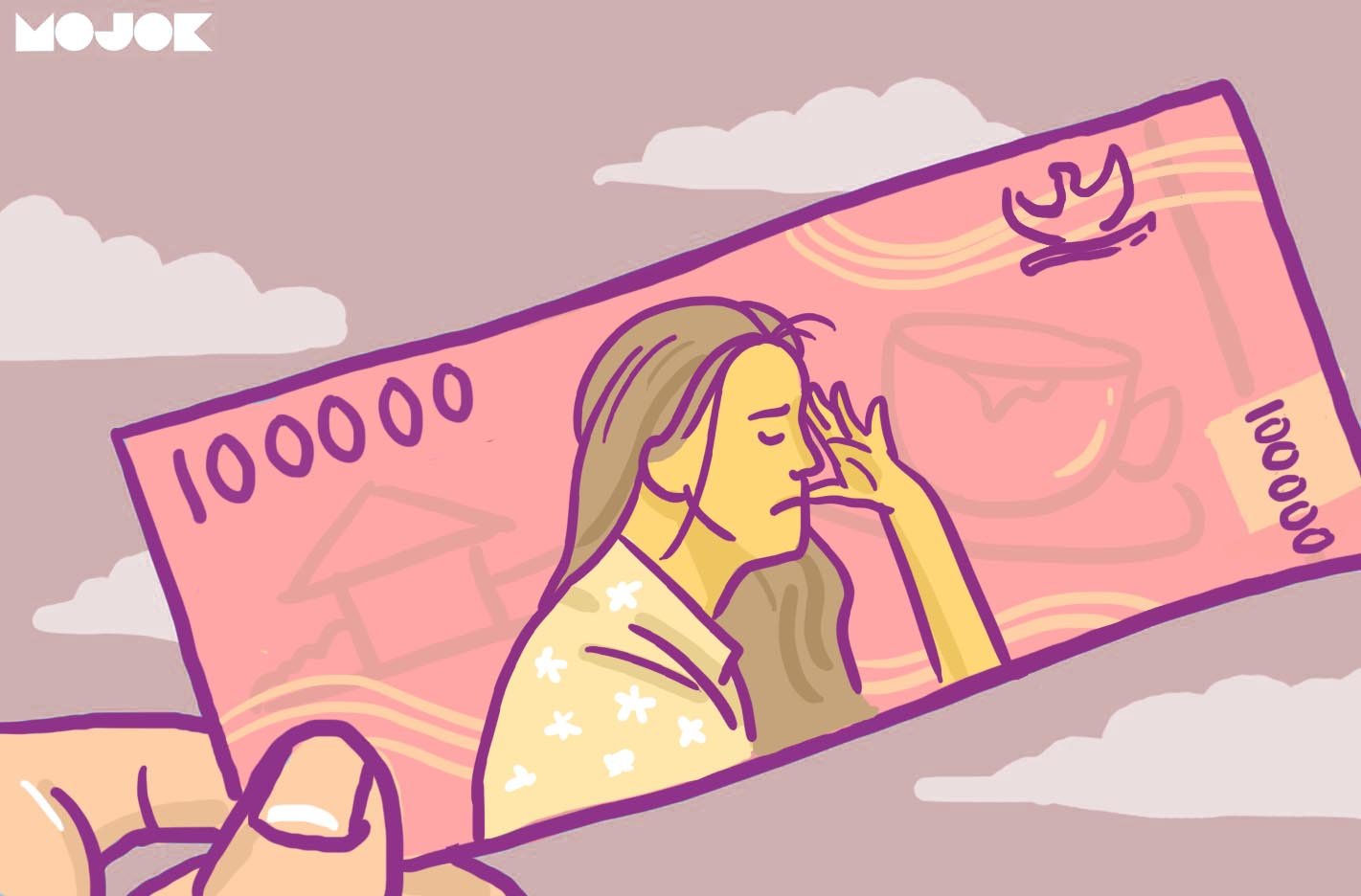Baca cerita sebelumnya di sini.
“Bu, tadi ada yang datang menagih utang,”
“Sudah tahu!”
“Kenapa Ibu menghindar?”
“Jangan menambah kepusingan. Kalau tidak bisa bantu, diam!”
Larasati undur dari hadapan Gayatri. Wajahnya dingin merangkum kesedihan dan kemarahan sekaligus. Gadis itu sebenarnya sudah tahu apa yang akan ibunya katakan. Tapi mau tak mau, ia harus menyampaikan apa yang telah terjadi.
Gayatri sendiri duduk sambil memijat-mijat kening. Duduknya tak tegak. Pantatnya ada di ujung depan kursi, tengkuknya bertumpu di pucuk sandaran, dan kepalanya tertunduk nyaris terlipat ke dada. Kakinya lurus menjulur pasrah sejauh-jauhnya. Napasnya pendek-pendek, namun sesekali ia menghelanya amat panjang.
“Buatkan kopi!” seru Darman tiba-tiba.
Lelaki itu baru saja mandi. Handuk masih ia pegang sambil ia gosok-gosokkan ke rambutnya yang basah.
“Gula habis. Tinggal kopi saset seribuan itu. Seduh sendiri saja,” sergah Gayatri ketus tanpa mengubah posisinya.
Darman beranjak ke dapur. Denting kecil gelas saling beradu di rak plastik, lalu bunyi kopi saset yang entah untuk alasan apa dikocok-kocok dalam plastiknya. Sesaat sempat terdengar lelaki itu bersiul-siul, tapi hanya sesaat, hanya sampai terdengar suara tutup termos terbuka.
Bantingan benda berat membuyarkan segala yang ada di atas meja. Darman membanting termos besar yang ternyata kosong itu.
“Bangsat! Tidak induk tidak anak, semua pemalas. Air panas saja tidak punya!” rutuknya, disusul bantingan gelas di lantai plester dapur dekil rumahnya.
Ia melangkah meninggalkan semua kekacauan itu, menyambar jaket, dan melaju dengan motor tuanya yang meraung-raung mengepulkan debu. Gayatri, yang dilewatinya tanpa ditoleh, tak sedikit pun terprovokasi. Ia tetap terpejam dengan kepala tertekuk dan tangan memijit kening. Diam.
Justru Larasati yang mendengar semuanya dari balik tirai kamar itulah yang terpicu. Wajahnya memerah, napasnya memburu. Ia pun ikut-ikutan menyambar jaket, memakai helm, dan menyalakan mesin motornya dengan kasar.
Kali ini Gayatri bereaksi.
“Laras! Mau ke mana?!” teriaknya.
Teriakan yang sia-sia. Anak gadis itu melaju tanpa sempat mendengarnya. Tapi, ia sempat melihat buliran air mata jatuh di pipi Larasati. Sebenarnya, ia pun marah dan kalut, namun ia tak berdaya. Ia tahu anaknya sudah mengambil banyak peran menggantikannya sebagai orang tua.
Atas nama balas budi dan bakti, ia justru merasa berhak meminta lebih dan terus-menerus. Hatinya merasakan itu semua. Tetapi nalar dan semesta berpikirnya berputar-putar pola; anak-harus-berbakti-pada-orang-tua.
***
Sisa air mata ia habiskan di atas kendaraan. Ia biarkan angin menguapkan kesedihan dan gumpalan benang kusut di otaknya. Laju motornya tak terlalu kencang. Larasati mengambil jalur paling tepi di jalanan kota.
Tak ada tempat khusus yang hendak ia tuju. Beberapa kafe dan tempat jajanan sempat ditoleh, tapi belum satu pun menarik hatinya untuk singgah. Sesekali, tangan kirinya lepas dari kemudi, menyeka pipi. Ia mengedipkan mata lebih sering agar air mata lekas jatuh dan tak mengaburkan pandangan.
Berlama-lama di atas motor sendirian rupanya bisa juga meredakan badai yang bergulung-gulung di hatinya. Air matanya mulai surut. Ia belum berniat kembali, tapi tak jua menentukan tempat berhenti. Akhirnya, tanpa menoleh lagi, ia melaju lebih kencang ke tepian kota; ke arah kompleks perumahan tempat seorang saudaranya tinggal.
Deretan rumah yang berbentuk dan berwarna seragam menyambutnya. Jika ada beda, maka itu adalah bentuk teras dan susunan tanaman di depannya. Larasati menyusuri jalan lurus dengan simpangan tajam-tajam sampai ke ujung belakang kompleks perumahan. Ia berhenti di depan sebuah rumah dengan banyak tanaman bumbu dapur dalam kantong-kantong hitam berderet-deret di halaman sempitnya.
Seorang perempuan seusia Gayatri terlihat sedang berjongkok menyiangi rumput di antara tanamannya. Melihat kedatangan Larasati, perempuan itu menoleh sebentar dan menghela napas dengan bola mata bergulir. Ia terlihat tidak suka.
“Assalamualaikum, Bulik…” sapa Larasati pelan.
“Waalaikumsalam. Eee, Laras… sendirian saja?” Kentara sekali ia hanya berbasa-basi.
“Iya, Bulik. Aku tahu Ibu pasti sudah ke sini tadi. Aku datang tidak untuk pinjam uang, kok.”
Larasati merasa tak perlu basa-basi lagi. Bulik Sarah, orang yang didatanginya ini sudah terlalu sering menolong keluarganya, tapi berkali-kali dikhianati kepercayaanya oleh ibu dan bapaknya. Ia adalah orang yang entah mengapa jarang sekali bisa berkata “tidak”, meski sebetulnya tahu ujung-ujungnya akan menyakiti dirinya sendiri.
Wajah Bulik Sarah melembut. Ia menghentikan kegiatannya dan menyongsong Larasati. Diajaknya gadis itu masuk ke ruang tamunya yang mungil. Ia sempat memegang pipi Larasati untuk memastikan bahwa yang membasahinya adalah air mata.
“Aku tahu, Ibu pasti sudah datang untuk pinjam uang karena hanya Bulik satu-satunya orang yang masih mau meminjamkan,” ucap Larasati lirih.
“Iya, Ras, tapi aku sudah tidak bisa lagi. Ibumu meminta pinjaman terlalu besar. Aku tak punya uang sebanyak itu. Lagi pula, aku juga sedang punya kepentingan sendiri,” sahut Bulik Sarah.
“Gajiku bulan ini sudah habis. Adik butuh biaya yang tidak sedikit untuk sekolahnya. Listrik, air, gas… semua menjerit minta dibayar,”
“Ibumu tidak pernah minta ke Bapak, ya?”
“Minta juga percuma, Bulik. Bapak bisanya cuma marah dan menghardik kami. Bapak parasit.”
“Apa bapakmu masih tetap seperti dulu itu?”
“Sudah watak Bapak begitu. Rasanya mustahil Bapak berubah, kecuali jika kepalanya terbentur rel kereta!”
“Hush! Tidak baik mengatai orang tua begitu.”
“Sepanjang hidupku, Bulik, sepanjang hidupku, Bapak tak pernah kulihat bisa berguna sedikit pun dalam keluarga kami.”
“Ibumu itu kok ya masih percaya saja kalau Bapak akan berubah, ya…”
Larasati menghela napas. Ia menyeka air matanya yang meleleh kembali. Kesedihannya tak meghilang saat itu, namun gumpalan beban luruh ketika Bulik Sarah bersedia menyediakan telinga dan usapan lembut di punggung tangannya. Disambutnya uluran tangan Bulik Sarah yang mengangsurkan secangkir teh hangat.
“Aku sering sekali merasa ingin melawan Bapak, tapi Ibu selalu menghalangi dan membela Bapak. Mau pergi dari rumah pun aku masih pikir-pikir. Adik akan terlunta-lunta kalau aku tak ada,” Larasati sekarang bisa berkata lebih tenang.
“Bertahanlah untuk adikmu, Ras,” Bulik Sarah menguatkan.
“Sebenarnya aku pun kasihan melihat Ibu jungkir balik jualan apa saja. Tenaganya terkuras habis, tapi hasilnya entah ke mana tak jelas. Bapak sering merampas uang ibu.”
“Dari dulu itu ibumu sudah kuperingatkan soal Bapak. Bahkan sejak sebelum menikah. Darman itu bajingan. Tapi ibumu malah mendem kedanan, sampai-sampai ia turuti nasihat dukun tak jelas untuk meludahi kopi Darman supaya si bajingan itu melembutkan peringainya.”
Larasati terperanjat. Sebuah gelombang kejut umpama aliran listrik ia rasakan menjalari sekujur tubuhnya. Sebuah fragmen berkelebat berulang-ulang dalam benaknya. Ibu. Kopi. Ludah. Bapak.
“Jadi, Ibu meludahi kopi Bapak itu maksudnya supaya Bapak berubah jadi baik, begitu?” seru Larasati.
“Ya begitulah anjuran dukun tidak jelas yang selalu diugemi ibumu. Puluhan tahun ia melakukan itu. Apa sekarang ada hasilnya?” jawab Bulik Sarah santai sekali.
Hati Larasati rusuh. Sungguh tak masuk akal baginya bahwa tindakan ibunya yang semula ia pikir sebagai pelampiasan amarah seorang istri yang disakiti suaminya itu ternyata adalah sebuah ikhtiar untuk mengubah sang suami menjadi lebih baik.
Ya, tindakan brutal yang ia saksikan pada pagi hari itu adalah usaha ibunya untuk sebuah kebaikan yang diyakininya.
Baca cerita berikutnya di sini.