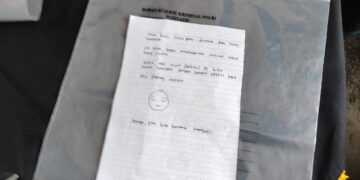Baca cerita sebelumnya di sini.
Tidak seperti judul buku seorang seniman mime, aku bangun pagi dengan rasa tidak bahagia. Entahlah, semacam ada ruang kosong yang hampa di hatiku.
Biasanya, setiap pagi, aku pasti melihat keriuhan grup WhatsApp yang hanya berisi kami bertiga: Mbak Sonya, Mas Adimas, dan aku. Kami menamakan grup itu “Grup Rasan-Rasan”.
Kami tidak selalu membicarakan hal-hal berat, seperti urusan negara dan politik. Kadang, kami hanya bergosip tentang artis yang ditikung temannya atau hal-hal remeh dalam hidup kami.
Aku melihat obrolan terakhir kami. Tidak ada firasat apa-apa. Kami hanya berencana nongkrong dan menerbitkan buku bersama sebagai dokumentasi persahabatan. Sayang, aku yang beda kota belum bisa memenuhi ajakan mereka. Andai waktu bisa terulang kembali, aku pasti tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu.
Subuh belum benar-benar pergi ketika aku memutuskan pergi ke sendhang, tempat favorit Mbak Sonya ketika main ke sini. Pohon beringin besar yang berada di tepi sumber mata air itu seharusnya terlihat angker, tapi tidak bagiku. Aku teringat cerita Mbak Sonya yang pertama kali ketemu Mas Aran. Katanya, Mas Aran bersembunyi di balik pohon beringin itu sambil mengintip Mbak Sonya mencuci.
Jantungku hampir copot ketika kulihat ada seorang perempuan duduk di tepi sendhang. Jelas saja bukan penduduk sekitar. Aku mengenalnya, sangat mengenalnya. Alih-alih takut, aku malah berjalan mendekatinya, lalu duduk di sampingnya.
“Ril, bolehkah aku minta tolong?” perempuan itu berkata tanpa mengubah pandangannya ke depan.
“Apa yang bisa kubantu, Mbak?” aku juga menjawab tanpa memandang wajahnya.
“Tolong, katakan apa yang tidak bisa kukatakan. Pada mereka, orang-orang yang menyayangiku, pada mereka, orang-orang yang tersakiti olehku.”
“Jika itu bisa membuat Mbak Sonya tenang, tidak ada alasan bagiku untuk menolaknya,” aku menoleh ke arahnya.
“Terima kasih, Ril.” Dia tersenyum kepadaku. Senyum penuh harap.
***
Perjalanan ini tidak bisa tidak mengingatkanku pada Mbak Sonya, Si Gadis Kereta. Dia bisa cerita apa saja yang baru saja dilihatnya: tentang penumpang yang menyebalkan, pemandangan yang kami lihat di jendela, atau stasiun-stasiun yang kami lewati.
“Tahu nggak, Ril? Kadang diriku merasa seperti stasiun-stasiun yang kita lewati tadi: hanya sebagai persinggahan, bukan tujuan utama,” katanya suatu hari sambil makan bekal nasi dan tempe goreng andalan ibuku.
“Sekalian saja tambahi, Mbak, kalau dirimu dan dirinya itu seperti sepasang rel: berdampingan, tapi tidak mungkin bersatu. Kalau bersatu, malah membahayakan orang lain,” kataku cuek sambi tetap mengunyah tempe goreng. Waktu itu Mbak Sonya baru putus dari pacarnya yang dulu. Ah, baru kusadari ternyata kata-kataku yang dulu kuanggap asal saja, bisa jadi mengerikan jika kuhubungkan dengan kondisi saat ini.
Setelah lima jam perjalanan, akhirnya aku sampai ke kota tempat tinggal Mbak Sonya. Aku sempat bingung hendak menghubungi siapa. Akhirnya, aku putuskan untuk mengontak Mas Dimas untuk bertemu. Kami bertemu di alun-alun kota sambil minum wedang rondhe dan asle.
“Jadi apa rencanamu, Ril?” tanya Mas Dimas sambil menyerahkan semangkok wedang rondhe padaku.
“Kamu boleh mengatakan kalau aku gila, Mas, tapi aku harus menemui Mas Aran besok. Mbak Sonya yang memintaku.”
“Sonya? Dia bilang begitu?”
“Iya, dia menemuiku di sendhang.”
Kulihat Mas Dimas terdiam, seperti ada hal yang disembunyikannya.
“Dia juga menemuiku kok, Ril. Dia menangis karena melihatku memasukkan racun untuk Aran. Dia bilang jangan karena dirinya aku menjadi orang jahat,”
Aku tersedak, “Hah? Kamu mau membunuh Mas Aran, Mas?”
“Hush, jangan keras-keras. Aku juga tidak merencanakannya. Hal itu terlintas begitu saja. Aku juga tidak tahu. Aku menyesal pada akhirnya. Aku kesal dengan Aran, tapi aku sebenarnya tidak tega melakukan hal itu. Bagaimanapun, Aran adalah suami Sonya.”
Aku terdiam. Aku tidak menyalahkan Mas Dimas. Aku bersaksi dia adalah orang baik. Terlalu baik malah. Dia terlalu menyayangi Mbak Sonya.
Tapi, apa-apa yang berlebihan memang tidak baik. Dia bisa menjadi sesuatu yang membunuhmu di kemudian hari.
“Besok tolong sampaikan padanya bahwa sebenarnya aku tidak membencinya sampai begitu. Aku hanya… Entahlah, aku selalu ingin menjaga Sonya. Harusnya aku tahu, aku tidak boleh keterlaluan begitu. Aku mungkin akan menemuinya setelah kau menemuinya. Aku ingin meminta maaf. Aku pasrah jika aku juga masuk ke penjara demi Sonya.”
Kami mengakhiri pertemuan malam itu dengan pikiran yang berkecamuk di kepala.
***
Laki-laki di depanku memandangku dengan canggung. Aku memang sahabat istrinya dan sebenarnya kami lahir di kota yang sama, tapi aku malah lebih dekat dengan Mas Dimas. Mas Aran hanya numpang lahir di desaku, di sendhang dekat rumahku, itu lalu ia dibawa keluarganya ke ibu kota. Aku hanya kadang-kadang saja melihatnya pulang kampung ke tempat pakdhenya yang ketua RT itu. Yang jelas, selama ini aku tidak punya konflik dengannya.
“Halo, Mas Aran,” aku mencoba memecah kecanggungan.
“Halo, Rilla. Eh, sebenarnya namamu siapa sih? Kok Pakdhe sepertinya tidak memanggilmu begitu?”
Ah, ternyata Mas Aran tidak semenakutkan yang kukira. Dia juga mau membuka obrolan dengan baik.
“Hahaha…. Nama lengkapku itu Rinancang Mulya Larasati, Mas. Rilla itu nama beken pemberian Mbak Sonya dulu. Mbak Sonya, kan, memang begitu sesukanya mengubah nama orang, tapi aku senang-senang saja.” Tidak kusangka, ternyata Mbak Sonya belum pernah cerita soal namaku.
“Oh ya, Mas. Boleh dong diriku minta tanda tanganmu. Aku mengikuti karya komikmu, loh. Walau kadang-kadang dark-dark gimana gitu, tapi Aranz selalu bisa membuatku penasaran.”
Aku menyiapkan kalimat barusan untuk jaga-jaga kalau aku tidak bisa ngobrol dengannya.
“Halah, apaan sih kamu, Ril. Minta tanda tangan pesakitan. Sana, minta tanda tangan Adimas saja, sahabatmu itu.”
Sialan, aku tidak mau terjebak dalam situasi ini. Bagaimanapun, tidak bisa kupungkiri kalau aku lebih dekat dengan Mas Dimas daripada Mas Aran.
Dulu, aku kenal Mas Dimas dan Mbak Sonya di balai budaya yang sedang menyelenggarakan workshop menulis. Waktu itu, pembicaranya adalah Mbak Sonya. Beruntung, dari sana, karyaku pernah dimuat dalam satu halaman bersama dengan tulisan Mbak Sonya. Mulai sejak saat itu, aku dekat dengan mereka. Aku mengenal Mbak Sonya dan Mas Dimas jauh lebih dulu daripada Mas Aran mengenal mereka.
“Maaf, Ril, bukan maksudku…”
“Nggak papa, Mas. I see.”
Aku hampir memasukkan komik yang seharusnya kumintakan tanda tangan, tapi Mas Aran memintanya, lalu menandatanganinya. Dia bilang memang karakternya temperamen, apalagi kalau mendengar nama Adimas.
Hmm, padahal aku tidak menyebut namanya sejak tadi.
“Jadi, apa keperluanmu ke sini, Ril?” tanyanya.
“Aku mimpi bertemu Mbak Sonya di sendhang, Mas. Dia memintaku menengokmu. Oh ya, aku juga bawain oleh-oleh. Kata Mbak Sonya kamu suka nasi tempe goreng kemul khas kota kita, kan?
“Tenang, makanan ini nggak beracun, kok. Aku coba satu nih, Mas, kalau nggak percaya,” tambahku.
“Banyak omong kau Ril. Sini, aku sudah lama tidak makan enak.”
Mas Aran memakan bekal dariku sambil bercerita. Berkali-kali, dia menyebut-nyebut nama Mas Dimas dengan nada emosi. Tentang Mbak Sonya yang lebih suka teh buatan Mas Dimas, hingga tentang Mbak Sonya yang membandingkan dirinya yang merokok dan Mas Dimas yang tidak merokok.
Bicara soal masalah teh, aku tidak terlalu ingin berkomentar. Aku pribadi tidak menampik bahwa Mas Dimas memang jago membuat teh. Aku hanya ingin menjelaskan bagian ketidakkonsistenan Mbak Sonya yang tidak menyukai asap rokok. Padahal, semua orang yang lama mengenalnya tahu, Mbak Sonya tidak anti asap rokok.
Semua orang dekat kami, sebelum Mas Aran, sudah tahu bahwa yang membuat Mbak Sonya jatuh cinta dengan mantannya dulu, Mas Bayun, adalah bau rokoknya. Apalagi, almarhum kakek Mbak Sonya adalah pemilik pabrik rokok klobot Sinuwun yang legendaris itu, yang sekarang dipegang oleh pakliknya.
“Mas Aran, bolehkah aku bercerita sebentar? Sepertinya kita masih punya waktu,” aku minta izinnya dan dia mengangguk membolehkan.
“Aku tidak ingin membela siapa-siapa di sini. Sebagai sahabat Mbak Sonya, aku menyayangi kalian semua.
“Soal kedekatanku dengan Mas Dimas, itu tidak bisa dipungkiri. Aku mengenalnya sebagai orang yang menyayangi Mbak Sonya. Dia juga dekat dengan keluarga Mbak Sonya.
“Aku bisa paham kenapa Mas Aran cemburu, tapi Mas Dimas tidak sejahat itu. Bahkan kemarin dia bilang ingin menemuimu untuk meminta maaf. Aku tahu karakternya, dia tidak bisa lama-lama menyimpan dendam.”
Kulihat Mas Aran melengos tapi aku tetap melanjutkan ceritaku.
“Soal teh, Mbak Sonya mungkin memang salah tidak bisa menempatkan diri ketika bersamamu. Bertahun-tahun, Mbak Sonya menghirup aroma teh dari Mas Dimas, mungkin dia belum bisa menyesuaikan diri.
“Aku pernah berkata padanya, sebaiknya jika sedang bersama Mas Aran, minumlah minuman yang sama-sama kalian suka. Entah, apakah Mbak Sonya menerima saranku atau tidak. Tapi, aku pun tidak berhak ikut campur urusan rumah tangga kalian, kan?
“Untuk soal rokok. Harus kuceritakan padamu hal yang sebenarnya membuat Mbak Sonya uring-uringan jika kamu merokok, Mas.
“Mas Aran masih ingat Bayun, kan? Dia mantan Mbak Sonya. Mbak Sonya cerita padaku kalau Mas Aran pernah membakar buku puisi Mbak Sonya yang dibuat untuk Mas Bayun.
“Yang membuat Mbak Sonya jatuh cinta sama Mas Bayun adalah bau rokok. Dia ingin menghilangkan masa lalu itu, Mas. Setiap melihat rokok, dia masih terbayang Mas Bayun. Andai saja Mas Aran tahu betapa nelangsanya Mbak Sonya dicampakkan Mas Bayun, pasti Mas Aran akan paham. Jadi sebenarnya bukan masalah di rokok Mas Aran, tapi kenangan pahit yang menyertainya.
“Mbak Sonya tidak mau bercerita soal ini padamu. Memang, yang aku sesalkan, kenapa dia harus membandingkan dirimu dan Mas Dimas dengan alasan tak masuk akal soal hidup sehat itu. Sebagai sahabat, aku juga memarahinya.
“Kurasa, seharusnya dia tidak usah membawa-bawa Mas Dimas. Aku paham memang Mas Dimas-lah yang ada di sisi Mbak Sonya ketika terpuruk, tapi seharusnya Mbak Sonya juga bisa menjaga perasaan Mas Aran. Seharusnya dia jujur saja kepada Mas Aran, toh Mas Aran suaminya. Tapi memang Mbak Sonya adalah orang yang susah ditebak.”
Mas Aran terdiam mendengar ceritaku. Sebenarnya aku juga bingung dengan diriku sendiri. Sudah benarkan aku berbuat demikian? Apakah aku sok bijak? Sok netral? Terlalu ikut campur? Tapi, sungguh, aku hanya tidak ingin semua ini semakin berlarut-larut. Membiarkan Mbak Sonya tidak tenang, membiarkan Mas Dimas hidup dengan rasa sedih dan bersalah, membayangkan Mas Aran harus menghabiskan berapa tahun hidupnya dalam penjara. Semoga saja pengacara Mas Aran bisa melakukan tugasnya dengan baik untuk melobi keringanan hukuman kepada hakim mengingat Mas Aran melakukannya dengan tidak sengaja.
Waktu kami berbincang sudah habis. Aku masih sempat berkata pada Mas Aran sebelum dia kembali ke ruang tahanannya.
“Mas, relakan Mbak Sonya, ya. Biarkan dia kembali ke tempat ke mana seharusnya dia kembali. Juga maafkan Mas Dimas, maafkan aku pula yang sudah lancang berkata seperti ini. Sungguh, aku tidak ingin rasa cinta yang berlebihan pada Mbak Sonya membuat kita saling membunuh.”
Mas Aran menyalamiku. Aku tidak bisa menerjemahkan raut mukanya: apakah dia marah atau sedih atau entahlah. Aku melihatnya berjalan menjauhiku.
“Itu raut muka terima kasih, Ril. Terima kasih, ya, sudah datang menemuinya.”
Aku melihat Mbak Sonya berada di sampingku, memegang bahuku. Ia tersenyum. Bolehkah aku berharap kisah ini berakhir bahagia?