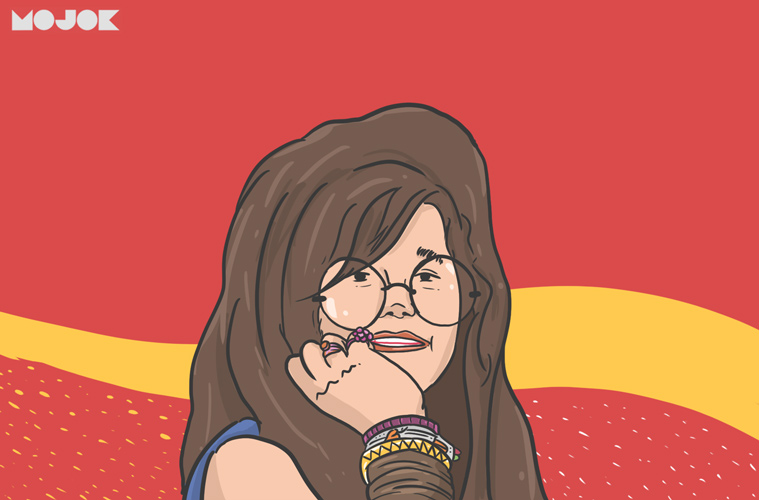Baca cerita sebelumnya di sini.
“Jangan khawatir seberapa tinggi kau melompat. Pastikan saja parasutnya bekerja.”
Perempuan itu memalingkan wajah. Suara yang ia dengar keluar dari mulut seorang laki-laki yang berdiri dekat tangga, lima belas meter di belakangnya. Usianya akhir dua puluhan, mengenakan jaket kulit kedodoran dan celana jins hitam yang ketatnya bukan main. Sepatunya boleh dibilang tak layak pakai. Laki-laki itu tampak salah tingkah, yang kemudian berusaha ia samarkan dengan mengusap kepala gundulnya.
“Aku tidak kepengin mati sekarang,” kata perempuan itu sedikit berang. Ia menjulurkan kepala, mengira-ngira ketinggian bangunan dari atap tempat ia berdiri sekaligus memastikan apa yang ia inginkan dan apa yang tidak ia inginkan saat itu. Jujur saja, dua botol bir dingin yang ia tenggak belum lama ini membuat kepalanya terasa berat dan ia kepengin buang air kecil.
Dengan hati-hati, perempuan itu kemudian mundur, menyeret langkahnya pelan seolah lantai bangunan itu bakal membuatnya tergelincir. “Lagi pula gedung ini cuma tiga lantai,” katanya lagi. “Kalaupun aku melompat, kurasa aku tak bakalan mati.”
Perempuan itu membalikkan badan. Ia lalu membawa kedua tangannya ke mulut, meniupnya untuk menghalau rasa dingin yang bersarang di sana. Dengan langkah sedikit terhuyung, ia berjalan ke arah si lelaki. “Percaya atau tidak, harusnya aku mati setahun yang lalu,” ucapnya. Barangkali ia setengah mabuk atau barangkali ia memang gemar meracau tengah malam, pikir si lelaki.
Mereka kini berhadap-hadapan. Si lelaki mengulurkan bungkus rokok. Perempuan itu menarik sebatang, sementara si lelaki menggeret batang korek api buat si perempuan..
Perempuan itu menyulut rokok sembari membungkukkan badan. “Aku sering melihatmu di sini,” katanya mengembuskan asap di mulutnya.
Saat menjentikkan puntung korek api, laki-laki itu menyadari kalau ia juga sering melihat perempuan itu sendirian di bar yang berada di lantai dua. Ia sama sekali tak mengenal perempuan itu. Namun, ia merasa mereka punya kesamaan, meski ia belum yakin di mana letak kesamaan mereka.
Barangkali, ini barangkali saja, perempuan itu pernah bermimpi sebagaimana mimpinya empat tahun lalu: melihat sepasang bayi ikan arapaima berputar-putar dalam sebuah ember milik seorang petani kakao di Ekuador, Amerika Selatan. Ketika ia berusaha menangguk ikan itu dengan gayung, seekor ikan arapaima lantas menjelma sebutir telur ayam kampung, sementara yang satunya lagi berubah menjadi seorang astronom tak terkenal.
Ia tak tahu artinya mimpinya. Namun, temannya (ia tak begitu yakin mereka berteman sebab usia mereka terpaut cukup jauh), Sal, menempelengnya bolak-balik tiga kali dan bilang ia terlalu banyak minum soda.
“Aku Tom,” ucap si lelaki. Ia menyalakan rokok untuk dirinya sendiri.
Untuk sejenak, perempuan itu membiarkan rokok terselip di bibirnya meski asap membuat matanya perih. “Maaf-maaf saja, ya,” katanya sambil mengikat rambut dengan gelang karet. “Namamu memang—cuma—tiga huruf, tapi akhir-akhir ini aku susah sekali mengingat nama seseorang. Harusnya kau tak menyebut nama. Jadi, andaikan kita ketemu lagi, setidaknya aku tak merasa bersalah kalau sekiranya nanti aku lupa.”
Laki-laki itu menyeringai. “Tom bukan nama asliku, sebenarnya. Kucomot dari majalah,” ucapnya mengaku.
Kebenarannya memang seperti itu. Malam itu, sembari menunggu penampil di acara Blues on Tuesday menyetem gitar, ia membolak-balik majalah musik usang terbitan Desember 2011 dan tak sengaja menemukan sebaris tulisan: Tom Waits, ‘Bad as Me’. Tom terdengar bagus, pikirnya.
“Nama asliku Suharto.”
Si perempuan menjentikkan abu rokok. “Terserah kau sajalah. Lagi pula aku tak peduli namamu Suharto atau Try Sutrisno” jawabnya tak ambil pusing. “Tapi, baiklah, malam ini namamu Tom. Tom, apa yang kau lakukan di sini?”
“Sama dengan yang ingin kutanyakan,” kata Tom atau Suharto atau Try Sutrisno atau siapa pun namanya. “Apa yang kau lakukan di sini?” tanyanya balik dengan intonasi yang sama.
“Sejujurnya, aku tidak tahu apa yang kulakukan di sini. Hanya saja, lagu terakhir yang dibawakan penyanyi tadi membuatku kepengin muntah sekaligus mengingatkanku seseorang.”
“Penyanyi yang mana?”
“Yang membawakan lagu The Doors dan Nick Cave.”
“Aku tadi malah hampir menangis. Dia bernyanyi seperti Nick Cave bernyanyi,” ucap Tom tulus. Kata “menangis” adalah pujian tertinggi yang bisa ia berikan seolah air matanya begitu berharga buat dihamburkan. “Aku suka sekali dengan lagu itu, terutama di bagian ‘in a world where everybody fucks every body else over’,” ujar Tom. Ia mengisap rokoknya.
“Kau boleh saja tak percaya dan menganggapku masih berbohong, tapi aku benar-benar mengenal penyanyi itu.” Tom kemudian menyebutkan sebuah nama.
Si perempuan dan kita, para pembaca, boleh saja tak percaya. Namun, Tom mengaku kalau ia adalah salah seorang yang menjadi saksi hidup bagaimana sebuah band bisa hancur gara-gara sepasang sepatu futsal dan seorang personel mereka jatuh cinta.
Saat itu ia masih kelas dua SMA. Guru bahasa Indonesia di sekolah membuatnya harus berkunjung ke ruang baca yang letaknya tak jauh dari tempat ia tinggal. Kau tahu, Tom tak dikasih uang saku selama dua bulan gara-gara kedapatan mengisap lem di belakang rumah. Toko buku yang jauh dan harga buku yang terlalu mahal adalah alasan sampingan yang bisa ia sodorkan.
Saat itu, ia dan teman-temannya diwajibkan menulis resensi novel Laskar Pelangi. Tom menyukai novel itu meski bagian “dihadang buaya” dan “bersepeda puluhan kilometer ke sekolah” terdengar berlebihan buatnya.
Dihadapkan dengan kewajiban seperti itu, bolak-balik ke ruang baca, Tom justru bertemu dengan orang-orang baru dan mereka lumayan asyik. Singkat cerita, ia berkenalan dengan Sal. Sal bersama teman-teman kuliahnya membentuk sebuah grup musik. Aliran musik mereka secara bulat-bulat menghadap ke Seattle. Tom berulang kali meminta agar ia didapuk menjadi anggota band. Saat itu—barangkali sekarang masih begitu—menjadi “anak band” sungguh terdengar keren dan, meminjam istilah Sal, di sekolah kau tak bakal kesulitan menemui siswa perempuan yang rela antre buat menyentuh pesak celanamu.
Sal dan teman-temannya jelas tak punya pikiran buruk tentang Tom. Di suatu Minggu sore yang cerah, mereka lantas mendapuk Tom jadi manajer, lebih tepatnya tukang suruh-suruh. Namun, Tom tak sedikit pun merasa tersinggung. Ia merasa bagian dari sesuatu dan melakukan tugasnya lebih baik dari personel lain.
Tiga bulan setelah ia resmi menjadi manajer, Perahu Tua—nama band mereka—mulai mentas di kafe-kafe pinggiran di kota kecil itu. Masalah muncul saat salah seorang dari pemilik kafe protes sebab, setelah Perahu Tua tampil di kafenya, pengunjungnya malah makin sepi. Pemilik kafe menuding Sal, sang vokalis, tidak bisa main musik dan musik mereka terdengar seperti bunyi knalpot motor terminator.
Saat itu, Tom kepengin sekali menumbuk mulut si pemilik kafe sampai hancur, kalau bisa lukanya langsung sembuh sehingga ia bisa menumbuknya sekali lagi, sampai hancur. Menurut Tom, suara Sal tidak buruk-buruk amat, malah bisa dibilang lumayan. Sementara itu, permainan bassnya boleh diadu.
“Sal orangnya agak sensitif,” ucap Tom. “Ia mogok latihan selama seminggu. Namun, ia juga orang paling lapang dada yang pernah kukenal. Di hari kedelapan, ia mengumpulkan semua anggota band di depan ruang baca. Kemudian, dengan besar hati, ia mengumumkan akan melepas posisi vokalis pada seorang laki-laki tampan, teman baru mereka yang tak bisa main alat musik, agar Perahu Tua tetap bisa manggung. Yang membuat hatiku hancur adalah ketika Sal bilang, ‘setidaknya aku masih bisa seperti Krist Novoselic.’”
Tom menjatuhkan puntung rokok kemudian melindasnya dengan ujung sepatu. “Asal kau tahu, laki-laki yang menyanyikan lagu The Doors dan Nick Cave tadi dulunya adalah vokalis Perahu Tua yang menggantikan Sal.”
“Lalu apa yang terjadi?” tanya si perempuan.
“Tak ada yang benar-benar terjadi. Maksudku, semuanya berjalan lancar dan permainan mereka terdengar jauh lebih jernih,” ujar Tom. “Lalu gitaris kami, Jojen, jatuh cinta.”
Tiba-tiba si perempuan tertawa. “Boleh kulanjutkan?” pintanya seraya melentingkan puntung rokok. Tom tak menjawab.
“Jojen sering mangkir dari latihan,” tebak si perempuan puas. “Kalau boleh kutambahkan, ia mencintai perempuan yang salah,” kata si perempuan mencemooh.
Tom tersenyum getir. Ia kembali mengusap kepala gundulnya saat menyadari perempuan di hadapannya punya lesung pipit, seperti kekasihnya dulu. Ternyata tak perlu uang untuk membuat seorang perempuan tersenyum, pikirnya.
“Ya, barangkali takdir selalu berlaku demikian. Memilih lalu mencintai orang yang salah adalah cara tuhan mengerjai manusia,” ucap Tom.
“Tai memang,” kata si perempuan mengangguk pelan. Ia kepengin muntah dan buang air kecil sekaligus. “Kurasa semua orang punya kecenderungan buat memilih pasangan yang salah, lalu secara tak sadar menikmati saat mereka tersakiti sambil berdalih itulah yang dinamakan cinta.”
Tom terdiam untuk sesaat. Perempuan itu ada benarnya, pikirnya.
“Bangsat, dingin sekali!” maki Tom seraya mengosok-gosokkan kedua telapak tangannya. “Aku hampir tak bisa merasakan telingaku sendiri.”
“Hari ini aku baru saja ditinggalkan pacarku,” ucap si perempuan tiba-tiba, agak tertahan. “Boleh aku menginap di tempatmu?” tanyanya nyaris menangis. “Aku tak ingin pulang malam ini.”
Tom tak mengerti apa yang terjadi. Ia hanya menjawab dengan anggukan, lalu mengeluarkan ponsel dari saku celana. Pukul 01:42. Ia mengedarkan pandangannya. Kota kecil itu sudah terlelap. Kemudian, entah kenapa, sejenis perasaan haru hinggap di dadanya.
Mereka berbalik dan berjalan berdampingan. Ketika sampai di mulut tangga, si perempuan seolah teringat sesuatu. “Kau belum menceritakan tentang sepasang sepatu futsal itu,” katanya serak. Ia terhuyung dan nyaris rubuh andai Tom tak segera menahan tubuhnya.
“Masalah sepatu futsal itu akan kuceritakan setelah kau tidak mabuk lagi dan bisa mengingat nama seseorang dengan benar.”
“Namamu Try Sutrisno, bukan?”
Kemudian si perempuan muntah-muntah, mengeluarkan setengah isi perutnya.
Baca cerita berikutnya di sini.