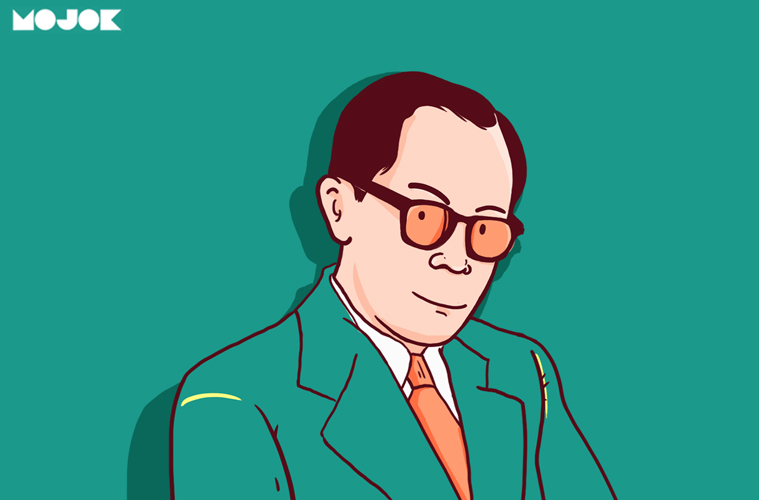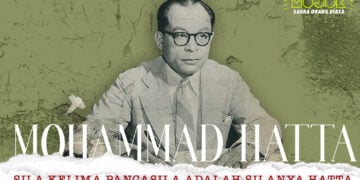MOJOK.CO – Di tengah jamuan makan malam yang meriah, seorang tamu pernah bertanya kapan hari ulang tahun si Om Kacamata. “Hari ini,” jawab Mohammad Hatta pendek.
Lelaki berkacamata itu lahir hari ini, 12 Agustus, 117 tahun silam di Bukittinggi. Mohammad Hatta merupakan tipikal lelaki yang sangat serius, berdisiplin tinggi, tak dapat berpisah dengan buku-buku, dan bersumpah tak akan menikah sebelum bangsa ini terbebas dari kolonialisme. Hatta baru merayakan ulang tahunnya yang ke-44 dengan Rahmi, seorang perempuan yang baru saja dinikahinya pada 18 November 1945, tiga bulan setelah Indonesia merdeka.
Pagi ini saya duduk di beranda kamar, menghadap Gunung Api, gunung yang menjadi berkah alam untuk tanah vulkanik Banda Neira, Maluku, tanah yang menumbuhkan pepohonan pala terbaik sedunia. Di pulau yang sama pada tahun 1936, Hatta dan Syahrir tiba dengan kapal Fommel Haut dari Boven Digoel di tengah kabut gerimis yang menutupi separuh wajah Gunung Api. Dalam pengasingannya selama enam tahun di Banda Neira, tiada seorang pun yang menyadari kapan tepatnya hari ulang tahun Hatta.
Des Alwi, anak angkat Hatta dari Banda Neira, menulis bahwa Om Kacamata adalah tuan rumah yang baik ketika mengadakan pesta meski dia tidak pernah berdansa layaknya Syahrir yang mahir berdansa. Hatta hanya menjadi penonton ketika para tamu mulai berdansa waltz, foxtrot, tango dan diselingi tarian-tarian lokal. Ia memilih bermain kartu dan sungguh-sungguh memperhatikan para undangannya, jikalau ada yang belum menikmati hidangan dengan cukup kenyang.
Di tengah jamuan makan malam yang meriah, seorang tamu pernah bertanya kapan hari ulang tahunnya. “Hari ini,” jawab Hatta pendek. Tetapi tamu tersebut tidak mempercayainya. Tak ada seorang pun yang mempercayainya karena mengira Hatta bercanda dan tak pernah secara terbuka mengumumkan hari ulang tahunnya.
Meski sama-sama di tempat pengasingan, kehidupan Hatta dan Syahrir di Banda jauh berbeda ketimbang kehidupan mereka di Tanah Merah, Digoel. Mereka berdua terserang malaria dan kekurangan makanan. Des Alwi dalam Sejarah Banda Naira (edisi revisi, 2010), teringat wajah pucat Hatta dan Syahrir ketika datang di pelabuhan bersama delapan koper kayu berisi buku dan empat tas besar dari kulit.
Sementara itu, Trikoyo Ramidjo, salah satu tahanan politik di Tanah Merah, juga menuliskan kenangannya pada Hatta ketika merayakan ulang tahun.
“Aku ingat Om Hatta. Pada hari itu, kami di Digoel, Tanah Merah, berkumpul. Tidak terkecuali Om Sutan Syahrir. Memperingati hari ulang tahun Om Hatta. Kami makan roti bersama dengan telur mata sapi atau telur ceplok,” kenang Ramidjo.
Di Banda Neira dengan uang tunjangan sebesar 75 gulden untuk tahanan yang masih membujang, Hatta mampu menyewa rumah bekas seorang Belanda, pemilik kebun pala yang kaya (meski konon, menurut orang-orang sekitar berhantu), mengirimkan bantuan untuk para tahanan politik yang lain dan menyisakan uangnya untuk menggaji tukang masak dan pembantu laki-laki.
Diasingkan di Banda, di kepulauan yang menjadi pusat perdagangan rempah dan kota kosmopolitan hingga pertengahan abad 19, membuat kehidupan Hatta dan Syahrir bercorak borjuis, dan hal ini sempat dikeluhkan Syahrir dalam salah satu suratnya yang terhimpun dalam buku Renungan dan Perjuangan.
Bagaimana pun, masa pengasingan ini membuat mereka berdua punya limpahan waktu untuk membaca, membuka sekolah sore di teras belakang rumah, serta mengembangkan gagasan-gagasan kritis mengenai nasionalisme. Dalam sepucuk surat kepada kenalannya, Johannes Eduard Post, Hatta meminta dikirimi Das Kapital jilid dua.
“Terkait ini, saya harus menggangu anda sekali lagi. Apakah mungkin bahwa saya mengambil hanya jilid II dari salah satu kawan, yang tidak butuhnya lagi? Seperti anda tahu saya memiliki jilid I dan III lengkap. Apakah ibu Holst bisa bantu dalam hal ini? Dia kenal seluruh karya Marx dan tidak butuh Marx lagi untuk pekerjaan dia.”
Tak hanya demi asupan intelektualnya, Hatta juga meminta dikirimi buku-buku untuk para remaja, perempuan dan anak-anak demi mengembangkan pengetahuan generasi muda Banda. Kecintaan Hatta pada buku pun, membuatnya dengan sangat berat hati meninggalkan dua peti kayu berisi buku-buku dan atlas Nederlandsch Indie oleh Lekkerkerker sebab pesawat Catalina yang akan membawanya dan Syahrir ke Surabaya masih kelebihan beban 130 kilogram. Kelak, Des Alwi, menyusul ke Jawa dengan membawa serta dua peti buku tersebut.
Sehari-hari, kehidupan Hatta begitu tertata. Seusai bangun pada pukul enam pagi, ia bercukur lalu mandi. Masih mengenakan piyama bergaris-garis biru ia menyeruput kopi tubruk di meja makan. Pukul delapan pagi, ia berganti pakaian necis dan menunggu Syahrir untuk sarapan bersama.
Menu sarapan sehari-hari roti dengan mentega atau selai diselingi nasi goreng dengan lauk sisa semalam. Menu siang dan malam sederhana saja: ikan, sambal dan dua jenis sayur bersantan. Rabu dan Sabtu giliran menyantap ayam goreng atau ayam rendang, hari Jumat gulai kambing hadir di atas meja makan mereka berdua.
Des Alwi menulis, kambing biasa disembelih penduduk Muslim Banda pada hari Jumat. Daging sapi hanya dapat diperoleh satu kali sebulan, itu pun jika penjagal yang berkeliling dari rumah ke rumah telah mendaftar cukup banyak permintaan daging. Kemarin, untuk pertama kalinya saya makan daging sapi oleh sebab hari Idul Adha. Waktu bergerak lambat di sini.
Daging sapi masih hanya benar-benar dinikmati setahun sekali oleh orang-orang Banda, kecuali ada orang kaya yang mengadakan hajatan besar, dan tak setiap bulan—tidak seperti zaman pengasingan Hatta—penjagal mengumumkan akan menyembelih sapi (kini pengumuman itu disiarkan pula di grup Facebook).
Saya tak ingin mengatakan bahwa waktu di Banda Neira terasa berhenti. Meski sinyal telepon dan internet cukup bagus—berlaku bagi satu operator saja—berjarak kurang dari dua kilometer dari ibu kota kecamatan, sinyal melemah di Kampung Tanah Rata yang kontur tanahnya tak benar-benar rata, padahal masih satu pulau yang sama.
Pasokan kebutuhan sehari-hari didatangkan seminggu dua kali dari Ambon, Makassar dan Jawa. Daging ayam beku perlu didatangkan dari Jawa. Buku-buku bacaan dan pelajaran baru bisa dibeli di Ambon, berjarak delapan jam melintasi jalur laut.
Seminggu sudah saya menunggu paket kiriman buku dari Yogyakarta sampai di Banda Neira. Estimasi pengiriman bisa mencapai sepuluh hari lebih, tergantung jadwal kapal dan cuaca dan entah bagaimana rute ekspedisi yang rumit yang membuat Banda terasa sangat jauh.
Memang, saya tidak perlu menunggu berbulan-bulan lamanya seperti Hatta menunggu kiriman buku-bukunya datang. Tetapi, di hari ulang tahunnya ini saya pikir, kehidupan terus berjalan di luar sana, dan Banda Neira yang tak pernah memunggungi laut seolah memunggungi sejarah, masa ketika pala mempertemukan para pedagang lintas dunia dengan masyarakat multietnis.
“Itu kenapa kata Pak Hatta, Banda Neira adalah miniatur Indonesia!” ucap Bu Nona berkali-kali sembari menunggui singkong yang tengah ia goreng. Saya mengangguk, bersepakat.
Di tepi laut, menghadap Gunung Api, empat kucing kelaparan tengah memakan abon ikan yang saya tuangkan. Saya termenung menatap mereka. Tiba-tiba saja saya ingin menamai mereka seperti Hatta menamai kucing-kucingnya di Neira: Hitler, Mussolini, Franco, dan Tito.
Om kacamata yang sangat serius itu ternyata mempunyai selera humor juga. Tapi, tentu saja, saya akan menamai keempat kucing kampung ini dengan nama diktator lain. Kim Jong Un, Pol Pot, Idi Amin, dan Harto mungkin.