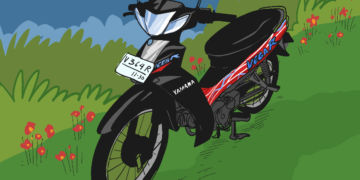MOJOK.CO – Makan nasi jagung tak pernah senikmat ini.
Di tengah semakin banyaknya acara jalan-jalan yang disertai review kulinernya, saya tahu saya tidak bisa menawarkan jaminan apa-apa dalam tulisan kuliner ini.
Tapi, kalau Anda memang seorang yang menikmati pengalaman spiritual dalam menghadapi meja penuh makanan, dan kalau Anda seorang yang mengapresiasi keindahan jukstaposisi antara hal-hal yang saling bertolak belakang, mungkin tulisan ini untuk Anda.
Inilah sebuah tulisan tentang sebuah warung makan yang bersahaja, dengan menu bersahaja, di tempat yang bersahaja pula, tapi menawarkan pengalaman yang luar biasa.
Warung ini terletak di Dusun Krapyak, Desa Kutogirang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Sebagai gambaran kasar tapi akurat, lokasinya ada di lereng utara Gunung Penanggungan. Kalau Anda ada di Surabaya dan melihat ke arah selatan, Anda akan melihat jajaran pegunungan. Dua yang paling tinggi adalah Gunung Welirang dan Gunung Arjuno. Nah, gunung yang berukuran setengahnya di bagian depan jajaran itu, yang berbentuk tumpeng sempurna, itulah Gunung Penanggungan. Di lereng yang bisa dilihat dari Surabaya tersebut terletak warung nasi jagung tokoh cerita ini berada.
Warung itu sederhana. Letaknya di sebuah teras rumah di satu pertigaan kampung kecil, berseberangan dengan sebuah musala kampung kecil. Pendeknya, dari muka, warung ini tidak tampak sebagai tempat yang bakal menyedot perhatian banyak orang.
Di seberang warung itu ada pekarangan kosong yang difungsikan sebagai tempat parkir motor dengan dua juru parkir berjaga. Untuk mobil, tetap saja harus diparkir di pinggir jalan kampung yang kecil dan berpaving rapi.
Kesan yang menunjukkan bahwa warung ini kurang menjanjikan sebagai sebuah tempat berkumpul akan mulai terkikis begitu Anda mendekat dan melihat lebih dalam. Di sana, ada satu bagian seperti panggung yang bisa dipakai untuk makan 7 hingga 10 orang. Di bagian samping, di antara rumah si pemilik warung dan rumah tetangga sebelahnya, sudah disiapkan berderet-deret meja pendek yang bisa menampung lebih dari 30 orang.
Ini warung lesehan. Anda harus melepas sandal dan makan sambil duduk bersila (atau bersimpuh. Atau selonjor. Atau berdiri, kalau Anda cukup nekat).

Terus, apa istimewanya kuliner yang disajikan warung ini sampai Anda harus menunggu beberapa paragraf sebelum sampai pada bagian yang menyentuh lidah?
Nama warung itu sendiri sudah cukup jelas. Menu utama yang ditawarkan adalah nasi jagung atau nasi yang berasnya dicampur dengan tumbukan kasar jagung. Dalam bahasa Jawa, makanan ini disebut dengan menir. Tentu, buat Anda yang lebih konvensional dan enggan bereksperimen, ada nasi putih standar yang bisa dipesan.
Menu sampingan alias lauk-pauknya justru tidak standar dan butuh penjelasan mendetail tersendiri. Yang saya pesan ketika datang ke sana, misalnya, terdiri dari dadar jagung (atau bakwan jagung), tempe goreng, tempe menjeng, bakwan petai, ikan asin, dan ikan wader. Memang bisa dibilang di sini hanya ada lauk-pauk yang bersahaja.
Lele dan ayam goreng, yang sudah populer sebagai elemen wajib menu lalapan, tidak terwakili di warung ini. Sekali lagi, warung ini menyasar lauk-pauk bersahaja saja, yang bisa dibuat siapa pun. Kalau kita terjebak ke dalam eksotisme, bisa kita bayangkan bahwa inilah lauk-pauk yang dulu dibawa Pak Tani ke sawah dan dimakan di gubuk pinggir pematang.
Untuk melengkapi lauk-pauk tersebut, ada kuah sayuran. Untuk hari ini, kami memesan sayur kelor. Pada prinsipnya, sayur kelor adalah sayur bening dengan bumbu standar plus kunci (kunci ini kunci yang bumbu temannya jahe, kunyit dan lengkuas ya, bukan kunci motor matic Anda). Bersama daun-daun kelor, ada biji-biji lamtoro (petai kecil) yang tentu saja menambah tekstur dan rasa kuah sayur bening tadi. Kalau Anda punya susuk atau “add-on kesaktian” tersisip di tubuh Anda, tolong pikirkan masak-masak sebelum memesan sayur kelor. Konon, daun kelor ini bersifat menetralisir dan mematikan kekuatan susuk. Semacam anti malware kalau di dunia perangkat lunak.
Yang unik adalah harga dan pilihan lauk-pauk ini. Para waiter (ehem, sampean waiter, kan, Cak!) akan datang kepada Anda dengan membawa sebuah loyang lurik biru legendaris yang isinya adalah lauk-pauk berbagai rupa (sebut saja “assorted lauks” agar terdengar internasional). Anda menentukan sendiri lauk pauk apa yang Anda pilih. Ambil satu piring penuh dengan harga Rp10.000,00. Kalau dirasa kurang, ya silakan ambil lagi.
Paling akhir, sebagai penajam rasa, ada satu elemen yang saat ini kian populer di mana-mana: sambal aneka rupa. Saya menyebutnya sambal tujuh warna, meskipun saya tidak yakin berapa jenis sambal yang ada di sana.
Sambal diantarkan di atas cobek tanah liat yang lebar (mungkin setara dengan 12-inch pizza kalau Anda pesan di Domino’s Pizza). Cobek tersebut terbagi ke dalam beberapa bagian sambal. Biang sambalnya sendiri sama, yaitu sambal terasi (dengan pedas sesuai selera). Tapi isinya yang berbeda-beda: ada sambal tempe (dengan tempe kukus dan yang dipenyet hingga lumat), sambal ontong (hati dari bunga pisang yang dikukus dan dipenyet hingga lumat), sambal kacang panjang (kacang panjang muda yang masih renyah kriak-kriak, juga dipenyet hingga agak lumat bersama terasi), serta sambal turi (tentu saja dari bunga turi, yang dulu merupakan elemen penting dari “turinisasi” atau penanaman turi di pinggir jalan pada masa orde baru, yang juga dipenyet hingga agak lumat). Namun, yang paling saya gemari (bersaing dengan sambal kacang panjang) adalah sambal pencit (sambal dengan mangga muda yang diserut dan dipenyet bersama sambal terasi hingga menghasilkan sari mangga yang… “Oh!”).
Mak! Ayo ditabuh kendange, Cak Met!
Saya tidak ingat pasti apa lagi sambal yang ada di sana. Yang pasti, saya sekarang jadi ingat dan sadar bahwa sambal warna-warni tadi seperti pizza yang dipesan oleh pelanggan cerewet, yang minta seperempat diisi jalapeno, seperempat nanas, seperempat jamur kancing, seperdelapan anchovy (alias ikan asin), dan seperdelapan greek cheese. Tapi tentu saja, tadi, ketika makan, saya tidak bisa terbayang tentang pizza sama sekali. Pesona sambal tadi terlalu kuat~
Kami duduk bersila, makan dengan telap-telep, tentu saja dengan tangan kosong. Setelahnya, kami menggelontor makanan yang lezat-lumizat tadi dengan es jamu (Anda bisa pesan jamu kunir asem atau jamu beras kencur). Kedua-duanya, bagi saya, benar-benar ratusan kali lebih nikmat dari Mountain Dew (soda favorit saya), Dr. Pepper (soda yang rasanya kayak sirup obat batuk), atau bahkan root beer lokal dari salah satu pedesaan Arkansas (yang sangat saya hormati ketulusan rasanya). Sayangnya, lagi-lagi untuk selera saya, rasa kunir asem maupun beras kencur itu terlalu manis.
Kayaknya, semua minuman zaman sekarang ini terlalu manis buat saya. Tapi, kalau dengar kata kanan-kiri, mengurangi konsumsi gula itu selalu lebih baik.
Jadi begitulah yang bisa saya ceritakan tentang Warung Nasi Jagung Kutogirang. Kalau Anda tertarik sejarah dan ingin menjadi seorang gastronom seperti almarhum Pak Bondan Winarno, mungkin Anda bisa melanjutkan tulisan bersahaja ini dengan penelusuran mengenai jagung sampai bisa menjadi makanan bersahaja bagi orang desa.
Sebagaimana Anda tahu, jagung berasal dari daratan Amerika dan lekat dalam mitologi penduduk asli Amerika. Dalam kepercayaan suku Maya, manusia diciptakan oleh Tuhan dari jagung (setelah sebelumnya gagal diciptakan dari tanah, kayu, dan lain-lain). Wow!
Jagung tiba di Nusantara melalui perantaraan orang-orang Portugis. Entah bagaimana ceritanya, jagung akhirnya diasosiasikan dengan makanan bersahaja, lebih bersahaja dari beras, yang beberapa milenium sebelumnya masuk ke Nusantara.
Atau, kalau Anda gemar arkeologi, mungkin Anda bisa menelusuri kenapa desa ini bernama Kutogirang (Kota Girang). Sebagai informasi tambahan, di dekat Kutogirang ini terdapat situs arkeologi bernama Patirtan Jolotundo, yang menurut sebuah prasasti merupakan tempat pemandian hadiah dari Raja Udayana dari Bali bagi puteranya, Raja Airlangga, yang menjadi Raja Kahuripan pada abad ke-10. Patirtan atau pemandian ini merupakan sumber air yang dipercaya memiliki kualitas air sangat bagus, bahkan bersaing dengan sumber air zam-zam di Mekkah. Sayangnya, sampai saat ini, saya belum menemukan hasil dari pemeriksaan ilmiah yang kira-kira bisa diterima secara luas.
Tapi, kalau Anda tidak menelusuri kesejarahan terkait jagung dan tempat warung ini, saya pikir tidak jadi soal. Anda bisa menikmati kuliner bersahaja saja di tempat yang bersahaja ini. Itu sudah cukup! Lagi pula, di sini bisa Anda dapati peleburan antara kebersahajaan dan keluarbiasaan. Dan, saya memilih untuk menanggapinya secara bombastis. Meminjam judul puisi William Blake, di Warung Nasi Jagung Kutogirang ini, akan Anda temukan “the marriage of bersahaja and luar biasa”.
Oh ya, saking luar biasanya, tadi waktu saya keluar dari warung, saya lihat ada beberapa kelompok orang yang makan di teras depan rumah tetangga warung ini. Ternyata, saat meluber, pemilik warung ini mempersilakan pelanggan untuk makan di teras rumah tetangga.
Sekali lagi, ini sungguh menjadi perkawinan kebersahajaan dan keluarbiasaan!