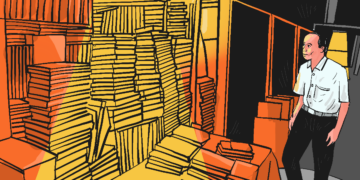Terkadang membeli buku adalah perihal memberi kejutan untuk diri sendiri. Yah… Sesedih itu memang. Dan memutuskan untuk tidak mencari tahu tentang buku yang akan dibeli bisa jadi pilihan bijak untuk para pemalas seperti saya. Dari Twitwar ke Twitwar, misalnya. Anggap saja saya membelinya karena alasan tunggal: penulisnya-Arman-Dhani-jadi-saya-perlu-beli-buku-ini. Titik.
Saya memang tak berekspektasi apapun dengan buku Dhani ini. Terlebih berpikiran negatif, seperti ‘ah, ini cuma kumpulan tulisan dan/atau twit-twitnya Dhani yang dibukukan’. Kendati seingat saya dulu dia pernah nyinyir terhadap semua buku yang isinya merupakan kumpulan tulisan yang pernah diposting di media sosial. Namun, setelah membaca buku ini sampai selesai, saya kemudian belajar, bahwa berpikir positif tidak selamanya menyehatkan.
Terlepas dari itu semua, saya percaya Dhani bukan tanpa alasan sudah berbaik hati membukukan sebagian banyak tulisannya—tentu selain untuk mendukung Buku Mojok yang tengah rajin-rajinnya menerbitkan buku. Dan daripada saya menebak-nebak apa yang terjadi sebenarnya, akan lebih menarik jika saya iseng-iseng menuding siapa saja sasaran Dhani dalam buku Dari Twitwar ke Twitwar.
Manusia-Manusia Dungu yang Gagal Melihat Perbedaan Sebagai Fitrah
Itu istilah Dhani, lho. Blio memang senang mengistilahkan seseorang/sekelompok orang dengan lebih panjang. Seperti juga, “manusia-manusia minim prestasi atau rendah pengetahuan yang menciptakan berhala-berhala baru mereka di media sosial”. Yaowoooh, membaca istilah tersebut, saya membayangkan Dhani seperti tengah berbusa-busa meneriaki patung Pancoran di tengah sekelompok orang yang khyusuk twitteran.
Balik ke topik. Dengan membaca tulisan-tulisan Dhani, saya bisa bilang, secara khusus, dia sebenarnya menyasar ‘orang-orang nomor (1)’, naif dalam membaca peristiwa dan memutuskan keberpihakan. Dia menyinggung mereka yang melakukan kekerasan atas nama agama, makhluk-makhluk yang gampang marah dengan demo buruh, manusia-manusia yang dengan mudah menghitam-putihkan ibukota, dan lain sejenisnya.
Pertanyaan kemudian, kira-kira jadi apa ‘orang-orang nomor (1)’ itu setelah membaca buku ini? Dhani mungkin akan menjawab, tergantung, sejauh mana mereka bertekad bersetia dengan kedunguan mereka sendiri.
Feminis
Dari beberapa tulisan di buku ini yang terkait dengan perempuan, bisa dimengerti bahwa Dhani tengah rajin memproklamirkan diri kepada mbak-mbak dan mas-mas feminis, perihal keberadaannya, sebagai seorang yang juga mempunyai tujuan yang sama, entah sebagai pembela hak perempuan atau sekadar sebagai selebtwit yang memperluas daerah kerjanya. Tidak salah tentu saja, selama itu bermanfaat.
Dengan Arman Dhani yang sudah bergabung di barisan pejuang yang ini, bersiaplah, berhati-hatilah, siapapun dari kalian yang lebih suka memandang, menikmati, merendahkan keberadaan perempuan, dan kerap menasihati mereka untuk belajar menjaga diri dan selangkangan. Allahu Akbar!
Pasangan Lintas Agama
Bagi yang sudah akrab dengan tulisan Dhani, otomatis juga akan akrab dengan mantan pacarnya yang beda agama, yang sering ia bawa-bawa di tulisannya, sebagai trivia. Meski begitu, Dhani sebenarnya ingin memberi semangat kepada pasangan lintas agama, bahwa bukan cuma mereka saja yang jatuh cinta dan merasakan perih bersama-sama, dia juga iya, dulu. Iya, dulu, yang oleh karenanya sampul buku ini saja bertuliskan mantan.
Tapi, ah, tidak cuma kalian saja yang merasakan perihnya beda agama kok, tidak pula Dhani semata, saya juga pernah, dan sialnya itu berjalan tak cuma sebulan-dua bulan, tapi tiga tahun–iya ini curhat. Dengan laki-laki (tentu saja), Kristen, Cina pula. Tapi bedanya, saya sudah berdamai, sedang Dhani menolak lupa.
Lalu apakah yang pertama lebih mulia dibanding yang kedua? Tentu saja tidak. Selebtwit selalu punya alasan untuk menolak lupa, seperti juga selalu punya alasan untuk menolak tidak twitwar.
Orang-Orang yang Selama Ini Menganggap Eksistensi adalah Hal Utama
Dhani sendiri yang mengatakan bahwa kutukan paling mengerikan dari menjadi manusia ialah kebutuhan untuk bereksistensi. Dan respons paling menjijikkan selama ia dikukuhkan menjadi selebtwit adalah: menolak dilabeli tetapi menikmati. Menolak dianggap sebagai rockstartwit, tetapi menikmati segala kemewahan berkat stereotipe tersebut.
Tetapi, kadang kita semua memang tidak bisa menolak, terlebih saat ada kesempatan untuk mengekspresikan diri, menjadikan diri sendiri dikenal, dan kemudian terkenal. Dan jika kalian butuh menciptakan kesempatan itu sendiri, Arman Dhani adalah guru tanpa tanda jasa.
Saya sendiri percaya, dengan kemampuannya sebagai mesin kata-kata, suatu saat Dhani akan mendapatkan balasan yang setimpal, entah dari dedek-dedek gemez yang sebatas hora-hore saja, orang-orang yang aslinya sudah pemarah tapi dibuat menjadi lebih ngamuk gara-gara Dhani, atau mereka yang masih betah merayakan mediokritas. Entahlah. Bisa dari siapa saja.
Joko Anwar pernah menyebutkan bahwa banyak film Indonesia yang mean spirited, auranya jahat. Filmmaker seakan-akan bikin film cuma pengen bilang, “Gue hukum nih penonton dengan nonton film gue”. Dan kecenderungan tersebut yang dewasa ini hidup, tumbuh, berkembang di lingkup penulis dan pembaca. Sudah dari dulu, sih. Bedanya, sekarang lebih vulgar.
Seiring dengan perkembangan gawai cerdas dari 2G menjadi 3G dan denger-denger sekarang sudah ramai 4G, bertambah rajin juga masyarakat menulis apapun di manapun. Beberapa penulis—orang-orang yang menulis, sadar atau tidak, merasa perlu melempar durian utuh ke kepala pembaca untuk membuat pembacanya ngerti.
Tentu saja saya tidak melulu membicarakan Dhani, apalagi menyalahkannya. Karena saya sendiri semakin sadar, bahwa membicarakan mean spirited bukan lagi perkara boleh-tidak boleh, perlu-tidak perlu, atau penting-tidak penting. Lha wong ini sudah menjadi style menulis kita semua, kok.
Sampeyan gak ngerasa gitu? Berarti sampeyan butuh baca buku Dhani yang onoh.