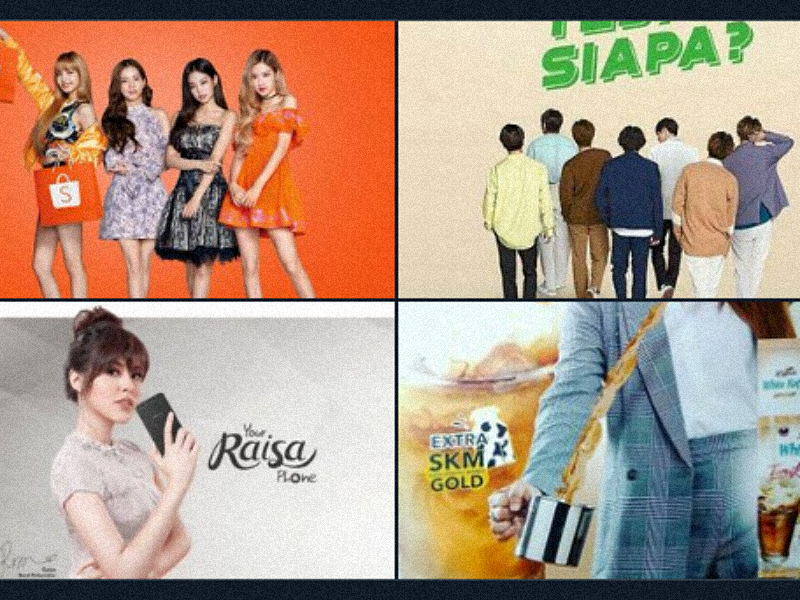Pemerintah Indonesia melalui Kemenparekraf sedang menggarap program wisata unggulan (prioritas) atau 10 Bali baru yang katanya untuk meningkatkan perekonomian daerah dan menyejahterakan warganya. Daerah pariwisata prioritas tersebut adalah Pulau Morotai (Maluku Utara), Mandalika (Nusa Tenggara Timur), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Tanjung Kelayung (Bangka Belitung), Danau Toba (Sumatra Utara), Tanjung Lesung (Banten), Bromo (Jawa Timur), Labuan Bajo (NTT), dan Borobudur (Jawa Tengah).
Jika kalian kebetulan tinggal di 10 daerah tersebut, bersiap-siaplah mendapatkan fasilitas “istimewa” dan pembangunan infrastruktur. Misalnya, jika sebelumnya sinyal telekomunikasi buruk, pasti sebentar lagi akan dibangun BTS baru. Kalau akses jalannya jelek, tenang saja, tak lama lagi akan diperbaiki. Kalau sebelumnya tidak ada bandara atau bandaranya masih skala lokal, jangan khawatir, selama daerah kalian masuk destinasi super prioritas, pemerintah dengan senang hati akan merubahnya menjadi bandara internasional.
Demi cuan, negara akan membuat keindahan alam kita menjadi komoditas yang bisa diperjualbelikan. Kadang, berkedok wisata.
Tanah-tanah akan dipatok untuk pembangunan resort, pantai-pantai direklamasi, suku asli direlokasi dan semuanya dilakukan atas nama menyejahterakan rakyat atau demi kebaikan rakyat. Pertanyaannya, rakyat yang mana? Apakah warga lokal pernah diajak rembukan dalam program wisata unggulan? Apakah warga lokal akan menjadi majikan di tanahnya sendiri? Jika kita berkaca pada Pulau Komodo, tepatnya Taman Nasional Komodo, yang terjadi adalah sebaliknya.
Negara memang hadir di Pulau Komodo, namun dalam bentuk “pengusiran” warga asli Pulau Komodo. Ata Modo (orang asli Komodo) yang selama ini hidup berdampingan dengan kadal purba “dipaksa” pergi dari tanahnya sendiri. Mereka direlokasi ke tempat lain dan dilarang berburu dan bertani di Pulau Komodo.
Ata Modo kemudian beralih menjadi nelayan. Namun, pemerintah kembali memperluas wilayah konservasinya sampai ke laut, sehingga Ata Modo beralih profesi ke sektor pariwisata, menjadi pekerja resort, pengrajin souvenir, atau pekerjaan lain yang mengandalkan upah dari majikan. Mereka kehilangan alat produksinya sendiri yaitu tanah, hutan di sekitar dan tercerabut dari ruang hidup alaminya. Negara secara tidak langsung telah merampas kehidupan Ata Modo dan menjadikan penduduk lokal sebagai budak di kampungnya sendiri.
Padahal, kalau memang ingin menyejahterakan rakyat, membangun wisata berbasis konservasi dengan Ata Modo bukanlah hal yang sulit. Ata Modo sudah puluhan tahun hidup di Pulau Komodo, dan hidup harmonis dengan kadal purba bahkan sebelum UNESCO menetapkan TNK sebagai situs warisan dunia pada 1991. Bicara soal menjaga habitat asli komodo, mereka jelas sudah teruji. Tapi, ya tetap saja pemerintah mengabaikan suara mereka dan bersikukuh melakukan relokasi.
Jika kita pergi ke Labuan Bajo hari ini, hampir seluruh pesisir pantainya juga sudah dikuasai oleh BUMN dan korporasi swasta. Dulu, warga Manggaria Barat masih bisa menikmati keindahan Pantai Pede dengan leluasa karena pantai tersebut adalah pantai umum. Namun, beberapa tahun ke belakang, resort-resort dibangun, tembok dan pagar mulai bermunculan lengkap dengan sekuritinya. Akhirnya, melihat pemandangan alam dengan spot terbaik tak mungkin lagi kita nikmati secara bebas dan gratisan.
Sekarang, mari kita lihat apa yang terjadi di Pulau Morotai yang juga sedang dalam proses pembangunan wisata unggulan. Daerah yang masuk 3T tersebut tengah dipoles wajahnya agar nampak lebih memesona di mata investor. Jaringan telekomunikasi ditingkatkan, resort-resort mulai dibangun, bahkan ada resort yang tarif per malamnya mencapai Rp20 jutaan. Jangan bertanya siapa pemiliknya, sudah tentu bukan rakyat jelata.
Kementerian PUPR bulan lalu juga baru saja menyelesaikan 170 unit homestay di Morotai dan mengatakan jika pengelolaannya akan melibatkan masyarakat setempat. Jangan senang dahulu wahai warga Morotai. Dulu, warga di sekitar Pulau Komodo dan Flores juga dijanjikan hal yang serupa, tapi ujung-ujungnya tetap korporasi besar yang berkolaborasi dengan pemangku kebijakan yang menjadi pemenangnya.
Melihat proses pembangunan wisata unggulan yang sudah berjalan, setidaknya ada tiga mekanisme atau pola yang selalu muncul. Pertama adanya regulasi dari pemerintah terkait kepemilikan sumber daya alam dan ijin usaha (resort, hotel dll) yang dibuat tidak untuk rakyat, tapi untuk mereka yang bermodal.
Kedua, adanya penguasaan lahan-lahan strategis. Biasanya warga lokal akan “dipaksa” menjual tanahnya ke pemodal dengan iming-iming harga mahal. Dan, dirayu kalau nantinya di daerah tersebut akan dibangun pariwisata unggulan yang kelak akan menguntungkan juga untuk warga. Warga juga bisanya dijanjikan akan diberi lapangan pekerjaan ketika sektor pariwisatanya telah berkembang.
Ketiga, pembanguan infrastruktur. Setelah adanya regulasi terkait kepemilikan SDA, lahan-lahan starategis dikuasai korporasi (swasta atau BUMN), pejabat setempat dan kelas elit lainnya. Infrastruktur akan digenjot besar-besaran agar banyak mendatangkan wisatawan. Untuk mengurangi risiko konflik atau protes masa, biasanya warga akan diajak terlihat dalam proses pembanguan entah menjadi pekerja bangunan atau pekerjaan lain yang sifatnya tidak dominan.
Dengan mekanisme pengelolaan wisata yang seperti ini, mengharapkan rakyat kecil menjadi majikan di kampungnya sendiri dan sejahtera dalam pengertian yang sesungguhnya adalah omong kosong.
Pada akhirnya, tanah-tanah yang telah dijual warga dan kini dimiliki korporasi dan pemodal, sangat menguntungkan secara ekonomi saat wisatawan sudah mulai berdatangan. Perlahan tapi pasti, warga yang awalnya memiliki tanahnya sendiri, justru menjadi manusia yang terperangkap pada sistem kerja upahan dan menggantungkan hidup dari pemilik resort. Sementara kesejahteraannya nggak akan jauh berbeda dengan sebelum-senyumnya. Mungkin saja lebih buruk lantaran sudah tak lagi memiliki tanah dan segala sesuatunya harus beli.
Pariwisata memang mampu mengangkat perekonomian, tapi tidak akan menjadi solusi untuk mengentaskan kemiskinan warga setempat selama negara tidak memposisikan dirinya menjadi pelindung untuk rakyat. Justru menyerahkan mekanisme pembangunan pariwisata unggulan sesuai kehendak pasar. Ha yo repot kalau begitu, bukannya kaya dan sejahtera, penduduk lokal malah miskin secara berjamaah.
Akhir kata, kita tentu tak ingin kembali hidup di jaman purba dengan menolak pembanguan infrastruktur dan kemajuan teknologi. Namun, sebagai rakyat yang tak memiliki kuasa menentukan kebijakan, kita harus tetap waspada terhadap segala bentuk iming-iming yang kelihatan menarik dan gigantik. Sebab, dalam sistem ekonomi kapitalistik, tidak ada yang gratis.
Penulis: Tiara Uci
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA Betapa Bahagianya Jadi Warga Gunungkidul, Jadi Turis di Kampungnya Sendiri