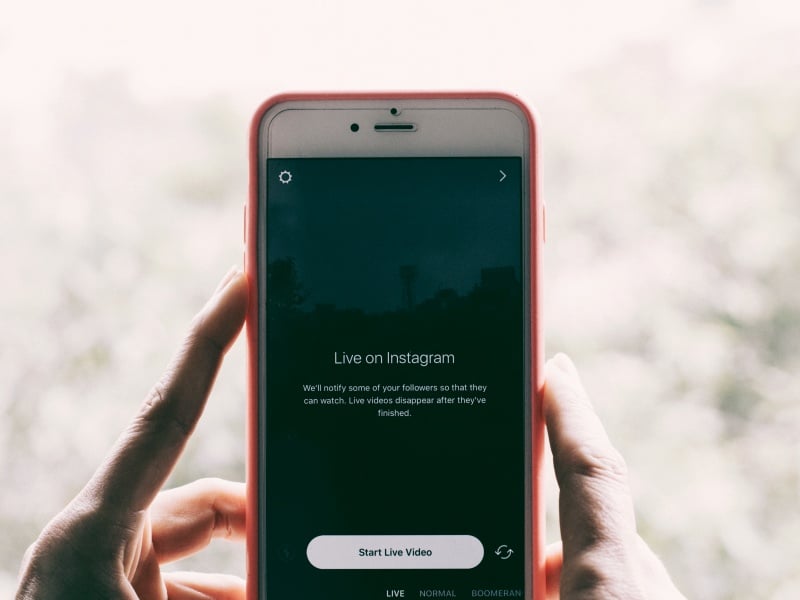Beberapa waktu lalu, ketika saya mengunggah foto sebuah pemandangan di luar negeri, ada teman yang berkomentar semacam ini—wuih, jalan-jalan mulu, nih! Komentar itu kedengarannya biasa saja, ya? Namun kalau dimaknai lebih dalam lagi, kamu akan punya perasaan yang sama dengan saya—teman saya ini, entah iri atau entah menganggap bahwa saya kaya dan kasta saya sudah jauh berada di atasnya.
Padahal untuk bisa ke negara tetangga itu, saya mesti mengumpulkan uang hasil kerja berbulan-bulan. Di sana juga tidak mungkin saya memesan makan malam mewah di atap Hotel Marina Bay, atau candlelight dinner sembari menikmati putaran Singapore Flyer.
Ini bukan pertama kalinya saya mendengar komentar memuji-tetapi-nyindir. Bukan cuma buat saya—tetapi buat orang lain juga. Misalnya nih, saat membeli tas baru yang branded, beberapa orang akan cuap-cuap begini—gila, tasnya mahal banget, kayak Syahrini. Melakukan aktivitas yang dianggap mewah oleh lingkungan sosial—termasuk mengenakan barang-barang mewah—seringkali dianggap sebagai bentuk perilaku pamer.
Makanya—kalau kamu rajin membuka Instagram—kamu akan melihat betapa banyaknya hujatan yang diberikan pada para selebritas yang ke luar negeri, pakai tas branded, atau makan di restoran sushi eksklusif yang pemotongan ikannya dilakukan di depan mata pelanggan. Metode hujatannya beragam, tetapi yang paling sering saya baca kurang lebih begini—banyak orang yang susah makan/kena bencana/hidup di daerah konflik, tapi lo masih aja enak-enakan begini.
Irasional? Ya jelas. Menurut saya, tidak ada korelasi jelas antara ada konflik di daerah tertentu, sama orang yang memang punya gaya hidup mewah. Mungkin buat kalian—tas Louis Vuitton seharga dua puluh juta itu mahal harganya. Namun buat orang lain—bisa saja nilai rasanya sama seperti kamu yang beli tas di Miniso misalnya. Jadi, ketika dia menunjukkan hal itu di media sosial bahkan di depanmu sekalipun, kemungkinan besar dia tidak benar-benar berniat untuk pamer.
Menyebalkannya, masyarakat kita sulit untuk menerima hal itu di antara berbagai kesenjangan sosial yang hadir atau yang mereka rasakan. Maka, tidak heran kalau sekarang banyak sobat kaya yang mengaku sebagai sobat miskin—atau kata bekennya, misqueen.
Pengakuan itu bisa dilakukan melalui berbagai macam cara. Pertama, dengan membandingkan diri dengan konglomerat kaya, kemudian mengklaim bahwa mereka merasa seperti ceceran kopi kekinian di lantai. Kedua, dengan mengatakan bahwa tas yang mereka beli adalah tas bekas/palsu, pura-pura mendapatkan tiket promo atau gratisan kuis liburan, atau bilang bahwa di perusahaan, posisi mereka hanyalah staf biasa. Ketiga, mengaku kalau tabungan mereka ludes karena membeli barang tertentu atau liburan ke suatu tempat. Namun, ketiga cara itu akan patah dengan kalimat ini: ah lo mah sok merendah.
Pujian itu dulu memang terdengar menyenangkan. Namun, lama-kelamaan, itu menjadi sindiran yang menunjukkan ketidakpercayaan orang terhadap kemiskinan seseorang. Prasangka itu kemudian berkembang menjadi cap sombong, rasa sakit hati, hingga tuduhan korupsi. Maka, tidak mengherankan apabila banyak orang yang justru ingin terlihat miskin. Kontradiktif memang dengan istilah BPJS alias budget pas-pasan jiwa sosialita yang memang sudah jadi sebuah fenomena masyarakat sejak lama.
Keduanya memang punya bentuk kesulitan yang berbeda. Bagi mereka yang pura-pura kaya, kesulitan terletak pada bagaimana cara untuk menyembunyikan jumlah asli tabungan dan meraih barang-barang serta gaya hidup yang mewah. Bagi mereka yang pura-pura miskin, mau tidak mau mereka harus menurunkan gaya hidup, tidak terlalu berkoar-koar saat liburan, dan juga menjaga lingkaran pertemanan. Iya, yang terakhir ini penting. Bukannya sombong, tetapi pertemanan, layaknya jodoh, akan ideal kalau selevel.
Karena kalau beda level sedikit, maka risikonya adalah, naiknya potensi sindir-sindiran antarteman ini. Teman dengan kelas sosial yang lebih rendah akan merasa bahwa kawannya terlalu sombong. Sementara itu, mereka dengan kelas sosial yang lebih tinggi akan berpikir bahwa kawannya tidak punya selera yang baik. Terlepas dari kelas sosial seperti apa, harus selalu berpura-pura untuk miskin hanya demi menjaga perasaan orang lain, memang menyebalkan. Karena, bukankah kita semua punya hak untuk menikmati apa yang sudah kita usahakan sebelumnya?