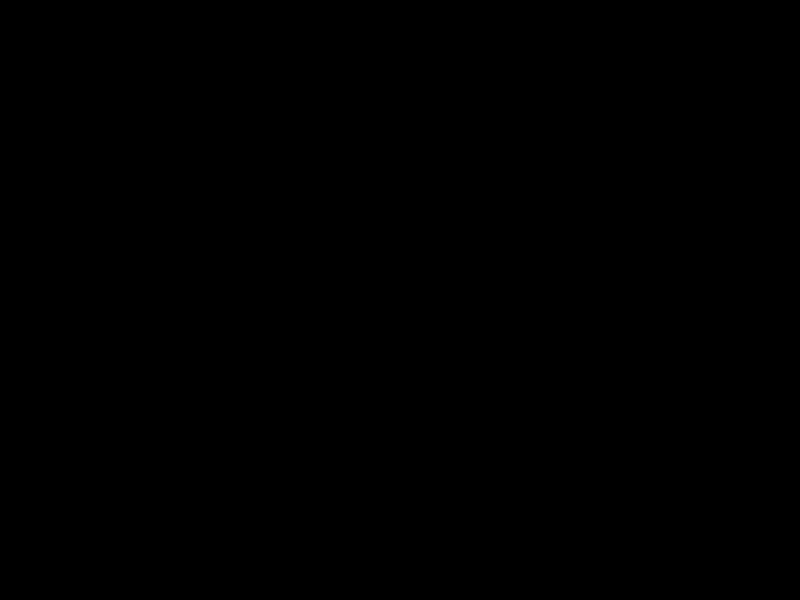Sebagai orang yang pernah mendekam di pesantren, bagi saya pribadi nggak bisa dimungkiri kalau pesantren adalah gudangnya pengalaman. Ketika lulus, stok kenangan seperti nggak ada habisnya buat diceritain, saking melimpahnya. Dari yang paling klise, seperti antre mandi, gosob sandal, join sabun atau sampo, kena takziran bersihin WC atau cukur gundul, makan bareng satu nampan, sampai yang paling sentimentil: apalagi kalau bukan gudiken. Itu masih belum seperempatnya.
Namun, ada satu kenangan kelam yang sering menghantui sebagian besar anak pesantren—meski bukan seluruhnya. Sesuatu yang kalau diingat-ingat bisa bikin bergidik, jijik, dan perasaan campur aduk sejenis itu. Yaitu, kasus-kasus pelecehan seksual sesama jenis yang sebenarnya sudah umum terjadi di kalangan para santri sejak dulu kala. Lebih khusus di pesantren cowok, nggak tahu kalau pesantren cewek kayak gimana.
Pertama Kali ke Pesantren
Dulu ketika pertama kali berangkat ke pesantren, saya nggak pernah bayangin apa pun kecuali kehidupan yang super ketat dan lingkungan yang suka nggak suka bakal membentuk para santri jadi pribadi yang lebih relijiyes. Subhanallah, heuheuheu. Sampai suatu ketika, tiga bulan sejak kedatangan saya di pesantren, saya menemukan satu masalah yang menurut saya sudah di level mengerikan. Yap, kasus pemerkosaan sesama jenis yang dilakukan oleh beberapa oknum santri.
Ceritanya, malam itu saya ngelilir karena kebelet kencing. Saya pun turun dari kamar ke toilet sebelah musala. Sehabis ngeluarin hajat kecil tersebut, saya bergegas kembali ke kamar karena masih ngantuk luar biasa. Langkah saya terhenti di tangga menuju kamar. Saya seperti melihat ada bayangan orang naik-turun di dalam musala yang remang-remang.
Karena penasaran, saya pun mengendap ke dekat pintu musala yang terbuka lebar-lebar. Ketika saya mengintip ke dalam, bajilak, itu adalah pemandangan pertama yang membuat tidur saya jadi nggak jenak berhari-hari berikutnya. Di depan sana, seorang santri tengah menunggangi santri lain yang sudah terlelap.
Kebiasaan-Kebiasaan Absurd Pesantren
Belakangan kemudian saya baru tahu dari beberapa santri lain, kalau santri yang “itu” emang udah kebiasaan kayak gitu. “Apa nggak dilaporin ke pengurus atau Pak Kiai?” pernah suatu hari saya bertanya demikian. “Halah, nanti malah jadi panjang masalahnya,” hanya begitu respons dari temen saya. “Lagi pula, hal kayak gitu udah biasa kok di pesantren-pesantren cowok mana pun. Kalau nggak mau jadi sasaran, pas tidur mending kunci aja kamarmu.”
Belakangan juga saya baru tahu kalau ada dua istilah khusus untuk menyebut aktivitas “aneh” tersebut, yaitu mairil dan nyampet. Mairil digunakan untuk menyebut tindakan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh si santri. Misalnya seperti yang saya contohkan di atas. Tapi lebih cocok kalau disebut sebagai tindakan pemerkosaan, sih. Karena korban bisanya nggak pernah menghendaki buat digituin. Pelaku mairil biasanya santri-santri senior dan korban kebanyakan adalah santri baru dengan tampang ganteng, putih, atau yang baby face gitu lah.
Kalau nyampet beda lagi. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan hubungan saling suka antara sesama jenis. Sederhananya, hubungan pacaran antara sesama santri laki-laki. Dan ini benar-benar ada dan terjadi di banyak pesantren di mana-mana. Jadi bisa dikatakan suka sama suka lah. Nggak ada unsur paksaan sebagaimana kasus mairil.
Penyebab Mairil dan Nyampet
Dari penelitian yang dilakukan oleh beberapa akademisi, setidaknya ada dua faktor utama yang menjadi sebab terjadi penyimpangan mairil dan nyampet di dunia pesantren. Pertama, alasan klasik adalah karena keterbatasan akses komunikasi antara santri cowok dengan santri cewek lantaran tempat mereka yang disekat atau bahkan dipisah jauh. Karena sudah kadung terbiasa hidup bareng, tidur bareng, bahkan ada yang juga mandi bareng dengan sesama jenis, akhirnya tumbuh lah hasrat tersebut.
Kedua, kurangnya kontrol dari pihak pesantren. Banyaknya jumlah santri membuat otoritas pesantren keteteran kalau harus memantau satu per satu kasus semacam ini. Alhasil, meski si korban mengadu berkali-kali, tetap saja pihak pesantren nggak bisa memvonis hukuman pada si pelaku mairil maupun nyampet karena bukti atau saksi yang dihadirkan nggak begitu kuat. Pernah ada yang melapor, tapi karena merasa kasusnya diacuhkan begitu saja, si korban pun membawa orang tuanya menghadap kepada kepala pengurus. Bukannya diusut tuntas, si korban malah dikeluarkan dari pesantren dengan tuduhan pencemaran nama baik.
Wawancara Korban Mairil
Saya sendiri pernah berkesempatan mewawancarai salah seorang korban mairil. “Jijik, Mas, hihhh, sampeyan bayangke wae tho. Siapa coba yang rela tubuhnya digerayangi sama sejenisnya sendiri?” akunya. “Saya sempat lapor. Tapi ya itu tadi, bukti saya nggak kuat. Kasus saya pun akhirnya menguap dan dilupain begitu saja.” Ada juga yang sengaja nggak ngelaporin ke pengurus. Alasannya, dia malu. Karena jika berita itu sampai di telinga pengurus dan diam-diam menyebar di kalangan santri lain, dia bisa jadi bahan olok-olokan. “Hiii, sudah ternodai, hiii,” misalnya dengan ungkapan seperti itu.
Kali lain saya juga sempat bertanya-tanya dengan pihak pengurus. Satu-satunya langkah preventif yang diambil adalah dengan jalan mengajak santri untuk selalu mengingat Allah, itu saja. Alhasil, kasus semacam ini lambat laun menjadi hal lumrah di lingkungan pesantren. Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi. Saking sudah dianggap sebagai hal yang biasa, bahkan ada yang mulai terang-terangan melakukannya.
Kalau kepada pelaku, saya masih belum kepikiran buat mengadakan dialog. Bukannya mendapat jawaban, salah-salah nanti malah saya yang diincar. Hla yo wegaaahhh.
BACA JUGA Pondok Pesantren Salaf Rasa Milenial dan tulisan Aly Reza lainnya.
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
Pernah menulis di Terminal Mojok tapi belum gabung grup WhatsApp khusus penulis Terminal Mojok? Gabung dulu, yuk. Klik link-nya di sini.