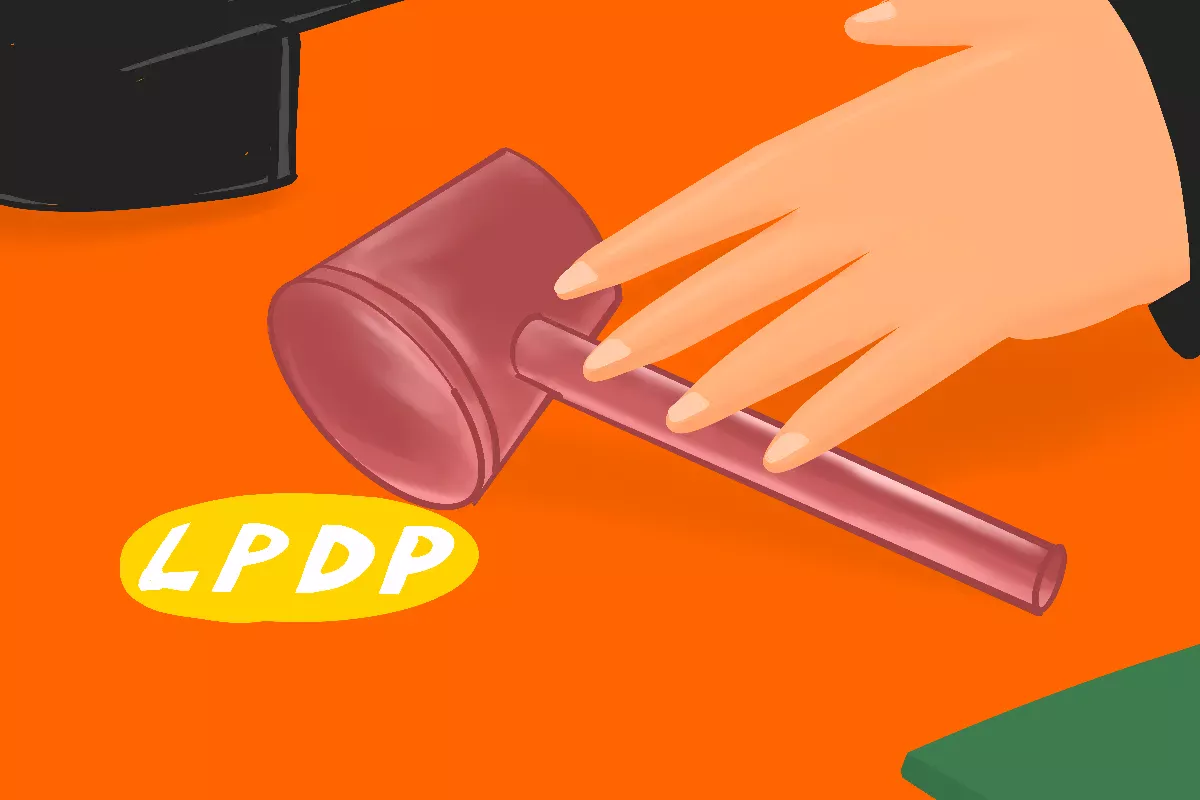Di kebun sawo, Misbah dan Kang Salim seru sekali ngobrolin soal ulama dan teladan nabi….
“Apa yang disampaikan sama ustaz yang ngisi ngaji rutinan semalem itu, rasa-rasanya kok masih ngganjel banget di hati saya, Kang,” gerutu Misbah sambil mencuci sawo yang baru pagi tadi dipetik bareng Kang Salim.
“Gimana ya, saya malah panas sendiri denger ceramahnya,” lanjut Misbah. “Hla mosok tradisi sedekah laut yang beberapa hari lalu kita gelar dikritisi habis. Katanya bidah lah, nggak ada tuntunannya lah. Parahnya, kok sempet-sempetnya jelek-jelekin salah satu ulama yang jadi panutan masyarakat sini. Mana diksinya kasar banget lagi. Semula saya kira orang ini ilmunya udah sundul langit jadi berani bilang begitu. Eh pas bacain Alquran, hla kok kocar-kacir. Ngawur nggak karuan. Heran saya kok bisa-bisanya nadir masjid ngundang ustaz kayak gitu.”
“Kebanyakan ngersula kerjaan kamu nggak kelar-kelar itu, Mis.” Tegur Kang Salim yang sudah merampungkan pekerjaannya. “Yaudah juga lah, Mis, ustaz tersebut berargumen begitu itu kan emang pemahamannya baru sebatas itu. Kalau kamu ngerasa nggak cocok, tinggalin aja, ambil pendapat ustaz atau kiai lain yang menurut kamu lebih pas dan menenteramkan.”
“Nah itu dia masalahnya. Semalem si ustaz sempet bilang, apa pun dawuh kiai atau ulama, harus ditaati. Sebab ulama itu warasatu al-anbiya, pewaris para Nabi. Menolak dawuh ulama itu sama dengan menolak dawuh para Nabi. Saya sendiri dalam situasi bimbang kalau udah kepentok sama dalil-dalil semacam itu, Kang.”
Kang Salim merogoh sebatang kretek dari kantong celananya untuk disulut. Setelah satu tarikan, baru Kang Salim memberikan suara, “Dan nggak cuma satu-dua orang sih, yang makai hadis itu buat melegitimasi ceramahnya. Memonopoli kebenaran versinya sendiri biar dibenerin sama orang-orang.”
“Maaf, Kang, saya potong. Ini hadis karet, rawan banget jadi bahan monopoli. Pertanyaan saya, jadi apakah bener ulama itu pewaris para Nabi?” Kali ini Misbah sudah menyelesaikan pekerjaannya.
“Mau itu model ulama yang suka jelek-jelekin, baca Alquran-nya berantakan, yang suka nyumpah serapah dan menebar kebencian, apakah tetep bisa disebut sebagai pewaris atau penyambung risalah para Nabi? Sehingga kita patut menghormati dan menaatinya. Masalahnya itu hadis sahih loh, Kang, nggak mungkin tho kalau disangkal.”
Kang Salim menyesap kembali kreteknya dengan khdimat, untuk kemudian berucap, “Kalau saya sih, dari dulu udah punya makna lain, Mis, buat hadis tersebut.”
“Maksut sampeyan, warasatu al-anbiya itu bukan pewaris para Nabi dalam arti harfiah yang selama ini kita pahami gitu ta, Kang?”
“Yap, ternyata kamu udah bisa nebak isi kepala saya, Mis,” Kang Salim terkekeh. “Saya curiga, jangan-jangan ada diksi yang tersembunyi di dalam redaksi hadis tersebut. Seperti udah jadi ciri khas kalimat-kalimat bahasa Arab yang emang cenderung nyastra. Mangkanya dalam ilmu nahwu ada yang namanya teori tamyiz, buat nyari maksud redaksi yang agak rumpang.”
“Lantas, apa diksi yang tersembunyi itu, Kang?”
“Bisa jadi redaksi hadis tersebut bermaksud al-ulamau (an yajibu) warasatu al-anbiya, ulama (harus menjadi) pewaris para Nabi. Jadi bukan sebuah klaim, tapi sebuah titah. Piye, paham nggak?”
Misbah mengangguk, entah paham atau tidak, tapi Kang Salim kembali meneruskan penjelasannya.
“Jadi, jika ada orang yang ngaku bahwa dia adalah ulama, seorang tokoh agama, maka dia harus mewarisi suri tauladan para Nabi. Misalnya dalam hal kesabaran mewarisi kesabaran dari Nabi Ayub. Dalam hal ketaatan dan keridaan mewarisi Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Atau mencoba mewarisi uswatun hasanah dari Rasulullah yang selalu berkata jujur dan yang baik-baik. Nggak pernah benci atau jelek-jelekin orang lain. Yang dermawan, bukan pendendam, Yang selalu lemah lembut sama siapa pun, rendah hati, dan segala uswatun hasanah dari Kanjeng Nabi lah.”
“Artinya, kalau ada orang ngaku ulama, tapi sama sekali nggak mencerminkan akhlak para Nabi, berarti belum ngamalin titah harus menjadi warasatu al-anbiya ya, Kang?” tanya Misbah.
“Yoi, Mis. Dan kalau udah begitu, berarti dia nggak pantes juga ngaku sebagai ulama. Yang berhak ngaku sebagai ulama cuma mereka yang emang bener-bener mewarisi uswatun hasanah dari para Nabi itu. Ini penting, Mis. Kalau dulu umat Islam bisa ngelihat secara langsung bagaimana kepribadian Rasulullah sehingga bisa menauladaninya, kita nggak bisa. Untuk itulah kenapa Rasulullah bersabda demikian. Harus ada yang mewarisi budi luhur para Nabi, biar umat juga bisa ikut menauladaninya. Dalam hal ini adalah ulama-ulama itu tadi.”
“Eh, Kang, apa yakin maksudnya demikian? Sebab kalau mengacu pada Abu Yazid al-Bustami, ulama itu adalah hujjah Allah, loh. Katanya, kalau mengikuti jejak ulama, itu sama dengan telah mengikuti Allah. Namun sebaliknya, kalau jauh dari ulama, berarti jauh pula dari Allah.”
“Bagi saya itu adalah konsekuensi dari hadis warasat tadi sih, Mis. Jadi kalau ulama udah bisa jadi pewaris Nabi, dalam artian seperti yang kita bahas sebelumnya, maka dia juga bisa disebut sebagai hujjah Allah. Yang artinya, seluruh perilakunya atau tutur katanya harus didasarkan pada hukum kasih sayang, harus bener-bener mengejawantahkan sifat Allah yang rahman-rahim dan rahmatan li al-alamin. Atau bahasa sufinya, takhalluq min akhlaqillah, berakhlak dengan akhlaknya Allah. Kalau udah kayak gitu, akhirnya nggak ada model ceramah yang mengandung kebencian lagi.”
“Nah, kalau udah di fase menyadari bahwa dia harus jadi hujjah Allah, maka dia bakal hati-hati kalau mau berbuat atau berucap. Semua didasari atas malu pada Allah kalau dia gagal jadi hujjah-Nya. Termasuk ketika ceramah, mestinya dia bakal malu kalau-kalau yang dia omongin itu nggak sesuai dengan karepe Gusti Allah. Sebab dia sadar betul, ilmu yang dia punya itu asalnya dari Allah. Lah kalau salah penyampaian maksud, kan bisa menyinggung Allah akhirnya. Begitu kata Rumi. Yang terjadi selanjutnya, dia jadi sosok yang hati-hati dalam bicara. Nggak bakal berkomentar atas satu pun perkara kecuali perkara yang bener-bener dia pahami.”
“Iya sih, Kang, Nggak kayak kebanyakan ulama saat ini, yang kalau pakai istilah al-Ghazali disebut, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Yang nggak tahu, tapi nggak tahu kalau dia nggak tahu. Akhirnya ngomong ngaco untuk sesuatu yang sebenenernya belum atau sama sekali nggak dia kuasai. Belum lancar baca Alquran sok-sok ngasih ceramah dan ngajarin ngaji. Nggak pernah sekolah kedokteran sok-sok ngomongin dunia medis. Ini kan bahaya. Sangat berpotensi menjerumuskan. Atau kayak jomblo yang sok-sok ngasih nasihat sama pengantin baru gitu, hahaha.”
“Istilah kerennya, dunning krugger effect. Yang nggak tahu banyak, justru bicaranya paling banyak, dan suaranya paling lantang.” Sebatang kretek sudah tandas di mulut Kang Salim.
“Semakin berilmu seseorang, dalam artian menyadari bahwa dia nggak punya ilmu kecuali dari Allah, maka bakal semakin rendah hati lah dia. Kata al-Ghazali, puncak tertinggi pengetahuan seseorang adalah ketika sampai pada pemahaman, ana la adri. Yaitu dia yang pada akhirnya tahu kalau satu-satunya yang dia tahu adalah bahwa dirinya tidak tahu apa-apa. Dia yang sadar bahwa ternyata lebih banyak yang dia nggak tahu selama ini.”
“Allahu Akbar,” gumam Misbah dengan kepala keliyengan.
*Rujukan; Terjemah Fihi Ma Fihi (Jalaluddin Rumi)
BACA JUGA Perkara yang Membuat Sebagian Orang Abangan Nggak Respek Sama Kiai (1) dan tulisan Aly Reza lainnya.
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
Pernah menulis di Terminal Mojok tapi belum gabung grup WhatsApp khusus penulis Terminal Mojok? Gabung dulu, yuk. Klik link-nya di sini.