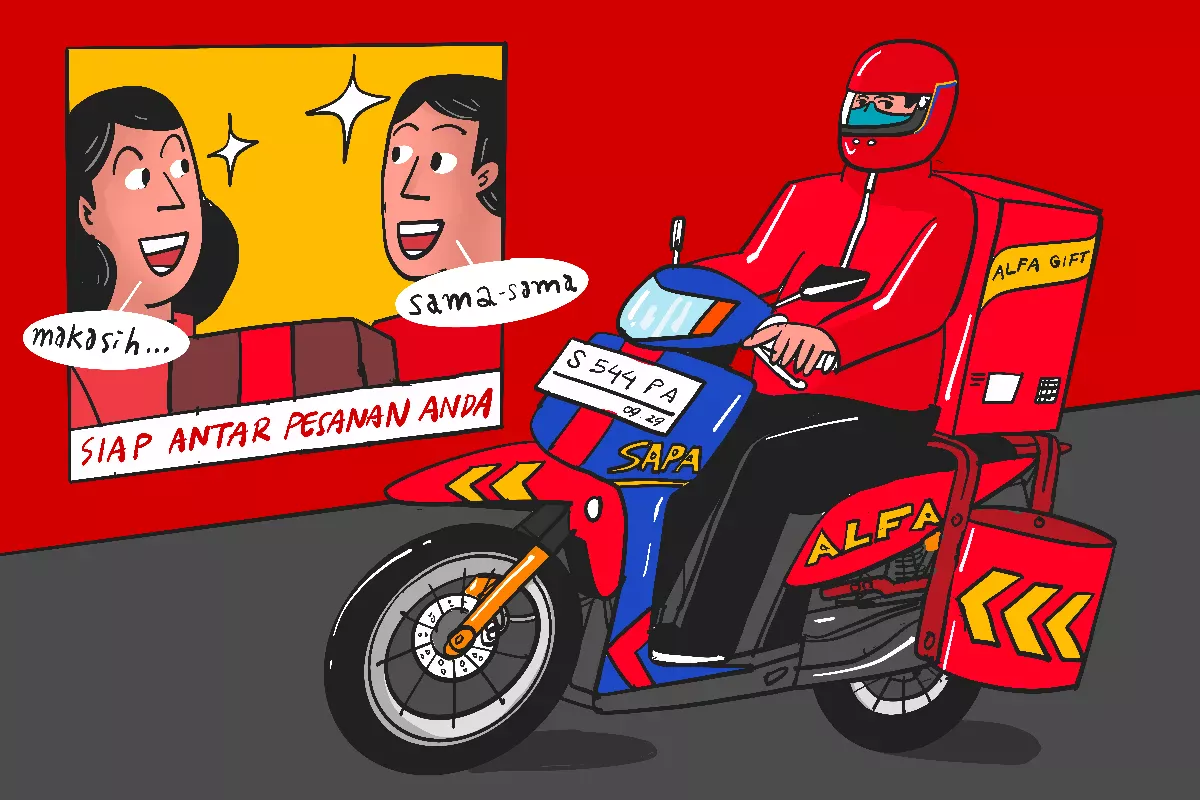Pertanyaan menggelikan ini mengganggu pikiran saya sejak beberapa waktu yang lalu. Belum lagi diiringi dengan asumsi bahwa memindahkan tempat dakwah dari masjid ke diskotik atau klub malam ialah salah satu penurunan harga diri seorang pendakwah. Menurut saya, ada proses berfikir yang belum selesai dalam argumen tersebut.
Tren berdakwah di lingkungan yang terkesan “kotor” bagi sebagian besar kaum yang merasa suci ini telah dimulai sejak beberapa dekade silam oleh seorang kiai bernama lengkap Hamim Thohari Djazuli atau biasa disapa oleh anak-anak dan para santrinya dengan sebutan Gus Miek, beliau ialah pendiri pondok pesantren Al-Falah, Ploso, Mojo, Kediri. Dakwah beliau dari satu klub ke klub yang lain banyak menuai kritik pada masa itu karena dianggap tidak mu’tabarah (berkesinambungan sanad dengan ilmu-ilmu kiai NU), namun justru menjadi sejarah manis hingga hari ini dengan meninggalkan sebuah gerakan bernama dzikrul ghafilin (pengingat bagi orang-orang lupa) yang awalnya digelar untuk orang-orang di bar dan diskotik saja namun kemudian dikembangkan di tempat—tempat terbuka menjadi sebuah majelis rutin.
Baru-baru ini, ada pula Gus Miftah yang ramai menjadi bahan perbincangan karena gaya dakwah yang beliau lakukan mirip dengan Alm. Gus Miek yaitu di klub malam, bar, dan lain-lain. Tapi, perdebatannya kini semakin dangkal yaitu menganggap bahwa dakwah hendaknya dilaksanakan di masjid bukan tempat-tempat kotor yang bahkan tidak pantas untuk para pendakwah menginjakkan kaki tersebut.
Tapi ingatkah kita bagaimana kondisi bangsa Arab (yang di elu-elukan itu) pra Islam? Mereka barbar, menggunakan hukum rimba dalam peradabannya, mabuk-mabukan dan menghalalkan pertumpahan darah demi kekuasaan dan segala yang diinginkannya. Bagaimana jadinya jika saat itu, Muhammad (yang diutus untuk menyempurnakan akhlak [QS. 21:7]) memaksa semua masyarakat barbar itu mengikuti nilai yang beliau anut dan memaksa membersihkan Ka’bah dari berhala-berhala? Mungkin yang terjadi hanya penolakan dan cibiran atau bahkan pertumpahan darah sehingga cerita tentang Islam hanya menjadi sejarah peradaban yang tak pernah tersampaikan. Tapi untunglah Tuhan tidak salah memilih, Muhammad bukan seorang pendakwah yang pemarah dan gengsian untuk sekedar berbaur dan menyapa duluan kepada Kaum Kafir Quraisy yang belum paham Islam. Ia juga tidak menyumpah serapahi orang-orang kafir itu dengan ucapan “celakalah kau ahli neraka”. Seandainya Muhammad memilih untuk jaga harga dirinya sebagai makhluk terbaik utusan Tuhan dengan tidak melibatkan diri pada peradaban barbar itu, mungkin Islam hanya akan menjadi dongeng penghantar tidur.
Kembali pada pernyataan soal dakwah di masjid (yang suci) atau diskotik (yang kotor), menurut saya penyataan dikotomis ini perlu diuji kembali. Benarkah bahwa masjid ialah satu-satunya tempat yang layak untuk berdakwah? Kalau memang demikian, kenapa dulu Rasulullah Muhammad tidak menyeret saja orang-orang Kafir Quraisy menuju masjid? Karena tidak adanya masjid? Menurut saya bukan itu jawabannya, tapi karena Islam diturunkan sebagai bentuk rahmat Allah (cinta kasihnya) kepada alam semesta sehingga siapapun di manapun layak merasakan rahmat itu.
Perkara masjid sebagai tempat ibadah, sudah pernah baca hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Taimiyah yang berbunyi “bahwasannya setiap jengkal muka bumi ini ialah masjid, kecuali kuburan dan WC” ? Apa maksudnya? Mereduksi makna masjid yang secara harfiah merupakan tempat untuk bersujud, memanjatkan puja puji dan merasakan cinta kasih menjadi sebuah bangunan kokoh dengan segala arogansinya untuk menolak makhluk Tuhan ialah bentuk lain dari kesombongan. Selain bentuk lebih kecilnya ialah membangun banyak masjid megah sebagai kebanggaan, kemudian membiarkannya sepi jamaah dengan berbekal aturan jam malam seperti yang tertulis dalam artikel Surat Terbuka Untuk Takmir Masjid Jelang Berakhirnya Bulan Ramadan, lha gimana orang-orang klub malam mau mampir kalau jam 9 aja udah digembok?
Kata dakwah sendiri berasal dari Bahasa Arab yang berarti panggilan atau seruan. Dakwah memiliki dua metode yang secara umum dijelaskan dalam Alquran dengan kalimat bil- hikmah wa mauidzotil hasanah (dengan kalimat-kalimat dan contoh-contoh yang baik). Sementara pengejawantahannya baik ceramah, seminar, menulis, dan sebagainya tidak mengurangi esensi dakwah sebagai sebuah panggilan dan ajakan selama dilakukan dengan cara-cara yang baik. Dalam perbincangan ini sebenarnya tidak ada masalah dengan dakwah di diskotik yang justru merupakan seni “memanggil” yang sangat sopan.
Senangkah kita jika didatangi di rumah kemudian diajak mengenal sesuatu yang mungkin baru dan menyegarkan? Atau lebih nyaman jika diteriaki dari jauh untuk keluar dari “rumah” yang nyaman itu sekedar untuk berbincang? Memaksakan diri menyeru orang-orang di klub malam, bar dan diskotik dengan speaker masjid yang bahkan tak pernah mereka dengar gaungnya? Logika sebercanda apa ini?
Perdebatan terakhir ialah terkait khawatiran akan harga diri para pendakwah atau harga diri (muruah) agama akan runtuh ketika berdakwah di tempat “kotor”. Hati saya runtuh mendengar ini, betapa arogannya kita sehingga sanggup melabeli bahwa orang-orang yang berada di lokalisasi ialah pasti orang yang jauh lebih buruk di banding kita. Masih terngiang di kepala saya sebuah nasihat, “beribadah dan istiqamah memang berat, tapi godaan yang lebih berat ialah untuk tidak menyombongkan diri sebagai ahli ibadah dengan menganggap bahwa diri kita ialah pribadi yang lebih baik dibanding orang lain.”
Jika uang seratus ribu rupiah saja tidak kehilangan nilainya hanya karena berkubang lumpur, apalagi Islam, agama yang Allah janjikan menjadi rahmat bagi semesta. Lalu, apakah Indonesia kekurangan masjid untuk berdakwah? Tidak, kita hanya perlu meluaskan hati untuk menyadari bahwa rahmat Tuhan tidak terbatas pada jenis bangunan.