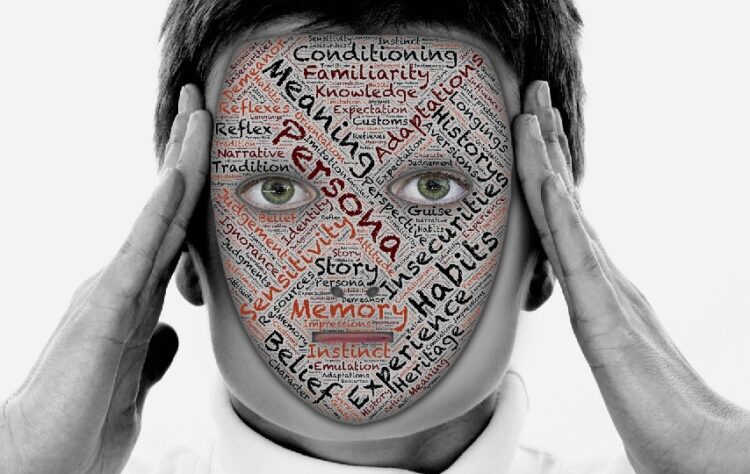LinkedIn kini nggak bisa jadi tempat bersyukur, malah bikin insecure
Dulu sewaktu kuliah, saya suka insecure dengan postingan Instagram orang yang hidupnya kelihatan enak. Postingannya macam-macam, ada yang kerjanya makan mulu di restoran mewah, dugem melulu tiap weekend, sampai liburan ke luar negeri.
Semakin dewasa, saya udah nggak lagi insecure dengan postingan Instagram orang lain karena saya tahu itu cuma pencitraan doang. Yang mereka posting cuma hal yang ingin mereka tampilkan saja. Bagian nggak enaknya ya nggak mereka posting. Semakin dewasa saya justru lebih insecure ketika melihat platform sosial media dikhususkan untuk keperluan profesional dunia kerja, yakni LinkedIn.
Setiap kali saya membuka LinkedIn, saya harus menerima kenyataan pahit bahwa saya jauh tertinggal dibandingkan teman saya saat sekolah dan kuliah bertahun-tahun yang lalu. Ada yang bekerja sebagai manajer di salah satu startup unicorn terkemuka, ada yang bekerja sebagai karyawan BUMN, ada yang bekerja sebagai salah satu staf junior pada kantor Kementerian di Ibukota, ada yang kerja di luar negeri, hingga ada yang sukses bikin usaha sendiri. Sedangkan saya? Ya bisa kalian lihat sendiri di laman LinkedIn saya.
Nggak mau ya? Nggak apa-apa, wong ko ngene kok dibanding-bandingne.
Pasalnya, LinkedIn berbeda jauh dengan Instagram. Di Instagram, kita bisa melakukan pencitraan dengan posting foto yang sudah kita edit sedemikian rupa biar Instagrammable. Supaya damagenya lebih ngena, dibumbui caption panjang dan bijak supaya orang lain terkesima.
Di LinkedIn, kita cenderung tidak bisa melakukan hal tersebut. Memang, kita bisa melakukan praktik “swindling” supaya profil LinkedIn kita lebih berbobot dan terkesan profesional, tapi orang nggak bisa melakukan bluffing secara radikal, berbeda jauh dengan Instagram.
Ketika pengguna LinkedIn melakukan praktik pencitraan, ditelusurinya gampang banget. Sedikit investigasi, bubar itu pencitraan.
Kembali ke masalah insecure.
Melihat postingan LinkedIn orang-orang yang kariernya bagus dan suka posting postingan seputar dunia kerja profesional pun bikin saya insecure. Saya jadi suka mikir, “Salah saya di mana ya? Kok nggak bisa kayak mereka?”
Saya jadi membatin, “Kok mereka bisa ya kerja di startup unicorn terkemuka? Kok bisa sih mereka kerja di salah satu BUMN? Kok bisa sih mereka bekerja di salah satu Kementerian? Kok bisa sih mereka kerja di luar negeri?”
Saya jadi mengevaluasi value diri saya sendiri dengan, “Wah saya harus meningkatkan berbagai skill yang ada pada diri saya seperti kemampuan public speaking saya nih biar kayak mereka!”
Saya juga harus meningkatkan berbagai skill yang ada pada diri saya seperti kemampuan menulis yang saya miliki, kemampuan desain grafis yang saya punya, hingga belajar hal-hal baru seperti digital marketing, SEO, hingga data analysis supaya karier saya bisa secemerlang orang-orang yang saya lihat di LinkedIn.
Saya juga masih harus memiliki sejumlah aspek lainnya seperti kemampuan berbahasa asing supaya punya nilai tambah. Saya juga harus pintar-pintar milih teman buat diajakin nongkrong biar bisa kebawa nilai positif yang mereka miliki. Kasarnya, orang sukses kan nongkrongnya bareng dengan orang sukses juga.
“Lho, bukannya itu bagus? Jadi bikin kita terpacu?” Jawabnya, iya dan tidak.
Ada bedanya memperbaiki kualitas diri karena niat dengan yang karena terpaksa. Konteks terpaksa di sini ya karena ngeliat postingan orang lain dan merasa “iri”. Bagi yang karena niat, mereka belajarnya enjoy dan memang tahu, kalau nggak belajar, mereka merasa kurang. Coba liat temen kalian yang belajarnya karena niat dan emang tahu apa yang mau dilakukan. Progress belajarnya pasti bagus.
Bagi yang terpaksa, apalagi karena disikat realitas LinkedIn, mereka mau belajar dari mana aja bingung. Kalau udah belajar pun, mereka niatnya bukan karena agar jago, tapi biar nggak berada di bawah tangga sosial. Jadinya skill-skill tersebut berakhir jadi pencapaian saja, belum tentu paham juga. Kek gini ada? BANYAK!
Ibaratnya kayak bandingin orang yang viral karena skill dengan orang viral karena atraksi nggak penting. Kita jelas tahu mana yang lebih enak diikuti dan mana yang sebaiknya dikubur dalam-dalam.
Pada akhirnya, LinkedIn justru jadi tempat yang “mengubur” para pencari loker dengan bikin mereka ambruk gara-gara orang pamer. Memang, hal terbaik itu adalah tidak menyerah. Tapi, mentalitas get rich or die tryin’ itu nggak semua orang punya. Juga, LinkedIn harusnya justru ramah sama orang-orang yang nggak berpengalaman. Sebab, purpose dari platform ini adalah memperpendek jarak pencari kerja dengan penyedia kerja, bukan memperlebar tangga sosial, bukan?
Penulis: Raden Muhammad Wisnu
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA LinkedIn Lama-lama kok Malah Jadi Mirip Facebook, ya?