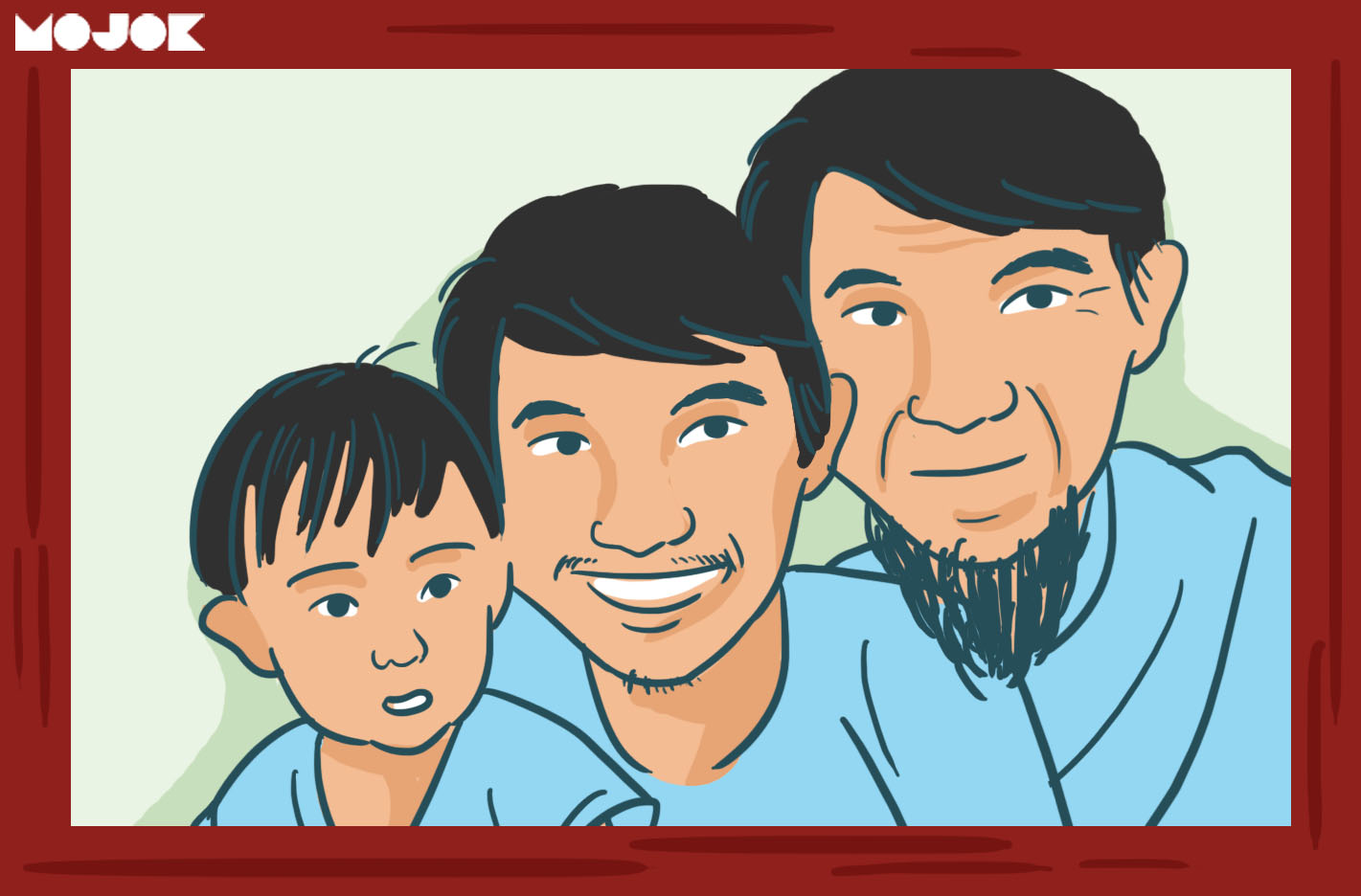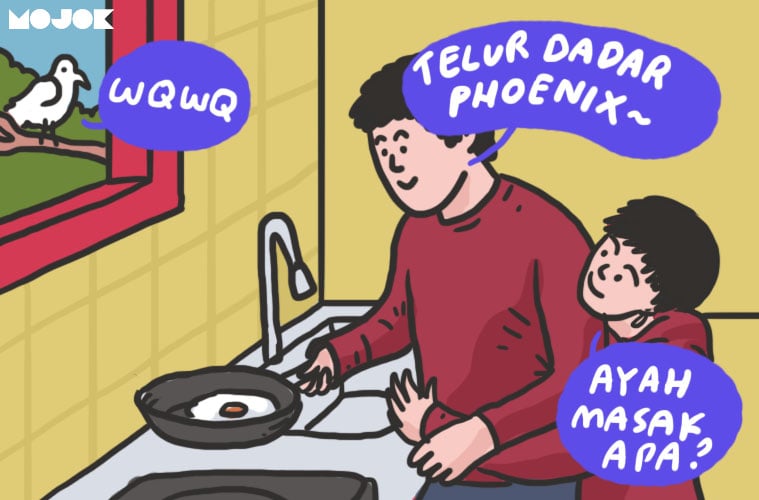MOJOK.CO – Hari Ayah memang tidak semelankolis Hari Ibu. Ketika kamu merasa tak dekat dengan ayahmu, maka hal tersebut akan berubah kalau kamu sendiri yang jadi ayah.
Orang terdekat seorang anak—biasanya—yang pertama adalah ibunya, yang kedua ayahnya. Dulu saya tahu betul premis itu. Bahkan nggak cuma tahu, saya hapal luar kepala sampai merasa itu merupakan ungkapan klise mirip kayak jargon baliho kampanye yang membosankan. Sama membosankannya dengan Hari Ayah yang kebetulan jatuh pada hari ini, 12 November.
Karena jadi yang kedua (kalau ikut hadis malah yang keempat), seorang ayah seringkali dilupakan dalam tumbuh kembang seorang anak. Benar memang ayah adalah sosok yang bertanggung jawab soal dapur ngebul. Tapi karena kewajiban ini pula, seorang ayah harus sering ke luar rumah.
Hal ini yang kemudian bikin sosok seorang ayah nggak punya waktu sebanyak ibu untuk bercengkerama dengan anak. Maka ketika ada seorang anak tidak dekat dengan ayahnya, sering kali hal tersebut jadi pemandangan lumrah—terutama jika si anak adalah anak cowok.
Boro-boro mau mengucapkan “Selamat Hari Ayah”, ke ayahnya, lha wong ketika kita sebagai anak cowok dirindukan oleh sosok ayah saja kadang rasa risih muncul. Entah kenapa ada perasaan berasa jadi cemen ketika sesama cowok semelankolis itu kepada ayahnya. Mbok ya sudah, biasa saja to, Yah. Sama keluarga sendiri aja kok.
Tapi itu pemandangan lumrah kalau melihat model hubungan cowok dengan cowok. Jika lama tidak bertemu dengan sahabat lama, cowok akan menyapa sahabatnya dengan perkataan yang sangat kasar di mulut, “Eh, kamu, masih hidup aja? Ke mana aja? Kirain udah mati,” padahal dalam hati, “Bedebah setan, aku kangen banget.”
Bagi cowok, ada rasa gengsi yang lebih utama ketimbang tunduk pada perilaku melankolis ketika ketemu sahabat cowoknya. Hal yang sedikit banyak juga terjadi ketika ketemu dengan ayahnya sendiri.
Hampir tidak pernah saya dapati pemandangan seorang anak cowok memeluk ayahnya, sambil berkata, “Selamat Hari Ayah ya, Yah? Aku kangen.” Dalam ranah privat pun saya ragu pemandangan itu akan bisa terjadi. Apalagi jika dilakukan di ranah publik.
Entah kenapa ada stereotipe yang tidak bisa ditolak bagi kebanyakan cowok. Bahwa kalau menangisi mantan yang nikah sama orang lain itu adalah hal yang memalukan, sedangkan menangisi kerinduan sahabat cowok yang lama tak ketemu merupakan hal yang sangat menggelikan. Itu baru dengan sesama teman cowok, belum kalau sama ayahnya.
Kesimpulan ini lahir karena selama saya hidup di pondok pesantren, hampir tak pernah sesama teman santri menangis (di hari-hari pertamanya mondok) karena merindukan sosok ayahnya. Yang ada ya kangen ibunya. Bahkan ketika kebetulan ibunya sudah tiada, yang dirindukan tetap teman-teman di kampung halamannya, kucing di rumahnya, atau sekadar ogah tinggal di lingkungan baru. Alasan kangen sama ayah? Pfft, alasan macam apa itu?
Meski ada juga beberapa teman yang benar-benar punya hubungan yang sangat dekat dengan ayahnya. Kedekatan ini seringkali terjadi dalam hubungan yang absurd. Bahkan jika terlalu dekat, seorang ayah akan terlihat seperti seorang teman bagi anak cowoknya. Hal yang sejujurnya sering membuat saya iri ketika melihat pemandangan seperti itu dari sedikit teman saya.
Perasaan iri ini muncul, sebab hubungan saya dengan ayah saya memang tidak dekat. Wajar saya pikir karena jarak usia kami yang kelewat jauh. Usia kami terbentang jarak 53 tahun, karena saya adalah anak kesepuluh dari ayah saya. Jadi kalau kami bersebelahan, orang akan mengira saya adalah cucu pertama dari ayah saya.
Jika saya cuma tahu era peralihan Presiden Soeharto ke era Reformasi, ayah saya sudah hidup sejak Pendudukan Jepang, Agresi Militer I dan II Militer Belanda, Kekerasan 1965, sampai Perang Arab-Israel (karena kebetulan sedang sekolah di sana). Ada banyak pengalaman yang sering diceritakan pada saya pada masa-masa perang tersebut, tapi karena bentang cara berpikir yang terlalu jauh, sering kali saya tidak paham apa saja yang diceritakan.
Apalagi jika mendapati usia ayah saya yang sekarang beranjak menuju 90 tahun. Saya jadi harus terbiasa menceboki ayah saya sendiri ketika beliau sakit muntaber beberapa tahun silam, mengantarnya ke kamar mandi, atau sekadar mengantar ke rumah sakit untuk periksa karena usia sesepuh itu penyakit memang mudah datang.
Meski begitu, saya menyadari bahwa saya tak terlalu peduli dengan ayah saya sebelum ada hal yang mengubah cara pandang itu. Dan perubahan itu datang ketika saya kebetulan dianugerahi anak cowok. Anak yang sangat mirip dengan ayah saya. Entah kenapa, mendadak ketakutan-ketakutan muncul di benak saya.
Bagaimana jika anak cowok saya merasa tidak mau dekat dengan ayahnya? Bagaimana jika dia nanti ketika dewasa lebih ingin bergaul dengan teman-temannya ketimbang bercengkerama dengan saya? Bagaimana jika nanti dia menikah lalu meninggalkan saya begitu saja sebagai ayahnya? Ketakutan-ketakutan yang muncul karena merasa bahwa saya sendiri tidak merasa dekat dengan ayah saya.
Sebelumnya, saya akui saya tidak pernah terlalu memperhatikan ayah saya. Boro-boro peduli hari ayah, ayah saya ngapain saja di masa senjanya saja saya tak pernah peduli karena alasan pekerjaan. Dan sejak anak saya lahir, semua pandangan ke ayah saya mendadak berubah.
Bagi kamu yang punya anak, saya yakin ikut juga merasakannya. Maksud saya, merasakan bagaimana rasa sayang karena dibutuhkan oleh anak itu luar biasa menyenangkan. Bahkan jika kamu pikir nembak gebetan dan diterima itu membahagiakan, tunggu sampai kamu punya anak. Itu perasaan yang tidak tertandingi.
Nah, di saat itulah saya menyadari, betapa perasaan mencintai anak ini tidak akan sama ketika anak saya nanti dewasa dan mencintai ayahnya. Saya tahu betul, tidak mungkin anak saya akan secinta seperti saya mencintainya. Sebab, itu yang saya pahami dari hubungan saya dan ayah saya.
Sebesar-besarnya saya mencintai ayah saya, tidak mungkin saya bisa mendekati perasaan beliau mencintai saya. Dan atas dasar itulah saya paham, betapa sosok ayah saya di mana pun berada tidak kalah luar biasa ketimbang sosok ibu karena bisa lebih rela tidak dirindukan oleh anaknya.
Berhari-hari selalu mencoba meyakinkan diri, bahwa keputusan-keputusan anaknya, meskipun berat, harus tetap direstui. Si anak harus merantau, pergi jauh, bahkan sampai menetap di kota lain. Sosok ayah, mau serindu apa pun dengan anaknya, tetap sadar bahwa anaknya juga butuh menjalani hidupnya sendiri.
Meski di sisi lain ada juga kesadaran, bagaimana seiring usia yang menua, perasaan ingin dekat dengan anak itu luar biasa besar. Perasaan ingin diperhatikan anak itu juga merupakan perasaan membahagiakan dan ingin diulang-ulang. Hanya saja tidak pernah ada keberanian untuk mengatakan itu kepada anak sendiri. Sebab tidak ada orang tua yang mau membebani anaknya. Dan sebagaimana seseorang yang tidak ingin jadi beban, seorang ayah juga ogah menjadi beban bagi anaknya.
Hal-hal yang saya sadari akan saya alami sendiri puluhan tahun ke depan. Ketika anak saya beranjak dewasa dan mulai meninggalkan saya untuk membangun keluarganya sendiri. Dan sebelum itu terjadi, saya ingin sekadar mengucapkan selamat Hari Ayah kepada ayah saya sendiri—meski saya tahu hal itu bakal terasa begitu cengeng dan terasa membosankan.