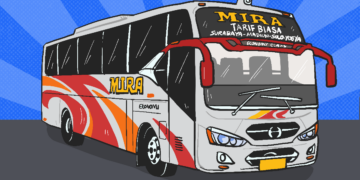Jika kamu kebetulan bertemu dengan seorang lelaki yang menjinjing kardus mi instan atau kardus bekas air mineral di terminal bis mana pun di dunia, langsung saja sapa dengan bahasa Madura, “Mios ka ka’emma, Pak?” insyaallah tak salah.
Di Jawa Timur, terutama area Tapal Kuda, orang bawa kardus (sebagai ransel yang tertunda) itu adalah pemandangan biasa di terminal-terminal. Bawa ayam pun biasa. Dan semua item itu lebih sering masuk kabin daripada bagasi, diperlakukan terhormat layaknya manusia. Kalau si penumpang tajir dan kardusnya berisi kitab suci atau barang berharga lainnya, ada kalanya barang bawaan diletakkan di atas bangku dan dibelikan karcis.
Pernah kejadian, seekor anak ayam terlepas di dalam bis. Tidak perlu bantuan kru, penumpang lain langsung berjibaku menangkap ayam untuk mengembalikannya ke dalam kisa, rumah sementaranya.
“Mengapa Bapak bawa ayam ini dari rumah? Apakah di Jember tidak ada ayam?”
“Kalau saya beli ayam di Jember untuk dibawa sebagai oleh-oleh kepada saudara yang mimang tinggal di Jember, itu beda, Dik, karena ayam Jember yang diberikan kepada orang Jember kurang istimiwa soalnya tidak pernah merasakan perjalanan jauh naik DAMRI.”
Peristiwa di atas, secara umum, biasa terjadi di Indonesia, di terminal maupun dalam perjalanan menggunakan bis. Di negara lainnya, mungkin juga ada, tapi saya tidak tahu. Suasana unik yang sangat khas Madura ini boleh saja dikiaskan dengan kekhasan naik sepur di Jaipur atau naik gondola di Venesia.
Bukan hanya soal keunikan penumpang, bis-bis di Indonesia itu juga menyimpan banyak sensasi yang mungkin susah dicarikan tandingannya di negara lain. Di luar negeri, baik yang saya alami maupun cerita teman, tidak ditemukan adanya orang bawa kardus Aqua, tidak ada yang meletakkan sepeda motor atau koper besar di atas atap, seperti terlihat pada bis-bis Sumatra dan bis tujuan Bima. Jerman bikin Mercy, Swedia bikin Scania, Jepang bikin Hino, tapi yang bisa memberdayakan ciptaan mereka secara maksimal bahkan secara ugal-ugalan, ya sopir dan montir Indonesia.
Kali ini, saya tidak akan bicara soal sensasi naik bis yang mewah meskipun itu juga ada di sini. Biarlah ia urusan orang lain saja sebagai modal menanggapi. Sementara saya mau ngurus tiga sensasi yang ini saja.
Sensasi Balap
Saya pernah naik bis yang bangkunya kosong di dua deret terdepan. Setiap kali ada penumpang naik, langsung nyosor ke tengah. Apakah dua deret terdepan itu kursi panas? Ataukah sebetulnya ada makhluk-makhluk tak kasat mata di situ yang hanya menampakkan diri pada orang-orang yang gamang pada kecepatan tinggi? Lucu juga sih melihat kondisi macam itu: penumpang bersebaran di belakang, tapi tak ada satu pun yang mau duduk di depan.
Tanpa harus menyebut nama, saya yakin kamu pasti bisa menebak itu PO apa. Banyak orang takut naik bis itu di saat yang lain malah memburunya. Golongan kedua jelas para penggila kecepatan. Sensasi balapnya bukan cuma dihitung dari seberapa cepat waktu tempuh, melainkan juga gaya menyetir sopirnya: saat nyalip di jalur padat, lama tidaknya ngintil; menyalip di saat berpapasan, dan seterusnya. Kadang saya menunduk kalau naik bis ini saat mendahulu di jarak yang sangat dekat dengan lawan yang datang dari depan, menunduk ngeri, bukan malu.
Eh, apa film yang temanya tentang kecepatan itu? Fast and Food? (Saya hanya sekali seumur hidup masuk bioskop, maafkan.) Coba itu aktor-aktornya suruh naik Sumber Kencono 7611 dari Bungur dan paksa ia duduk di kap mesin. Mungkin belum sampai di Krian dia sudah minta turun, atau setidaknya akan mempertimbangkan peristiwa yang dialaminya itu sebagai scene untuk episode lanjutannya.
Sayangnya, lakon “Tujuh Enam Sebelas” itu cerita lama. Sekarang sudah ada penggantinya, mestinya. Cak Awan dulu pernah nantang, “Yang berani duduk di kap mesin 7611, akan saya traktir ongkosnya!” kepada sesama temannya yang suka makan pecel di Kertosono lalu tektok lagi ke Surabaya.
Bis yang doyan balap seperti ini konon juga ada di tempat lain, seperti Kuningan—Cirebon untuk jarak dekat, atau bis Muriaan (area plat K) untuk jarak jauh. Pulau Andalas pasti juga punya cerita, seperti yang berlaga di rute Yungas-nya Sumatera, Kabanjahe, dan Sibolga. Pilihan sensasi naik bis cepat tersedia di banyak daerah, jangan ragu mencoba.
Sensasi Mistis
Cerita-cerita mistis dunia bis itu juga banyak. Dulu, Wahyudi Irianto (jika saya tak salah ingat) pernah menuliskan pengamatannya tentang tema ini. Ia mengamati perilaku seorang sopir yang selalu menabur rupa-rupa kembang di dasbor, juga di bagian dalam, di sekitar mesin.
Yang pernah saya dengar langsung adalah cerita Cak No tentang Sugeng. Nama ini adalah seorang legenda AKAS. Namanya moncer ketika jadi pengemudi Mila Sejahtera yang berjuluk “Bledex”. Masih menurut Cak No, mendiang Sugeng punya kebiasaan unik sebelum berangkat, sebelum menjalankan mesin. Biasanya ia mengusap-usap setir serta kaca dengan tangannya sembari berkata, “Hayo, tangi, tangi, tangi …,” ayo, bangun, seolah menyapa teman atau anaknya sendiri.
“Sugeng bisa melihat jalan meskipun tidak ada lampu, Mas, sak mereme …,” kata Cak No, “saya saksinya!”
“Bahkan ia pernah lakukan kayak begitu dari sampe Solo.” Mungkin maksud dia dari Probolinggo sampai Solo, perkiraan saya begitu.
Saya percaya pada cerita Cak No ini karena pernah saya saksikan sendiri aksinya dengan mata kepala sendiri. Kalau tak salah kejadiannya di pertengahan 1996 di Hutan Saradan. Saat itu bis kami berpapasan dengannya (saya tahu kalau bis yang datang dari arah depan itu pegangan Sugeng karena sopir kami spontan menyebut namanya saat bilang kepada kernetnya; juga berdasarkan enam lampu mayang berwarna kuning). Kala itu, di trek lurus, dari jarak yang sangat jauh Sugeng mematikan lampu. Waduh, saya ini naik bis beneran atau sedang mimpi? Gila benar. Ternyata benar, dia seperti kelelawar, bisa melihat jalan dalam keadaan yang sama sekali gelap.
Bahkan ada pula cerita bis yang lampu utamanya dipasangi rajah. Kalau dia ngedim, otomatis apa pun kendaraan yang datang dari arah depan pasti menyingkir. Tentu saja kalau yang berpapasan itu masih semacam mobil, bukan panser atau stum.
Sensasi Jarak
Di akhir 2012 lalu, saya bertemu Fatih di Jambi. Dia berangkat dari Bima naik bis. Entah berapa kali oper-operannya. Ibarat kata, saat berangkat dia masih sebagai singkong di tanah, sampai di Jambi sudah jadi tape dalam kemasan. Kalau saja dia lanjutkan ke atas, ke Aceh, mungkin perjalanannya setara perjalanan dari India, Pakistan, Afganistan, Iran, dan Turki.
Kalau kita iseng mencoba meletakkan peta Indonesia di atas benua Eropa, lalu kita ukur skalanya, cocokkan agar Banda Aceh berada di atas Cardiff (Inggris), maka hasilnya akan memosisikan Medan berada di posisi Paris (Prancis). Coba kamu berfantasi: melakukan perjalanan dengan bis PMTOH ke Palur (Solo) artinya kamu sedang bepergian dari Cardiff menuju Tirana (di Albania) sebagai Solo-nya. Sedangkan jika kamu naik ALS dari Medan menuju Jember, maka saat tiba di Jambi, ibaratnya kamu sudah melakukan perjalanan darat dari Paris ke Milan (di Italia).
Sekalian berfantasi, sekalian dibangetkan saja. Bayangkan kalau naik bisnya itu yang non-AC. Betapa kayak apa nanti bau para penumpangnya ya! Istirahat di sana sini, mandinya cukup (se)sekali. Ayo, lanjut. Kamu akan melewati Abruzzo sebagai Jakarta-nya, lanjut lagi ke Lehze (Albania) sebagai Semarang-nya (menyeberangi Laut Adriatik), lalu tiba di Skopje (Makedonia) sebagai Tuban-nya dan Osogovo (Makedonia) sebagai Surabaya-nya. Jember di mana? Di dalam peta, jika Medan dicocokkan dengan Paris, Jember jadi sejajar dengan Maroneia-Sapes, sebuah dataran tinggi di Yunani.
Saya bayangkan, kalau saja bis seperti PMTOH atau ALS itu dihadapkan ke atas, dengan melakukan perjalanan sebanyak 26 kali PP jarak Aceh—Jember tadi, maka ia sudah menempuh jarak setara dengan perjalanan dari Bumi ke Bulan.