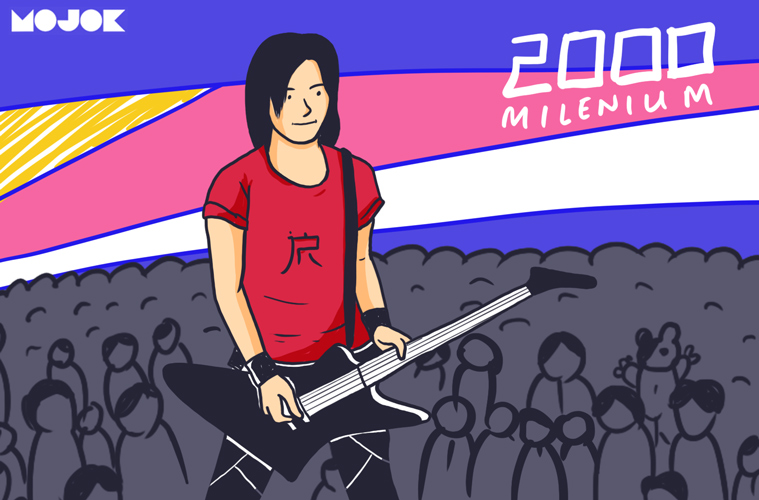Joko, seorang pemuda tanggung dari desa, baru saja merantau untuk menempuh gelar sarjananya di salah satu kota besar di Indonesia. Dengan bangganya, sebagai salah satu penggemar berat Pee Wee Gaskins dan Lyla, Joko berbagi referensi musik dengan kawan-kawan barunya. Namun, bukannya mendapat pujian karena pilihan musiknya, justru sikap sinis teman-temannya yang dia terima.
“Ah, Jok! Pilihan musik lo itu kampungan banget, apalagi itu Pee Wee Gaskins dan Lyla. Cuma alay yang dengar lagu kayak itu,” kata teman-temannya.
Joko heran, musik seperti apa yang kemudian menjadi representasi kaum urban, apakah berbeda jauh dengan musik-musik yang justru didengar oleh kaum rural seperti Joko.
“Coba dengerin musik-musik kayak Barasuara, Payung Teduh, Float, Banda Neira, dan lainnya. Musik-musik seperti itu sekarang lagi digemari banyak orang,” kata temannya yang lain, pria yang baru-baru ini menangis bahagia setelah menonton langsung Mocca untuk kali pertama di Bandung.
Joko kemudian mencoba mendengarkan berbagai jenis musik yang direkomendasikan temannya sembari mulai meninggalkan Lyla dan PWG yang sering Joko dengar sebelum tidur. Efeknya luar biasa, Joko mulai benci dengan musik-musik yang sebelumnya sering dia dengar, karena tidak ingin lagi dianggap norak.
Setelah satu tahun Joko mengikuti berbagai perkembangan musik lokal, dengan mantap, Joko kembali ke kampungnya untuk memberikan warna baru untuk teman di kampungnya soal musik berkualitas dari kaum urban. Joko beranggapan, teman-teman di kampungnya akan keluar dari jurang “kenorakan” dan bisa bergaul dengan kaum urban, sebab Joko yakin, salah satu yang mampu menaikkan derajat kaum rural adalah lewat musik berkualitas. Joko pernah sekali-dua kali ngamen untuk dana usaha acara di kampusnya dengan membawakan lagu dari Monkey To Millionaire dan dapat banyak uang.
Sesampainya di kampung, justru Joko kembali mendapat sikap sinis dari teman-temannya. “Senar Senja atau Silampukau ini enak sih, Jok. Tapi yakin kamu ndak sekadar ikut-ikutan dengerin ginian? Aku ndak ngerti apa bedanya cara menikmati lagu ini sama Noah dan Kerispatih,” kata temannya yang juga Sahabat Kotak.
Joko bingung, siapa yang sebenarnya punya selera musik buruk. Joko memaklumi temannya berasal dari dua kaum yang berbeda. Joko sendiri merasa baik itu Lyla atau Barasuara sebenarnya menarik untuk didengar. Toh, Joko merasa semua musik yang dia dengar cocok di kupingnya yang tidak terlalu ngota tapi tidak terlalu ndeso pula.
Perpustakaan dalam otak Joko setelah satu tahun bergerilya mencari musik terbaik untuk kaumnya cukup besar meski belum lengkap terisi oleh berbagai musik. Joko menikmati dentuman hyperblast dari musik dengan aliran slamming brutal death metal yang bahkan Joko kadang tidak mengerti apa yang mereka nyanyikan, hingga senangnya melihat kecantikan yang seragam dari aliran pop Jepang dan Korea, seperti LinQ dan F(X).
Tapi, yang tidak bisa Joko pahami adalah apa yang membuat karya musik punya indikator abstrak terkait ‘buruk’ dan ‘baik’ terutama dalam masalah sosial.
Polemik yang dihadapi Joko juga sering saya alami. Kadang, saya sering dilontarkan pertanyaan musik seperti apa yang saya suka. Pertanyaan seperti ini biasanya berakhir dengan jawaban sinis, “selera lo gitu amat” karena saya kadang juga menjawabnya dengan “Pee Wee Gaskins dan Lyla”.
Saya tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan saat bertanya kenapa saya harus membenci dua musisi tadi. Khusus PWG, yang juga punya basis haters dengan nama APWG (Anti-PWG) sepertinya dibenci tanpa alasan yang cukup kuat, hanya karena penikmatnya sering mendapat titel ‘alay’ akibat banyaknya musuh PWG di skena Jakarta kala itu. Buktinya, teman saya yang dulu sempat menggilai PWG, hingga punya berbagai merchandise khas mereka dengan tega membakar seluruh koleksinya hanya karena banyak yang mengejeknya dengan titel yang sama. Sama halnya dengan Lyla, saya bahkan punya playlist khusus untuk lagu-lagu milik Lyla, Kotak, Samsons, Seventeen, dan lainnya di Spotify karena toh buat saya lagu mereka tidak jelek-jelek amat.
Malah, saya yakin dengan satu hal; kebanyakan yang mendengarkan Barasuara, Payung Teduh, Banda Neira, dan lainnya adalah orang-orang yang mengalami bias kognitif. Saya tentu menghargai yang memang sampai bergerilya menikmati Barasuara, tapi tidak yang kemudian bersusah payah hanya untuk mencerna substansi lirik milik Efek Rumah Kaca pada setiap albumnya. Sederhananya, bias kognitif menjadikan seseorang membuat penilaian yang tidak masuk akal hanya karena persepsi dan masukan lainnya mereka peroleh dari orang lain yang dianggapnya lebih berpengaruh. Bahasa kerennya, mereka mengalami sebuah teori bernama bandwagon.
Sesuatu yang saya pahami adalah, bias kognitif ini meliputi berbagai aspek. Payung Teduh tidak jauh beda dengan Letto yang punya lirik romantis, atau justru saya malah melihat substansi komposisi musik Vagetoz lebih jelas dan sederhana dibandingkan Banda Neira atau Senar Senja yang butuh dua hingga tiga kali dicerna sebelum akhirnya paham maksud komposisinya.
Toh, saya yakin jika D’Masiv mengubah namanya menjadi Abhipraya dan membuat musik dengan lirik layaknya The Trees and The Wild tanpa orang tahu mereka ada dibalik nama Abhipraya, tentu banyak yang akan sukarela mendengar musiknya.
Saya pun meyakini hal lainnya; akan banyak yang protes saat saya menyatakan pendengar Barasuara itu alay, sedangkan tidak ada yang protes saat saya menyatakan pendengar Wali dengan hal yang sama.
Saya menganggap tidak elok rasanya jika kemudian memberikan indikator abstrak terkait bagus dan tidaknya sebuah musik hanya karena masalah kelas-kelas sosial yang diciptakan oleh kita sendiri. Hanya karena fansnya bukan berasal dari kaum menengah atau urban yang terbiasa mengonsumsi lirik yang lebih kompleks, kemudian merendahkan musik yang sebenarnya tetap menarik untuk dinikmati, sayangnya musik mereka milik kaum rural dan marjinal. Toh, kelas-kelas sosial ini juga diciptakan lewat satu medium yang sama; pasar.
Efek Rumah Kaca juga menekankan, pasar bisa diciptakan. Pasar yang berbeda untuk kelas urban dan rural bagi saya tidak layak menjadi sebuah indikator kuantitatif dan kualitatif terkait karya musik.
Saya toh tidak malu menyetel musik-musik tadi di tempat umum karena memang masih layak untuk didengar, sedangkan tidak sedikit pula yang malu untuk menyetel lagu yang sama hanya karena masalah socio-labelling dari orang-orang di sekitarnya. Sama halnya saat saya menyetel lagu Kesempurnaan Cinta milik Rizky Febian yang direspon, “wah, bagus ini lagunya, punya siapa?” yang kemudian direspon berbeda saat tahu itu lagu anak dari salah satu komedian ternama Indonesia (Hasyah, sebut saja Sule).
Saya benci jika harus menjadi seperti Joko, yang kebingungan ingin terlihat seperti kaum urban hanya untuk diakui selera musiknya bagus meski dasarnya kupingnya lebih cocok mendengar lagu-lagu yang dinikmati kaum rural. Tapi, saya juga ingin bisa seperti “Joko”, yang bisa menikmati hampir semua lagu, mulai dari slamming brutal death metal, pop korea-jepang, sampai koplo-jaranan ala-ala OM Sagita.
Assololeeeey